Kaidah Ke-1: Allah dan Rasul-Nya Tidaklah Memerintahkan Sesuatu Kecuali Mendatangkan Maslahat
Kaidah Pertama
الشَّارِعُ لاَ يَأْمُرُ إِلاَّ بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلاَ يَنْهَى إِلاَّ عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ
Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidaklah memerintahkan sesuatu, kecuali yang murni mendatangkan maslahat, atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu, kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.
Kaidah ini mencakup seluruh syariat agama ini. Tidak ada sedikit pun hukum syariat yang keluar dari kaidah ini, baik yang berkaitan dengan pokok maupun cabang-cabang agama ini, juga berhubungan dengan hak Allah ﷻ maupun yang berhubungan dengan hak para hamba. Allah ﷻ berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” [QS. an-Nahl/16:90].
Tidak ada satu keadilan pun, juga ihsan (perbuatan baik), dan menjalin silaturahim yang terlupakan, kecuali semuanya telah diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam ayat yang mulia ini. Dan tidak ada sedikit pun kekejian dan kemungkaran yang berkait dengan hak-hak Allah ﷻ, juga kezaliman terhadap makhluk dalam masalah darah, harta, serta kehormatan mereka, kecuali semuanya telah dilarang oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ mengingatkan para hamba-Nya agar memerhatikan perintah-perintah Allah ﷻ ini, memerhatikan kebaikan dan manfaatnya, lalu melaksanakannya. Allah ﷻ juga mengingatkan agar memerhatikan keburukan dan bahaya yang terdapat dalam larangan-larangan Allah ﷻ tersebut, lalu menjauhinya.
Demikian pula firman Allah ﷻ:
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
Katakanlah: “Rabbku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri) mu di setiap salat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. [QS. al-A’raf/7:29].
Ayat ini telah mengumpulkan pokok-pokok semua perintah Allah ﷻ, dan mengingatkan kebaikan perintah-perintah itu. Sebagaimana ayat selanjutnya menjelaskan pokok-pokok semua perkara yang diharamkan, dan memeringatkan akan kejelekannya. Allah ﷻ berfirman:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Katakanlah: “Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) memersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” [QS. al-A’raf/7:33].
Dalam ayat yang lain, tatkala Allah ﷻ memerintahkan agar bersuci sebelum melaksanakan salat, yaitu dalam firman-Nya:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memeroleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. [QS. al-Maidah/5:6].
Allah ﷻ menyebutkan dua macam thaharah (bersuci), yaitu thaharah dari hadats kecil dan hadats besar dengan menggunakan air. Dan jika tidak ada air atau karena sakit, maka bersuci dengan menggunakan debu. Selanjutnya Allah ﷻ berfirman:
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” [QS. al-Maidah/5: 6]
Dalam ayat ini Allah ﷻ mengabarkan, bahwa perintah-perintah-Nya termasuk jajaran kenikmatan terbesar di dunia ini, dan berkaitan erat dengan nikmat-Nya nanti di Akhirat.
Perintah Allah ﷻ yang maslahatnya seratus persen, dan larangan Allah dari sesuatu yang benar-benar rusak, dapat diketahui dari beberapa contoh berikut:
Sebagian besar hukum-hukum dalam syariat ini mempunyai kemaslahatan yang murni. Keimanan dan tauhid merupakan kemaslahatan yang murni, kemaslahatan untuk hati, roh, badan, kehidupan dunia dan Akhirat. Sedangkan kesyirikan dan kekufuran, bahaya dan mafsadatnya murni, yang menyebabkan keburukan bagi hati, badan, dunia, dan Akhirat.
Kejujuran maslahatnya murni, sedangkan kedustaan sebaliknya. Namun jika ada maslahat yang lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan akibat kedustaan, seperti dusta dalam peperangan, atau dusta dalam rangka mendamaikan manusia, maka Nabi ﷺ telah memberikan rukhshah (keringanan) dalam masalah perbuatan dusta seperti ini, dikarenakan kebaikannya atau maslahatnya lebih dominan.
Demikian pula keadilan mempunyai maslahat yang murni. Sedangkam kezaliman seluruhnya adalah mafsadat. Adapun perjudian dan minum khamr, mafsadat dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karena itu Allah ﷻ mangharamkannya. Allah ﷻ berfirman:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. [QS. al-Baqarah/2:219].
Jika ada maslahat-maslahat besar dari sebagaian perkara yang mengandung unsur perjudian, seperti mengambil hadiah lomba yang berasal dari uang pendaftaran peserta dalam lomba pacuan kuda, atau lomba memanah, maka hal demikian ini diperbolehkan. Karena lomba-lomba ini mendukung untuk penegakan bendera jihad.
Adapun memelajari sihir, maka sihir hanyalah mafsadat semata-mata. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
Dan mereka memelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya, dan tidak memberi manfaat. [QS. al-Baqarah/2:102].
Demikian pula diharamkannya bangkai, darah, daging babi, dan semisalnya yang mengandung mafsadat dan bahaya. Jika maslahat yang besar mengalahkan mafsadat akibat mengonsumsi makanan yang diharamkan ini, seperti untuk mempertahankan hidup, maka makanan haram ini boleh dikonsumsi. Allah ﷻ berfirman:
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [QS. al-Maidah/5:3].
Pokok dan kaidah syariah yang agung ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan, bahwa ilmu-ilmu modern sekarang ini, serta berbagai penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan dunia meraka, bisa digolongkan ke dalam perkara yang diperintahkan dan dicintai Allah ﷻ dan Rasul-Nya, sekaligus merupakan nikmat yang diberikan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya; karena mengandung manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan sebagai sarana pendukung.
Oleh karena itu, adanya telegram dengan berbagai jenisnya, industri-industri, penemuan-penemuan baru, hal-hal tersebut sangat sesuai dengan implementasi kaidah ini. Perkara-perkara ini ada yang masuk kategori sesuatu yang diwajibkan, ada yang sunnah, dan ada yang mubah, sesuai dengan manfaat dan amal perbuatan yang dihasikannya. Sebagaimana perkara-perkara ini juga bisa dimasukkan dalam kaidah-kaidah syariyah lainnya yang merupakan turunan dari kaidah ini.
Kaidah Ke-2: Hukum Wasilah Tergantung Pada Tujuan-Tujuannya
Kaidah Kedua:
الوَسِيْلَةُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ
Hukum Wasilah Tergantung Pada Tujuan-Tujuannya
Beberapa hal yang masuk dalam kaidah ini di antaranya ialah, bahwasanya perkara wajib yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib pula. Dan perkara sunnah yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut sunnah juga hukumnya. Demikian pula sarana-sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram atau mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka hukumnya mengikuti perkara yang haram atau makruh tersebut.
Demikian pula termasuk turunan dari kaidah ini, bahwa hal-hal yang mengikuti ibadah ataupun amalan tertentu, maka hukumnya sesuai dengan ibadah yang menjadi tujuan tersebut.
Kaidah ini merupakan kaidah yang sifatnya kullliyah (menyeluruh), yang membawahi beberapa kaidah lain.
Pengertian الوَسِيْلَةُ (wasilah) yaitu jalan-jalan (upaya, cara) yang ditempuh menuju (perwujudan) suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya. Demikian pula hal-hal lain yang berkait dan lawaazim (konsekuensi-konsekuensi) yang keberadaannya mengharuskan keberadaan perkara tersebut, serta syarat-syarat yang tergantung hukum-hukum pada sesuatu tersebut.
Jadi apabila Allah ﷻ dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu, maka itu berarti sebuah perintah untuk melaksanakan obyek yang diperintahkan, dan hal-hal terkait yang menyebabkan perintah tersebut tidak sempurna kecuali dengan hal-hal tersebut. Demikian pula perintah tersebut juga mencakup perintah untuk memenuhi semua syarat-syarat dalam syariat, syarat-syarat dalam adat, yang maknawi ataupun kasat mata. Hal ini dikarenakan Allah, Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Memiliki Hikmah, mengetahui apa yang menjadi pengaruh-pengaruh yang muncul dari hukum-hukum yang Dia ﷻ syariatkan bagi hamba-Nya berupa lawaazim, syarat-syarat, dan faktor-faktor penyempurna. Sehingga perintah untuk mengerjakan sesuatu, bermakna merupakan perintah untuk obyek yang diperintahkan tersebut. Dan juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang tidaklah bisa sempurna perkara yang diperintahkan tersebut, kecuali dengannya. Dan (sebaliknya), larangan dari mengerjakan sesuatu merupakan larangan dari hal tersebut, dan larangan dari segala sesuatu yang mengantarkan kepada larangan tersebut.
Atas dasar keterangan di atas, berjalan untuk melaksanakan salat, menghadiri majelis zikir, silaturahim, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan lain-lain masuk dalam kategori ibadah juga. Demikian pula orang yang pergi untuk melaksanakan haji dan umrah, serta jihad fi sabilillah (di jalan Allah ﷻ ), sejak keluar dari rumah sampai pulang kembali, maka orang tersebut senantiasa dalam pelaksanaan ibadah. Karena keluarnya (orang tersebut dari rumah) merupakan wasilah (cara) untuk melaksanakan ibadah, dan menjadi penyempurnanya. Allah ﷻ berfirman:
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
“Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” [QS. at-Taubah/9:120-121].
Dalam hadis yang Shahih, Nabi ﷺ bersabda:
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ أَوَ سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ
“Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memerjalankannya, atau memudahkan jalan baginya menuju ke Surga. [HR Muslim]. [1]
Sungguh terdapat hadis Shahih yang menjelaskan tentang pahala berjalan untuk melaksanakan salat, dan setiap langkah yang ditempuh dalam perjalanan tersebut ditulis baginya satu kebaikan dan dihapuskan satu kejelekan.
Dan firman Allah ﷻ:
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ
“Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).” [QS. Yasin/36:12].
Yang dimaksudkan dengan “Bekas-bekas yang mereka tinggalkan” pada ayat di atas ialah perpindahan langkah-langkah dan amalan-amalan mereka, apakah untuk melaksanakan ibadah ataukah sebaliknya. Oleh karena itu, sebagaimana melangkahkan kaki dan upaya-upaya untuk melaksanakan ibadah dihukumi sesuai dengan hukum ibadah yang dimaksud, maka melangkahkan kaki menuju kemaksiatan juga dihukumi sesuai dengan hukum kemaksiatan tersebut, dan kemaksiatan yang lain.
Maka perintah untuk melaksanakan salat adalah perintah untuk melaksanakan salat, dan perkara-perkara yang salat tidak sempurna kecuali dengannya, seperti thaharah (bersuci), menutup aurat, menghadap Kiblat, dan syarat-syarat lainnya. Dan juga perintah untuk memelajari hukum-hukum yang pelaksanaan salat tidaklah bisa sempurna, kecuali dengan didahului dengan memelajari ilmu tersebut.
Demikian pula, seluruh ibadah yang wajib atau sunnah, yang tidaklah bisa menjadi sempurna kecuali dengan suatu hal, maka hal itu juga wajib karena perkara yang diwajibkan tersebut, atau menjadi amalan sunnah dikarenakan perkara yang sunnah tersebut.
Termasuk cabang kaidah ini adalah perkataan ulama [2]: “Jika datang waktu salat bagi orang yang tidak menjumpai air, maka wajib baginya untuk mencari air di tempat-tempat yang diperkirakan dapat ditemukan air di sana”. Dikarenakan kewajiban tersebut tidak sempurna, kecuali dengan keberadaan hal-hal itu sehingga hukumnya juga wajib. Demikian pula wajib baginya untuk membeli air atau membeli penutup aurat yang wajib dengan harga yang wajar, atau dengan harga yang lebih dari harga wajar, asalkan tidak menyusahkannya dan tidak menyedot seluruh hartanya.
Dan masuk di dalam kaidah ini juga adalah tentang wajibnya memelajari ilmu perindustrian yang sangat dibutuhkan oleh kaum Muslimin untuk mendukung urusan agama dan dunia mereka, baik urusan yang besar maupun yang kecil.
Demikian pula masuk dalam kaidah ini adalah wajibnya memelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat terbagi menjadi dua macam:
- Pertama: Ilmu yang hukum memelajarinya Fardhu Ain, yaitu ilmu yang sifatnya sangat diperlukan oleh setiap orang dalam urusan agama, Akhirat, maupun urusan muamalah. Setiap orang berbeda-beda tingkat kewajibannya sesuai dengan keadaan masing-masing.
- Kedua: Ilmu yang hukum memelajarinya Fardhu Kifayah, yaitu ilmu yang merupakan bersifat tambahan dari ilmu yang harus dipelajari oleh setiap individu, yang dibutuhkan oleh muasyarakat luas.
Dari sini, ilmu yang sangat dibutuhkan oleh individu hukumnya Fardhu Ain. Adapun ilmu yang sifatnya tidak mendesak jika ditinjau dari sisi kebutuhan individual, namun masyarakat luas membutuhkannya, maka hukumnya Fardhu Kifayah. Sebab, perkara yang hukumnya Fardhu Kifayah ini, jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang dengan jumlah yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Dan jika tidak ada sama sekali orang yang melaksanakannya, maka menjadi wajib atas setiap orang.
Oleh karena itu, termasuk cabang kaidah ini adalah semua hal yang hukumnya Fardhu Kifayah, seperti mengumandangkan azan, iqamah, mengendalikan kepemimpinan yang kecil maupun yang besar, amar ma`ruf nahi munkar, jihad yang hukumnya Fardhu Kifayah, pengurusan jenazah dalam bentuk memandikan, mengafani, menyalatkan, membawanya ke pemakaman, menguburkannya, serta hal-hal yang menyertainya, persawahan, perkebunan, dan hal hal yang menyertainya.
Termasuk pula dalam kaidah ini, usaha seseorang dalam bekerja yang menjadi wasilah (sarana) baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri, istri, anak-anak, budak, dan juga binatang ternaknya, serta untuk melunasi utangnya. Dikarenakan hal-hal tersebut hukumnya adalah wajib, dan tidak bisa dipenuhi kecuali dengan mencari rezeki dan berusaha mendapatkannya.
Demikian pula tentang wajibnya memelajari tanda-tanda datangnya waktu salat, mengetahui arah Kiblat, dan arah mata angin bagi orang yang membutuhkan hal tersebut. Hal-hal tersebut masuk juga dalam kaidah ini.
Termasuk pula dalam kaidah ini setiap perkara mubah yang menjadi wasilah (jalan) untuk meninggalkan kewajiban, atau menjadi wasilah dalam melaksanakan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, diharamkan jual beli setelah azan kedua pada Salat Jumat, berdasarkan firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan Salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” [QS. al-Jumu’ah/62:9].
Demikian pula diharamkan menjual sesuatu kepada orang yang akan menggunakannya untuk kemaksiatan, seperti menjual anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi minuman keras (khamr). Atau menjual senjata kepada orang dalam kondisi fitnah, atau menjualnya kepada musuh dan perampok. Dan juga tidak diperbolehkan menjual telur atau semisalnya kepada orang yang akan menggunakannya dalam berjudi.
Termasuk dalam kaidah ini pula adalah perbuatan seseorang yang diberi wasiat oleh orang lain, kemudian ia membunuh orang yang memberi wasiat tersebut. Atau pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pemilik harta [3] supaya segera memeroleh warisan tersebut. Maka keduanya dikenai hukuman dengan tidak berhak memeroleh isi wasiat atau warisan yang menjadi tujuannya tersebut.
Demikian pula seorang suami yang menindas istri tanpa alasan yang dibenarkan, agar istri menyerahkan kekayaan kepada suami hingga mau menceraikannya.
Begitu pula hiyal (tipu-muslihat) yang ditempuh sebagai wasilah untuk melaksanakan perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka hukumnya adalah haram. Sedangkan hiyal yang dipergunakan untuk memeroleh sesuatu yang menjadi hak seseorang hukumnya diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Hal ini dikarenakan seorang hamba diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang sudah menjadi haknya dan hak-hak lain yang berkaitan dengannya, baik dengan cara yang terang-terangan maupun tersembunyi.
Hal ini merujuk firman Allah ﷻ tatkala menyebutkan muslihat yang dilakukan Nabi Yusuf Alaihissallam supaya saudaranya tetap tinggal bersamanya:
كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ
“Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf.” [QS. Yusuf/12:76].
Sama dalam masalah ini tipu-daya untuk menyelamatkan jiwa dan kekayaan, sebagaimana yang dilakukan Khidhir dengan cara merusak perahu yang ia tumpangi, supaya perahu tersebut tidak dirampas oleh raja yang zalim yang merampas setiap perahu bagus yang ia lihat.
Oleh karena itu, hukum suatu muslihat mengikuti tujuan peruntukan muslihat tersebut, apakah tujuannya baik ataukah tidak.
Termasuk pula dalam kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…. [QS. an-Nisa`/4:58].
Sedangkan yang dimaksud dengan amanat adalah segala sesuatu yang seseorang mendapatkan kepercayaan untuk mengurusinya, seperti barang titipan, mengurus anak yatim, menjadi nadzir wakaf dan semisalnya. Maka termasuk dalam upaya untuk menjalankan amanat kepada kepada pemiliknya, adalah menjaga amanat tersebut dengan ditempatkan di tempat penyimpanan yang sesuai.
Dan termasuk upaya menjaga amanat tersebut adalah memberikan makanan dan lainnya, jika yang diamanatkan tersebut bernyawa. Adapun dalam penggunaannya, tidak teledor dan tidak berlebih-lebihan.
Di antara cabang kaidah ini adalah bahwasannya Allah ﷻ mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, dan melarang mendekat kepada semua wasilah yang dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang pada perkara yang diharamkan tersebut. Misal, menyendiri dengan wanita yang bukan mahramnya, atau melihat kepada sesuatu yang diharamkan.
Atas dasar itu, Rasulullah ﷺ bersabda:
وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ
Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar, maka ia telah jatuh ke dalam wilayah perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan; dikhawatirkan ia akan masuk ke daerah larangan itu. Ingatlah, setiap raja memiliki daerah larangan; dan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. [HR Bukhari]. [4]
Termasuk cabang kaidah ini pula, adalah adanya larangan mengerjakan sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Misalnya, menyerobot pembeli dari penjual Muslim lainnya, menimpali akad orang lain, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, atau mengajukan perwalian atas pengajuan Muslim yang lain.
Sebagaimana termasuk cabang kaidah ini pula, adalah memberikan dorongan untuk komitmen dengan kejujuran, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Pengecualian dalam Kaidah ini
Adapun perkara yang tidak masuk dalam kaidah ini adalah permasalahan nadzar. Hal ini dikarenakan suatu hikmah tertentu yang khusus pada permasalahan tersebut. Sebab, menunaikan nadzar ketaatan hukumnya adalah wajib, sedangkan bernadzar hukumnya makruh. Padahal menunaikan nadzar tidaklah bisa dilaksanakan kecuali dengan menetapkan nadzar.
Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan agar nadzar dilaksanakan dan melarang orang untuk bernadzar. Beliau ﷺ bersabda:
إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ, وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ
“Sesungguhnya nadzar itu tidaklah mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya nadzar itu dikeluarkan dari seorang yang bakhil.” [HR Bukhari]. [5]
Keadaan demikian ini karena mengurangi keikhlasan dalam amalan yang dinadzarkan tersebut, dan menyebabkan orang yang mengikat nadzar terjebak pada kesulitan padahal awalnya ia berada dalam kelapangan. Wallahu a’lam.
______
Footnote
[1]. HR Muslim dalam Kitab adz-Dzikr wa ad Du’aa`, Bab: Fadhl al-Ijtima’ ‘ala Tilawatil-Qur`an, no. 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lafalnya adalah:
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ
[2]. Al Mughni 1/314
[3]. Misalnya, seorang anak membunuh orang tuanya yang kaya, dengan tujuan agar segera mendapatkan warisan dari sang ayah, Red.
[4]. HR Bukhari no. 52, dan Muslim no. 1599 dari Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu.
[5]. HR Bukhari no. 6693, dan Muslim no. 1639.
Kaidah Ke-4:
Kaidah Ketiga:
المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ
Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan
Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting untuk dipahami. Karena, seluruh rukhshah dan keringanan yang ada dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini.
Di antara dalil yang menyangkut kaidah ini, yaitu firman Allah ﷻ:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. [QS. al-Baqarah/2:185].
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. [QS. al-Baqarah/2:286].
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [QS. al-Hajj/22:78].
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. [QS. at-Taghabun/64:16].
Ayat-ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga ini. Dikarenakan seluruh syariat dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Lurus tauhidnya, terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah ﷻ semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.
Demikian pula, syariat ini penuh toleransi dalam hukum-hukum dan amalan-amalannya. Sebagai contoh, ibadah-ibadah yang tercakup dalam rukun Islam. Salah satunya dalam ibadah salat. Jika kita lihat ibadah ini merupakan amaliah yang mudah dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Demikian pula zakat, hanya memerlukan sebagian kecil dari harta orang yang terkena kewajiban zakat. Itu pun diambil dari harta yang dikembangkan, bukan harta tetap. Dan zakat ini dilaksanakan hanya sekali dalam setahun. Juga ibadah puasa Ramadan yang hanya dilaksanakan selama satu bulan setiap tahun. Ibadah haji yang wajib dilaksanakan sekali saja seumur hidup bagi orang yang mempunyai kemampuan. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka datang secara insidental sesuai dengan sebab yang melatarbelakanginya.
Seluruh ibadah-ibadah tersebut sangat mudah dan ringan. Allah ﷻ juga mensyariatkan beberapa hal yang bisa membantu dan memberikan semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya dengan disyariatkannya berjamaah dalam salat lima waktu, Salat Jumat, dan salat hari raya. Demikian pula pelaksanaan puasa yang dilaksanakan secara bersama-sama pada bulan Ramadan. Juga ibadah haji yang dilaksanakan bersama-sama pada bulan Dzulhijjah.
Tidak diragukan lagi, pelaksanaan ibadah secara berjamaah akan lebih meringankan pelaksanaan berbagai ibadah, lebih memberi semangat, serta lebih mendorong untuk saling berlomba meraih kebaikan. Sebagaimana juga Allah ﷻ telah menyediakan pahala bagi orang yang mau menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi-Nya, baik pahala di dunia maupun di Akhirat. Pahala yang tidak bisa diukur besarnya. Janji Allah k merupakan pendorong terbesar dalam melaksanakan amal kebaikaan dan meninggalkan kejelekan.
Di samping kemudahan-kemudahan ini, masih ditambah lagi, jika ada yang mempunyai uzur sehingga menyebabkannya tidak mampu atau kesulitan melaksanakan hukum-hukum syariat, maka Allah ﷻ telah memberikan keringanan sesuai dengan kedaaan dan kondisi orang bersangkutan. Hal ini nampak jelas dalam beberapa contoh berikut.
- Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan salat dengan berdiri maka boleh salat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka salat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud.
- Seseorang diwajibkan bersuci (thaharah) dengan menggunakan air. Namun, jika tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak ada air, maka diperbolehkan melaksanakan Tayammum.
- Seorang musafir yang sedang menanggung beratnya perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, diperbolehkan untuk menjama’ dan mengqashar salat, serta diperbolehkan mengusap khuf selama tiga hari, sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudhu.
- Orang yang sakit atau sedang bepergian jauh (safar) tetap dicatat mendapatkan pahala dari amal-amal kebaikan yang biasa ia kerjakan ketika dalam keadaan sehat dan tidak bepergian.
Kaidah ini diterapkan dalam berbagai macam pembahasan yang tercakup dalam syariat agama Islam yang mulia ini. Adapun perwujudan kaidah ini secara nyata dapat diketahui dari contoh-contoh berikut ini:
- Jika pakaian atau badan seseorang terkena sedikit darah maka dimaafkan, dan tidak harus mencucinya.
- Boleh beristijmar (membersihkan najis dengan batu atau semisalnya) sebagai pengganti dari istinja’ (membersihkan najis dengan air), meskipun dijumpai adanya air.
- Sucinya mulut anak kecil yang terkadang memakan najis dikarenakan belum bisa membedakaan benda-benda di sekelilingnya.
- Sucinya kucing, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
إَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sesungguhnya ia termasuk binatang yang selalu menyertai kalian. [1]
- Termaafkan, jika terkena cipratan tanah jalanan yang diperkirakan bercampur dengan najis. Jika memang benar ada najisnya, maka dimaafkan dari najis yang sedikit.
- Jika pakaian seseorang terkena kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan tambahan selain ASI, maka cukup membasahi pakaian tersebut dengan air dan tidak perlu mencucinya. Demikian pula jika terkena muntahan bayi tersebut.
- Penjelasan para ahli ilmu, bahwa hukum asal sesuatu zat adalah suci, kecuali jika diketahui secara pasti tentang kenajisannya. Dan hukum asal segala makanan adalah halal dikonsumsi, kecuali jika diketahui secara pasti tentang keharamannya.
- Dalam membersihkan badan, pakaian, atau bejana dari najis cukup menggunakan perkiraan. Jika tidak bisa atau kesulitan menentukan kesuciannya secara pasti, maka cukup dengan dikira-kira, jika dianggap sudah suci, maka cukup.
- Dalam menentukan telah datangnya waktu salat, cukup dengan perkiraan kuat bahwa waktunya telah datang. Yaitu, jika sulit mengetahui datangnya waktu tersebut secara pasti.
- Orang yang melaksanakan haji secara tamattu’ dan qiran, mereka bisa melaksanakan haji sekaligus umrah dalam sekali perjalanan saja.
- Diperbolehkan memakan makanan haram, seperti bangkai dan semisalnya, bagi orang yang terpaksa untuk memakannya.
- Bolehnya jual beli ‘ariyah [2] jika ada hajat untuk mendapatkan kurma ruthab (kurma basah).
- Boleh mengambil upah dari perlombaan pacu kuda, mengendarai unta, dan perlombaan memanah.
- Bolehnya seorang laki-laki merdeka menikahi budak wanita jika laki-laki tersebut tidak bisa menunda pernikahan dan khawatir akan terjatuh dalam perzinaan.
- Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan tanpa kesengajaan, maka karib kerabat orang yang melakukan pembunuhan tersebut menanggung pembayaran Diyat (denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban). Hal ini dikarenakan pelaku pembunuhan tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan, sehingga ia mempunyai uzur. Maka, merupakan hal yang layak jika karib kerabat si pembunuh tersebut menanggung pembayaran Diyat tersebut tanpa memberatkan mereka, yaitu dengan membagi Diyat tersebut sesuai kadar kekayaan masing-masing. Dan pembayaran tersebut diberi tenggang waktu selama tiga tahun. Adapun jika pembunuh tersebut termasuk orang yang berkecukupan dalam harta, apakah ia turut menanggung pembayaran Diyat tersebut ataukah tidak? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama.
Implementasi (perwujudan) dari kaidah ini sangatlah luas. Contoh-contoh di atas sudah cukup mewakili untuk menunjukkan sedemikian penting kaidah ini.
______
Footnote
[1]. HR Ahmad (5/296, 303), Abu Dawud dalam kitab ath-Thaharah, Bab: Su’ril Hirrah (no. 75), at-Tirmidzi dalam kitab ath-Thaharah, Bab: Ma Ja`a fi Su’ril Hirrah (no. 92), an-Nasa`i (1/55), Ibnu Majah dalam kitab ath-Thaharah, Bab: al-Wudhu` bi Su’ril Hirrah (no. 367), Malik (1/45), Abdurrazaq (no. 353), al-Humaidi (no. 430), Ibnu Abi Syaibah (1/31), ad-Darimi (1/187), Ibnu Hibban (no. 121), ath-Thahawi dalam al-Musykil (3/270), Hakim (1/159).
Hadis ini diShahihkan oleh at-Tirmidzi dan Hakim. Dalam kitab at-Talkhis (1/41) disebutkan: “Hadis ini diShahihkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Uqaili, dan Daruquthni”. Hadis ini juga diShahihkan oleh Baihaqi, sebagaimana disebutkan dalam al-Majmu’ (1/215), dan diShahihkan juga oleh an-Nawawi.
[2]. ‘Ariyah, adalah jual beli kurma ruthab (kurma basah) yang masih berada di pohonnya dengan perkiraan semisal harganya jika kurma itu sudah tua dan menjadi kurma kering, dan dilakukan secara takaran. (Syarah al-Muntaha, 2/197)
Kaidah Ke-4: Pelaksanaan Kewajiban Terkait Dengan Kemampuan
Kaidah Keempat:
الوُجُوْبُ يَتَعَلَّقُ بِاْلاِسْتِطَاعَةِ, فَلاَ وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ, وَلاَ مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ
Pelaksanaan Kewajiban Terkait Dengan Kemampuan, Kewajiban Melaksanakan Sesuatu Menjadi Gugur Jika Tidak Mampu Melaksanakannya, Suatu Yang Dilarang (Diharamkan) Menjadi Boleh Saat Kondisi Darurat.
Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. [QS. At Thaghabuun/64: 16]
Dan Rasulullah ﷺ bersabda:
إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. [1]
Kaidah ini mencakup dua kaidah turunan:
Kaidah Pertama: Gugurnya keharusan untuk melaksanakan kewajiban jika seseorang tidak mampu melaksanakannya.
Kaidah Kedua: Halalnya sesuatu yang haram ketika seseorang berada dalam keadaan darurat. Sebagaimana firman Allah ﷻ setelah menyebutkan tentang haramnya bangkai, darah, dan yang selainnya:
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [QS. al Maaidah/5:3]
Dan Allah ﷻ berfirman:
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. [QS. al An’aam/6:119]
Ayat ini dengan tegas menjelaskan tentang bolehnya memakan makanan yang haram dikarenakan keadaan yang darurat. Hanya saja perlu dipahami bahwa pembolehan ini hanya sebatas keperluan saja. Jika telah hilang keadaan darurat tersebut maka wajib baginya untuk berhenti memakannya.
Berkaitan dengan kaidah pertama dalam pembahasan ini, terapannya terdapat dalam beberapa kasus berikut:
- Orang yang tidak mampu memenuhi sebagian syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban dalam salat, maka hal tersebut tidaklah wajib untuk dipenuhi dan ia melaksanakan salat sesuai dengan kadar kemampuannya.
- Orang yang tidak mampu mengerjakan puasa dikarenakan sakit yang terus-menerus dan tidak diharapkan lagi kesembuhnya, atau orang yang sudah tua renta, demikian pula orang yang sedang safar, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan jika kemudian uzurnya tersebut hilang, maka mereka mengqadha puasa sebanyak hari yang ia tinggalkan tersebut.
- Orang yang tidak mampu mengerjakan haji dikarenakan suatu uzur, sedangkan ada kemungkinan uzurnya tersebut akan hilang dalam beberapa kemudian, maka ia bersabar menunggu sampai hilangnya uzur itu. Namun, jika hilangnya uzur tersebut tidak bisa diharapkan lagi, maka diperbolehkan baginya untuk memerintahkan seseorang untuk menghajikannya.
Berkaitan dengan kaidah kedua ini pula Allah ﷻ berfirman:
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit.” [QS. an Nur/24: 61]
Ayat ini berkaitan dengan diberikannya keringanan bagi orang-orang yang buta, pincang, atau sakit dalam ibadah-ibadah yang pelaksanaannya bergantung dengan keberaadaan penglihatan, kesehatan badan, dan kesempurnaan anggota badan, seperti jihad dan semisalnya.
Dari sini dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban disyaratkan adanya kemampuan. Barang siapa yang tidak mampu mengerjakannya maka Allah ﷻ tidak membebankan kepadanya sesuatu yang tidak ia mampui Demikian pula Nabi ﷺ bersabda dalam hadis yang Shahih:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ
Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengingkari itu dengan tangannya, jika tidak mampu maka ingkarilah dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka ingkarilah dengan hatinya, dan itu adalah serendah-rendah keimanan. [2]
Allah ﷻ berfirman ketika menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah berupa pakaian dan semisalnya kepada keluarganya:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. [QS. at Thalaaq/65: 7]
Demikian pula Rasulullah ﷺ bersabda ketika menjelaskan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami berkaitan dengan harta:
اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ
“Mulailah dengan dirimu sendiri kemudian orang-orang yang menjadi tanggunganmu.” [6]
Termasuk dalam penerapan kaidah kedua ini pula adalah praktik pembayaran Kaffarah yang sifatnya murattabah (ada urutan pembayarannya), di mana jika seseorang tidak mampu membayar dengan Kaffarah yang urutannya lebih tinggi, barulah ia membayar Kaffarah dengan urutan di bawahnya.
Demikian pula, di antara terapan kaidah ini adalah keberadaan uzur-uzur syari yang membolehkan seseorang untuk tidak datang menghadiri Salat Jumat dan salat Jamaah.
Adapun berkaitan dengan kaidah kedua dalam pembahasan ini, maka di antara implementasinya adalah beberapa hal sebagai berikut:
- Karena keadaan darurat, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika itu, dan sebagai konsekuensinya ia wajib membayar Fidyah, sebagaimana hal ini dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih. [3]
- Ketika salat berjamaah, seseorang diperbolehkan salat dengan berdiri sendirian di belakang shaf jika ia tidak mendapatkan tempat yang kosong pada shaf di depannya. Hal ini dikarenakan perkara-perkara yang wajib dan lebih besar dari permasalahan shaf tersebut suatu ketika bisa gugur jika seseorang tidak mampu mengerjakannya. Maka, dalam hal ini permasalahan shaf lebih pantas untuk gugur.
_______
Footnote
[1]. HR. Bukhari, Kitab Al I’tisham Bab Al Iqtidaa’ bi Sunani Rasulillah ﷺ No. 7.288. Muslim, Kitab Al Hajj Bab Fardhu Al Hajj No. 1.337, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
[2]. HR. Muslim, Kitabul Iman, Bab Bayanu Kauni An Nahyi ‘an Al Munkari min Al Iman, hadis No. 49.
[3]. Lihat Syarah Al Muhazab 2/20.
Kaidah Ke-5: Syariat Berdiri Di atas Dua Hal, Yaitu Ikhlas dan Meneladani Rasul
Kaidah Kelima:
الشَّرِيْعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ: الإِخْلاَصُ لِلْمَعْبُوْدِ وَالْمُتَابَعَةُ لِلرَّسُوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Syariat Berdiri Di Atas Dua Hal, Yaitu Ikhlas Kepada Allah ﷻ Dan Meneladani Rasul ﷺ
Dua hal tersebut merupakan syarat diterimanaya amal ibadah, baik berupa amalan lahiriyah, seperti perkataan dan perbuatan anggota badan; dan juga amalan bathiniyah, seperti amalan hati.
Allah ﷻ berfirman:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” [QS. al-Bayyinah/98: 5].
Kata الدِّينَ dalam ayat tersebut telah ditafsirkan oleh Nabi ﷺ dalam hadis Jibril, bahwa makna الدِّينَ adalah rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, dan ihsan, yang merupakan inti amalan hati. [1]
Oleh karena itu, semua perkara tersebut harus dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk Allah ﷻ semata, dalam rangka mengharapkan wajah-Nya, rida-Nya, dan pahala dari-Nya.
Selain itu, amalan tersebut harus dilaksanakan dengan landasan hukum dari Alquran dan Hadis. Allah ﷻ berfirman:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. [QS. al-Hasyr/59: 7].
Allah ﷻ telah mengumpulkan eksistensi kedua syarat diterimanya amal ibadah tersebut dalam firman-Nya:
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan. [QS. an-Nisa`/4: 125].
Dalam ayat tersebut, pengertian أَسْلَمَ وَجْهَهُ adalah mengikhlaskan amalan-amalan yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah hanya untuk Allah ﷻ. Dan yang dimaksud dengan وَهُوَ مُحْسِنٌ, adalah ia berbuat ihsan dengan meneladani Rasulullah ﷺ dalam amal-amal ibadah yang ia kerjakan tersebut.
Sehingga amalan yang diterima, yaitu amalan yang terkumpul di dalamnya dua sifat tersebut. Apabila salah satu atau kedua sifat tersebut tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tertolak dan masuk dalam kategori amalan yang disebutkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” [QS. al-Furqan/25: 23].
Allah ﷻ berfirman ketika membedakan antara amalan orang-orang yang ikhlas dengan amalan orang-orang yang riya:
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” [QS. al-Baqarah/2:265].
Demikian pula Rasulullah ﷺ telah bersabda ketika menjelaskan tentang hijrah yang termasuk amalan utama:
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.
“Barang siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.” [2]
Rasulullah ﷺ juga pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin unjuk keberanian, berperang karena fanatisme kesukuan, dan karena bertujuan untuk mendapatkan ghanimah, siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah ﷻ. Maka beliau ﷺ bersabda:
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فيِ سَبِيْلِ اللهِ
#Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah adalah yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah.# [3]
Oleh karena itu, barang siapa yang jihadnya secara lisan maupun perbuatan diniatkan karena Allah ﷻ dan untuk menolong kebenaran maka ia adalah seorang yang ikhlas dalam jihadnya. Dan barang siapa yang meniatkan selain hal itu, maka ia akan memeroleh sebatas apa yang ia niatkan sedangkan amalannya tidaklah diterima.
Dan pada ayat yang lain Allah ﷻ telah berfirman ketika menjelaskan tentang amalan yang dilaksanakan tanpa meneladani Rasulullah ﷺ:
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. [QS. al-Kahfi/18: 103-104].
Oleh karena itu, amalan saleh yang dikerjakan seseorang karena riya, maka amalan tersebut batil, karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Dan amalan yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah ﷻ namun amalan tersebut tidak ada landasan hukumnya secara syari, maka amalan tersebut batil pula, karena tidak disertai mutaba’ah. Demikian pula, keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasannya dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah ﷺ, seperti keyakinan ahlul bidah yang menyelisihi apa yang dilandasi oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, semuanya itu masuk dalam sabda Nabi ﷺ:
إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
“Sesungguhnya setiap perbuatan dilaksanakan dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.” [4]
Sabda Nabi ﷺ:
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
“Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan (ibadah) yang tidak berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak.” [5]
Hadis pertama tersebut menjadi timbangan amalan dari sisi batinnya, dan hadis kedua menjadi timbangan amalan dari sisi lahirnya.
Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah ﷻ semata merupakan perkara yang telah disinggung nash-nash Alquran dan Sunnah yang memerintahkannya, menjelaskan keutamaannya, dan batilnya suatu amalan jika tidak disertai dengannya. Adapun niat untuk mengerjakan amalan itu sendiri, maka meskipun hal itu harus ada dalam setiap amalan, akan tetapi hal tersebut dipastikan keberadaannya dalam setiap amalan yang dikerjakan oleh orang yang memiliki akal dan kesadaran. Karena niat dalam makna tersebut merupakan suatu keinginan untuk mengerjakan suatu perbuatan, dan setiap orang yang berakal pasti meniatkan amalan yang ia kerjakan tersebut.
Sebagaimana kaidah ini masuk dalam permasalahan ibadah, maka masuk pula dalam permasalahan muamalah. Maka setiap muamalah baik berupa jual beli, ijarah (sewa-meyewa), syirkah (persekutuan dagang), atau selainnya yang terdapat larangannya dalam syariat, maka muamalah tersebut batil dan haram dilaksanakan, meskipun pelaku muamalah tersebut saling rida. Dikarenakan keridaan dalam masalah ini disyaratkan setelah terpenuhinya keridaan Allah ﷻ dan Rasul-Nya
Oleh karena itu, praktik-praktik muamalah yang dilarang oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, seperti melebihkan sebagian anak atas sebagian yang lain dalam pemberian, wasiat, dan warisan. Rasulullah ﷺ bersabda:
لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
“Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris.” [6]
Demikian pula, dalam permasalahan wakaf, syarat yang diberikan oleh orang yang mewakafkan haruslah tidak menyelisihi syariat. Jika ternyata menyelisihi syariat maka syarat tersebut tidaklah dianggap. Dalam hal ini, yang menjadi timbangan dalam penentuan syarat tersebut secara umum adalah sabda Nabi ﷺ:
الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ, إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
“Kaum Muslimin di atas syarat-syarat yang mereka tentukan, kecuali jika syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. “ [7]
Berkaitan dengan masalah pernikahan, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bentuk-bentuk nikah yang dihalalkan dan yang diharamkan, masalah talak, ruju’, dan seluruh hal yang berkaitan dengannya, haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari, jika tidak demikian maka hal tersebut tertolak.
Allah ﷻ berfirman:
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [QS. an-Nisa`/4: 59].
Demikian pula tentang permasalahan sumpah. Seseorang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah ﷻ, atau nama-nama-Nya, atau sifat-sifat-Nya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dan dalam permasalahan nadzar, Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ
“Barang siapa yang bernadzar untuk melaksanaakan ketaatan kepada Allah maka hendaklah ia menunaikan nadzarnya, dan barang siapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah maka janganlah ia menunaikan nadzarnya.” [8]
Bahkan masalah fikih dari awal sampai akhir tidak terlepas dari kaidah ini. Karena sesungguhnya, hukum-hukum syari diambil dari empat landasan, yaitu: Al-Kitab, as-Sunnah, yang keduanya menjadi pokok dalil syari; kemudian Ijma yang disandarkan pada keduanya, dan Qiyas berdasarkan istimbat dari keduanya.
_______
Footnote
[1]. Yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab al-Iman, Bab: Su`alu Jibril an-Nabiyya ﷺ (no. 50), Muslim dalam kitab al-Iman, Bab: Bayanul-Iman (no. 9).
[2]. HR al-Bukhari dalam kitab Bad’il Wahyi (no. 1), Muslim dalam al-Imarah, Bab: Qaulihi ﷺ: “Innamal a’malu bin-niyyah” (no. 1907).
[3]. HR Bukhari dalam kitab al-‘Ilm, Bab: Man Sa`ala wa Huwa Qaim (no. 123). Muslim dalam kitab al-Imarah, Bab: Man Qatala li Takuna Kalimatullahi Hiyal ‘Ulya (no. 1904).
[4]. HR Bukhari dalam kitab Bad’il Wahyi (no. 1), Muslim dalam kitab al-Imarah, Bab: Qaulihi ﷺ: “Innamal a’malu bin-niyyah” (no. 1907).
[5]. HR Muslim dalam Kitab al-Aqdhiyah, Bab: Naqdhil-Ahkamil-Bathilah, no. 1718.
[6]. HR Ahmad (5/267), Abu Dawud dalam kitab al-Washaya, Bab: Ma Ja`a fil-Washiyyati lil-Warits (no. 2870), Tirmidzi dalam kitab al-Washaya, Bab: La Washiyyata li Waritsin (no. 2121).
[7]. HR Tirmidzi, no. 1370.
[8]. HR Bukhari dalam kitab al-Aiman wan-Nuzur, Bab: an-Nadzr fith-Tha’ah, no. 6696.
Kaidah Ke-6: Hukum Asal Dalam Peribadahan Adalah Dilarang
Kaidah Keenam:
الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْحَظْرُ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ, وَاْلأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ اْلإِبَاحَةُ فَلاَ يَحْرُمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ
Hukum Asal Dalam Peribadahan Adalah Dilarang,Mmaka Tidak Disyariatkan Kecuali Yang Disyariatkan Oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Dan Hukum Asal Dalam Perkara Adat (budaya) aAalah Diperbolehkan, Sehingga Tidaklah Haram Kecuali Yang Diharamkan Oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.
Kaidah yang mulia ini mencakup dua kaidah penting. Imam Ahmad dan kalangan imam lainnya telah menyatakan kaidah ini. Dalil-dalil dari Alquran dan Hadis telah mendukungnya. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ berkaitan dengan eksistensi kaidah yang pertama:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
“Apakah mereka mempunyai Sembahan-Sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” [QS. asy-Syura/42: 21].
Dan berkaitan dengan eksistensi kaidah yang kedua Allah ﷻ berfirman:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” [QS. al-Baqarah/2: 29].
Maksudnya, Allah ﷻ telah menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat. Allah ﷻ menghalalkan secara keseluruhan kecuali yang ada larangannya di dalam syariat dikarenakan adanya unsur yang membahayakan manusia.
Demikian pula Allah ﷻ berfirman:
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat.” [QS. al-A’raf /7: 32].
Pada ayat tersebut, Allah ﷻ mengingkari perbuatan orang yang mengharamkan apa-apa yang telah Allah ﷻ ciptakan untuk para hambanya berupa makanan, minuman, pakaian, dan semisalnya.
Dalam hal ini, eksistensi kedua kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwa hakikat peribadahan adalah apa-apa yang telah Allah ﷻ perintahkan dengan perintah yang wajib ataupun sunnah. Maka setiap perkara yang diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, atau perkara yang sunnah, maka itu termasuk ibadah yang Allah ﷻ diibadahi dan ditaati dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang menyatakan tentang diwajibkannya atau disunnahkannya suatu perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh Al Kitab maupun As Sunnah, maka ia telah mengada-adakan perkara agama yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ, dan amalan tersebut tertolak atas pelakunya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
“Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan (ibadah) yang tidak berdasarkan perintah kami maka ia tertolak.” [1]
Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pula pada kaidah terdahulu bahwa syarat diterimanya amalan ibadah adalah bahwasannya amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas karena Allah ﷻ dan dilaksanakan sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.
Hendaknya diketahui pula bahwa perkara bidah yang diada-adakan dalam agama ini, ada yang jenisnya sama sekali tidak ada pensyariatannya dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Dan ada yang asalnya disyariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya dengan suatu sifat, waktu pelaksanaan, dan tempat tertentu, kemudian dilaksanakan tidak sesuai yang ketentuan tersebut.
Misalnya orang yang menyatakan tentang wajibnya melaksanakan suatu salat atau puasa tertentu tanpa adanya dalil yang menunjukkan tentang kewajibannya dari Alquran maupun As Sunnah. Atau seorang yang mengada-adakan perkara bidah dalam pelaksanaan Wuquf di Arafah. Atau menganjurkan untuk melempar jumrah di selain waktunya. Demikian pula orang yang menyatakan sunnahnya ibadah di suatu waktu atau tempat tertentu tanpa adaya petunjuk dari Allah ﷻ dan tidak ada dalilnya yang syari. Dan Allah ﷻ adalah Zat yang Maha Bijaksana kepada para hambanya, sehingga tidak ada hukum yang sesuai dengan manusia kecuali hukum-Nya dan tidak ada agama yang benar kecuali agama-Nya.
Adapun perkara adat, seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, perindustrian, dan semisalnya, maka asalnya diperbolehkan. Maka, barang siapa yang menyatakan haramnya suatu hal dari perkara-perkara tersebut, padahal Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mengharamkannya maka ia adalah seorang yang mengada-adakan perkara bidah. Perbuatan orang tersebut semisal dengan perbuatan orang-orang musyrik yang mengharamkan sebagian makanan yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.
Demikian pula perbuatan orang yang mengharamkan berbagai macam industri, serta penemuan-pememuan baru tanpa adanya dalil yang mengharamkannya. Maka orang yang melakukannya termasuk orang yang tersesat dan jahil.
Berkaitan dengan perkara adat ini, maka hal-hal yang haram darinya telah dirinci dalam Al Kitab dan As Sunnah. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
“…Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu,…. “ [QS. al- An’am/6: 119].
Dalam hal ini perlu dipahami, bahwa Allah ﷻ tidak mengharamkan sesuatu pun kecuali itu adalah sesuatu yang buruk dan membahayakan. Oleh karena itu, barang siapa yang meneliti perkara-perkara yang haram maka ia akan mendapati bahwa di dalamnya terkandung kejelekan dan bahaya baik untuk hati, badan, agama, maupun dunia.
Maka termasuk sebesar-besar nikmat Allah ﷻ adalah bahwa Allah ﷻ mengharamkan apa-apa yang menimbulkan madharat untuk kita. Dan termasuk nikmat-Nya yang terbesar adalah bahwa Allah ﷻ menghalalkan apa-apa yang menumbuhkan manfaat untuk kita.
Kedua kaidah ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Di mana dengan kaidah tersebut seseorang bisa mengetahui perkara-perkara bidah baik berkaitan dengan ibadah maupun adat. Maka barang siapa menyatakan tentang disyariatkannya suatu amalan ibadah padahal tidak ada tuntunannya di dalam syariat maka ia adalah seorang yang mengada-adakan perkara bidah. Dan barang siapa yang mengharamkan suatu perkara adat yang Allah ﷻ tidak mengharamkannya, maka ia adalah seorang pembuat perkara bidah pula.
_______
Footnote
[1]. HR Muslim dengan lafalh ini dalam kitab al-Aqdhiyah, Bab: Naqdhil Ahkamil-Bathilah, no. 1718. Dan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim dengan lafal:
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
“Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (berasal) darinya maka ia tertolak.” (Diriwayarkan oleh Bukhari dalam kitab ash-Shulh, Bab: Idza Ishthalahu ‘ala Amrin Jaur, no. 2697. Dan diriwayatkan Muslim di tempat tersebut di atas.
Kaidah Ke-7: Taklif Adalah Syarat Wajib Beribadah Adapun Tamyiiz Menjadi Syarat Sah Ibadah
Kaidah Ketujuh:
التَّكْلِيْفُ وَهُوَ الْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ الْعِبَادَاتِ, وَالتَّمْيِيْزُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا إِلاَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَصِحَّانِ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ, وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ الرُّشْدُ لِلتَّصَرُّفَاتِ, وَالْمِلْكُ لِلتَّبَرُّعَاتِ
Taklif yang memuat unsur baligh dan berakal adalah syarat wajib beribadah (atas seseorang, red). Adapun (usia) Tamyiiz menjadi syarat sah ibadah, kecuali dalam ibadah haji dan umrah yang tetap sah bila dilaksanakan oleh orang yang belum memasuki usia Tamyiiz. Selain syarat-syarat di atas, juga disyaratkan adanya sifat ar-Rusyd [1] dalam penggunaan harta (melakukan tasharruf) dan sifat kepemilikan untuk melakukan tabarru’.
Penjelasan Kaidah
Kaidah ini mencakup beberapa pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah, baik ibadah wajib maupun sunat, dan juga dasar pelaksanaan Akad Tasharruf (wewenang menggunakan harta dalam jual beli, sewa menyewa dsb.) dan Tabarru’ (menyumbangkan harta, pent).
Maksudnya, seseorang yang Mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal, telah terkena kewajiban untuk melaksanakan seluruh ibadah yang bersifat wajib, dan pundaknya telah terbebani dengan seluruh beban syariat.
Hal ini dikarenakan, Allah ﷻ Rauf Rahim (Zat yang Maha Santun dan Maha Penyayang terhadap hamba-Nya). Sebelum seorang insan mencapai usia dimana ia telah sanggup menjalankan ibadah-ibadah dengan sempurna, yaitu pada usia baligh, maka Allah ﷻ tidak membebankan beban-beban syariat kepadanya. Demikian pula, jika seseorang tidak memiliki akal (gila atau tidak sadar, red) – yang menjadi hakikat seorang insan-, maka ia lebih utama untuk tidak dikenai beban. Orang yang tidak memiliki akal, tidak berkewajiban melaksanakan ibadah apapun dan jika pun ia mengerjakannya, maka apa yang dilakukan tidak sah. Karena, ada di antara syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah yang tidak terpenuhi yaitu niat. Niat tidak mungkin terwujud dari orang yang tidak berakal.
Usia baligh dapat diketahui dengan beberapa tanda di antaranya dengan keluarnya air mani, baik dalam keadaan terbangun ataupun ketika tidur, atau jika telah genap berusia lima belas tahun, atau dengan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Ketiga tanda tersebut berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Dan khusus untuk perempuan ada satu tanda lagi yang menunjukkan dia telah baligh yaitu haid. Jika ia telah haid, berarti ia telah baligh.
Perlu diperhatikan, dalam perjalanan usianya, seorang manusia akan memasuki fase Tamyiz sebelum memasuki fase baligh. Seorang yang telah masuk fase Tamyiz (berusia tujuh tahun), maka ia diperintahkan untuk melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang mampu ia kerjakan. Ibadah-ibadah tersebut bukan berstatus wajib atas dirinya, karena ia belum baligh. Jika telah berusia sepuluh tahun, namun ia belum juga mau rutin dalam melaksanakan salat maka orang tuanya disyariatkan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, dalam kerangka pendidikan (dan pembinaan), bukan dalam kerangka sedang mewajibkan.
Dari sini dapat diketahui bahwa semua ibadah yang dikerjakan oleh anak-anak yang telah mencapai usia Tamyiz itu telah sah. Karena jika dia telah bisa membedakan beberapa hal serta secara global bisa mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, berarti ia memiliki akal yang bisa ia pakai untuk merangkai niat dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan.
Sedangkan anak yang belum sampai pada usia Tamyiz, maka semua ibadahnya tidak sah. Karena dalam kondisi seperti ini, ia sama dengan orang yang tidak berakal yang tidak mempunyai niat yang shahih. Kecuali dalam ibadah haji dan umrah. Kedua ibadah ini tetap sah, kendati dikerjakan oleh anak yang belum mencapai usia Tamyiz. Dalam sebuah hadis yang Shahih diterangkan:
رَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًا فِي الْمَهْدِ, فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
Seorang wanita mengangkat seorang anak kecil yang masih digedong kearah Rasulullah ﷺ, lalu ia bertanya: Bolehkah anak ini melaksanakan haji? Nabi ﷺ menjawab: Boleh, dan bagimu pahala. [2]
Dengan demikian anak yang belum mencapai usia Tamyiz, jika melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka ibadahnya sah. Dalam hal ini, walinya yang meniatkannya untuk ihram dan menjauhkannya dari perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Demikian pula, si wali harus membawa si anak untuk hadir di tempat-tempat manasik haji dan tempat-tempat masyair semuanya. Dan si wali mewakili si anak dalam mengerjakan manasik yang tidak mampu ia kerjakan seperti melempar jumrah.
Selain ibadah haji dan umrah, ibadah maliyyah termasuk ibadah yang diperkecualikan. Karena ibadah maliyah seperi membayar zakat, nafkah wajib serta Kaffarah adalah wajib atas semua orang; dewasa, anak kecil, yang berakal ataupun orang yang tidak berakal. Hal ini berdasarkan keumuman nash baik dari perkataan maupun perbuatan Nabi ﷺ. [3]
Adapun dalam masalah tasharruf (wewenang menggunakan harta untuk jual beli, sewa menyewa dsb.), maka disamping disyaratkan baligh dan berakal juga ditambah Rusyd. Karena tujuan utama dalam tasharruf ini adalah menjaga harta. Rusyd maksudnya orang tersebut mempunyai sifat bijak dalam penjagaan dan pemanfaatan harta tersebut serta memahami akad. Allah ﷻ berfirman:
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” [QS. an Nisa’/4: 6]
Dalam ayat ini, Allah ﷻ memberikan syarat kepada wali yang mengurusi anak yatim dalam menyerahkan harta kepada anak yatim tersebut, yaitu telah terpenuhi dua syarat pada anak yatim. Dua sifat itu adalah baligh dan Rusyd. Jika walinya masih ragu, apakah syarat Rusyd telah terpenuhi atau belum, maka Allah ﷻ memerintahkan untuk menguji kemampuan anak tersebut dalam menjaga dan membelanjakan harta. Jika anak tersebut ternyata telah mempunyai kemampuan yang baik, maka harta anak yatim yang ada dalam kekuasaan wali bisa diserahkan kepada si yatim. Namun jika belum, maka hartanya tetap ditahan (tetap berada di tangan wali, red) guna menghindarkannya dari penyia-nyiaan terhadap harta.
Dari sini dapat diketahui bahwa baligh, berakal dan mempunyai sifat Rusyd merupakan syarat sah melakukan semua bentuk muamalah (jual beli, sewa menyewa dan semisalnya). Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini maka semua muamalah yang dia lakukan tidak sah dan hendaklah dilarang dari melakukan muamalat.
Adapun masalah Tabarru’ (menyumbangkan harta) yaitu memberikan harta dengan tanpa imbalan, bisa berupa hibah, sedekah, wakaf, membebaskan budak, dan semisalnya, maka selain persyaratan baligh, berakal, dan Rusyd, orang yang berTabarru’ haruslah orang yang memiliki harta tersebut. Sehingga akadnya menjadi sah. Karena orang yang sekadar menjadi wakil dari pemilik harta, atau orang yang sekadar diberi wasiat, saksi wakaf, ataupun wali anak yatim dan wali orang gila, jika ia yang melakukan Tabarru’ dengan harta orang yang menjadi tanggungannya itu, akadnya tidak sah. Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.” [QS. al-An’am/6: 152]
Yaitu dengan cara yang baik untuk harta mereka, lebih menjaga dan lebih bermanfaat untuk harta mereka tersebut. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Penulis akan menerangkan maknanya di akhir pembahasan.
[2]. HR. Muslim dalam Kitabul Hajj bab Shihhatu Hajjis Shabiyyi, no. 1336, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhu.
[3]. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda:
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ….
“Tidak ada seorang pemilik emas ataupun perak yang tidak ia tunaikan hak yang wajib untuk ia bayarkan darinya (berupa zakat) kecuali pada Hari Kiamat nanti hartanya akan dijadikan lempengan-lempengan yang dipanaskan dalam Neraka untuk menyiksanya….” [HR. Muslim dalam Kitabuz Zakah bab Itsmi Mani’iz Zakah 2/680]
Kaidah Ke-8: Hukum Syari Tidak Akan Sempurna Kecuali Terpenuhi Syarat Dan Rukunnya
Kaidah Kedelapan:
الأَحْكَامُ اْلأُصُوْلِيَّةُ وَالْفُرُوْعِيَّةُ لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ: وُجُوْدُ شُرُوْطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا
Hukum-Hukum Syari, Baik Perkara Ushul (Pokok) Maupun Furu’ (Cabang) Tidak Akan Sempurna Kecuali Dengan Dua Hal: Terpenuhinya Syarat Dan Rukunnya Serta Tidak Adanya Mawani’ (Penghalang Akan Keabsahannya)
Kaidah agung ini mencakup permasalahan-permasalahan dalam syariat, baik yang bersifat ushul (permasalahan pokok) maupun furu’ (permasalahan cabang).
Di antara sisi manfaat terbesar kaidah ini bahwa kita banyak menjumpai nash-nash (dalil-dalil) memuat janji akan masuk Surga dan selamat dari Neraka dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu. Begitu juga banyak nash-nash yang berisi ancaman masuk Neraka, terhalang masuk Surga atau ancaman tidak bisa mendapatkan sebagian nikmat Surga. Untuk memahami nash-nash tersebut tidaklah cukup dengan melihat makna lahiriahnya (tekstual) semata (tanpa menghubungkannya dengan dalil dan kaidah-kaidah syari yang lain).
Demikian pula, nash-nash tentang ancaman bagi seseorang yang mengerjakan suatu larangan tertentu bahwa ia akan dimasukkan ke Neraka atau diharamkan masuk Surga atau diharamkan dari sebagian nikmat Surga, maka realisasi nash-nash itu pun harus dikaitkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disertai dengan tidak adanya mawani’ (faktor-faktor penghalangnya).
Dengan penjelasan tersebut maka terjawablah pertanyaaan dan masalah mengenai maksud banyak nash-nash yang memuat janji dan ancaman.
Oleh karena itu, jika ada yang berkata: “Telah disebutkan dalam syariat bahwa seseorang yang mengucapkan perkataan tertentu atau mengerjakan amal tertentu, maka ia akan dimasukkan ke dalam Surga. Apakah sudah cukup mengerjakan yang demikian itu bagi seseorang?”
Maka jawabannya adalah bahwa kita wajib mengimani seluruh nash dalam Alquran dan Hadis. Maka selain mengerjakan amal perbuatan yang menjadi sebab seseorang dijanjikan masuk Surga, harus pula disertai dengan keimanan, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang disyaratkan dalam syariat. Ditambah lagi, mawani’ (faktor-faktor penghalang) mesti nihil semisal murtad (keluar dari Islam) atau penghalang lain yang menghapuskan amal kebaikan.
Demikian pula jika seseorang berkata: “Allah ﷻ telah menyebutkan dalam kitab-Nya perihal balasan masuk Neraka kekal bagi orang yang membunuh seorang Mukmin secara sengaja, apakah pasti faktanya pasti demikian?
Maka jawabannya, bahwa perbuatan membunuh seorang Mukmin secara sengaja termasuk faktor penyebab yang mengharuskan si pelaku masuk Neraka kekal di dalamnya. Akan tetapi dalam hal ini, jika yang melakukannya adalah seorang Mukmin, maka dijumpai adanya penghalang pada dirinya (untuk kekal abadi di Neraka, red) yaitu keimanannya. Nash-nash tentang persoalan ini datang secara mutawatir (banyak sekali). Dan para ulama Salaf telah bersepakat bahwa orang yang mempunyai keimanan dan tauhid yang benar, maka ia tidak akan kekal abadi di Neraka jika ia masuk ke sana.
Atas dasar itu, nash-nash lain yang semisal dengannya, maka cara memahaminya adalah sebagaimana contoh di atas.
Bertolak dari kaidah ini pula Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan adakalanya terkumpul cabang keimanan dan cabang kekufuran atau kemunafikan pada diri seseorang. Dan terkadang cabang kebaikan dan cabang kejelekan berpadu pada dirinya. Adakalanya pula terkumpul antara perkara yang mendatangkan pahala dan perkara yang memunculkan azab dalam diri satu orang, berdasarkan nash-nash yang banyak tentang itu. Oleh karena itu, di waktu pemberian balasan amal, perhitungan amal dilakukan. Dan hal itu juga merupakan pengaruh dari sifat adil dan hikmah Allah ﷻ.
(Penerapan Kaidah):
– Termasuk pula dari penerapan kaidah ini adalah pelaksanaan ibadah salat.
Ibadah tersebut tidak sah sampai terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Serta tiadanya pembatal-pembatal salat dalam bentuk pengurangan baik syarat atau rukunnya tanpa alasan yang dibenarkan atau melakukan sesuatu yang membatalkan salat tersebut.
– Ibadah puasa.
Seseorang tidak sah puasanya kecuali dengan memenuhi seluruh perkara yang wajib dalam puasa tersebut, memenuhi syarat-syaratnya, dan tiadanya penghalang terhadap keabsahannya yaitu pembatal-pembatal puasa.
– Demikian pula haji dan umrah.
– Dan juga masalah jual-beli, serta seluruh muamalah (transaksi), aktifitas barter barang ataupun segala jenis Tabarru’ (pendonoran kekayaan). Semua perkara tersebut akan menjadi sah jika syarat-syaratnya terpenuhi dan hal-hal yang merusak dan membatalkannya tidak ada.
– Termasuk juga permasalahan warisan. Seseorang tidak bisa mendapatkan warisan jika tidak ada padanya faktor penyebab untuk memeroleh warisan, dan belum terpenuhinya syarat-syarat untuk itu. Demikian juga, pembagian warisan tidak dapat dilakukan kecuali telah diketahui tidak ada penghalang untuk menerimanya, seperti terdakwa sebagai pembunuh (orang yang akan diwarisi hartanya), berstatus sebagai budak, dan adanya perbedaan agama.
– Masalah nikah. Tidaklah sah suatu pernikahan sampai dipenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, serta tidak ada faktor penghalang keabsahan pernikahan tersebut.
– Demikian pula permasalahan had (penegakan hukum pidana)), pelaksanaan Qishash, dan hukum-hukum lainnya, haruslah syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan seluruh faktor penghalangnya tidak ada. Semua ini secara terperinci dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.
Kesimpulan:
Setiap ibadah, muamalah, ataupun akad yang tidak sah, maka hal itu disebabkan oleh salah satu dari dua kemungkinan, adakalanya disebabkan tidak terpenuhinya sesuatu yang harus ada di dalamnya atau karena adanya suatu penghalang khusus yang membatalkannya. Wallahu a’lam.
Kaidah Ke-9: Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat
Kaidah Kesembilan:
العُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ, وَلَمْ يَحُدَّهُ بِحَدٍّ
Urf dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat Yang Batasannya Tidak Ditentukan Secara Tegas
Kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam syariat, baik muamalat, penunaikan hak, dan yang lain. Karena penentuan hukum suatu perkara dalam syariat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu:
- Mengetahui batasan dan rincian perkara yang akan dihukumi.
- Penentuan hukum terhadap perkara tersebut sesuai ketentuan syari.
Apabila Allah ﷻ dan Rasul-Nya telah menentukan hukum sesuatu secara jelas, baik wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah, juga telah dijelaskan batasan dan rinciannya, maka kewajiban kita adalah berpegangan dengan rincian dari Allah ﷻ sebagai penentu syariat ini. Misalnya, dalam perintah salat, Allah ﷻ telah menjelaskan batasan-batasan dan rincian-rinciannya. Oleh karena itu, kita wajib berpegang dengan perincian ini. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, seperti zakat, puasa, dan haji, Allah ﷻ dan Rasul-Nya n telah menjelaskannya secara detail.
Sedangkan jika Allah ﷻ dan Rasul-Nya telah mensyariatkan sesuatu, sementara batasan dan penjelasan detailnya tidak disebutkan secara tegas, maka dalam masalah seperti ini, al-Urf (adat) dan kebiasan yang telah populer di tengah-tengah masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menentukan batasan dan rincian perkara tersebut.
Dalam mengembalikan batasan suatu perkara kepada adat kebiasaan tersebut, terkadang Allah ﷻ menyebutkannya secara langsung. Misalnya firman Allah ﷻ tentang perintah kepada para suami untuk memergauli istri dengan baik:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“Dan bergaullah dengan mereka dengan cara maruf.” [QS. an-Nisa’/4: 19]
Kata ‘maruf’’ (yang baik) dalam ayat tersebut mencakup sesuatu yang baik menurut syariat, juga yang baik menurut akal.
Demikian pula, firman Allah ﷻ:
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
“Dan perintahkanlah manusia untuk mengerjakan yang maruf.” [QS. al-A’raf/7: 199]
Dari sini kita dapat mengetahui, bahwa dalam perkara-perkara syari yang tidak ditentukan batasannya secara tegas dalam syariat, maka rincian batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah dikenal di tengah-tengah manusia. Penerapan kaidah yang mulia ini dapat dilihat pada contoh-contoh berikut:
- Perintah Allah ﷻ agar kita melakukan ihsan (berbuat baik) kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, dan ihsan kepada seluruh makhluk. Maka, segala sesuatu yang dianggap baik di masyarakat masuk dalam kandungan perintah ini. Karena Allah ﷻ menyebutkan kalimat ihsan secara mutlak (umum). Ihsan lawan kata dari isa’ah (berbuat jelek). Pengertian kata ihsan bahkan juga bertentangan segala upaya menahan kebaikan baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau harta.
Rasulullah ﷺ telah bersabda dalam hadis yang Shahih:
كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ
Setiap perkara yang maruf adalah sedekah. [1]
Hadis ini merupakan nash (dalil) tegas yang menunjukkan bahwa setiap ihsan (perbuatan baik) dan maruf yang dikerjakan seseorang itu adalah sedekah.
- Dalam setiap akad ataupun Tabarru’ (sumbangan), di antara syarat sahnya adalah keridaan dua belah pihak. Namun syariat tidak menentukan lafalh tertentu secara tegas untuk melakukan akad ini ataupun yang menunjukkan keridaan tersebut. Oleh karena syariat tidak menentukan lafalh tertentu, maka semua lafalh dan perbuatan yang menunjukkan bahwa telah terjadi akad dan keridaan dari kedua belah bisa digunakan dan akadnya sah. [2]
Namun, dalam hal ini para ulama mengecualikan beberapa masalah. Mereka mengharuskan adanya ucapan supaya akadnya sah, misalnya dalam akad nikah. Para ulama mengatakan: “Harus ada ucapan ijab (serah) dan qabul (terima) dalam akad nikah.” Demikian pula, dalam persoalan talak (perceraian). Talak tidak sah kecuali dengan ucapan atau tulisan si suami.
- Dalam akad-akad yang disyaratkan adanya qabdh (serah terima secara langsung). Pelaksanaan qabdh ini sesuai dengan adat kebiasaan yang ada dan bentuknya pun berbeda-beda. Bila dalam satu masyarakat tertentu, ada tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk serah terima secara langsung, maka itu bisa dijadikan pedoman dalam menjelaskan makna qabdh dan pelaksanaannya.
- Demikian pula tentang al-hirz (tempat penyimpanan harta yang layak). Seseorang yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta orang lain, ia wajib menyimpan dan menjaga harta yang diamanahkan kepadanya itu di tempat penyimpanan yang layak menurut kebiasaan masyarakat sekitarnya. Masing-masing harta mempunyai tempat penyimpanan yang layak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika ini sudah dilakukan, kemudian barang tersebut hilang atau dicuri, maka orang yang diberi amanah tidak wajib menggantinya. Ini berarti standar kelayakan itu mengikuti urf (adat kebiasaan setempat).
Namun jika orang yang mendapatkan amanah ini tidak hati-hati atau lalai dalam menjaga sehingga mengakibatkan barang yang diamanahkan kepadanya rusak atau hilang, maka ia wajib bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Dalam hal ini, untuk menentukan apakah ia hati-hati atau tidak, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Jika standar setempat menilai dia tidak hati-hati, maka dia wajib mengganti. Namun jika dinilai sudah berhati-hati, maka tidak wajib mengganti.
- Orang yang mendapatkan Luqathah (barang temuan), ia wajib mengumumkan barang temuannya selama setahun untuk mencari pemiliknya. Cara mengumumkannya, disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Apabila telah diumumkan selama satu tahun, namun tidak juga diketahui pemiliknya, maka barang tersebut menjadi hak milik si penemu.
- Mengenai wakaf, maka penggunaan harta yang diwakafkan itu dikembalikan kepada syarat dan ketentuan dari orang yang mewakafkan, selama tidak menyelisihi syariat. Namun, jika syarat dan ketentuan tersebut tidak diketahui oleh orang yang mewakafkan, maka penggunaannya disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.
- Secara hukum asal, kepemilikan suatu barang ditetapkan berdasarkan kenyataan keberadaan barang tersebut. Apabila barang tersebut secara nyata berada di tangan seseorang, maka barang tersebut ditentukan sebagai miliknya, kecuali jika ada bukti yang memalingkan dari hukum asal tersebut.
- Perintah untuk memberikan nafkah kepada istri, sanak kerabat, hamba sahaya, pekerja, dan semisalnya secara maruf. Allah ﷻ dan Rasul-Nya telah menyebutkan secara tegas untuk kembali kepada Urf (adat kebiasaan masyarakat setempat) dalam muasyarah (memergauli) istri secara baik. [3] Makna muasyarah lebih umum daripada memberikan nafkah. Karena muasyarah mencakup seluruh urusan yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, baik dengan perkataan, perbuatan, dan lainnya. Dan semua itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.
- Seorang wanita yang mengalami istihadhah (mengeluarkan darah penyakit-red), tapi tidak bisa membedakan antara darah istihadhah dengan darah haidnya, maka ia menentukan lama haidnya sesuai kebiasaan sebelum mengalami istihadhah. Namun, jika ia tidak mengetahui kebiasaan haidnya sebelum mengalami istihadhah karena lupa atau alasan lainnya, maka ia menentukan lama waktunya sesuai dengan kebiasaan haid wanita di keluarganya, kemudian juga kebiasaan wanita di daerahnya.
- Keberadaan aib (cacat dalam barang dagangan), ghabn (menjual atau membeli dengan harga yang jauh dari harga pasar umumnya), dan tadlis (menutupi cacat yang ada pada barang dagangan). Batasan dalam semua masalah ini dikembalikan kepada Urf. Kapan saja suatu kondisi dianggap mengandung unsur aib, ghabn, atau tadlis dalam adat kebiasaan masyarakat, maka berlakulah hukum yang terkait dengannya.
- Dalam satu pernikahan yang maharnya tidak disebutkan secara jelas, atau disebutkan namun fasid (tidak sesuai ketentuan syari), maka penentuan maharnya dikembalikan kepada mahrul mitsl (standar mahar yang berlaku secara umum di masyarakat setempat). Nilai mahar tersebut sesuai dengan perbedaan wanita, perbedaan waktu, dan perbedaan tempat.
Contoh-contoh penerapan kaidah di atas sangat banyak dan bisa dilihat dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para ulama. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. HR. al-Bukhari no. 6021 dan Muslim no. 1005.
[2]. Dalam al-Ikhtiyarat, hlm. 121, Syaikhul Islam t berkata: Setiap ucapan ataupun perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan manusia menunjukkan akad jual beli atau hibah, maka jual beli atau hibah ini sah dengan ucapan dan perbuatan tersebut. (al-Ikhtiyarat, hlm. 121)
[3]. Di antaranya firman Allah ﷻ dalam surat an-Nisa’: 19. Dan berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda kepada Hindun radhiyallahu anha:
خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ
“Ambillah (dari harta tersebut) untuk memenuhi kebutuhan dirimu dan anakmu sesuai yang maruf.” [HR. Bukhari dalam Kitab al-Buyu’, Bab Man Ajra Amral Amshari ‘ala Ma Yata’arafan…., No. 2211. Muslim dalam Kitab al- Aqdhiyah, Bab Qadhiyyatu Hindin, No. 1714]
Kaidah Ke-10: Bukti Wajib Didatangkan Oleh Orang yang Menuduh
Kaidah Kesepuluh:
البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فِي جَمِيْعِ الْحُقُوْقِ, وَالدَّعَاوَى, وَنَحْوِهَا
Bukti Wajib Didatangkan Oleh Orang yang Menuduh, Dan Sumpah Itu Wajib Bagi Yang Mengingkari Tuduhan Itu, Hal Ini Berlaku Dalam Seluruh Persengketaan Hak, Tuntutan, Dan Semisalnya
Kaidah yang mulia ini telah disebutkan oleh Nabi ﷺ dalam salah satu sabdanya. Di mana beliau ﷺ bersabda:
البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُنْكِرِ
“Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari tunduhan itu.” [HR. Baihaqi dengan sanad Shahih dan asal hadis ini ada dalam As Shahihain]. [1]
Para ahli ilmu telah bersepakat tentang eksistensi kaidah ini. Di mana kaidah ini sangat dibutuhkan oleh para Qadhi (hakim), mufti (pemberi Fatwa), dan dibutuhkan pula oleh setiap orang.
Allah ﷻ berfirman:
وَآَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
“Dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.” [QS. Shad/38: 20]
Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fashlul khithab (kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan) dalam ayat tersebut adalah kaidah: ” Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh, dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari tunduhan itu.” Penerapan kaidah ini mengharuskan terlepasnya perkara-perkara yang samar dan terurainya seluruh persengketaan. Maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu termasuk dalam kategori fashlul khithab. Karena fashlul khithab memiliki makna yang lebih luas dari makna yang terkandung dalam kaidah tersebut.
Barang siapa yang meng-klaim bahwa barang yang ada di tangan orang lain adalah miliknya, atau meng-klaim bahwa orang lain punya utang darinya, atau menyatakan bahwa orang lain mempunyai kewajiban yang harus ia tunaikan kepadanya, maka ia harus mendatangkan bukti atas tuntutannya tersebut.
Adapun yang dimaksud dengan bukti adalah setiap hal yang menunjukkan benarnya tuntutan orang tersebut. Yang mana, kadar bukti tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan perkara yang dipersengketakan.
Apabila orang yang menuntut atau menuduh itu tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituntut diperintahkan untuk bersumpah dalam rangka menolak tuduhan tersebut.
Demikian pula, jika telah tetap adanya suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang, berupa utang yang harus ia bayar atau selainnya, kemudian ia meng-klaim bahwa kewajiban tersebut telah ia tunaikan atau telah ia lunasi, maka secara asal kewajiban tersebut masih ada dalam tanggungannya kecuali jika ia bisa mendatangkan bukti bahwa kewajibannya tersebut telah ia lunasi. Adapun jika ia tidak bisa mendatangkan bukti, maka cukuplah bagi orang yang berhak menerima pelunasan kewajiban tersebut untuk menyatakan sumpah bahwasannya orang tersebut belum menunaikan kewajibannya, dan keputusan hukum berpihak kepada si penerima hak itu.
Berkaitan dengan orang yang meng-klaim bahwa dirinya berhak untuk memeroleh bagian dalam wakaf atau warisan tertentu, maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti yang memastikan bahwa ia memang benar-benar berhak mendapatkan bagian tersebut. Apabila ia tidak bisa mendatangkan bukti tersebut maka ia tidaklah berhak menerima bagian dari wakaf atau warisan tersebut.
Adapun yang dimaksud dengan Bayyinah (bukti) dalam persengketaan harta, hak-hak, serta kesepakatan-kesepakatan, adakalanya terdiri atas dua orang laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah si penuntut, atau dakwaan si penuntut dan ketidaksediaan si tertuntut untuk mengucapkan sumpah.
Dalam hal ini, jika harta yang diperkarakan tersebut berada di tangan orang yang tidak meng-klaim harta tersebut sebagai miliknya, maka bukti si penuntut adalah pensifatan atau ( penggambaran )nya terhadap barang tersebut dengan sifat yang sesuai. Misalnya, ada seseorang yang menemukan Luqathah (barang temuan). Kemudian setelah berselang beberapa waktu datanglah kepadanya seseorang yang mendakwakan mengaku bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, maka, orang yang meng-klaim tersebut harus mendatangkan bukti kebenarannya dengan menyebutkan sifat barang tersebut secara tepat. Maka, pensifatan (penggambaran) merupakan bukti dalam dakwaan jika pemegang harta tersebut tidak menganggap harta itu sebagai miliknya. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. HR. Bukhari dalam Kitab At Tafsir, Bab ( …إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ ) No. 4552. Muslim dalam Kitab Al Aqdhiyah, Bab Al Yamin ‘ala Al Mudda’a ‘alaihi, No. 1771, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma. Lafal hadis ini menurut Riwayat Muslim adalah:
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ, وَلَكِنِ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
“Apabila setiap manusia diberikan semua tuntutan-tuntutannya, maka mereka akan menuntut darah dan harta. Akan tetapi sumpah itulah yang wajib bagi yang dituntut.”
Kaidah Ke-11: Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula
Kaidah Kesebelas:
اْلأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ, وَالْيَقِيْنُ لاَ يَزُوْلُ بِالشَّكِّ
Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula, Dan Keyakinan Tidak Bisa Hilang Karena Keraguan
Kaidah yang agung ini telah ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ dalam salah satu hadis Shahih. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ untuk mengadukan keadaan yang dirasakannya sewaktu salat. Laki-laki itu merasakan sesuatu di perutnya seolah-olah telah berhadats, sehingga ia ragu-ragu apakah telah berhadats ataukah belum. Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadanya:
لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيْحًا
“Janganlah keluar dari salat sehingga engkau mendengar suara atau mendapatkan baunya.” [1]
Yaitu, janganlah ia keluar (berhenti -red) dari salatnya disebabkan apa yang ia rasakan di perutnya tersebut, sampai benar-benar ia yakin telah berhadats.
Oleh karena itu, seseorang yang yakin terhadap suatu perkara tertentu, maka asalnya perkara yang diyakini tersebut tetap dalam keadaannya semula. Dan perkara yang diyakini tersebut tidaklah bisa dihilangkan hanya sekadar karena keragu-raguan.
Adapun penerapan kaidah yang mulia ini dapat diketahui dari contoh-contoh berikut:
- Seseorang yang yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci (tidak berhadats) kemudian muncul dalam benaknya keraguan apakah ia telah berhadats ataukah belum, maka asalnya ia masih dalam keadaaan suci, sampai ia yakin bahwa ia memang telah berhadats. Demikian pula, seseorang yang yakin bahwa ia dalam keadaan berhadats kemudian ragu-ragu apakah ia sudah bersuci ataukah belum maka asalnya ia tetap dalam keadaan berhadats.
- Seseorang yang ragu-ragu terhadap air yang ada dalam suatu wadah, apakah air tersebut masih suci ataukah tidak, maka ia mengembalikan pada hukum asalnya, yaitu hukum asal air adalah suci (tidak najis), sampai muncul keyakinan bahwa air tersebut memang telah berubah menjadi tidak suci lagi karena terkena najis. Demikian pula, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Maka kapan saja seseorang ragu-ragu tentang kesucian air, baju, tempat, bejana, atau selainya maka ia menghukuminya dengan hukum asal tersebut, yaitu asalnya suci. Oleh karena itu, jika seseorang terkena air dari suatu saluran air, atau menginjak suatu benda basah, padahal ia tidak mengetahui apakah benda tersebut suci ataukah tidak, maka asalnya benda tersebut adalah suci (tidak najis).
- Apabila seseorang ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam salatnya, apakah sudah dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka ia berpedoman pada keyakinannya, yaitu ia mengembalikan kepada jumlah rakaat yang lebih sedikit, kemudian ia melakukan sujud sahwi di akhir salat.
- Seseorang yang sedang melaksanakan Thawaf di Baitullah, jika ia menemui keraguan tentang jumlah putaran yang telah ia lakukan, maka ia menentukan sesuai yang ia yakini, yaitu ia kembali pada jumlah yang paling sedikit. Demikian pula seseorang yang ragu-ragu ketika melaksanakan Sai.
- Seseorang yang ragu-ragu tentang jumlah basuhan ketika berwudhu, mandi wajib atau selainnya, maka ia berpedoman kepada keyakinan sebelumnya, yaitu kembali pada jumlah basuhan yang terkecil.
- Seorang suami yang ragu-ragu, apakah telah mentalak istrinya ataukah belum, maka asalnya ia belum mentalak istrinya. Dikarenakan hubungan suami istri sejak semula telah terjalin dengan keyakinan, maka hubungan tersebut tidaklah terputus hanya sekadar karena keraguan.
- Seorang suami yang ragu-ragu tentang jumlah talak yang telah ia ucapkan kepada istrinya, maka ia mengambil jumlah yang paling sedikit.
- Apabila seseorang mempunyai tanggungan untuk mengqadha salat yang ditinggalkannya karena uzur, kemudian ia ragu-ragu tentang berapa jumlah salat yang ditinggalkannya, maka ia melaksanakan salat sehingga muncul keyakinan bahwa tanggungannya telah ditunaikan. Hal ini karena kewajiban mengqadha salat telah tetap atasnya, sehingga kewajiban itu tidaklah lepas dari tanggungannya kecuali dengan keyakinan. Demikian pula jika ia mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasa.
- Apabila seorang wanita ragu-ragu apakah ia telah keluar dari masa iddahnya ataukah belum, maka asalnya ia masih tetap dalam masa iddah.
- Jika timbul keraguan tentang jumlah susuan yang mengkonsekuensikan hubungan mahram antara anak susuan dengan ibu susuannya, apakah sudah lima kali susuan ataukah belum, maka yang dijadikan patokan adalah jumlah yang terkecil, sampai muncul keyakinan bahwa jumlah susuan sudah mencapai lima kali.
- Jika seseorang melempar binatang buruan (dengan tombak, panah atau senjata lainnya) dengan menyebut nama Allah k terlebih dahulu, kemudian setelah beberapa waktu ia menemukan binatang itu mati terkena senjatanya, namun ia lalu ragu-ragu apakah binatang itu mati karena lemparan senjatanya ataukah karena sebab yang lain, maka asalnya binatang tersebut halal untuk dikonsumsi (bukan bangkai). Karena pada asalnya tidak ada sebab lain yang mengakibatkan kematian binatang tersebut, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang Shahih. [2]
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita ragukan keberadaannya, maka hal tersebut asalnya tidak ada. Dan segala sesuatu yang kita ragukan jumlahnya maka asalnya kita kembalikan pada bilangan yang terkecil.
Banyak sekali contoh permasalahan yang masuk dalam kaidah ini. Jika kita mau mencermati dan meneliti pembahasan dalam kitab-kitab fikih, maka kita akan mengetahui betapa besar manfaat kaidah ini. Sebagaimana kita juga akan mengetahui manfaat yang besar dari kaidah-kaidah fikih lainnya yang mengumpulkan berbagai permasalahan yang serupa dan menghukuminya dengan hukum yang sama.
Apabila seseorang menguasai kaidah-kaidah fikih tersebut, maka ia akan memiliki kemampuan untuk mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada pokoknya dan menggabungkan perkara-perkara ke dalam kaidah yang sesuai. Wallahu al Muwaffiq.
_______
Footnote
[1]. HR. Bukhari dalam Kitab Al-Wudhu’ Bab La yatawaddha’ min as-syak, No. 137. Muslim dalam Kitab al-Haidh, Bab Al-wudhu’ min luhumi al-ibil, No. 361 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu
[2]. HR. Bukhari dalam Kitab adz-Dzaba-ih, Bab as-Shaidu idza ghaba ‘anhu yaumaini…., No. 5484. Muslim dalam Kitab as-Shaid, Bab As-Shaid fi al-kilabi al-mu’allamah, No. 1929 dari Adi bin Hatim.
Kaidah Ke-12: Harus Ada Saling Rida Dalam Setiap Akad
Kaidah Kedua Belas:
لاَ بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيْعِ عُقُوْدِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُوْدِ التَّبَرُّعَاتِ
Harus Ada Saling Rida Dalam Setiap Akad Yang Sifatnya Mu’awadhah (Bisnis) Ataupun Tabarru’ (Sumbangan)
Kaidah ini telah ditunjukkan oleh Alquran, Sunnah, dan Ijma. Allah ﷻ telah berfirman berkaitan dengan akad mu’awadhah:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” [QS. an-Nisa’/4:29]
Dalam ayat tersebut Allah ﷻ mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah ﷻ menghalalkan tijarah (perniagaan), yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memeroleh penghasilan dan keuntungan. Allah ﷻ mensyaratkan adanya saling rida antara orang-orang yang melakukan akad dalam perniagaan tersebut.
Dengan demikian, dalam segala bentuk pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa, perkongsian dagang dan semisalnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling rida.
Allah ﷻ berfirman berkaitan dengan akad Tabarru’ (sumbangan tanpa mengharapkan keuntungan):
وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” [QS. an-Nisa’/4:4]
Dalam ayat di atas Allah ﷻ menjelaskan bahwa pemberian seorang istri berupa sebagian mahar kepada suaminya, hal itu diperbolehkan dengan syarat dilandasi kerelaan hati dari sang istri, yaitu adanya keridaan darinya. Pemberian seorang istri kepada suaminya tersebut termasuk akad Tabarru’ karena hal itu dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan.
Maka seluruh akad Tabarru’ mempunyai hukum yang sama dengan permasalahan mahar tersebut. Di mana dalam akad tersebut disyaratkan adanya saling rida dari orang-orang yang melaksanakan akad.
Seluruh akad, baik mu’awadhah ataupun Tabarru’ tidaklah sempurna kecuali disertai saling rida antara orang-orang yang melaksanakan akad tersebut. Hal ini disebabkan akad-akad tersebut mengkonsekuensikan perpindahan kepemilikan dan hak dari satu pihak kepada pihak yang lain atau merubah suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kesemuanya itu mengharuskan adanya saling rida. Maka, barang siapa yang dipaksa untuk melaksanakan suatu akad, atau membatalkannya tanpa alasan yang haq, maka akad atau pembatalan akad tersebut tidaklah sah. Keberadaannya sama seperti ketidak-adaannya.
Namun demikian, ada beberapa pemasalahan yang dikecualikan dari kaidah yang bersifat umum ini. Contohnya adalah seseorang yang dipaksa untuk melaksanakan suatu akad tertentu atau membatalkan suatu akad dengan paksaan yang sifatnya haq, maka hal tersebut diperbolehkan. Kaidah dalam masalah ini adalah barang siapa yang menolak menunaikan kewajiban yang harus ia tunaikan, kemudian ia dipaksa untuk menunaikannya maka ia dipaksa dengan haq. Implementasinya dapat diketahui dengan beberapa contoh berikut:
- Apabila seseorang dipaksa oleh Qadhi (hakim) untuk menjual sebagian hartanya supaya bisa melunasi utangnya, maka ini adalah pemaksaan yang diperbolehkan dan termasuk pemaksaan yang haq. Demikian pula jika seseorang dipaksa untuk membeli barang-barang untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib ia nafkahi, maka ini pun termasuk pemaksaan yang haq.
- Jika ada dua orang yang berserikat dalam kepemilikan suatu barang, kemudian salah satu dari keduanya berkeinginan untuk memiliki sendiri bagiannya dari barang tersebut, sedangkan barang tersebut tidak bisa dibagi secara langsung kecuali dengan dijual terlebih dahulu, [1] maka apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak setuju untuk menjual barang yang diserikatkan, diperbolehkan bagi Qadhi (hakim) untuk memaksannya menjual barang tersebut.
- Seseorang yang secara syari wajib menceraikan istrinya disebabkan sesuatu hal yang mewajibkan adanya percerain antara keduanya, kemudian si suami tersebut menolak untuk menceraikan istrinya, maka ia dipaksa oleh Qadhi (hakim) untuk menceraikan istrinya.
- Seseorang yang secara syari wajib untuk membebaskan budaknya untuk membayar Kaffarah (denda) atau nadzar (sumpah) yang wajib ia tunaikan, kemudian ia menolak untuk membebaskan budaknya tersebut, maka ia dipaksa untuk membebaskan budaknya. Pemaksaan dalam kasus seperti ini termasuk pemaksaan yang haq. Wallahu a’lam.
Footnote
[1]. Misalnya adalah dua orang yang berserikat dalam kepemilikan seekor unta. Unta tersebut tidak mungkin dibagi secara langsung kepada kedua pemiliknya karena akan timbul suatu madharat. Maka apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memiliki sendiri bagiannya dari unta tersebut, haruslah unta tersebut dijual terlebih dahulu, barulah kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing. (Pent.)
Kaidah Ke-13: Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama
Kaidah Ketiga Belas:
الإِتْلاَفُ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْمُتَعَمِّدُ وَالْجَاهِلُ وَالنَّاسِيْ
Perbuatan Merusakkan Barang Orang Lain Hukumnya Sama, Apakah Terjadi Karena Kesengajaan, Ketidak Tahuan, Atau Karena Lupa
Kaidah ini memberikan patokan dalam perbuatan seseorang yang melakukan perusakan, baik kepada jiwa ataupun harta orang lain. Kaidah ini juga menjelaskan bahwa barang siapa yang merusakkan barang orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti barang yang ia rusakkan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta. Sama saja, apakah kerusakan tersebut terjadi karena kesengajaan olehnya, atau karena tidak tahu, atau karena lupa.
Maka kewajiban mengganti barang atau membayar ganti rugi tersebut tidaklah terbatas pada perusakan yang dilakukan dengan sengaja. Bahkan kewajiban terebut tetap berlaku meskipun perbuatan perusakan dilakukan tanpa kesengajaan, atau ketidak tahuan, atau karena lupa. Oleh karena itulah Allah ﷻ mewajibkan pembayaran Diyat (ganti rugi) dalam pembunuhan yang terjadi karena khatha’ (tersalah).
Adapun sisi perbedaan antara perusakan yang dilakukan secara sengaja dengan yang dilakukan tanpa kesengajaan adalah ada tidaknya dosa sebagai akibat perbuatan tersebut. Seseorang yang melakukan perusakan dengan sengaja, tentulah mendapatkan dosa, berbeda dengan orang yang melakukannya dengan tanpa kesengajaan atau ketidak tahuan.
Beberapa contoh penerapan kaidah tersebut adalah:
- Seseorang yang melepaskan hewan piaraannya, kemudian hewan itu merusak harta orang lain atau memakan tanaman orang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada pemilik harta atau pemilik tanaman, meskipun kerusakan terjadi bukan karena kesengajaan darinya.
- Seseorang yang melepaskan hewan piaraannya yang biasa menyerang manusia, kemudian hewan itu menyerang manusia di pasar-pasar atau di tempat-tempat lain, maka ia wajib membayar ganti rugi. Bahkan hal itu bisa dikategorkan sebagai perbuatan merusak yang dilakukan secara sengaja.
- Seseorang yang sedang ihram dalam ibadah haji atau umrah dilarang untuk membunuh shaid (binatang buruan). Apabila ia membunuh binatang buruan maka wajib baginya untuk membayar jaza’ (denda). Sama saja apakah ia membunuhnya dengan sengaja atau tidak. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama, termasuk empat imam madzhab. [1]
Namun demikian, dalam masalah ini masih ada perbedaan pendapat. Di mana sebagian ulama lain berpendapat bahwa kewajiban membayar denda tersebut wajib bagi orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja. [2] Berdasarkan firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” [QS. al-Maidah/5:95]
Pendapat kedua inilah yang lebih tepat. Karena sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat di atas. Adapun yang membedakan kasus ini dengan contoh-contoh sebelumnya adalah bahwa hal ini berkaitan dengan hak Allah ﷻ. Yaitu bahwa hukuman atas pelanggaran terhadap hak Allah ﷻ terkait dengan niat orang yang melanggar. Berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Lihat: Badai’us Shana-i’ 2/188, 195, dan 201. Al-Bahrur Ra-iq 3/13. Mawahibul Jalil 3/154. Hasyiyatud Dasuqi 2/52. Al-Majmu’ 7/342. Nihayatul Muhtaj 2/452. Al-Furu’ 3/462. Al-Inshaf 3/527-528.
[2]. Ini adalah salah satu pendaat dalam Madzhab Hambali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Hazm (I’lamul Muwaqqi’in 2/50, Al-Furu’ 3/463, Al-Inshaf 3/528, Al-Muhalla 7/214)
Kaidah Ke-14: Kerusakan Barang Di Tangan Orang Yang Diberi Amanah
Kaidah Keempat Belas:
التَّلَفُ فِي يَدِ اْلأَمِيْنِ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطْ, وَفِي يَدِ الظَّالِمِ مَضْمُوْنٌ مُطْلَقًا
Kerusakan Barang Di Tangan Orang Yang Diberi Amanah Tidak Mengharuskan Pembayaran Ganti Rugi Jika Ia Tidak Melanggar Atau Melalaikan. Dan Wajib Membayar Ganti Rugi Secara Mutlak Jika Barang Tersebut Rusak Di Tangan Orang Yang Zalim
Kaidah ini menjelaskan perbedaan antara harta yang ada di tangan al-amin (orang yang diberi amanat) dengan harta yang ada di tangan orang yang zalim. Yaitu tentang ada tidaknya kewajiban mengganti harta tersebut jika mengalami kerusakan di tangannya.
Al-amin adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk membawa harta orang lain dengan izin pemiliknya, atau dengan izin syariat, atau dengan izin wali pemilik harta tersebut.
Di antara yang masuk dalam kategori Al-Amin adalah:
- Al-wadi’ (orang yang dititipi barang)
- Al-wakil (orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk memperdagangkan sejumlah harta, menyewakannya, atau bentuk tasharruf (aktivitas yang lain)
- Al-murtahin (pembawa barang gadaian)
- Al-ajir (penyewa barang)
- Asy-syarik (salah satu dari para pemilik suatu barang yang dimiliki secara bersama)
- Al-mudhArab (orang yang dipercaya oleh pemilik barang untuk memperdagangkannya, dengan memeroleh bagi hasil dari laba yang diperoleh)
- Al-multaqith (orang yang mendapatkan barang temuan)
- Nazhir wakaf (yang ditugaskan mengelola wakaf)
- Pengurus anak yatim
- Pengurus orang majnun (gila)
- Pengurus orang yang kurang akal
- Al-washiy (orang yang mendapatkan wasiat untuk melakukan tasharruf terhadap harta tertentu setelah pemiliknya meninggal)
- Aminul Hakim (orang yang mendapatkan kepercayaan dari hakim)
Orang-orang yang mempunyai status sebagai al-amin tersebut tidak dibebani kewajiban untuk mengganti atau menanggung ganti rugi jika barang yang diamanahkan kepadanya rusak. Yang demikian ini merupakan konsekuensi amanah yang telah ia pikul dalam membawa dan menjaga harta tersebut. Kerusakan barang yang terjadi di tangannya itu seolah-olah terjadi di tangan pemiliknya.
Namun demikian jika kerusakan itu terjadi karena ta’addi (pelanggaran terhadap harta) atau tafrith (melalaikan penjagaan harta); maka dalam hal ini ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi tersebut.
Adapun perbedaan antara ta’addi dan tafrith adalah bahwa ta’addi merupakan tindakan mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap harta yang diamanahkan, berupa memanfaatkan atau melakukan tasharruf terhadap harta tersebut. Adapun yang dimaksud dengan tafrith adalah meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia kerjakan terhadap harta yang diamanahkan, yaitu melalaikan penjagaan terhadap harta tersebut.
Apabila harta tersebut rusak dikarenakan ta’addi atau tafrith dari orang yang diserahi amanah tersebut, maka ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut.
Berkaitan dengan penerapan kaidah ini, para ulama berbeda pendapat tentang harta yang rusak di tangan musta’ir (peminjam barang). Banyak ahli ilmu yang berpendapat bahwa jika barang yang dipinjam mengalami kerusakan di tangan peminjam, maka ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi secara mutlak, baik kerusakan tersebut terjadi karena ta’addi atau tafrith, ataukah tidak. Dan inilah pendapat yang masyhur dalam Madzhab Hambali. [1]
Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa seseorang yang menerima pinjaman dari orang lain, maka ia termasuk dalam kategori orang yang menerima amanat. Apabila barang yang ia pinjam tersebut rusak di tangannya, maka ia tidak wajib mengganti atau membayar ganti rugi, kecuali jika kerusakan itu terjadi karena ta’addi atau tafrith darinya. Dan inilah pendapat yang benar. Wallahu a’lam. [2]
Adapun orang yang membawa harta atau benda orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi kepada pemilik harta tersebut secara mutlak apabila harta tersebut mengalami kerusakan di tangannya. Sama saja apakah kerusakan itu terjadi karena ta’addi, atau tafrith, ataukah tidak. Yang demikian ini dikarenakan ia telah melakukan pelanggaran secara zalim kepada hak milik orang lain.
Di antara yang masuk dalam kategori ini adalah:
- Orang yang melakukan ghashab (menggunakan barang orang lain tanpa izin pemiliknya).
- Orang yang khianat dalam amanah yang diembankan kepadanya.
- Orang yang menolak untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya kepada pemilik harta tersebut tanpa alasan yang benar.
- Penemu Luqathah (barang temuan), kemudian ia tidak mau mengumumkan penemuan barang tersebut.
- Orang yang di rumahnya mendapatkan suatu harta atau benda milik tetangganya kemudian ia tidak mau mengembalikannya atau tidak mau mengkhabarkan kepada tetangganya tersebut tanpa alasan yang benar. Maka orang yang masuk dalam kategori ini wajib secara mutlak untuk mengganti atau membayar ganti rugi, jika harta atau benda tersebut mengalami kerusakan di tangannya. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Bidayatul Mujtahid 2/313. Al-Umm 3/250. Masa-il Ahmad libnihi `Abdillah hal. 308. Al-Furu’ 4/474.
[2]. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyyah. (Al-Mabshuth 11/134. Bada-i’us Shana-i’ 6/117)
Kaidah Ke-15: Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan
Kaidah Kelima Belas:
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain
Kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafal sabda Nabi ﷺ dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” [1]
Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syariat ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Dan semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsan, seperti karib kerabat, istri, tetangga, dan semisalnya.
Di antara penerapan kaidah ini adalah:
- Seseorang dilarang menggunakan barang miliknya jika hal itu menimbulkan madharat (gangguan atau bahaya) kepada tetangganya. Meskipun ia mempunyai hak milik secara penuh terhadap barang tersebut, namun dalam pemanfaatannya haruslah diperhatikan supaya tidak memadharatkan, mengganggu, ataupun merugikan tetangganya.
- Tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan kaum Muslimin, di pasar-pasar mereka, ataupun di tempat-tempat kaum Muslimin yang lain. Baik gangguan itu berupa kayu atau batu yang menggangu perjalanan, atau lobang galian yang bisa membahayakan, atau bentuk gangguan lainnya. Karena semuanya itu bisa menimbulkan madharat kepada kaum Muslimin. [2]
- Di antara bentuk dharar yang paling besar adalah jika seorang suami menimbulkan madharat kepada istrinya dan menjadikannya merasa susah, dengan tujuan supaya si istri minta diceraikan, sehingga si suami bisa mengambil harta dari si istri sebagai konsekuensi permintaan cerainya. Ini termasuk perbuatan dharar yang paling besar. Allah ﷻ berfirman:
وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” [QS. ath-Thalaq/65:6]
Dan Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” [QS. al-Baqarah/2:231]
- Masing-masing pihak dari pasangan suami istri dilarang menimbulkan madharat kepada yang lain, berkaitan dengan anak mereka berdua. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.” [QS. al-Baqarah/2:233]
- Larangan menimbulkan madharat dalam akad utang piutang, baik dari sisi orang yang berutang, penulis akad, ataupun saksinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ
“Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan.” [QS. al-Baqarah/2:282]
Kata kerja يُضَارَّ pada ayat di atas ada kemungkinan berbentuk kata kerja aktif, sehingga bermakna ‘mempersulit’. Dengan demikian makna ayat tersebut adalah bahwa saksi dan penulis akad dilarang menimbulkan madharat kepada pemilik hak (pengutang) dengan mempersulit kepadanya.
Dan ada kemungkinan kata kerja يُضَارَّ tersebut berbentuk kata kerja pasif sehingga bermakna ‘dipersulit’. Dengan demikian makna ayat tersebut adalah bahwa pemilik hak dilarang menimbulkan madharat kepada saksi dan penulis akad dengan mempersulit keduanya. Kedua kemungkinan tersebut sama-sama mempunyai makna yang benar.
- Seseorang yang mewariskan hartanya dilarang merugikan sebagian dari ahli warisnya. Demikian pula orang yang memberikan wasiat dilarang menimbulkan madharat kepada orang yang diberikan wasiat. Allah ﷻ berfirman:
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
“Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).” [QS. an-Nisa’/4:12]
Dengan demikian setiap madharat yang ditimbulkan kepada seorang Muslim termasuk perkara yang diharamkan.
Kemudian jika seseorang dilarang menimbulkan madharat kepada dirinya sendiri ataupun orang Muslim lainnya, maka sebaliknya ia diperintahkan untuk memunculkan ihsan dalam setiap amalan yang ia kerjakan. Allah ﷻ berfirman:
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” [QS. al-Baqarah/2:195]
Dan Rasulullah ﷺ bersabda:
إِنَّ اللهَ كَتَبَ اْلإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ
“Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan (kebaikan) dalam segala hal. Maka jika kamu membunuh, berbuat baiklah dalam membunuh. Dan jika kamu menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih, hendalah ia tajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya.” [3]
Dalam hadis tersebut Nabi ﷺ memerintahkan untuk berbuat ihsan, sampai dalam perkara menghilangkan nyawa. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi seseorang untuk senantiasa memerhatikan konsep ihsan dalam setiap aktivitas yang ia kerjakan. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu, No. 2341. At-Thabrani dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jabir al-Ja’fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini mempunyai banyak syahid sehingga semakin kuat. Di mana hadis ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, Abu Sa’id al-Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin `Abdillah, `Aisyah, Tsa’labah bin Abi Malik al-Qurazhi, dan Abu Lubabah radhiyallahu anhum.
[2]. Lihat Asy-Syarhul-Kabir ma’al-Inshaf 13/195.
[3]. HR. Muslim dalam Kitab Ash-Shaid, Bab Al-Amru bi Ihsani Adz-Dzabhi, no. 1955, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu
Kaidah Ke-16: Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Ssesuatu Dan Al-Fadhl (Tambahan) Itu Sunnah
Kaidah Keenam Belas:
العَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءِ وَالْفَضْلُ مَسْنُوْنٌ
Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhl (Tambahan) Itu Sunnah
Sebelum membahas implementasi dan contoh penerapan kaidah ini, kita perlu memahami tentang makna al-‘adl dan al-fadhl. Yang dimaksud dengan al-‘adl ialah jika seseorang menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan sebagaimana ia menuntut apa yang menjadi haknya. Sedangkan al-fadhl maknanya ialah seseorang berbuat ihsan sejak awal atau memberikan tambahan dari yang wajib ia tunaikan.
Allah ﷻ berfirman:
وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
“Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” [QS. al-Hujurat/49:9]
Demikian pula Allah ﷻ berfirman:
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” [QS. an-Nahl/16:126]
Implementasi dan contoh penerapan kidah ini cukup banyak dalam syariat ini, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Hal itu dapat kita ketahui dari contoh-contoh berikut:
- Apabila seseorang berbuat jahat kepada orang lain, maka orang yang dikenai kejahatan diperbolehkan untuk membalas kejahatan tersebut dengan balasan yang seimbang, inilah makna al-‘adl (keadilan). Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.” [QS. asy-Syura/42:40]
Namun demikian, Allah ﷻ menganjurkan orang yang terkena kejahatan untuk memberi maaf atas kejahatan tersebut, inilah makna al-fadhl (tambahan). Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ pada kelanjutan ayat tersebut:
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
“Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” [QS. asy-Syura/42:40]
- Berkaitan dengan akad utang piutang, maka orang yang mengutangi boleh menagih dan menerima pelunasan harta apabila orang yang berutang memang mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya ketika jatuh tempo pembayarannya. Namun, apabila ternyata belum mampu untuk membayar, maka Allah ﷻ memerintahkan supaya orang yang berutang diberi tangguh sehingga pembayarannya bisa ditunda. Inilah makna al-‘adl. Allah ﷻ berfirman:
وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” [QS. al-Baqarah/2:280]
Namun demikian jika orang yang mengutangi mau bersedekah dan menganggap lunas utang tersebut, maka itulah yang paling utama. Inilah makna al-fadhl dan hukumnnya sunnah. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ
“Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu.” [QS. al-Baqarah2:280]
- Apabila seseorang menjadi pengasuh anak yatim, maka ia diperbolehkan untuk makan dan minum bersama-sama anak yatim tersebut dengan harta yang dicampurkan dari hartanya dan harta anak yatim. Inilah makna al-‘adl. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. [QS. al-Baqarah/2:220]
Namun apabila pengasuh anak yatim tersebut berhati-hati dan memberikan makan dan minum kepada anak yatim tersebut dengan hartanya sendiri, maka inilah al-fadhl.
- Di dalam Alquran telah ditetapkan hukum Qishas. Yang mana jika seseorang melakukan pembunuhan, maka keluarga korban berhak menuntut supaya si pembunuh dihukum bunuh pula. Demikian pula jika seseorang mencederai anggota badan orang lain, seperti mata, telinga, atau selainnya maka ada hukum Qishas di sana. Inilah makna al-‘adl. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاْلأَنْفَ بِاْلأَنْفِ وَاْلأُذُنَ بِاْلأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada Qishasnya. [QS. al-Maidah/5:45]
Namun demikian, apabila keluarga korban atau orang yang dicederai tersebut memberi maaf, maka itu adalah perkara mulia yang dianjurkan. Inilah makna al-fadhl. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
“Barang siapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.” [QS. al-Maidah/5:45]
- Pada asalnya, mengucapkan perkataan yang buruk adalah dilarang. Namun, apabila seseorang dizalimi oleh orang lain, maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk mengucapkan perkataan yang buruk kepada orang yang menzaliminya, inilah makna al-‘adl. Allah ﷻ berfirman:
لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ
“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya.” [QS. an-Nisa’/4:148]
Dalam hal ini, apabila ia menolak kezaliman tersebut dengan cara yang lebih baik dan tidak mengucapkan perkataan yang buruk maka itulah yang dianjurkan, dan inilah makna al-‘fadhl. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَلاَ تَسْتَوِيْ الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ
“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” [Fusshilat/41:34]
- Berkaitan dengan ibadah wudhu, salat, puasa, haji, dan selainnya. Ibadah-ibadah tersebut ada dua kemungkinan pelaksanaan. Ada kemungkinan dilaksanakan secara mujzi’ (sekadar cukup untuk menggugurkan kewajiban), yaitu jika ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan dengan mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib di dalamnya saja. Inilah makna al-‘adl. Dan ada kalanya dilaksanakan secara kamil (sempurna), yaitu jika ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan dengan menyempurnakan perkara-perkara yang wajib sekaligus perkara-perkara yang sunnah di dalamnya. Inilah makna al-fadhl.
Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui tentang tiga golongan manusia, yaitu:
- Al-Munshifin (orang-orang yang berbuat adil), yaitu orang-orang yang berkomitmen dalam melaksanakan al-‘adl.
- As-Sabiqin (orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan), yaitu orang-orang yang berkomitmen dalam melaksanakan al-fadhl.
- Azh-Zalimin (orang-orang yang berbuat zalim), yaitu orang-orang yang berada di bawah kedua golongan di atas. Wallahu a’lam.
Kaidah Ke-17 dan Ke-18: Barang Mitsliyat Diganti Dengan Barang Semisalnya
Kaidah Ketujuh Belas:
مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ
Barang siapa Tergesa-gesa Ingin Mendapatkan Sesuatu Sebelum Datang Waktunya Maka Ia Mendapatkan Hukuman Dengan Tidak Mendapatkan Apa Yang Ia Inginkan Tersebut
Kaidah ini menjelaskan tentang ‘iqab (hukuman) yang didapatkan oleh seseorang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu yang ia inginkan sebelum datang waktunya. Ia mendapatkan hukuman berupa kebalikan dari apa ia inginkan itu. Demikian itu karena manusia adalah hamba yang dikuasai oleh Allah ﷻ dan berada di bawah perintah dan hukum-Nya. Maka sudah sepantasnya bagi manusia untuk tunduk kepada hukum yang telah digariskan oleh-Nya. Allah ﷻ berfirman:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” [QS. al-Ahzab/33:36]
Oleh karena itu, apabila seseorang tergesa-gesa mendapatkan perkara-perkara yang menjadi konsekuensi hukum syari sebelum terpenuhi sebab-sebabnya yang Shahih, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun, bahkan ia memeroleh hukuman berupa kebalikan dari yang ia inginkan.
Di antara implementasi dan contoh penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya atau orang lain dengan cara membunuh orang tuanya atau orang lain yang akan memberikan warisan kepadanya itu, maka ia mendapatkan ‘iqab (hukuman) berupa diharamkan dari mendapatkan warisan tersebut. Demikian itu dikarenakan ia telah tergesa-gesa untuk mendapatkan warisan dengan cara yang haram maka ia diharamkan dari mendapatkan warisan tersebut.
- Tentang orang yang mendapatkan wasiat, yang dijanjikan akan mendapatkan suatu harta tertentu setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Apabila ia tergesa-gesa untuk mendapatkannya dengan membunuh si pemberi wasiat maka ia tidak berhak mendapatkan wasiat tersebut.
- Tentang mudabbar, yaitu budak yang dijanjikan bebas oleh tuannya setelah tuannya tersebut meninggal. Apabila si budak tersebut tergesa-gesa untuk mendapatkan kebebasan dengan cara membunuh tuannya, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan kebebasan dari statusnya sebagai budak.
- Seorang laki-laki yang berada dalam keadaan sakit parah yang menyebabkan kematiannya. Apabila sebelum meninggal ia menceraikan istrinya dengan tujuan supaya istrinya tidak mendapatkan warisan darinya, maka dalam hal ini si istri tersebut tetap berhak mendapatkan warisan darinya, meskipun si istri tersebut telah selesai dari masa iddah, selagi belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan ada pula yang berpendapat bahwa si istri tersebut tetap mendapatkan warisan meskipun telah menikah lagi dengan laki-laki lain karena ia mempunyai uzur.
- Termasuk juga dalam implementasi kaidah ini adalah bahwasanya orang yang tergesa-gesa untuk melampiaskan syahwatnya di dunia dalam perkara-perkara yang haram, maka ia dihukum dengan tidak mendapatkannya di Akhirat selama belum bertaubat di dunia [1]. Allah ﷻ berfirman:
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
“Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke Neraka (kepada mereka dikatakan): “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.” [QS. al-Ahqaf/46:20]
Berkebalikan dengan kaidah ini, maka barang siapa meninggalkan suatu kejelekan dikarenakan mengharap keridaan Allah ﷻ, maka Allah ﷻ akan memberikan kepadanya suatu pengganti yang lebih baik dari yang ia tinggalkan tersebut. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Misalnya orang laki-laki yang memakai pakaian sutra di dunia maka ia diharamkan dari memakainya di Akhirat, dan orang yang minum khamr di dunia diharamkan dari meminumnya di Akhirat. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Barang siapa memakai sutra di dunia maka ia tidak akan memakainya di Akhirat. Dan barang siapa meminum khamr maka ia tidak akan meminumnya di Akhirat”. [HR. al-Bukhari no. 5832 dan Muslim 2073 dari Sahabat Anas bin Malik] (Pent)
Kaidah Ke-18
Kaidah Kedelapan Belas:
تُضْمَنُ الْمِثْلِيَّاتُ بِمِثْلِهَا وَالْمُتَقَوَّمَاتُ بِقِيْمَتِهَا
Barang Mitsliyat Diganti Dengan Barang Semisalnya Dan Mutaqawwamat Diganti Dengan Harganya
Kaidah ini berkaitan dengan kasus seseorang yang mempunyai tanggungan untuk mengganti barang orang lain dikarenakan barang tersebut ia rusakkan, ia hilangkan, atau karena sebab lainnya. Dalam hal ini, timbul permasalahan, apakah ia mengganti dengan barang yang semisal ataukah cukup mengganti dengan harga tertentu senilai barang yang harus diganti tersebut.
Maka kaidah ini menjelaskan, bahwa apabila barang yang dirusakkan tersebut berupa mitsliyat maka diganti dengan barang yang semisal dengannya. Dan apabila barang yang dirusakkan tersebut berupa mutaqawwamat maka diganti dengan nilai barang tersebut.
Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan mitsliyat dan mutaqawwamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa mitsliyat adalah semua barang yang diperjual-belikan dengan ditakar atau ditimbang. Sedangkan mutaqawwamat adalah barang-barang yang diperjual-belikan selain dengan ditakar atau ditimbang. [1]
Para ulama yang lain berpendapat bahwa mitsliyat itu lebih umum daripada batasan di atas. Mereka berpendapat bahwa mitsliyat adalah segala sesuatu yang mempunyai misal yang serupa atau mirip dengannya. Sedangkan mutaqawwamat adalah barang-barang selain kategori tersebut. Pendapat inilah yang benar dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:
- Rasulullah ﷺ pernah meminjam seekor unta, kemudian beliau ingin mengembalikan ganti unta tersebut kepada pemiliknya. Namun, beliau rahimahullahidak mendapatkan unta yang semisal. Maka beliau memberikan ganti berupa unta yang lebih baik dari unta tersebut. [2]
Hadis ini menunjukkan bahwa mitsliyat tidak terbatas pada barang-barang yang diperjual-belikan dengan ditimbang atau ditakar semata.
- Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menganti piring Zainab binti Jahsy, dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha telah memecahkan piringnya. [3]
- Karena memberikan ganti dengan barang yang semisal atau serupa terkandung di dalamnya dua hal bagi pemilik barang, yaitu didapatkannya nilai barang yang diganti dan terealisasinya maksud pemilik barang dalam manfaat barang tersebut. Maka, inilah pendapat yang benar berkaitan dengan batasan mitsliyat dan mutaqawwamat.
Di antara implementasi dan penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Berkaitan dengan perusakan barang. Seseorang yang merusakkan barang orang lain dan sedangkan barang tersebut termasuk kategori mitsliyat, maka ia wajib mengganti dengan barang yang serupa. Namun, apabila barang tersebut termasuk kategori mutaqawwamat maka ia cukup mengganti dengan nilai harga barang tersebut.
- Berkaitan dengan kasus pinjam meminjam. Seseorang yang meminjam barang orang lain untuk dimanfaatkan, misalnya ia meminjam sejumlah makanan atau selainnya untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia wajib mengembalikan barang tersebut. Apabila barang itu termasuk kategori mitsliyat maka ia wajib mengembalikan dengan barang yang serupa. Dan apabila barang tersebut termasuk kategori mutaqawwamat maka ia cukup mengembalikan dengan nilai harga barang tersebut.
- Seseorang yang dititipi barang oleh orang lain. Kemudian barang tersebut hilang dikarenakan keteledorannya, atau ia berlebih-lebihan dalam menggunakan barang tersebut. Maka, ia wajib mengganti barang tersebut. Apabila barang tersebut termasuk kategori mitsliyat maka ia wajib mengganti dengan barang yang serupa. Dan apabila barang tersebut termasuk kategori mutaqawwamat maka ia cukup mengganti dengan nilai harga barang tersebut.
- Seseorang yang menyembelih Udhiyah (hewan kurban). Kemudian ia memakan semua daging hewan kurbannya tersebut tanpa menyedekahkan sedikit pun. Maka, dalam hal ini ia wajib bersedekah dengan daging hewan sejenis sekadar jumlah yang wajib sebagai ganti atas kewajibannya bersedekah dengan daging hewan kurban tersebut.
Demikianlah kaidah ini diterapkan pada permasalahan-permasalahan lain yang serupa. Wallahu a’lam.
Kaidah Ke-19 dan Ke-20: Apabila Harga Yang Disepakati Tidak Diketahui, Dikembalikan Kepada Harga Pasar
Kaidah Kesembilan Belas:
إِذَا تَعَذَّرَ الْمُسَمَّى رُجِعَ إِلَى الْقِيْمَةِ
Apabila Harga Yang Disepakati Tidak Diketahui Maka Dikembalikan Kepada Harga Pasar
Dalam transaksi jual beli, pada asalnya pembeli wajib membayar kepada penjual senilai harga yang telah disepakati oleh keduanya. Namun, apabila harga yang telah disepakati tersebut tidak diketahui karena penjual dan pembeli sama-sama lupa atau karena sebab lainnya, maka dalam hal ini timbul permasalahan tentang penentuan harga barang tersebut.
Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut di kemudian hari tidak diketahui dikarenakan suatu sebab tertentu, padahal harga barang belum diserahkan oleh si pembeli, maka dalam hal ini harga barang ditentukan sesuai umumnya harga barang tersebut di pasaran.
Kaidah ini berbeda dengan kaidah sebelumnya. Karena, dalam suatu akad transaksi yang harganya telah ditentukan dan disepakati oleh pelaku transaksi, ada kemungkinan besarnya harga tersebut kemudian tidak diketahui lagi. Atau ada juga kemungkinan bahwa harga yang telah disepakati tersebut tidak mungkin diserahkan dikarenakan tidak sahnya akad transaksi, baik karena gharar (unsur tipuan), karena adanya perkara yang haram, atau sebab-sebab lainnya.
Di antara implementasi kaidah ini dapat diketahui pada contoh-contoh berikut:
- Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga tertentu, dan sebelum pembayaran diserahkan, keduanya tidak mengetahui berapa besarnya harga yang telah disepakati tersebut, maka dalam hal ini harga barang ditentukan sesuai harga secara umum di pasaran, karena umumnya barang-barang dagangan diperjual-belikan sesuai harganya secara umum di pasaran.
- Apabila seseorang mempekerjakan orang lain dengan kesepakatan upah tertentu, kemudian ketika datang waktu pemberian upah, ternyata tidak diketahui lagi berapa besarnya upah tersebut, dikarenakan kedua belah pihak lupa atau karena sebab lainnya, maka dalam hal ini dikembalikan kepada jumlah upah untuk pekerjaan semisal secara umum di daerah bersangkutan.
- Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, namun ia belum menentukan besarnya mahar yang harus ia serahkan kepada istrinya, maka dalam hal ini mahar ditentukan berdasarkan umumnya mahar yang diberikan untuk wanita semisal di daerah bersangkutan. Wallahu a’lam.
Kaidah Ke-20
Kaidah Kedua Puluh:
إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ جُعِلَ كَالْمَعْدُوْمِ
Apabila Pemilik Suatu Barang Tidak Diketahui Maka Barang Tersebut Dianggap Tidak Ada Pemiliknya
Apabila seseorang menemukan barang milik orang lain, namun tidak diketahui secara jelas siapa pemiliknya, maka dalam hal ini timbul permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan barang tersebut.
Oleh karena itu, kaidah ini menjelaskan bahwa suatu barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, maka barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya. Dan wajib untuk memanfaatkan barang tersebut dalam perkara-perkara yang paling bermanfaat bagi pemiliknya atau orang yang paling berhak untuk memanfaatkannya.
Di antara implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Berkaitan dengan barang temuan (Luqathah). Seseorang yang menemukan barang temuan, kemudian ia berusaha untuk mengumumkan tentang penemuan tersebut, namun pemiliknya tidak juga bisa diketahui, maka barang tersebut menjadi milik si penemu. Karena dialah orang yang paling berhak untuk memilikinya.
- Apabila seseorang memakai barang orang lain tanpa izin, kemudian tatkala ia ingin mengembalikan barang tersebut, ternyata tidak diketahui siapa pemiliknya, dan ia sangat kesulitan untuk mengetahui pemiliknya, maka dalam hal ini ia bisa menyerahkan barang tersebut ke Baitul Mal supaya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Atau bisa juga ia menyedekahkan barang tersebut atas nama pemiliknya dengan niat apabila pemiliknya datang maka ditawarkan kepadanya apakah ia setuju jika barang tersebut disedekahkan sehingga ia mendapatkan pahala sedekah, atau si pemilik barang ingin supaya barang tersebut diganti, sehingga pahala sedekah menjadi milik si penemu barang.
- Berkaitan dengan harta hasil curian atau hasil rampokan. Apabila harta tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, maka harta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, atau bisa juga disedekahkan kepada fakir miskin. Dan bagi orang yang menerima sedekah dari harta tersebut, halal baginya untuk memanfaatkannya, karena harta tersebut pemiliknya tidak diketahui, maka dianggap tidak ada pemiliknya.
- Seseorang yang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak diketahui, maka harta warisannya dimasukkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan dalam perkara-perkata yang maslahat.
- Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan namun tidak diketahui siapa walinya, maka ia dianggap seorang yang tidak punya wali. Sehingga ia dinikahkan oleh wali hakim. Wallahu `a’lam.
Kaidah Ke-22: Shulh (Berdamai) Dengan Sesama Kaum Muslimin Itu Boleh
Kaidah Kedua Puluh Dua
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً
Shulh (berdamai) Dengan Sesama Kaum Muslimin Itu Boleh Kecuali Perdamaian Yang Menghalalkan Suatu Yang Haram Atau Mengharamkan Suatu Perkara Yang Halal
Kaidah mulia yang sangat bermanfaat ini diambil dari lafal hadis yang telah diShahihkan oleh beberapa ahli hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
“Berdamai dengan sesama Muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” [1]
Hadis ini menjelaskan, bahwa seluruh macam shulh (perdamaian) antara kaum Muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.
Berikut beberapa contoh penerapan kaidah di atas:
- Shulhul iqrar atau as-shulh ma’al iqrar (perdamaian yang disertai pengakuan)
Misalnya seseorang melihat barang yang diakuinya sebagai milik dia, misalnya jam, namun jam itu berada di tangan orang lain. lalu dia mengatakan: “Jam ini milikku !” Orang yang sedang membawa jam itu mengatakan: “Ya, ini memang jammu. Namun aku ingin berdamai denganmu dengan cara memberikanmu sejumlah uang lalu jam ini menjadi milikku.” Jika si pemilik setuju, maka shulh ini sah dan inilah disebut as-shulh ma’al iqrar atau shulhul iqrar.
Apabila Ahmad menyetujui tawaran Zaid tersebut maka ini diperbolehkan. Ini termasuk kategori Shulhul Iqrar.
- Shulhul inkar atau as-shulh ma’al inkar (perdamaian yang disertai pengingkaran)
Contohnya kasus jam di atas. Jika yang membawa jam itu mengingkari pengakuan orang itu dengan mengatakan: “Jam ini bukan milikmu tapi milikku.” Kemudian dia khawatir permasalahan ini akan berkepanjangan, akhirnya dia ingin menyelesaikannya dengan mengajak damai. Dia mengatakan: “Kita damai saja, saya akan memberikanmu sejumlah uang dan jam ini tetap di tanganku sebagai milikku.” Jika orang pertama setuju, maka shulh ini sah dan disebut dengan shulhul inkar atau as-shulh ma’al inkar. Melihat dalam peristiwa ini ada indikasi bohong, syaikh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah mengatakan: “Bagi yang berbohong, maka akadnya tidak sah.”
- Berdamai dalam khiyar aib (hak pembeli untuk membatalkan transaksi karena ada cacat pada barang)
Apabila seseorang membeli sesuatu dengan harga tertentu, kemudian ia mengetahui ada cacat pada barang itu dan ia ingin mengembalikannya kepada penjualnya. Ketika mengembalikan barang tersebut, si penjual mengatakan: “Bagaimana jika barang ini tidak dikembalikan dan aku akan berikan ganti rugi kepadamu berupa uang sebesar sekian sebagai kompensasi dari kerusakan tersebut?”
Apabila si pembeli setuju tawaran ini, maka ini termasuk kategori berdamai yang diperbolehkan.
- Berdamai dalam khiyar Syarth (hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli)
Misalnya Ahmad hendak membeli rumah dari Zaid dengan kesepakatan si pembeli diberi waktu sepekan. Dalam waktu ini, dia berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Namun kemudian, sebelum lewat waktunya, Zaid mendatangi Ahmad dan mengatakan: “Bagaimana jika jual beli ini kita jadikan dan kita tuntaskan saja tanpa menunggu waktunya habis? Sebagai kompensasi, aku akan berikan kepadamu sejumlah uang.”
Apabila Zaid menerima tawaran Ahmad ini, maka shulh ini termasuk kategori shulh (berdamai) yang diperbolehkan dan masuk dalam keumuman kaidah di atas.
- Berdamai dalam hak syuf’ah
Apabila ada suatu barang dimiliki secara bersama oleh Ahmad dan Zaid, misalnya tanah atau rumah. Kemudian Ahmad menjual bagiannya kepada Yasir. Dalam hal ini Zaid bisa menggunakan hak syuf’ahnya untuk membatalkan jual beli tersebut. Zaid berhak menarik bagian yang sudah dijual Ahmad dan merubah statusnya menjadi milik Zaid atau membelinya dengan harga yang sudah disepakati oleh Ahmad dan Yasir. Dalam peristiwa ini, saat Zaid akan menggunakan hak syuf’ahnya, Yasir berkata: “Bagaimana jika engkau tidak menggunakan hak syuf’ahmu? Karena aku ingin memiliki barang ini. Sebagai konsekuensinya aku akan memberikan sejumlah uang kepadamu.”
Apabila Zaid setuju dengan tawaran Yasir ini, maka ini termasuk kategori shulh (berdamai) yang diperbolehkan.
- Berdamai dalam Diyat pembunuhan atau yang lain
Apabila terjadi suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan zalim, maka keluarga korban bisa menuntut hukum Qishash atau menuntut Diyat (ganti rugi atas pembunuhan tersebut). Jika menuntut Diyat, maka jumlahnya telah ditentukan dalam syariat yaitu sejumlah 100 ekor unta dengan memenuhi berbagai ketentuan lainnya. Dalam hal ini, apabila keluarga korban mengusulkan kepada keluarga si pembunuh supaya memberikan Diyat lebih dari 100 ekor lalu keluarga si pembunuh menyetujuinya, maka ini termasuk shulh (berdamai) yang diperbolehkan.
- Perdamaian dalam utang yang tidak diketahui jumlahnya
Apabila Ahmad berutang sejumlah uang kepada Zaid. Setelah beberapa waktu, keduanya sama-sama lupa nominalnya. Dalam kondisi ini, apabila Zaid mengatakan: “Bagaimana kalau kita tentukan saja nominalnya yaitu Rp. 100.000,-. Jika nominal sebenarnya lebih dari itu, maka aku merelakannya, namun jika nominal sebenarnya kurang dari seratus ribu, maka engkau yang merelakannya?” Apabila Ahmad menerima tawaran Zaid tersebut maka ini termasuk shulh (perdamaian) yang diperbolehkan.
- Perdamaian dalam hak-hak suami istri
Apabila seorang istri khawatir akan diceraikan oleh suaminya, kemudian si istri tersebut berkata kepada suaminya, “Aku ingin tetap menjadi istrimu, sebagai konsekuensinya aku relakan nafkahku dikurangi.” Apabila si suami setuju, maka ini termasuk perdamaian yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.” [QS. an Nisa’/4:128]
Demikian pula, seluruh perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di antara manusia, maka hal tersebut diperbolehkan dan masuk dalam keumuman kaidah ini, baik lewat perantara hakim atau yang lain. Kesimpulannya, hukum asal dari perdamaian itu adalah boleh selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram.
Di antara shulh (perdamaian) yang tidak diperbolehkan karena ada unsur haram di dalamnya dapat diketahui dari beberapa contoh berikut:
- Apabila Ahmad mempunyai utang uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Zaid. Setelah beberapa waktu, Zaid lupa nominal, sementara Ahmad masih ingat nominalnya, tetapi ia tidak mau memberitahukannya kepada Zaid. Dalam hal ini, apabia Ahmad berkata kepada Zaid, “Aku juga lupa berapa jumlah utangku itu. Bagaimana kalau kita tentukan saja jumlahnya Rp. 50.000? Aku rela jika jumlah utang sebenarnya lebih kecil dari itu. Dan relakanlah jika jumlah utang sebenarnya lebih besar dari itu.” Kemudian Zaid menyetujui tawaran Ahmad tersebut. Maka perdamaian tersebut haram bagi Ahmad, karena ia telah menghalalkan perkara yang haram.
- Apabila Ahmad mempunyai utang uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Zaid, dengan jangka waktu pengembalian selama satu pekan. Setelah berlalu satu pekan, ternyata Ahmad belum bisa melunasi utangnya. Kemudian Ahmad berkata kepada Zaid, “Berilah tenggang waktu kepadaku selama tiga hari untuk melunasi utangku. Dan sebagai konsekuensinya, aku akan membayar utangku sebesar Rp 100.000 dengan tambahan Rp. 20.000 untukmu.” Jika Zaid setuju, maka perdamaian seperti itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba.
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Hadis الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُُرُوْطِهِمْ diriwayatkan oleh imam Bukhari 4/451 secara mu’allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushul oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, al Hakim 2/45, Ibnu ‘Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lewat jalur riwayat Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi no. 1370 dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya, Rasulullah ﷺ bersabda:
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
Lafal ini dibawakan juga oleh Thabrani dalam al Kabir no. 30, Ibnu ‘Adiy no. 2081, Daruquthni 3/27, al Baihaqi 6/79, Ibnu Majah no. 2353 tanpa kalimat yang akhir. Hadis ini dikuatkan oleh hadis ‘Aisyah, Anas, Abdullah bin Umar, Rafi’ bin Khadij Rahiyallahu anhum. Dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya, maka hadis di atas itu tsabit atau sah.
Kaidah Ke-23: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati
Kaidah Kedua Puluh Tiga [1]
الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram
Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafal hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” [2]
Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syariat tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.
Syarat-syarat yang diperbolehkan sebagaimana hukum asalnya itu banyak, di antara contohnya:
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ
“Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tunaikan adalah syarat-syarat untuk menghalalkan pernikahan.” [3]
Adapun syarat-syarat yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, maka syarat-syarat tersebut tidak boleh dipenuhi dan tidak boleh dilaksanakan. Di antara contohnya adalah dalam kasus jual beli budak. Apabila seseorang menjual budak miliknya dengan syarat kalau budak itu nantinya dimerdekakan oleh si pembeli (tuannya yang baru) maka wala’nya [4] untuk si penjual tersebut. Syarat seperti ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ:
إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
“Sesungguhnya wala’ itu adalah milik orang yang memerdekakan budak.” [5]
Syarat-syarat yang diharamkan itu terbagi menjadi dua:
- Syarat-syarat yang haram dan menyebabkan akad tidak sah.
Misalnya adalah syarat mut’ah dalam pernikahan. Yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu tersebut selesai maka pasangan suami istri tersebut bercerai. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat pernikahan tersebut berlangsung selama satu bulan dan setelah itu pernikahan mereka berakhir.
Demikian pula syarat tahlil dalam pernikahan. Apabila seorang wanita telah ditalak sebanyak tiga kali oleh suaminya, maka si suami tidak bisa ruju’ bekas istrinya tersebut kecuali apabila wanita tersebut telah dinikahi laki-laki lain, telah berhubungan suami istri dengan suaminya yang baru tersebut dan telah diceraikan lagi oleh suaminya yang baru itu, tanpa ada unsur rekayasa. Jika ada rekayasa, misalnya ada laki-laki lain yang melamar wanita tersebut, kemudian si wanita ini mau tapi dengan syarat setelah menikah dan berhubungan suami istri, dia harus dicerai, supaya bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama. Inilah yang dimaksud dengan syarat tahlil dalam perrnikahan.
Syarat mut’ah dan syarat tahlil adalah syarat yang fasid (rusak) yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan awal pernikahan disyariatkan.
- Syarat-syarat yang haram tetapi tidak menyebabkan akadnya batal.
Misalnya, pernikahan dengan syarat tanpa mahar. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat tanpa memberikan mahar kepada istrinya.
Demikian pula apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau dengan syarat bahwa istrinya tersebut mendapatkan giliran lebih banyak atau lebih sedikit daripada istri-istrinya yang lain.
Maka syarat-syarat semacam ini termasuk syarat yang fasid (rusak) namun tidak sampai menyebabkan akad pernikahan itu batal. Karena syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan awal pernikahan, baru sebatas menafikan hal-hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan berupa hak-hak istri atas suaminya. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Diangkat dari al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wat Taqasim
[2]. Hadis الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُُرُوْطِهِمْ diriwayatkan oleh Imam Bukhari 4/451 secara mu’allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushul oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu ‘Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabbah. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1370 dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda:
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
Lafal ini pula yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabir no. 30, Ibnu ‘Adiy no. 2081, Daruquthni 3/27, al-Baihaqi 6/79, Ibnu Majah no. 2353 tanpa potongan kalimat terakhir. Hadis ini dikuatkan dengan hadis ‘Aisyah, Anas, Abdullah bin Umar, Rafi’ bin Khadij radhiyallahu anhum, sehingga hadis ini menjadi sah dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya.
[3]. HR. al-Bukhari dalam kitabun Nikah, Bab as-Syuruth fin Nikah, no. 5151. Muslim dalam kitab an-Nikah, Bab al-Wafa’ fis syuruth, no. 1418 dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu anhu.
[4]. Yang dimaksud dengan wala’ di sini adalah apabila seseorang memerdekakan budak, kemudian setelah merdeka budak itu meninggal dalam keadaan tidak mempunyai ahli waris, maka yang berhak mewarisi hartanya adalah orang yang memerdekakannya. Demikian pula apabila setelah merdeka, budak tersebut terbunuh sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakan itulah yang berhak menerima Diyat (dendanya). (Pen)
[5]. HR. al Bukhari dalam Kitab al-Mukatab, Bab Isti’anatul Mukatab, no. 2563. Muslim dalam Kitab al-‘Itqu, Bab Innamal Walla-u Liman A’taqa, no. 1504 dari Aisyah Radhiyallahu anha
Kaidah Ke-24: Yang Tercepat Yang Lebih Baik
Kaidah Kedua Puluh Empat
مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
Barang siapa Lebih Dahulu (Menemukan Atau Mendapatkan) Yang Mubahat Maka Dia Yang Lebih Berhak Atas Perkara Tersebut
Kaidah yang mulia ini menjelaskan bahwa siapa saja yang terlebih menemukan atau mendapatkan yang mubahat, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan atau memanfaatkannya. Mubahat maksudnya segala yang tidak ada hak kepemilikan secara khusus atasnya, baik berupa tanah, tempat tertentu, tanaman yang tumbuh di bumi atau yang lainnya.
Dalil yang menunjukkan keabsahan kaidah ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Asmar bin Mudharris radhiyallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
“Barang siapa lebih dahulu sampai kepada suatu perkara daripada orang Muslim lainnya, maka dia yang lebih berhak atas sesuatu tersebut.” [1]
Juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
“Barang siapa mengelola tanah yang tidak dimiliki siapa pun, maka ia lebih berhak terhadap tanah itu.” [2]
Hadis ini menjelaskan, bahwa seseorang yang lebih dahulu mendapatkan dan mengelola tanah yang tidak bertuan, maka dia yang lebih berhak untuk memiliki dan memanfaatkan tanah itu. Kemudian perkara mubahat lainnya diQiyaskan dan dihukumi sama seperti tanah yang disebutkan dalam hadis di atas.
Adapun implementasi kaidah ini, dapat diketahui dari contoh-contoh berikut:
- Berkaitan dengan pengairan sawah dari air sungai. Apabila para pemilik sawah berselisih tentang sawah manakah yang paling didahulukan untuk mendapatkan pengairan dari sungai tersebut. Maka dalam hal ini yang paling didahulukan adalah sawah yang posisinya paling tinggi, karena biasanya posisinya lebih dekat dengan suangi. Setelah sawah tersebut dialiri air dan telah cukup maka barulah dialirkan ke sawah di bawahnya.
- Berkaitan dengan hewan buruan, baik di darat maupun di laut. Siapa saja yang lebih dahulu menangkapnya atau senjatanya lebih dahulu mengenainya maka dia yang lebih berhak untuk memiliki hewan tersebut. Adapun sebatas melihat hewan tersebut, maka kepemilikannya belum bisa ditentukan. Demikian pula keberadaan kayu di hutan, rerumputan yang ada di padang rumput, barang siapa lebih dahulu sampai kepadanya maka dia lah yang lebih berhak mendapatkannya.
- Berkaitan dengan tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti masjid atau selainnya. Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat orang tersebut. Misalnya Ahmad sedang duduk di suatu tempat di masjid mendengarkan pengajian. Kemudian Zaid datang dan menyuruh Ahmad berdiri, kemudian Zaid duduk di tempat tersebut. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Ahmad lebih dahulu sampai di tempat tersebut sehingga dia yang lebih berhak untuk duduk di sana.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma dijelaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:
لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا
“Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di sana, akan tetapi hendaklah kalian memberi kelonggaran dan keluasan.” [3]
- Berkaitan dengan harta-harta yang diwakafkan, baik berupa tanah, rumah, atau barang-barang lainnya yang dalam pemanfaatannya tidak memerlukan persetujuan dari nazhir (pengurus) barang yang diwakafkan. Maka siapa saja yang lebih dahulu sampai pada barang-barang tersebut, dia lebih berhak untuk memanfaatkannya. Misalnya seseorang mewakafkan sebuah rumah untuk ditempati oleh fakir miskin, maka fakir miskin mana saja yang lebih dahulu sampai ke rumah tersebut, dia yang lebih berhak untuk memanfaatkannya, sampai kebutuhannya terhadap rumah itu selesai.
Ini berkaitan dengan harta-harta wakaf yang tidak ada nazhirnya secara khusus. Adapun jika harta-harta wakaf itu diurusi oleh nazhir (pengurus) yang khusus maka pemanfaatannya tergantung pada persetujuan nazhir tersebut, tidak berdasarkan siapa yang lebih dahulu sampai pada barang-barang itu.
- Berkaitan dengan lahan mati, yaitu tanah yang tidak bertuan secara khusus. Siapa saja yang lebih dahulu menghidupkan tanah tersebut dan mengelolanya, maka dia yang lebih berhak memiliki tanah tersebut.
Dalam hal ini, seseorang dikatakan menghidupkan tanah yang mati di antaranya dengan membuat pagar pembatas sehingga tanah itu tidak dimasuki hewan-hewan liar, atau dengan membangun sumur di area tanah tersebut sehingga bisa mengairinya. Demikian pula bisa dilakukan dengan mengalirkan air ke tanah tersebut baik dari sungai, atau selainnya untuk mengairi tanah tersebut. Atau dengan membersihkan tanah tersebut dari bebatuan, genangan air, atau benda-benda lain yang menghalangi pemanfaatan tanah tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
“Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya.” [4]
- Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melamar wanita yang telah dilamar orang lain, selama lamaran tersebut belum ditolak oleh si wanita atau tidak ada izin dari si pelamar pertama. Hal ini dikarenakan orang yang pertama lebih dulu melamarannya sehingga dia lebih berhak, Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:
لاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
“Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang telah dilamar orang lain sampai pelamar itu meninggalkannya atau mengizinkannya.” [5]
- Rasulullah ﷺ telah mengabarkan tentang pahala yang besar yang akan didapatkan oleh seseorang apabila berdiri di shaf pertama dalam salat berjamaah. Sebagaimana sabda beliau ﷺ:
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ اْلأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا
“Seandainya manusia mengetahui besarnya pahala mengumandangkan azan dan pahala berdiri di shaf pertama sementara mereka tidak bisa memerolehnya kecuali dengan berundi tentulah mereka akan berundi.” [6]
Dalam hal ini, seseorang yang lebih dahulu sampai di shaf pertama tersebut, dia yang paling berhak untuk menempati posisi tersebut daripada orang lain setelahnya. Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. HR. Abu Dawud dalam Kitabu al-Kharaj, Bab Fi Iqtha’i al-Ardhina, no. 3071; al Baihaqi 6/142; at-Thabrani dalam al Kabir 1/76; al Maqdisi dalam al Mukhtarah 1/458 dari Asmar bin Mudharris. Sanad hadis ini dha’if.
[2]. HR. Bukhari dalam Kitabul Hartsi wa al-Muzara’ah, Bab Man Ahya Ardhan Mawatan, no. 2335.
[3]. HR. Bukhari dalam Kitabul Isti’dzan, Bab La Yuqimur Rajulu ar-Rajula min Majlisihi, no. 6269 dan 6270; Muslim dalam Kitabus Salam, Bab Tahrimu Iqamatil Insani min Maudhi’ihil Mubahi alladzi Sabaqa Ilaihi, no. 2177.
[4]. HR. Abu Dawud dalam Kitabul Kharaju wal Imaratu wal Fai’, Bab Fi Ihya’il Mawat, no. 3073; Tirmidzi, no. 1378, beliau mengatakan: “Ini hadis hasan gharib”. Hadis ini diShahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Irwa’ul Ghalil no. 1550.
[5]. HR. Bukhari, no. 5144; Muslim, no. 1412.
[6]. HR. Bukhari, no. 615.
Kaidah Ke- 25: Pengundian Disyariatkan Apabila Yang Berhak Tidak Diketahui
Kaidah Kedua Puluh lima
تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَذَّرَتِ الْقِسْمَةُ
Pengundian Disyariatkan Apabila Orang Yang Berhak Tidak Diketahui Dan Pembagian Tidak Mungkin Untuk Dilakukan
Telah disebutkan dalil disyariatkannya pengundian [1] -saat tidak diketahui siapa yang berhak- dalam Alquran dan Hadis. Allah ﷻ berfirman:
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
“Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam pengundian.” [QS. ash-Shaffat/37:141]
Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Yunus Alaihissallam ketika meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman kepada beliau, sehingga sampailah beliau di tepi pantai dan melihat kapal yang akan berlayar, maka beliau pun naik ke kapal tersebut. Ternyata muatan kapal tersebut terlalu penuh muatannya, sehingga saat berada di tengah lautan kapal tidak bisa bergerak ke depan maupun ke belakang di tengah-tengah lautan. Bila muatan tidak dikurangi, seluruh penumpang akan tenggelam. Untuk itu, mereka mengadakan pengundian untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan dikeluarkan dari kapal. Setelah dilakukan undian, keluarlah nama Nabi Yunus Alaihissallam. Selanjutnya beliau dilemparkan keluar dari kapal. Dan masuklah beliau ke mulut seekor ikan dan tinggal beberapa waktu di perut ikan itu sampai diselamatkan Allah ﷻ. [2]
Contoh lain, Allah ﷻ berfirman:
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
“Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan pena-pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.” [QS. Ali ‘Imran/3:44]
Ayat ini berkaitan dengan kisah para pengemuka Bani Israil yang berselisih untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam. Maka mereka bersepakat pergi ke suatu sungai untuk mengundi siapa yang berhak mengasuhnya dengan melemparkan pena-pena mereka, dengan kesepakatan bahwa siapa di antara mereka yang penanya tidak hanyut terbawa arus sungai, maka dia lah yang berhak mengasuh Maryam. Ternyata pena Nabi Zakariya Alaihissallam lah yang tidak hanyut terbawa air sungai, sehingga beliaulah yang berhak mengasuh Maryam. [3]
Adapun dalil dari Sunnah, disebutkan dalam hadis:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهَ.
Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: “Dahulu Rasulullah ﷺ apabila ingin bepergian, maka beliau mengundi para istrinya. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau akan pergi bersamanya.” [4]
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, baik berkaitan dengan permasalahan ibadah ataupun muamalah. Dia antaranya adalah sebagai berikut:
- Apabila ada dua orang berebut untuk mengumandangkan azan, sedangkan keduanya bukan muadzin ratib [5] dan tidak ada kelebihan salah satu dari yang lain, baik dari sisi keindahan dan kenyaringan suara, ataupun karakteristik lain yang diperhatikan dalam azan, maka penentuan yang berhak mengumandangkan azan dilakukan dengan pengundian.
- Apabila ada dua orang atau lebih sama-sama berkeinginan menjadi imam salat, sedangkan mereka setara dari sisi keindahan bacaan, kedalaman ilmu agama, hijrah, dan usia, maka yang berhak menjadi imam ditentukan dengan pengundian.
- Apabila seseorang ingin memberikan suatu barang tertentu, baik berupa air, pakaian, bejana, atau selainnya kepada orang yang paling layak mendapatkan barang tersebut di antara sekelompok orang. Ternyata sekelompok orang tersebut mempunyai sifat latar belakang yang sama, dan sulit ditentukan siapa di antara mereka yang paling layak mendapatkan barang tersebut. Maka orang yang berhak mendapatkannya ditentukan dengan pengundian.
- Apabila ada beberapa jenazah yang akan disalatkan maka jenazah orang yang paling berilmu diletakkan paling dekat dengan imam [6]. Namun apabila semua jenazah tersebut mempunyai kesetaraan dari sisi keilmuan, tidak ada yang lebih utama salah satu dari yang lainnya, maka yang diletakkan paling dekat dengan imam ditentukan dengan pengundian.
- Apabila ada dua jenazah yang terpaksa dikuburkan dalam satu liang lahat karena tempat yang sempit, waktu yang sempit, atau tenaga pengubur yang sedikit, maka yang lebih didahulukan dimasukkan ke liang lahat dan diletakkan lebih dekat ke arah Kiblat adalah jenazah orang yang paling utama di antara mereka. Yaitu, jenazah orang yang paling berilmu dan paling banyak menghafal Alquran [7] Namun, apabila kedua jenazah tersebut mempunyai kesetaraan dalam ilmu dan hafalan, maka yang berhak dimasukkan lebih dahulu ke liang lahat ditentukan dengan undian.
- Apabila ada dua orang sama-sama menyatakan bahwa suatu barang tertentu adalah miliknya, dan tidak ada qarinah (tanda-tanda) yang menguatkan salah satunya lebih berhak atas barang tersebut, maka orang yang berhak memilikinya ditentukan dengan pengundian. Namun demikian, apabila barang tersebut bisa dibagi dan keduanya bersepakat untuk membagi barang tersebut menjadi dua bagian dan masing-masing mendapatkan separuh bagian yang sama, ini diperbolehkan. [8]
- Apabila ada dua orang berebut untuk mendapatkan suatu barang atau perkara mubahat [9], dan barang tersebut tidak mungkin dimiliki secara bersama, maka orang yang berhak mendapatkannya ditentukan dengan pengundian Misalnya, apabila ada dua orang berbarengan dan sama-sama berkeinginan untuk duduk di suatu tempat tertentu di dalam masjid, maka dalam hal ini penentuan yang berhak duduk di tempat tersebut dilakukan dengan pengundian.
- Apabila seorang wanita akan melangsungkan pernikahan dan seluruh karib kerabat yang berhak menikahkannya berkeinginan menjadi wali nikahnya, padahal mereka semua sederajat, maka penentuan wali nikah dilakukan dengan pengundian.
- Apabila seseorang mempunyai beberapa budak, kemudian ia membebaskan salah satu budaknya, tetapi ia lupa budak manakah yang ia bebaskan, maka penentuannya ditetapkan dengan pengundian.
Kemudian berkaitan dengan pembahasan kaidah ini, perlu dipahami bahwa apabila kadar kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu harta ataupun piutang sudah diketahui secara jelas, kemudian mereka melakukan pengundian untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mendapatkan harta atau piutang tersebut secara penuh, maka ini termasuk perjudian yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil Alquran, Sunnah, dan Ijma. Di antara contohnya dapat diketahui melalui dua kasus berikut:
- Apabila sebuah mobil dimiliki secara bersama oleh dua orang. Kemudian keduanya melakukan pengundian dengan kesepakatan bahwa siapa di antara keduanya yang keluar namanya dalam undian, maka ia berhak memiliki mobil tersebut secara penuh, pengundian seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori perjudian.
- Apabila ada dua orang sama-sama mempunyai piutang kepada si Fulan (seseorang), kemudian kedua orang tersebut melakukan pengundian, dengan kesepakatan bahwa siapa di antara keduanya yang namanya keluar dalam pengundian, maka seluruh piutang si Fulan, baik dari orang pertama ataupun orang kedua, menjadi miliknya. Maka pengundian seperti ini termasuk dalam kategori perjudian. [10] Wallahu a’lam. [11]
_______
Footnote
[1]. Pengundian (undian) –seperti tercantum dalam kaedah di atas – ditujukan untuk menentukan pihak yang berhak mendapatkan sesuatu daripada pihak lain. Hal ini perlu ditekankan supaya tidak dibawa kepada undian-undian berhadiah – yang identik dengan perjudian – yang menjamur di media massa. Red)
[2]. Lihat Aisar at-Tafasir, Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Cet. VI, Tahun. 1424H/2003M. Maktabah Ulum wal Hikam, hlm. 1094
[3]. Lihat Tafsir Alquranul ‘Azhim, al-Hafizh Ibnu Katsir, Tahun. 1412 H/1992 M. Darul Fikr. Beirut, hlm. 446-447
[4]. HR. al-Bukhari no. 2593 dan Muslim no. 2770
[5]. Yaitu muadzin yang memang telah ditugaskan secara khusus untuk mengumandangkan azan di masjid tertentu.
[6]. Yang dimaksud dengan beberapa jenazah di sini adalah beberapa jenazah yang sejenis, yaitu sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Adapun jika jenisnya berbeda, maka jenazah-jenazah tersebut disalatkan dengan meletakkan jenazah laki-laki dewasa paling dekat dengan imam, kemudian anak laki-laki yang belum baligh, kemudian jenazah wanita dewasa, kemudian jenazah anak wanita yang belum baligh. Lihat Fatawa fi Ahkamil Janaiz, Syaikh al-‘Utsaimin. Cet. I, Tahun. 1423H/2003M. Dar ats-Tsurayya,. Riyadh, hlm. 102
[7]. Sebagaimana disebutkan dalam HR. al-Bukhari no. 1347
[8]. Lihat ta’liq (komentar) Syaikh al-’Utsaimin rahimahullaherhadap kitab al-Qawa’id wal Ushul al-Jami’ah wal Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Cet. I, Tahun. 2002 M. Maktabah as-Sunnah, Kairo, hlm. 130
[9]. Yaitu barang-barang atau perkara-perkara yang tidak ada hak kepemilikan secara khusus atasnya, baik berupa tanah, tempat, tanaman, atau selainnya, sebagaimana dijelaskan pada kaidah sebelumnya.
[10]. Lihat contoh-contoh lain dari penerapan pengundian yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam kategori perjudian dalam kitab Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh al-‘Utsaimin. Cetakan Pertama. Tahun 1426 H. Dar Ibi al-Jauzi. Dammam, hlm. 317-318.
[11]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wal Ushul al-Jami’ah wal Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, tahqiq Syaikh DR. Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Cet. II, Tahun. 1422H/2001M, Darul Wathan, Riyadh, hlm. 76-77 dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-26: Jika Terjadi Perselisihan
Kaidah Kedua Puluh Enam
يُقْبَلُ قَوْلُ اْلأُمَنَاءِ فِي الَّذِي تَحْتَ أَيْدِيْهِمْ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَاْلإِتْلاَفِ وَغَيْرِهَا إِلاَّ مَا خَالَفَ الْحِسَّ وَالْعَادَةَ
Perkataan Orang Yang Diserahi Amanah Berkaitan Dengan Pengelolaan, Kerusakan Dan Masalah Lain Yang Berhubungan Dengan Harta Yang Diamanahkan Kepadanya Diterima, Kecuali Apabila Menyelisihi Realita Dan Kebiasaan [1]
Kaidah ini sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan antara pemilik harta dan orang yang diserahi amanah [2] untuk mengelola harta tersebut. Dalam akad mudhArabah atau yang semisalnya, pemilik harta (pemodal) mempercayakan hartanya kepada orang lain untuk kelola, baik dalam perdagangan, sewa atau lain sebagainya. Dalam hal ini, apabila terjadi perselisihan antara pemilik harta dengan orang yang diserahi amanah berkaitan dengan harta tersebut, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi amanah. Karena pemilik harta telah mempercayakan harta kepadanya dan telah menposisikannya seperti dirinya.
Namun apabila pernyataan orang yang diserahi amanah tersebut menyelisihi kebiasaan atau tidak selaras dengan realita yang ada, maka pernyataannya tidak diterima. Misalnya, apabila seseorang yang dititipi barang mengatakan bahwa barang tersebut telah hancur karena musibah kebakaran. Sedangkan secara realita tidak ada indikasi musibah kebakaran, maka perkataannya tidak diterima. Apabila ada tanda-tanda musibah kebakaran, kemudian terjadi perselisihan antara pemilik harta dengan orang yang dititipi harta, misalnya, si pemilik harta bersikeras bahwa barang yang dititipkan itu tidak ikut terbakar, sementara orang yang diserahi amanah menyatakan bahwa barang itu juga terbakar, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi amanah. [3]
Kasus-kasus lain yang bisa menjadi contoh implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sejumlah barang. Beberapa waktu berselang, barang itu rusak. Lalu ia berkata kepada yang diserahi amanah, “Engkau wajib mengganti karena engkau tidak menjaga harta itu!” Sementara orang yang diserahi amanah menyanggahhh, “Saya sudah sungguh-sungguh menjaganya. Karenanya, saya tidak wajib mengganti.” Maka dalam kasus seperti ini, perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi amanah. Karena kedudukannya sebagai orang yang diserahi amanah, sehingga perkataannya berkaitan dengan kerusakan barang, diterima.
- Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sejumlah pakaian. Beberapa waktu kemudian terjadi perselisihan. Si pemilik harta berkata: “Engkau belum menawarkan pakaian itu !” Dan orang yang diserahi amanah berkata: “Saya telah menawarkannya.” Maka dalam kasus ini, perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi amanah. Karena kedudukannya sebagai orang yang diserahi amanah, sehingga perkataannya berkaitan dengan pengelolaan harta, diterima.
- Apabila seseorang meminjam suatu barang kepada orang lain. Setelah beberapa waktu, pemilik barang mendatangi orang yang meminjam untuk meminta supaya barangnya dikembalikan. Lalu si peminjam mengatakan bahwa barang tersebut telah rusak karena musibah. Maka dalam hal ini, perkataan si peminjam tersebut asalnya diterima karena kedudukannya sebagai orang yang diserahi amanah, dan sebelumnya memang ia telah mendapatkan izin dari pemilik harta untuk membawa ataupun memanfaatkan barang tersebut.
Adapun berkaitan dengan ganti rugi kerusakan, para ulama berbeda pendapat apakah si peminjam wajib mengganti barang tersebut ataukah tidak. Dan pendapat yang kuat adalah bahwa si peminjam tidak wajib mengganti atau membayar ganti rugi kecuali apabila ia tidak benar-benar menjaganya (tafrith) atau berlebihan dalam pemanfaatannya (ta’addi). [4]
- Apabila ada akad sewa menyewa antara dua orang. Kemudian setelah masa sewa selesai, pemilik barang mendatangi si penyewa untuk meminta supaya barangnya dikembalikan. Lalu si penyewa berkata bahwa barang tersebut rusak karena suatu kecelakaan. Maka perkataan si penyewa diterima karena kedudukannya sebagai orang yang diserahi amanah. [5]
- Dalam akad mudahrabah, [6] perkataan mudharib (pengelola barang mudhArabah) berkaitan dengan keuntungan ataupun kerugian dari pengelolaan barang, diterima. Demikian pula perkataannya berkaitan dengan penjualan barang, baik secara tunai, kredit, syarat-syarat akad yang ia lakukan dan sebagainya. Karena hal itu berkaitan dengan pengelolaan barang yang diamanahkan kepadanya. [7]
Dalam uraian di atas telah dijelaskan, bahwa pembahasan kaidah ini berkisar pada perselisihan antara pemilik harta dengan orang yang diserahi amanah berkaitan dengan pengelolaan dan kerusakan harta yang diamanahkan. Di sisi lain, terkadang timbul perselisihan berkaitan dengan pengembalian barang, apakah barang tersebut sudah dikembalikan atau belum. Yaitu, apabila orang yang diserahi amanah mengatakan bahwa harta yang diamanahkan sudah dikembalikan kepada pemilik harta, namun si pemilik menyangkalnya. Maka dalam kasus seperti ini, para ulama menjelaskan, apabila si penerima amanah tidak memiliki kepentingan sama sekali pada harta tersebut, maka perkataannya diterima. Namun apabila dia memiliki kepentingan, maka perkataannya ditolak.(apabila harta yang diamanahkan tersebut semata-mata untuk maslahat si pemilik harta maka asalnya perkataan orang yang diserahi amanah diterima. Namun apabila orang yang diserahi amanah mengambil manfaat dari harta yang diamanahkan kepadanya, maka asalnya perkataannya tidaklah diterima). [8]
Implementasinya sebagai berikut:
- Apabila Ahmad menitipkan sejumlah uang kepada Hasan. Selang beberapa waktu kemudian, Ahmad menemui Hasan untuk meminta uang yang dititipkannya itu. Kemudian Hasan berkata bahwa uang tersebut sudah dikembalikan kepada Ahmad. Maka dalam kasus seperti ini, perkataan yang diterima adalah perkataan Hasan dan ia tidak dituntut untuk mendatangkan bukti pengembalian. Karena Hasan membawa harta tersebut semata-mata untuk kepentingan Ahmad dan tidak berkepentingan dengannya. Dalam hal ini, ia juga telah berbuat ihsan ketika membantu Ahmad membawakan uangnya. Sementara Allah ﷻ berfirman berkaitan dengan orang yang berbuat ihsan:
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. at-Taubah/9:91]
- Apabila seseorang menyelamatkan harta orang lain dari kehancuran karena ada bencana alam atau semisalnya. Setelah itu, pemilik harta menyatakan bahwa seluruh harta tersebut atau sebagiannya belum dikembalikan kepadanya. Sedangkan orang yang menyelamatkan mengatakan bahwa ia telah mengembalikan semua harta yang ia selamatkan kepada pemiliknya. Maka dalam kasus seperti ini, perkataan berpihak kepada si penyelamat harta. Karena ia membawa harta tersebut demi kemaslahatan pemilik harta. Dan ini masuk juga dalam keumuman firman Allah ﷻ dalam Surat at-Taubah di atas. [9]
- Apabila Ahmad meminjam barang dari Hasan. Setelah beberapa lama, terjadi perselisihan. Ahmad mengaku telah mengembalikan barang tersebut, sementara Hasan menyangkal. Maka dalam kasus seperti ini, hukum berpihak kepada Hasan. Karena Ahmad membawa barang tersebut adalah untuk kepentingan dirinya serta untuk mengambil manfaat darinya. Maka pengakuan Ahmad tidak diterima kecuali jika ia bisa mendatangkan bukti pengembalian barang tersebut.
- Apabila Ahmad menyewa sebuah mobil dari Hasan. Setelah masa sewa habis, Hasan menemui Ahmad untuk meminta mobilnya dikembalikan. Lalu Ahmad mengatakan bahwa mobil telah ia kembalikan ke Hasan. Maka dalam hal ini, perkataan Ahmad tidak diterima, karena ia membawa mobil untuk kemaslahatannya dan ia mengambil manfaat darinya. [10]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wa at-Taqasimul Badi’atun Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cet. II. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh, hlm. 78. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
[2]. Orang yang diserahi amanah (al-amin) maksudnya orang yang mendapatkan kepercayaan untuk membawa harta orang lain dengan izin pemiliknya atau dengan izin syariat. (Lihat Tuhfatu Ahlit Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cet. Ke-2. Tahun 1423 H. Dar Ibni al-Jauzi. Damam, hlm. 38-39.
[3]. Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah terhadap kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wa at-Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Cet I. Tahun 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo, hlm. 131.
[4]. Ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin dalam Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi. Cet. I. Tahun 1426 H. Dar Ibni al-Jauzi. Damam, hlm. 278.
[5]. Lihat Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 278.
[6]. MudhArabah adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih, di mana harta berasal dari salah seorang di antara mereka, sedangkan yang lainnya berperan seabgai pengelola harta tersebut dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik harta. Lihat Mu’jam Lughah al-Fuqaha. Prof. Dr. Muhammad Rawas Qal’ah Jiy dan Dr. Hamid Shadiq Qunaibi. Cet. II. Tahun 1408 H/1988 M. Dar an-Nafais. Beirut. Pada kata ( المضاربة ).
[7]. Lihat contoh-contoh lain penerapan kaidah ini dalam Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 277-278.
[8]. Lihat penjelasan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah dalam kitab Tuhfatu Ahlit Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab, hlm. 38-39.
[9]. Lihat Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 276.
[10]. Lihat pula pembahasan kaidah ini dalam Taqrirul Qawa’id wa Tahrirul Fawa’id, al-Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali. Ta’liq Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Cet. I. 1419 H/1998 M. Dar Ibni Affan, hlm. 315-322. Dan Syarhul Qawa’idis Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil. Dar Athlas al-Kahadhra’, hlm. 186.
Kaidah Ke-27: Meninggalkan Perintah Dan Mengerjakan Larangan Dalam Ibadah
Kaidah Kedua Puluh Tujuh
مَنْ تَرَكَ الْمَأْمُوْرَ جَهْلاً أَوْ نِسْيَانًا لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ إِلاَّ بِفِعْلِهِ, وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْظُوْرَ وَهُوَ مَعْذُوْرٌ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَتَمَّتْ عِبَادَتُهُ
Barang siapa meninggalkan sesuatu perintah karena tidak tahu atau lupa maka ia masih tetap mempunyai tanggungan untuk mengerjakannya. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang karena tidak tahu atau karena lupa maka ia telah lepas dari tanggungan dan ibadah yang ia lakukan telah sempurna
Kaidah ini menjelaskan perbedaan hukum antara meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan dalam ibadah ataupun masalah lain. Apabila seseorang meninggalkan suatu yang diperintahkan karena jahil (belum tahu hukumnya) atau karena lupa, maka ia tetap masih mempunyai tanggungan untuk mengerjakan perkara yang diperintahkan tersebut. Adapun yang mengerjakan perkara yang dilarang karena uzur, yaitu belum tahu hukumnya atau lupa, maka ia dimaafkan dan tidak ada kewajiban yang harus ditanggung. [1]
Dalil yang mendasari kaidah ini di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:
مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ
“Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya apabila ia ingat, tidak ada Kaffarah atasnya kecuali mengerjakan salat tersebut.” [2]
Dalam hadis ini, Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa barang siapa yang lupa tidak mengerjakan salat karena lupa, maka ia masih tetap mempunyai kewajiban untuk mengerjakannya, karena salat, satu perintah sehinggga tidak gugur karena lupa. [3]
Dalam hadis yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ
“Barang siapa yang lupa dirinya sedang puasa lalu dia makan atau minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah.” ﷻ. [4]
Dalam hadis ini Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasa. [5] Karena makan dan minum saat berpuasa termasuk larangan, sehingga ketika ada yang mengerjakannya karena lupa maka itu tidak mengakibatkan puasanya batal. [6]
Di antara penerapan dan implementasi kaidah yang mulia ini dapat diketahui dari contoh-contoh kasus berikut:
- Apabila seseorang salat dalam keadaan berhadats karena lupa atau belum tahu hukumnya maka ia harus mengulangi salatnya. Karena salat dalam keadaan suci, termasuk perkara yang diperintahkan. Maka ketika itu ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu hukum maka ia tetap mempunyai tanggungan untuk mengerjakannya. [7]
- Seseorang yang salat, ia tidak tahu ada najis di badannya atau di bajunya dan ia baru mengetahuinya setelah selesai salat, maka salatnya tetap sah dan tidak wajib mengulangi salat. Karena keberadaan najis termasuk dalam kategori sesuatu yang dilarang. Maka ketika itu terjadi karena tidak tahu atau lupa maka itu tidak memengaruhii keabsahan salat. [8]
- Apabila seseorang salat dan meninggalkan salah satu rukun, karena lupa atau tidak tahu, maka ia masih mempunyai kewajiban mengerjakan rukun yang ia tinggalkan itu. Karena menyempurnakan rukun salat masuk dalam kategori perkara yang diperintahkan.
- Apabila seseorang dalam keadaan suci dari hadats kemudian ia makan daging unta [9] dan ia tidak tahu bahwa daging itu adalah daging unta. Setelah itu ia langsung melaksanakan salat tanpa berwudhu lagi. Maka ia harus mengulangi salatnya karena ia salat dalam keadaan suci termasuk perkara yang diperintahkan. [10]
Barang siapa lupa berniat pada malam hari untuk puasa wajib maka puasanya tidak sah. Karena berniat termasuk dalam kategori perkara yang diperintahkan, maka ketika ditinggalkan karena lupa, atau tidak tahu hukum, ia tetap harus mengulangi puasanya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, yang artinya, “Barang siapa tidak berniat sebelum terbit fajar (untuk puasa wajib) maka tidak ada puasa baginya. [11]
- Apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan ia meninggalkan salah satu dari perkara wajib dalam ibadah haji, misalnya tidak bermalam di Muzdalifah, atau tidak melaksanakan Thawaf Wada karena lupa atau belum tahu hukum maka ia wajib membayar dam. [12] Karena menyempurnakan kewajiban-kewajiban dalam haji termasuk perkara yang diperintahkan. Maka ketika ada yang meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, ia masih mempunyai tanggungan berkaitan dengan itu. Dalam hal ini dengan membayar dam sebagai pengganti ibadah yang ia tinggalkan tersebut.
- Apabila seseorang dalam keadaan ihram [13] dalam ibadah haji atau umrah, kemudian ia melanggar salah satu larangan ketika berihram, misalnya memakai minyak wangi, atau memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, atau memakai tutup kepala bagi laki-laki, karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka ia tidak terkena kewajiban untuk membayar Fidyah. [14] Karena pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori mengerjakan perkara yang dilarang, dan ia melakukannya karena lupa atau ketidaktahuan.
- Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu tertentu, kemudian ia mengerjakannya karena lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib untuk membayar Kaffarah. Karena melanggar sumpah termasuk dalam kategori mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka ketika itu dilakukan karena lupa atau tidak tahu maka ia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban yang harus ditanggung. [15]
Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas bahwa kaidah ini membahas tentang keberadaan seseorang yang meninggalkan perkara yang diperintahkan karena lupa atau belum tahu hukumnya. Adapun yang meninggalkannya tanpa uzur, maka disamping masih mempunyai tanggungan untuk mengerjakan, maka ia juga berdosa karena sengaja meninggalkannya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan perkara yang diperintahkan atau mengerjakan perkara yang dilarang karena lupa atau belum tahu hukumnya, maka ia tidak berdosa. [16] Sebagaimna firman Allah ﷻ tentang doa orang-orang yang beriman:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” [QS. Al Baqarah/2: 286]
Disebutkan dalam salah satu Hadis Qudsi, bahwasanya Allah ﷻ berfirman:
قَدْ فَعَلْتُ
“Sungguh Aku telah mengabulkannya.” [17]
Wallahu a’lam. [18]
_______
Footnote
[1]. al-Asybah wan Nazha-ir. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi. Cet. Ke-4, Th. 1418 H/1998 M. Dar al-Kutub al-‘Arabiy. Beirut. Hlm. 339.
[2]. HR. al-Bukhari, no. 597 dan Muslim no. 684.
[3]. Lihat al-Mausu’atul Fiqhiyyah, 40/268-271. Cet. Ke-2. 1404 H/1983 M. Wizaratul Auqaf, Kuwait.
[4]. HR. al-Bukhari, no. 1933 dan Muslim, no. 1155 serta ad-Darimi, no. 1725.
[5]. Lihat Taisirul ‘Allam. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Alu Bassam. Cet. I. Th. 1422 H/2002 M. Dar al-Aqidah. Kairo. Hlm. 361.
[6]. Lihat al-Mausu’atul Fiqhiyyah. 40/280, Cet. Ke-2. 1404 H/1983 M. Wizaratul Auqaf, Kuwait.
[7]. Lihat Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi. Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin. Cet. I, Th 1426 H. Dar Ibni al-Jauzi. Damam. hlm. 151.
[8]. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Abu Dawud, no. 650. Hadis ini diShahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 1/192.
[9]. Makan daging unta termasuk pembatal wudhu sebagaimana dalam hadis al-Barra’ bin ‘Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 184 dan diShahihkan Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi, No. 81.
[10]. Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin terhadap kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wa al-Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Cet. I. Th 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo. Hlm. 133.
[11]. HR. an-Nasai, no. 2331. Hadis ini diShahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Irwaul Ghalil, No. 914.
[12]. Dam adalah denda yang harus dibayar karena meninggalkan salah satu dari kewajiban dalam ibadah haji. Dam itu dengan menyembelih seekor kambing dan membagikannya kepada fakir miskin di tanah haram. Jika tidak mampu maka berpuasa sepuluh hari, tiga hari ketika masa haji dan tujuh hari jika telah pulang. (Lihat al-Mausu’atul Fiqhiyyah. 32/72, Cet. Ke-2. 1404 H/1983 M. Wizaratul Auqaf, Kuwait)
[13]. Ihram adalah niat untuk masuk ke dalam rangkaian manasik haji atau umrah. (Lihat, al-Mausu’atul Fiqhiyyah. 2/128-129)
[14]. Fidyah adalah denda yang harus dibayar karena mengerjakan salah satu perkara yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah. (al-Mausu’atul Fiqhiyyah, 32/72-73).
[15]. Lihat Syarhul Qawa’id as-Sa’diyah. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil. Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa-at-Tauzi’. Hlm. 188.
[16]. Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin terhadap kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wa al-Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Cet. I. Th 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo. Hal. 133-134.
[17]. HR. Muslim, no. 126.
[18]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wa al-Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh. Hlm. 78-80. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-28: Pengganti Menempati Posisi Yang Digantikan
Kaidah Kedua Puluh Delapan
يَقُوْمُ الْبَدَلُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَلَكِنْ لاَ يُصَارُ إِلَيْهِ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ اْلأَصْلُ
Pengganti Menempati Posisi Yang Digantikan, Namun Pengganti Tidak Dijalankan Kecuali Jika Pelaksanaan (Ibadah) Yang Diganti Terhalang
Ini sebuah kaidah yang masyhur di kalangan para ulama. Kaidah ini menjelaskan bahwa badal (pengganti atau ibadah pengganti) diberi hukum yang sama dengan mubdal (yang digantikan atau ibadah yang digantikan). Artinya, jika yang digantikan adalah suatu yang wajib maka penggantinya juga wajib. Jika yang digantikan hukumnya sunnah maka penggantinya pun sunnah. [1]
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini yaitu firman Allah ﷻ:
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memeroleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu.” [QS. al-Maidah/5:6]
Pada ayat ini, setelah menjelaskan kewajiban bersuci dengan air, kemudian Allah ﷻ menempatkan tanah sebagai pengganti air, ketika tidak ada air atau berbahaya jika menggunakannya. Dalam ayat ini diisyaratkan, bahwa dengan Tayammum (bersuci dengan tanah atau debu) seseorang diperbolehkan mengerjakan ibadah dan hal-hal lain yang hanya boleh dikerjakan jika sudah bersuci dengan air. Di sini juga ada isyarat bahwa Tayammum menempati posisi bersuci dengan air. [2]
Demikian pula sabda Nabi ﷺ:
الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ
Debu yang suci adalah alat bersuci bagi Muslim meskipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika ia telah menjumpai air maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan menyentuhkan air itu ke kulinya. [3]
Hadis di atas juga menunjukkan bahwa Tayammum dengan menggunakan debu merupakan pengganti air untuk bersuci apabila tidak ada air. [4]
Namun demikian seseorang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah pengganti kecuali jika sudah ia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah yang digantikan tersebut. Jika ia langsung mengerjakan ibadah pengganti padahal ia mampu mengerjakan ibadah yang digantikan maka itu tidak sah dan ia berdosa karena mengabaikan sesuatu yang menjadi hukum asal. [5]
Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi kaidah ini:
- Apabila seseorang bertayammum untuk melaksanakan salat Dhuha dan ia tidak batal sampai waktu Zuhur tiba, maka ia boleh Salat Zuhur dengan Tayammumnya tersebut. Karena Tayammum adalah pengganti wudhu, ketika tidak ada air.
- Seseorang yang bangun dari tidur dan menyadari dirinya dalam keadaan janabah. Maka ia boleh berTayammum sebagai ganti mandi janabah, apabila tidak ada air. Jika waktu Salat Zuhur tiba, maka ia tidak wajib berTayammum lagi untuk janabahnya. Yang wajib hanyalah bertayamum dari hadats kecil jika ia berhadats kecil di rentang waktu antara setelah bertayamum dan Zuhur.
- Namun jika ia bertayammum dari janabah, kemudian ia menjumpai air maka ia wajib untuk mandi. [6]
- Apabila seseorang bernadzar untuk menyembelih unta untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, namun ia tidak mendapatakan unta, lalu ia menyembelih tujuh ekor kambing sebagai gantinya, maka itu diperbolehkan. Dan kambing tersebut diberi status hukum yang sama dengan yang digantikan. Demikian pula sebaliknya.
- Apabila seseorang tidak mampu rukuk dan sujud saat salat, maka ia boleh untuk berisyarat sebagai pengganti dari rukuk dan sujud. Dan mestinya isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat rukuk. Jika ia mampu membungkukkan punggungnya untuk rukuk dan meletakkan keningnya di lantai untuk sujud, maka itulah yang wajib baginya dan tidak boleh diganti dengan isyarat.
- Seorang jamaah haji yang melaksanakan Haji Tamattu’ atau qiran, wajib baginya untuk menyembelih hadyu, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari nahr (tanggal sepuluh Dzulhijjah). Akan tetapi jika ia tidak mampu, maka ia boleh mengerjakan penggantinya yaitu berpuasa sepuluh hari, yaitu tiga hari dilaksanakan pada masa haji dan tujuh hari setelah ia pulang ke daerah asal. [7]
- Hukum dalam ibadah haji adalah dikerjakan oleh orang yang bersangkutan tanpa diwakilkan. Namun, jika fisiknya tidak memungkinnya berangkat haji, misalnya lumpuh, sementara ia hartanya cukup untuk ibadah haji, maka ia bisa mewakilkannya ke orang lain untuk menghajikannya. Ini adalah pengganti dari melaksanakan haji dengan badannya sendiri.
- Seseorang yang melanggar sumpahnya wajib baginya untuk membayar Kaffarah sumpah, yaitu dengan memilih salah satu dari beberapa opsi yang ditetap syariat seperti memberikan makanan sepuluh orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. [8] Ia boleh memilih salah satu dari ketiga hal tersebut. Namun, jika ia tidak mampu mengerjakan salah satunya, maka ia boleh mengerjakan penggantinya yaitu berpuasa selama tiga hari. Ia tidak boleh membayar Kaffarah dengan puasa tiga hari kecuali jika memang tidak mampu mengerjakan salah satu dari tiga opsi di atas.
- Berkaitan dengan Kaffarah Zhihar. [9] Seseorang tidak diperbolehkan memilih Kaffarah urutan kedua kecuali jika ia tidak mampu mengerjakan Kaffarah urutan pertama. Karena Kaffarah Zhihar bersifat tartib (urutan). Sehingga seseorang tidak boleh mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut jika ia mampu untuk membebaskan seorang budak. Karena posisi puasa dua bulan berturut-turut sebagai badal (pengganti) dari membebaskan budak.
Wallahu a’lam. [10]
_______
Footnote
[1]. Syarh Manzhumati Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi. Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin. Cet. 1. Tahun 1426 H. Dar Ibni al-Jauzi. Damam. Hlm. 298.
[2]. Lihat Hasyiyah Ibnu Abidin 1/241, al-Mudawwanah 1/42, al-Umm 1/39, Majmu’ al-Fatawa 21/353, dan al-Inshaf 1/263.
[3]. HR. Ahmad (5/180), Abu Dawud, no. 332; Tirmidzi, no. 124, dan Nasa-i no. 322. Dari Abu Dzar z.
[4]. Lihat Taudhihul Ahkam. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam. Cet. Ke-5. 1423 H/2003 M. Maktabah al-Asadi. Makkah al-Mukarramah. Hlm. 423.
[5]. Lihat Talqihul Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan. Kaidah Kelima.
[6]. Sebagaimana disebutkan dalam HR. Bukhari no. 337, Muslim no. 312, Ahmad (5/180), Abu Dawud no. 232, Tirmidzi no. 124, dan Nasa-i no. 322.
[7]. Sebagaimana dijelaskan dalam. al-Baqarah/2:196.
[8]. Kaffarah sumpah dijelaskan dalam al Maidah/5:89.
[9]. Zhihar adalah jika seorang suami menyatakan bahwa istrinya haram untuknya, dengan mengatakan: “Engkau bagiku seperti punggung ibuku”, atau ucapan semisalnya. Seorang suami yang telah menzhihar istrinya, lalu ingin kembali kepadanya maka ia harus membayar Kaffarah dengan membebeskan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin sebagaimana disebutkan dalam al-Mujadilah/58:3-4. (Lihat Minhajul Muslim. Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Tahun 2002 M. Dar Ibnu al-Haitsam. Kairo. Hal. 358).
[10]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasimil Badi’ah an-Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh. Hlm. 80. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya
Kaidah Ke-29: Memahami Keumuman Dan Kekhususan Sebuah Kalimat
Kaidah Kedua Puluh Sembilan
يَجِبُ تَقْيِيْدُ اللَّفْظِ بِمُلحَقَاتِهِ مِنْ وَصْفٍ، أَوْشَرْطِ، أَوِاسْتِشْنَاءٍ، أَوْ غَيْرِهَامِنَ الْقُيُوْدِ
Wajib Mengaitkan Perkataan Dengan Hal-Hal Yang Mengikatnya, Seperti Sifat, Syarat, Pengecualian Atau Pengikat Lainnya.
Kaidah ini menjelaskan tentang pentingnya memahami dan menerapkan konsekuensi perkataan yang bersyarat. Apabila sebuah perkataan bersifat umum, maka dipahami umum. Namun, jika sebuah perkataan dikaitkan dengan sesuatu, maka dipahami sesuai kaitannya tersebut [1]. Kaidah ini secara umum telah diketahui dan dikenal, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa lainnya.
Kaidah ini bisa diterapkan dalam memahami firman Allah ﷻ: sabda Nabi ﷺ dan perkataan semua orang. Banyak permasalahan yang masuk dalam penerapan kaidah ini, baik berkaitan dengan akad bisnis ataupun Tabarru’ (nirlaba), persyaratan wakaf, wasiat, pembebasan budak, talak, sumpah dan selainnya.
Kaidah ini mempunyai implementasi dan contoh penerapan yang cukup banyak, baik berkaitan dengan permasalahan ibadah ataupun muamalah (intraksi antara sesama manusia). Di antara contohnya:
- Apabila seseorang mewakafkan tanah dengan mengatakan: “Tanah ini saya wakafkan untuk orang-orang fakir”. Maka konsekuensi dari perkataan ini adalah yang berhak memanfaatkan tanah wakaf tersebut hanyalah orang-orang yang tergolong fakir, tidak selainnya. Karena dalam perkataan tersebut ada pengikatnya secara khusus, sehingga harus diterapkan sesuai dengan ikatannya tersebut. Ini adalah contoh pengikat dan menyebutkan sifat. [2]
- Apabila seseorang mengatakan: “Saya wakafkan tanah saya ini untuk Ahmad dan Zaid, dengan perincian, Ahmad dua pertiga dan Zaid sepertiga”. Konsekuensi dari perkataan ini adalah harus diterapkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan tersebut.
- Apabila seseorang mengatakan: “Saya wakafkan tanah saya ini untuk anak-anak Ahmad kecuali anak yang fasik”. Konsekuensi dari perkataan ini adalah harus diterapkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan tersebut.
- Dalam hadis dijelaskan bolehnya mengusap khuf (sepatu bot atau yang sejenisnya) ketika berwudhu. Pembolehan ini disebutkan secara mutlaq (umum), misalnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
“Nabi ﷺ telah menetapkan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim, yakni tentang mengusap dua khuf.” [3]
Dalam masalah ini, sebagian ulama menyebutkan beberapa syarat khusus terkait kondisi khuf. Namun syarat-syarat tersebut tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya [4]. Misalnya, syarat khuf yang boleh diusap sebagai ganti dari mencuci kaki adalah khufnya tidak bercelah (berlobang) yang menyebabkan telapak kaki terlihat. Penentuan syarat-syarat tersebut kurang tepat, karena pembolehannya disebutkan secara umum. Mengkhususkan sesuatu yang disebutkan secara umum oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, beresiko menimbulkan kesulitan kepada hamba Allah ﷻ dalam hal-hal yang diberi keleluasaan oleh Allah ﷻ.
- Nabi ﷺ menjelaskan bahwa mengkonsumsi daging unta termasuk pembatal wudhu, seperti dalam hadis riwayat Abu Sawud rahimahullah:
عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْوُضُوْءِمِنْ لُحُوْمِ اْلإِبِلِ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوامِنْهَا
Dari Al-Barra’ bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang berwudhu (setelah selesai) dari makan daging unta, maka beliau bersabda: berwudhulah darinya. [5]
Yang terpahami dari hadis ini adalah makan daging unta bisa membatalkan wudhu, baik daging unta yang masih mentah atau sudah matang. Karena Rasulullah ﷺ menyebutkan makan daging unta secara umum [6]. Dan perkataan yang datang secara umum, kita pahami sesuai keumumannya kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Dan perkataan yang datang secara khusus maka dipahami sesuai kekhususannya.
- Tentang pembebasan budak Kaffarah (denda) pembunuhan. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
“Dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (tidak sengaja, maka hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.” [QS. an-Nisa/4:92]
Dalam ayat ini, Allah ﷻ menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimerdekakan adalah hamba sahaya yang beriman. Maka tidak boleh membayar Kaffarah pada kasus pembunuhan dengan membebaskan budak non Muslim. Karena Allah ﷻ telah mengkhususkan budak yang beriman pada ayat ini. Dan hal-hal yang telah dijelaskan kekhususannya maka wajib difahami sesuai kekhususannya tersebut [7].
Dalam pembahasan kaidah ini, perlu dipahami bahwa adakalanya sebuah perkataan dihukumi bersifat khusus meskipun secara lahiriah bersifat umum, karena ada sebab tertentu yang menuntut demikian. Marilah kita perhatikan contoh-contoh kasus berikut:
- Apabila seorang suami melihat istrinya berbincang dengan lelaki lain. Lalu si suami tersebut mentalak istrinya karena menyangka bahwa lelaki itu bukan mahram istrinya. Setelah dia tahu bahwa lelaki tersebut adalah mahram istrinya. Maka dalam kasus ini, talaknya tidak jatuh. Meskipun talak yang diucapkan suami bersifat umum tetapi dihukumi secara khusus karena sebab tertentu. Dalam kasus ini, suami mentalak istrinya karena mengira lelaki yang berbincang-bincang dengan istrinya itu bukan mahramnya, namun ternyata dugaan itu tidak terbukti.
- Apabila Ahmad bersumpah tidak akan bertegur sapa dengan Zaid karena mengira Zaid adalah orang yang telah menzaliminya. Kemudian terbukti bukan Zaid. Apabila kemudian Ahmad menyapa Zaid, maka dalam kasus ini, Ahmad tidak dihukumi telah melanggar sumpah. Meskipun sumpah yang diucapkan Ahmad tersebut secara lahiriah bersifat umum, namun dihukumi khusus karena sebab tertentu [8].
Berkaitan dengan pembahasan kaidah ini pula, Para ulama menjelaskan, bahwa pengkhususan suatu perkataan diterima apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syari, baik Alquran maupun as-Sunnah. Jika bertentangan dengan ketentuan syari maka pengkhususan tersebut tidak bisa diterima [9]. Dengan demikian bisa dipahami, apabila seseorang mewakafkan hartanya khusus untuk pelaku kebidahan, atau untuk orang yang berbuat maksiat, atau khusus untuk pengikut madzhab tertentu maka persyaratan dan pengkhususan semisal itu tidaklah dianggap. Wallahu a’lam [10].
_______
Footnote
[1]. Lihat Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul, Imam Muhammad bin Ali Ay-Syaukani, Tahqiq Abu Hafs Sami bin al-Arabi al-Atsari. Cet.1 Tahun 1421H/2000M Darul Fadhilah hlm.711
[2]. Lihat Syarhul Qawaa’id As-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil. Dar Athlas al Kahadhra’, hlm.192
[3]. HR. Muslim dalam Kitabut Thaharah, bab at-Tauqif fil Mashi’alal Khuffaini, no. 85
[4]. Lihat as-Syarhul Mumti (1/232-233). Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin.cet.1 Tahun 1422H. Dar Ibnil Jauzi.
[5]. HR Abu Daud dalam Kitabut Thaharah, bab al Wudhu min Luhumil Ibil, no. 184. Hadis ini diShahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam Shahih sunan At-Tirmidzi no. 81
[6]. Sebagian ulama berpendapat bahwa makan daging unta yang membatalkan wudhu adalah apabila daging tersebut masih mentah, adapun makan daging unta yang telah dimasak maka tidak membatalkan wudhu. (Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, 43/397-398 Cet Ke-2 1404H/1983M Wizaratul Auqaf was Syu-un al-Islamiyah. Kuwait
[7]. Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, 38/122-123
[8]. Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah terhadap kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Cet. Ke-1 tahun 2002M. Maktabah as-Sunnah. Kairo hlm. 138-139
[9]. Lihat Syarhul Qawa’id as Sa’diyah. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah Az Zamil. Dar Athlas al Kahadhra lil Nasyri wat Tauzi hlm. 196
[10]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasimil Badi’ah an-Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh. Hlm. 80. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya
Kaidah Ke-30: Orang Yang Berserikat, Saling Menanggung Penambahan, Pengurangan Dan Perbaikan
Kaidah Ketiga Puluh
الشُّرَكَاءُ فِي اْلأَمْلاَكِ يَشْتَرِكُوْنَ فِي زِيَادَتِهَا وَنُقْصَانِهَا, وَيَشْتَرِكُوْنَ فِي التَّعْمِيْرِ اللاَّزِمِ وَتُقَسَّطُ عَلَيْهِمُ الْمَصَارِيْفُ بِحَسَبِ مِلْكِهِمْ وَمَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ يَتَسَاوَوْنَ
Orang-orang yang berserikat dalam kepemilikan suatu barang, saling menanggung penambahan dan pengurangan benda tersebut, dan bersama-sama menanggung perbaikan yang bersifat wajib. Dan hak masing-masing dibagi sesuai kadar kepemilikan mereka. Adapun jika kadar kepemilikan masing-masing tidak diketahui maka dibagi rata di antara mereka.
Kaidah ini menjelaskan tentang orang-orang yang berserikat dalam kepemilikan suatu benda. Mereka ini, sama-sama menerima untung jika ada penambahan nilai pada barang tersebut, namun jika sebaliknya, maka mereka sama-sama menanggung kerugian. Demikian pula, jika benda itu perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya ditanggung bersama-sama. Prosentase keuntungan dan kerugian sesuai dengan prosentase kepemilikannya terhadap benda yang dimiliki secara bersama-sama itu.
Penambahan tersebut bisa berupa penambahan dari sisi zatnya, sifatnya, tambahan yang terpisah atau tambahan yang menyatu dengan benda yang mereka miliki, demikian pula tambahan dari hasil usahanya [1].
Penerapan kaidah ini dapat diketahui dari contoh-contoh kasus, di antaranya:
- Apabila sebuah rumah dimiliki oleh dua orang. Salah satunya memiliki sepertiga dan yang lainnya memiliki dua pertiga dari rumah tersebut. Jika nilai jual rumah itu bertambah, maka tambahan ini menjadi milik bersama sesuai dengan prosentase kepemilikan masing-masing [2]. Sebaliknya jika terjadi kerusakan, dan salah satu pemiliknya ingin rumah itu diperbaiki, maka pemilik lainnya wajib ikut andil dalam perbaikan tersebut [3].
- Jika beberapa hewan ternak dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka biaya pemeliharaannya ditanggung berdua sesuai dengan kadar kepemilikannya. Artinya, yang kadar kepemilikan setengah, ia wajib menanggung setengah dari seluruh biaya. Dan, yang kadar kepemilikan sepertiga, ia wajib menanggung 1/3 dari seluruh biaya pemeliharaan [4].
- Jika sebidang tanah atau sebuah rumah diwakafkan untuk beberapa orang. Kemudian tanah atau rumah tersebut rusak dan perlu biaya perbaikan. Maka biaya tersebut ditanggung bersama [5].
- Apabila dua orang sepakat membangun dinding pembatas antara rumah mereka, kemudian dinding tersebut rusak. Lalu mereka berselisih tentang siapakah yang berkewajiban memperbaikinya. Maka, dalam masalah ini yang wajib memperbaiki adalah mereka berdua, karena mereka memanfaatkannya bersama [5].
- Beberapa ekor kambing yang dimiliki dua orang, kemudian jumlahnya bertambah karena ada yang melahirkan, atau kambing tersebut memproduksi susu. Maka tambahan tersebut menjadi milik bersama sesuai prosentase kepemilikan masing-masing. Ini adalah contoh an-nama’ al-munfashil (tambahan yang terpisah).
- Jika seekor ternak dimiliki dua orang, lalu hewan itu semakin gemuk. Ini berarti nilai jualnya bertambah. Pertambahan nilai jual ini menjadi milik mereka berdua. Ini adalah contoh an-Nama’ul muttashil (pertambahan yang menyatu dengan yang asli).
- Seseorang yang mahjur ‘alaihi (yang dilarang mengelola hartanya) karena bangkrut dan berkewajiban melunasi utang. Jika harta yang ia punya tidak cukup untuk melunasi utang, maka masing-masing orang yang mengutangi diambilkan dari harta tersebut sesuai kadar besarnya utang dari mereka [7].
- Apabila di antara dua rumah ada dinding yang membatasi dan dimanfaatkan bersama oleh kedua pemilik rumah tersebut, kemudian salah satunya ingin memasang atap atau memasang tiang pada dinding tersebut, maka yang lain tidak boleh melarangnya. Dengan syarat, pemasangan atap atau tiang tersebut tidak menimbulkan madharat dan dengan izin terlebih dahulu [8].
Sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk memasang kayu di dinding rumahnya.” [9]
Berkaitan dengan pembahasan kaidah ini, adakalanya kadar kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tidak diketahui dengan jelas. Jika ini terjadi, maka bagian masing-masing dianggap sama. Misalnya, seseorang mewakafkan atau mewasiatkan tanahnya untuk beberapa orang tanpa menentukan bagian masing-masingnya, maka dalam kasus ini kadar untuk masing-masing orang disamakan, tanpa melebihkan salah seorang dari yang lainnya. Wallahu a’lam. [10]
_______
Footnote
[1]. Lihat macam-macam an-nama’ (penambahan) dalam al-Mausu’atul Fiqhiyyah, 41/369-370. Cet. Kedua. 1404 H/1983 M. Wizaratul Auqaf was Syu-un al-Islamiyah. Kuwait.
[2]. Lihat Syarhul Qawa’idis Sa’diyah, hlm. 197. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil.
[3]. Lihat ta’liq Syaikh al-Utsaimin terhadap kitab al-Qawa’id wa al-Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, hlm. 140. Cet. Pertama. Tahun 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo.
[4]. Ibid.
[5]. Lihat Syarhul Qawa’idis Sa’diyah, hlm. 198. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil.
[6]. Lihat Taqrirul Qawa’id wa Tahrirul Fawa-id, 2/81. al-Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali. Ta’liq Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Cet. Pertama. 1419 H/1998 M. Dar Ibni Affan lin nasyr wat tauzi’. Khubar.
[7]. Syaikh Ibnu Utsaimin mencontohkan, jika total utangnya Rp. 10.000, dengan rincian Rp. 5.000,- dari A, Rp. 3.000,- dari B, dan Rp. 2.000,- dari C. Sedangkan harta yang bisa digunakan untuk bayar utang hanya sejumlah 5.000. Maka A diberi Rp. 2.500, B diberi Rp. 1.500, dan C diberi Rp. 1.000.
[8]. Lihat Syarhul Qawa’idis Sa’diyah, hlm. 198. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil.
[9]. HR. al-Bukhari, no. 2463; Muslim, no. 1609.
[10]. Diangkat dari al-Qawa’id wa al-Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh. Hlm. 81-82. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-31: Adakalanya Terjadi Perbedaan (Pemilahan) Hukum Dikarenakan Perbedaan Sebab
Kaidah Ketiga Puluh Satu
قَدْ تَتَبَعَّضُ اْلأَحْكَامُ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ أَسْبَابِهَا
Adakalanya Terjadi Perbedaan (Pemilahan) Hukum Dikarenakan Perbedaan Sebab
Kaidah yang mulia ini mempunyai implementasi yang cukup banyak dalam pembahasan fiqih. Kaidah ini menjelaskan tentang keberadaan hal-hal yang dalam kondisi tertentu status hukumnya bisa berubah atau perlu dirinci. Di antara dalil yang menunjukkan eksisitensi kaidah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ﷺ bersabda:
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ, وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةَ
“Dia saudaramu wahai ‘Abdu bin Zam’ah. Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang (suami) dan pezinanya mendapatkan kerugian. Dan berhijablah darinya wahai Saudah.” [1]
Latar belakang sabda Nabi ﷺ tersebut berkaitan dengan perselisihan antara ‘Abdu bin Zam’ah dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Ayah ‘Abdu, yaitu Zam’ah termasuk pembesar kaum Quraisy, ayah Saudah (istri Nabi). Zam’ah mempunyai budak wanita bernama Walidah. Di masa jahiliyah, budak wanita tidak merasa malu untuk berbuat zina. Maka terjadilah perzinaan antara ‘Utbah bin Abi Waqqash (saudara Sa’ad bin Abi Waqqash) dengan Walidah. Beberapa waktu kemudian Walidah hamil. Dalam kasus ini ada kemungkinan ia hamil karena hasil hubungannya dengan ‘Utbah dan ada kemungkinan pula dari hubungannya dengan tuannya. Namun, ‘Utbah yakin bahwa anak yang dikandung itu adalah hasil hubungannya dengan Walidah. Selang beberapa waktu kemudian, Walidah melahirkan seorang anak yang mirip dengan ‘Utbah.
Menjelang kematian, ‘Utbah berpesan kepada saudaranya yaitu Sa’ad bin Abi Waqqash agar mengambil anak tersebut karena dia yakin anak itu anaknya.
Ketika terjadi penaklukkan kota Mekah, Sa’ad pergi menemui anak-anak Zam’ah untuk mengambil anak tersebut. Namun, anak-anak Zam’ah tidak mau menyerahkannya karena menganggap anak itu adalah saudara mereka dan anak dari budak ayah mereka. Lalu Sa’ad dan salah seorang anak Zam’ah yaitu ‘Abdu mengadu kepada Rasulullah ﷺ. Lalu, Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa anak itu adalah anak Zam’ah, meskipun anak itu lebih mirip dengan ‘Utbah. Meski Rasulullah ﷺ telah memutuskan anak itu adalah saudara ‘Abdu, namun Rasulullah ﷺ juga memerintahkan kepada saudari ‘Abdu yaitu Saudah agar menjaga hijab dari anak itu. Hal ini untuk lebih berhati-hati, karena anak itu lebih mirip dengan ‘Utbah dan ada kemungkinan seperti itu.
Maka dari sini dapat diketahui adanya pembagian atau perincian hukum. Di mana kelaziman dari hubungan persaudaraan adalah keduanya mahram dan saling mewarisi namun dalam kasus tersebut ternyata hubungan mahram dibatasi karena adanya sebab tertentu.
Di antara penerapan dan implementasi kaidah ini dapat diketahui dari contoh-contoh kasus berikut:
- Berkaitan dengan kasus pencurian. Apabila seseorang menuduh orang lain melakukan pencurian, padahal ia hanya mempunyai seorang saksi laki-laki atau dua orang saksi perempuan. Kemudian ia bersumpah disertai persaksiaan seorang laki-laki atau dua orang perempuan itu. Jika ini terjadi, berarti pencurian itu telah terbukti dan si terdakwa berkewajiban mengembalikan harta yang didakwakan kepadanya. Karena dalam permasalahan harta, keberadaan seorang saksi laki-laki atau dua orang saksi perempuan disertai sumpah si penuduh sudah cukup sebagai bukti. Namun, ini tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi potong tangan kepada si pelaku, karena sanksi ini bisa diterapkan kecuali dengan persaksian dua orang saksi laki-laki. [3]
Konsekuensi awal dari pencurian adalah pengembalian harta yang dicuri dan hukum potong tangan. Dalam kasus di atas, syarat untuk pengembalian harta sudah terpenuhi, sedangkan syarat potong tangan belum terpenuhi. Inilah yang dimaksud dengan taba’ud (pemilahan) sebuah hukum karena sebab tertentu. Dalam hal ini yaitu perbedaan saksi.
- Hubungan ayah dan anak adalah lazimnya menjadi mahram, saling mewarisi dan berkewajiban memberikan nafkah. Namun ini tidak berlaku bagi anak susuan dengan bapak. Meski mereka berdua adalah mahram, namun mereka tidak saling mewarisi dan tidak pula wajib memberikan nafkah. [4]
- Apabila seorang lelaki berzina dengan seorang wanita sampai melahirkan anak, maka haram bagi si lelaki tersebut untuk menikahi anak hasil zina tersebut. Meskipun status nasab anak itu tidak disandarkan kepada lelaki tersebut dan tidak ada hubungan mahram antara keduanya tetapi tetap saja haram untuk dinikahkan. [5]
- Berkaitan dengan kasus khulu’ [6]. Apabila seorang suami menyatakan bahwa ia telah mengkhulu’ istrinya dengan tebusan sejumlah harta yang harus diserahkan oleh si istri kepadanya. Jika sang suami berani bersumpah untuk menegaskan bahwa khulu’ itu telah terjadi disertai persaksian seorang laki-laki, maka si istri telah berkewajiban menyerahkan harta yang disebutkan sang suami. Karena untuk yang berkaitan dengan harta, keberadaan seorang saksi laki-laki dan sumpah si penuduh sudah cukup sebagai bukti. Adapun perpisahan suami-istri tersebut dengan status khulu’ bukan karena keberadaan saksi tersebut tetapi karena pengakuan si suami. Karena penetapan khulu’ ditentukan dengan dua orang saksi laki-laki.
Berbeda halnya jika yang menyatakan terjadinya khulu’ dari pihak istri, padahal ia hanya memiliki seorang saksi laki-laki. Meskipun dia berani bersumpah untuk menguatkan saksi, namun khulu’ tetap tidak terjadi. Karena dalam kasus ini si istri tidak menuntut harta, namun menuntut adanya khulu’, sementara khulu’ tidak terwujud kecuali dengan dua orang saksi. [7]
- Tentang penisbatan seorang anak kepada orang tuanya. Secara umum, seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya dari sisi nasab, bukan kepada ibunya. [8] Apabila anak tersebut bernama Zaid, ayahnya bernama Ahmad, dan ibunya bernama Fatimah, maka dikatakan Zaid bin Ahmad, bukan Zaid bin Fatimah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma:
إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ, فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنٍ
“Sesungguhnya orang yang berkhianat ditegakkan baginya bendera pada Hari Kiamat, dan dikatakan, “Ini adalah pengkianatan yang dilakukan Fulan bin Fulan.” [9]
Adapun berkaitan dengan status si anak, apakah berstatus sebagai orang merdeka ataukah budak, maka ini ditentukan status ibunya. Sehingga, apabila seorang laki-laki menikahi budak wanita, maka anak mereka berstatus sebagai budak. [10] Sebaliknya, jika seorang budak laki-laki menikah dengan seorang wanita merdeka, maka anak mereka berstatus sebagai orang merdeka.
Sedangkan masalah agama si anak, maka itu dinisbatkan kepada agama terbaik kedua orang tuanya. Apabila seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, maka si anak mengikuti agama ayahnya yaitu agama Islam. Oleh karena itu, seandainya anak tersebut meninggal, maka ia dimandikan, dikafani, dan disalatkan, serta dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin.
Dari sini terlihat adanya pemilahan hukum berkaitan dengan hubungan anak dengan orang tuanya dikarenakan ada perbedaan sebab.
- Binatang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara binatang yang halal dan yang haram. Dalam hal ini, maka anak hasil perkawinan tersebut dihukumi haram. Misalnya bighal yang merupakan hasil perkawinan antara kuda yang halal dimakan dengan keledai yang haram dimakan. Bighal yang merupakan perkawinan silang kuda dengan keeledai ini haram dimakan. Karena sisi keharaman lebih dikedepankan daripada sisi kehalalannya. [11]
- Berkaitan dengan masalah syahadah (persaksian). Apabila seorang anak memberikan persaksian yang menguntungkan bagi orang tuanya, maka persaksiannya tidak diterima. Karena ada unsur tuhmah, yaitu ada kemungkinan keberadaan anak tersebut memang sengaja ingin menguntungkan orang tuanya padahal persaksian tersebut tidak sesuai fakta. Berbeda hal jika persaksian tersebut merugikan, maka persaksiannya diterima. Demikian pula, persaksian orang tua untuk anaknya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.” [QS. an-Nisa’/4:135]
Sebaliknya, orang yang memberikan persaksian yang menguntungkan bagi pihak lawan, maka persaksiannya diterima, jika merugikan, maka ditolak.
Dari sini dapat diketahui perbedaan hukum dalam persaksian karena perbedaan sifat persaksian yang diberikan.
- Apabila seseorang menjual satu paket barang yang terdiri dari dua barang, salah satunya haram dijual dan yang lainnya mubah. Maka transaksinya pada barang yang mubah itu sah, sedangkan pada barang yang haram itu tidak sah. Misalnya seseorang menjual satu wadah khamr dan satu wadah sirup dengan satu harga. Maka transaksi jual beli pada wadah sirup itu sah, sedangkan pada wadah khamr tidak sah. Dan dalam kasus ini tidak dihukumi dengan memenangkan sisi keharaman atas sisi kehalalan karena kedua barang tersebut bisa dipisahkan. [13]
Wallahu a’lam. [14]
_______
Footnote
[1]. HR. al-Bukhari, no. 2053 dan Muslim, no. 1457.
[2]. Lihat penjelasan hadis di atas dalam Syarh Shahih Muslim (9/279-281). Imam Muhyiddin an-Nawawi. Cet. Ke-XIV. Tahun 1428 H/2007 M. Daar al-Ma’rifah. Beirut.
[3]. Lihat Syarhul Qawa’idis Sa’diyah. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil. Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa-at-Tauzi’. Hlm. 199-200.
[4]. Lihat al-Mausu’atul Fiqhiyyah (22/241). Cet. Ke-2. 1404 H/1983 M.
[5]. Lihat rubrik Mabhats majalah As-Sunnah berjudul Status Anak Zina, edisi 09 th. XII hlm. 28.
[6]. Khulu’ adalah apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan sejumlah harta yang diserahkan istri kepadanya. (Lihat Mu’jam Lughah al-Fuqaha. Prof. Dr. Muhammad Rawas Qal’ah Jiy dan Dr. Hamid Shadiq Qunaibi. Cetakan kedua. Tahun 1408 H/1988 M. Dar an-Nafais. Beirut. Pada kata ( الخلع ).
[7]. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah. Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil. Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa-at-Tauzi’. Hlm. 200.
[8]. Kecuali Nabi Isa bin Maryam Alaihissallam. Beliau dinasabkan ke ibunya karena beliau rahimahullahidak memiliki ayah. (Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin terhadap atas kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat-Taqasimul Badi’ah an-Nafi’ah. Cet. I. Tahun 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo. Hlm. 144)
[9]. HR. al-Bukhari, no. o. 6178 dan Muslim, no. 1735.
[10]. Oleh karena itu haram hukumnya seorang laki-laki merdeka menikahi budak wanita, karena anak hasil hubungan mereka nantinya akan berstatus sebagai budak. (Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin atas kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat-Taqasimul Badi’ah an-Nafi’ah. Cet. I. Tahun 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo. Hlm. 145).
[11]. Lihat Minhajul Muslim. Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Tahun 2002 M. Hlm. 408.
[12]. Lihat as-Syarhl Mumti’ ‘ala Zadil Mustaqni’ (15/434-435). Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin. Cet. I. Tahun 1422 H. Dar Ibni al-Jauzi. Damam.
[13]. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menjelaskan bahwa dalam kasus ini pembagian harga kedua barang ditentukan dengan menganggap khamr itu sirup, bukan dengan harga khamr karena khamr tidak ada nilai secara syari. (Lihat ta’liq Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin atas kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat-Taqasimul Badi’ah an-Nafi’ah. Cet. I. Tahun 2002 M. Maktabah as-Sunnah. Kairo. Hlm. 146
[14]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat-Taqasimul Badi’ah an-Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh. Hlm. 83-84. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-32: Menunaikan Kewajiban Orang Lain Dengan Niat Mendapatkan Ganti
Kaidah Ketiga Puluh Dua
مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا بِنِيَّةِ الرُّجُوْعِ عَلَيْهِ رَجَعَ وَإِلاَّ فَلاَ
Barang siapa menunaikan kewajiban orang lain dengan niat mendapatkan gantinya maka ia berhak mendapatkannya, dan jika dia tidak meniatkan demikian maka dia tidak berhak mendapatkan gantinya
Makna Kaidah
Kaidah ini menjadi patokan dalam kasus seseorang yang menunaikan kewajiban orang lain yang berkaitan dengan harta. Apabila ia melakukannya dengan niat meminta ganti kepada yang terbeban kewajiban maka ia berhak untuk mendapatkan gantinya. Namun jika ia melakukannya dengan niat Tabarru’ (sedekah) bukan mengharapkan ganti, atau tanpa meniatkan sesuatu secara khusus [1] maka ia tidak berhak mendapatkan ganti harta dari pemilik kewajiban. [2]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” [QS. ath-Thalaq/65:6]
Ayat ini menjelaskan tentang seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya sementara keduanya memiliki anak yang masih harus disusui. Jika anak tersebut tetap disusui oleh ibunya, maka si ibu berhak mendapat upah atas susuannya tersebut. [3] Karena yang berkewajiban mencarikan susuan si anak adalah bapaknya. Dan karena si ibu telah menjalankan kewajiban ayah si anak, maka dia berhak mendapat upah dari ayah anak tersebut.
Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan: “Makna ayat ini, jika istri tersebut telah melahirkan anaknya sedangkan ia dalam keadaan ditalak, maka dengan kelahiran tersebut statusnya telah menjadi thalaq bain [4] karena masa iddahnya telah selesai. Dan boleh baginya untuk menyusui anak tersebut, boleh pula ia menolak, setelah anak tersebut diberikan liba’ [5], yaitu ASI yang pertama kali keluar dari ibunya yang umumnya bisa menambah kekuatan anak. Apabila ia tetap menyusui anaknya maka ia berhak mendapatkan upah sewajarnya.” [6]
Demikian pula Allah ﷻ berfirman:
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
“Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.” [QS. at-Taubah/9:91]
Ayat ini merupakan dalil umum tentang berhaknya seseorang mendapatkan ganti apabila ia menunaikan kewajiban orang lain yang berkait dengan harta dengan niat untuk mengambil ganti dari orang yang mempunyai kewajiban. [7]
العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ
Orang yang meminta kembali pemberian yang telah ia berikan seolah-olah seperti anjing yang memuntahkan sesuatu lalu mendatangi kembali muntahan itu dan memakannya. [8]
Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang menunaikan kewajiban orang lain yang berkait dengan harta dengan niat Tabarru’ maka ia tidak berhak meminta ganti kepada pemilik kewajiban.
Contoh Penerapan Kaidah
Contoh penerapan kaidah ini cukup banyak sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya:
- Apabila Ahmad mempunyai tanggungan utang pada Hasan. Kemudian Zaid melunasi utang tersebut tanpa sepengetahuan Ahmad. Dikemudian hari, muncul permasalahan, apakah Zaid berhak meminta ganti kepada Ahmad? Berdasarkan kaidah ini, maka perlu perincian. Jika saat pelunasan, Zaid berniat meminta ganti kepada Ahmad, maka ia berhak untuk meminta ganti kepada Ahmad. Namun, jika ia tidak berniat seperti itu, maka ia tidak berhak meminta ganti kepada Ahmad. [9]
- Apabila Ali meninggalkan keluarganya selama beberapa waktu untuk suatu keperluan. Suatu ketika, anak dan istrinya kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Kemudian Zaid menyerahkan sejumlah harta ke anak dan istri Ali untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila ketika menyerahkan harta itu, ia berniat meminta ganti kepada Ali, maka ia berhak meminta ganti darinya. Namun jika ia niatkan sedekah, maka ia tidak berhak meminta ganti dari Ali. [10]
- Berkaitan dengan barang gadaian. Jika Ahmad berutang kepada Hasan dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan. Dengan demikian, berarti status sepeda motor itu menjadi barang gadai. Dalam kasus ini, jika barang gadai tersebut membutuhkan biaya perawatan selama berada ditangan Hasan, maka Hasan berhak meminta ganti biaya yang dikeluarkannya tersebut kepada Ahmad jika saat mengeluarkan biaya tersebut ia berniat meminta ganti. Namun jika ia berniat suka rela tanpa mengharapkan imbalan maka ia tidak berhak meminta ganti. [11]
- Berkaitan dengan permasalahan wadi’ah (barang titipan). Apabila Ali menitipkan barang yang memerlukan biaya perawatan kepada Zaid. Jika Ali mengeluarkan biaya perawatan barang tersebut dengan niat meminta ganti kepada Zaid maka ia berhak meminta gantinya. Namun jika tidak berniat seperti itu maka ia tidak berhak mendapatkannya. [12]
- Berkaitan dengan permasalahan Luqathah (barang temuan). Apabila Ahmad menemukan barang temuan yang memerlukan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan, seperti hewan ternak atau semisalnya. Jika Ahmad mengeluarkan biaya perawatan itu dan saat mengeluarkannya dia berniat untuk meminta ganti ke pemilik barang jika sang pemiliknya datang, maka Ahmad berhak meminta ganti. Namun jika tidak berniat demikian, maka ia tidak berhak menuntut ganti biaya tersebut. [13]
Keterangan Tambahan:
Para ulama menjelaskan, bahwa kewajiban orang lain yang berkaitan dengan harta yang bisa ditunaikan oleh orang lain hanya terbatas pada kewajiban-kewajiban yang tidak disyaratkan niat dari orang yang mempunyai kewajiban tersebut. Jika kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban yang syarat sahnya niat dari orang yang bersangkutan, maka kewajiban itu tidak bisa bisa gugur jika ditunaikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan orang memiliki kewajiban tersebut. Karena kewajiban itu tidak bisa digugur, maka orang yang menunaikannya tidak berhak mendapatkan ganti sama sekali. Di antara kewajiban-kewajiban yang membutuhkan niat dari orang yang memiliki kewajiban adalah zakat, Kaffarah, nadzar dan semisalnya. [14]
Misalnya apabila Ali mempunyai kewajiban membayarkan zakat hartanya. Kemudian Zaid membayarkan zakat tersebut tanpa sepengetahuan Ali dan tanpa izinnya. Dalam hal ini, kewajiban Ali belum gugur karena ketika zakat itu ditunaikan tidak disertai niat dari Ali. Konsekuensi berikutnya, Zaid adalah tidak berhak meminta ganti dari Ali karena kewajiban zakat belum gugur. [15]
Wallahu a’lam. [16]
_______
Footnote
[1]. Yaitu tidak berniat untuk meminta ganti dan tidak pula berniat Tabarru’ (sumbangan).
[2]. At-Ta’liq ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah wal Furuq wat Taqasiml Badi’atin Nafi’ah, hlm. 189-190.
[3]. As-Syarhul Mumti’ 13/515-516.
[4]. Thalaq bain adalah perceraian yang mana si suami tidak bisa lagi meruju’ mantan istrinya. (Minhajul Muslim, hlm. 353)
[5]. Liba’ adalah Air Susu Ibu yang pertama setelah melahirkan. (al-Mausu’atul Fiqhiyyah 35/191).
[6]. Tafsir Alquranil ‘Azhim, 4/2870.
[7]. Penjelasan Syaikh Khalid al-Musyaiqih dalam ceramah beliau mensyarah kitab Manzhumah al-Qawa’id al-Fiqhiyah karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di di situs beliau www.almoshaiqeh.com pada penjelasan bait ke-46:
ومـن يــؤد عـن أخـيه واجبــا له الرجــوع إن نــوى يـطالبــا
[8]. HR. al-Bukhari no. 2589 dan Muslim no. 1622.
[9]. Lihat Syarhul Qawa’id as-Sa’diyah, hlm. 202.
[10]. Lihat Taqrirul Qawa’id wa Tahrirul Fawaid 2/77.
[11]. Idem, 2/82.
[12]. Lihat Tuhfatu Ahlit Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab, hlm. 78.
[13]. Idem.
[14]. at-Ta’liq ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah wal Furuq wat Taqasiml Badi’atin Nafi’ah, hlm. 190.
[15]. Oleh karena itulah Syaikh Muhammad bin Saleh al Utsaimin t memberikan taqyid (batasan atau syarat) terhadap kaidah ini dengan perkataan( إن برئ الغير به ) (apabila penunaian itu menyebabkan kewajiban orang lain yang ditunaikan itu gugur). (at-Ta’liq ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah, hlm. 89)
[16]. Diangkat dari kitab al Qawa’id wal Ushulil Jami’ah wal Furuq wat Taqasiml Badi’atin Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh. Hlm. 84. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-33: Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat Yang Lebih Besar Harus Didahulukan
Kaidah Ketiga Puluh Tiga
إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ اْلأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ اْلأَخَفُّ مِنْهَا
Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus, red), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah ﷻ. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi.
Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa masfsadat (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Dalil yang mendasari kaidah ini di antaranya adalah firman Allah ﷻ:
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
“Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan.” [QS. al-Baqarah/2:148]
Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Pada ayat ini Allah ﷻ memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali suatu hal itu lebih baik, maka kita diperintahkan untuk bersegera kepadanya (untuk melakukannya).” [2]
Demikian pula firman Allah ﷻ:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
“Dan janganlah kamu memaki Sesembahan-Sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” [QS. al An’am/6:108]
Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Pada ayat ini disebutkan berkumpulnya dua mafsadah (keburukan). Mafsadah yang pertama adalah meninggalkan celaan terhadap Sesembahan orang-orang musyrik. Mafsadah yang kedua adalah celaan (balasan) orang-orang musyrik kepada Allah ﷻ. Dan telah maklum bahwa celaan kepada Allah ﷻ lebih besar keburukannya daripada meninggalkan celaan kepada Sesembahan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Allah ﷻ melarang dari mencela SeSembahan orang-orang musyrik jika hal itu menyebabkan mereka mencela Allah ﷻ Rabbul ‘Alami.” [3]
Demikian pula kisah Khidhir Alaihissallam dan Nabi Musa Alaihissallam ketika mereka naik perahu dan kemudian Khidhir Alaihissallam merusak perahu tersebut. [4] Telah dimaklumi bahwa merusak perahu merupakan keburukan. Akan tetapi, Khidhir Alaihissallam menghendaki supaya perahu tersebut selamat dari perbuatan raja zalim yang suka merampas setiap perahu yang bagus. Maka, merusak perahu tersebut adalah mafsadah (merugikan), tetapi dirampasnya perahu tersebut lebih besar mafsadahnya (kerugiannya). Sedangkan jika perahu itu rusak, namun masih menjadi milik si empunya maka itu lebih ringan. Sehingga ditempuh mafsadah yang lebih ringan. [5]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Di antaranya:
- Apabila seseorang mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan ia ingin bersedekah kepada fakir miskin, sementara hartanya hanya cukup untuk membayar utang. Dalam kasus ini ada dua maslahat (kebaikan) yaitu membayar utang dan bersedekah kepada orang fakir sementara kondisi tidak memungkin dia untuk melakukan keduanya sekaligus. Mana yang harus dipilih? Yang wajib baginya adalah mendahulukan pembayaran utang. Karena membayar utang hukumnya wajib sedangkan bersedekah hukumnya sunnah. dan perkara wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah.
- Dalam masalah pengingkaran kemungkaran. Jika pengingkaran terhadap suatu kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka diperbolehkan untuk tidak mengingkarinya dengan tangan atau lisan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang artinya, “Dari Abu Sa’id al Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tak mampu juga, maka dengan hatinya, dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. [7]
Disebutkan pula dalam kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau dan salah seorang sahabatnya berpapasan dengan sekelompok orang Tatar yang sedang minum khamr. Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mencegah mereka minum khamr. Sahabatnya bertanya, mengapa beliau rahimahullah tidak mencegah mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab bahwa, jika mereka tidak minum khamr mereka akan melecehkan kehormatan kaum Muslimin dan merampas harta mereka dan itu kezaliman yang lebih besar karena berkaitan dengan orang lain. Sedangkan perbuatan mereka minum khamr itu kemungkaran yang hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri. [8]
- Apabila seseorang bernadzar untuk melaksanakan haji, sementara ia belum melaksanakan haji yang merupakan rukun Islam. Disini juga ada dua maslahat yaitu melaksanakan haji nadzar dan haji Islam, sementara kondisi tidak memmungkin dia mengerjakan dua-duanya dalam satu waktu. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah haji Islam, setelah baru melaksanakan haji yang telah ia nadzarkan. Meski keduanya sama-sama wajib, namun haji Islam lebih wajib daripada haji nadzar. [9]
- Jika seseorang ingin berangkat jihad, yaitu jihad yang belum sampai pada tingakatan Fardhu Ain, tetapi ia dilarang oleh orang tuanya. Maka, dalam kondisi ini, ia harus mendahulukan bakti kepada orang tua daripada jihad. [10] Apalagi jika orang tuanya sangat membutuhkan bantuannya. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, “Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, amalan apakah yang paling mulia?” Beliau ﷺ menjawab: “Salat pada waktunya.” Aku bertanya lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua.” Aku bertanya lagi: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Jihad di jalan Allah.” [11]
- Hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk atau rajam bagi pelaku zina dan hukuman Qishash, semua hukum ini merupakan mafsadat bagi si terhukum. Namun, jika hukuman tersebut tidak ditegakkan maka mafsadat yang lebih besar akan timbul seperti tersebarnya kekejian, hilangnya rasa aman, pembunuhan dan keburukan-keburukan lainnya. Oleh karena itu, mafsadat yang lebih kecil itu ditempuh untuk mencegah mafsadat yang lebih bersar. [12]
- Apabila seorang wanita berada di negeri kafir, dan ia ingin hijrah ke negeri Islam, namun dia tidak memiliki mahram yang menemaninya. Bagi wanita ini, pergi tanpa mahram, itu adalah mafsadat, namun jika ia tetap tinggal di negeri tersebut, maka mafsadatnya lebih besar, karena dapat merusak agamanya. Dalam hal ini, hendaknya ia hijrah dari negeri tersebut, bahkan wajib baginya untuk hijrah meskipun tanpa mahram. Dan dipilih mafsadat yang lebih kecil untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. [13]
Keterangan Tambahan:
Sebagian ulama mengemukakan satu isykal (permasalahan) berkaitan dengan kaidah ini. Mereka mengatakan bahwa kaidah ini tidak bisa diterapkan dalam setiap keadaan. Misalnya, dalam kasus sekelompok orang yang sedang naik perahu, dan dikhawatirkan perahu tersebut akan tenggelam, kecuali jika salah satu penumpangnya dikeluarkan darinya. Dalam kasus ini, para ulama sepakat bahwa tidak boleh mengeluarkan salah satu penumpang agar muatan perahu menjadi ringan sehingga para penumpang lainnya selamat. Dalam kasus ini, tidak dipilih mafsadah yang lebih kecil (dengan mengorbankan satu orang, red) untuk menghindari mafsadah yang lebih besar (kematian seluruh penumpang, red).
Demikian pula, jika suatu daerah kaum Muslimin dikepung oleh orang-orang kafir dengan rapat. Orang-orang kafir itu enggan mengakhiri pengepungan kecuali jika kaum Muslimin bersedia menyerahkan seseorang dari kalangan kaum Muslimin sebagai tebusan. Maka, dalam hal ini para ulama juga melarang menyerahkan tebusan. Dalam kasus ini pula, tidak dipilih mafsadah yang lebih kecil ((menyerahkan satu orang Muslim) demi menghindari mafsadah yang lebih besar.
Untuk menjawab isykal ini, sebagian ulama, seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa jiwa-jiwa kaum Muslimin itu sama dalam kehormatannya. Maka, tidak boleh mengorbankan salah satu jiwa demi keselamatan seseorang atau sekelompok orang lainnya. [14]
Wallahu a’lam. [15]
_______
Footnote
[1]. Taqrir al-Qawa’id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah hlm. 204, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, hlm. 527.
[2]. Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi hlm. 130.
[3]. Ibid.
[4]. Lihat QS. al-Kahfi/18:79
[5]. Idem, hlm. 132.
[6]. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang mewakafkan hartanya sedangkan ia masih memiliki utang yang jatuh tempo, maka wakafnya tidak sah. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam al-Bukhari rahimahullah. (Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, hlm. 33).
[7]. HR. Muslim no. 49, at-Tirmidzi no. 2173, Abu Dawud no. 4370, Ibnu Majah no. 4013, an-Nasa’i no. 5011
[8]. I’lam al-Muwaqqi’in 3/16, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah ma’a as-Syarh al-Mujaz hlm. 33
[9]. Imam Syafi’i rahimahullah dan Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa kewajiban haij nadzar lebih kuat daripada haji Islam. Berdasarkan pendapat ini, maka ia mendahukukan haji nadzar. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini seseorang cukup melaksanakan haji sekali saja dan itu sudah mencukupinya dari haji Islam dan haji nadzar. (Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah hlm. 33)
[10]. Lihat as-Syarh al-Mumti’ 8/12-13.
[11]. HR. Muslim no. 137
[12]. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha hlm. 533
[13]. Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, hlm. 36
[14]. Ibid hlm. 36-37.
[15]. Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh DR. Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih. Cet. II, Thn. 1422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh., hlm. 85-86, dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-34: Pilihan Dua Hal Yang Berkaitan Dengan Maslahat Dirinya Dan Orang Lain
Kaidah Ketiga Puluh Empat
إِذَا خُيِّرَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ التَّخْيِيْرُ لِمَصْلَحَتِهِ فَهُوَ تَخْيِيْرُ تَشَهٍّ وَاخْتِيَارٍ, وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ فَهُوَ تَخْيِيْرُ اجْتِهَادٍ فِي مَصْلَحَةِ الْغَيْرِ
Jika seseorang diberi pilihan dua hal berkaitan dengan maslahat dirinya maka dipilih sesuai keinginannya. Dan jika berkaitan dengan maslahat orang lain maka dipilih yang lebih mendatangkan maslahat bagi orang lain itu
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan tentang seseorang jika dihadapkan pada dua pilihan atau lebih. Mana yang harus ia pilih? Apakah pilihannya dikembalikan kepada keinginannya sendiri, ataukah ada ketentuan lain yang harus dipertimbangkan?
Penerapan kaidah ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena kaidah ini menjelaskan, jika pilihan tersebut berkaitan dengan kebaikan diri pribadinya, maka ia boleh memilih sesuai keinginan dan kecenderungannya. Namun jika pilihan itu berkaitan dengan kepentingan orang lain, maka ia harus memilihkan yang paling sesuai, terbaik atau paling bermanfaat bagi yang bersangkutan. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.” [QS. al An’am/6:152]
Pada ayat ini Allah ﷻ melarang pengurus atau wali anak yatim melakukan tasharruf (aktifitas bisnis) terhadap harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Termasuk, apabila pengurus anak yatim dihadapkan pada dua hal berkaitan dengan kepentingan si yatim, maka ia harus memiilih yang lebih memberikan maslahat bagi anak yatim tersebut.
Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah mengatakan: “Apabila dalam perkara yang berkaitan dengan hak anak yatim saja diperintahkan untuk memerhatikan hal ini [2], maka lebih utama lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak kaum Muslimin secara umum yang dilaksanakan oleh para pemimpin, yaitu dalam masalah harta untuk kepentingan umum. Karena perhatian syariat terhadap maslahat umum lebih besar daripada perhatiannya terhadap maslahat yang sifatnya personal.” [3]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, baik berkaitan dengan permasalahan ibadah, muamalah, ataupun jinayat. Di antaranya:
- Berkaitan dengan Kaffarah (denda) sumpah. Apabila seseorang melanggar sumpahnya, maka ia diberikan beberapa alternatif dalam pembayaran Kaffarah. Yaitu memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. [4] Sebagaimana firman Allah ﷻ:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
“Maka Kaffarah (denda karena melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka Kaffarahnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah Kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).” [QS. al Maidah/5:89]
Dalam hal ini seseorang boleh memilih salah satu dari tiga alternatif tersebut. Meskipun ia mampu membayar Kaffarah dengan membebaskan budak, ia boleh memilih memberi makan sepuluh orang miskin atau memberikan mereka pakaian. Jenis pilihan ditentukan sesuai keinginan dan kecenderungan si pembayar. Karena hal itu berkaitan dengan hak pribadinya. [5]
- Para ulama madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa apabila kaum Muslimin mendapatkan tawanan perang orang kafir harbi [6], maka pemimpin mempunyai lima alternatif dalam menyikapi tawanan tersebut. Apakah dijadikan budak, atau dibunuh, atau diambil jizyah (upeti) darinya, atau diambil tebusan darinya, atau dibebaskan begitu saja. [7] Penentuan sikap terhadap tawanan tersebut dikembalikan kepada apa yang terbaik bagi kaum Muslimin. Dalam hal ini pemimpin harus berIjtihad untuk menentukan manakah yang paling sesuai dan paling maslahat dari beberapa opsi tersebut. Karena perkara ini berkaitan dengan maslahat umum kaum Muslimin. [8]
- Berkaitan dengan fidyatul adza. Yaitu apabila seseorang mencukur rambutnya saat masih ihram dikarenakan ada penyakit di kepalanya. Maka ia wajib membayar Kaffarah, dengan beberapa pilihan, yaitu berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. [9] Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Alquran Surat al-Baqarah/2 ayat ke-196.
Maka orang yang membayar fidyatu adza ini boleh memilih yang paling mudah untuk ia bayarkan di antara ketiga pilihan tersebut. Karena ini termasuk dalam kategori pilihan yang penentuannya kembali pada keinginan orang yang mendapatkan pilihan, karena berkaitan dengan hak pribadinya. [10]
- Seseorang yang menjadi pengurus anak yatim, ada kalanya dihadapkan pada beberapa pilihan berkait dengan harta anak yatim tersebut. Apakah ia membelikan tanah bagi anak yatim tersebut supaya di kemudian hari bisa mendapatkan hasil? Ataukah membelikannya rumah? ataukah menyimpankannya tanpa dikelola? Dari alternatif-alternatif yang ada, dia harus mencarikan mana yang terbaik bagi si yatim, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi pengurusnya. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain maka diperhatikan perkara yang paling maslahat baginya.
Keterangan Tambahan:
Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa seseorang yang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan berkaitan dengan hak pribadinya, maka ia boleh memilih sesuai keinginan dan kecenderungannya. Namun demikian, perlu diperhatikan juga apabila dari beberapa opsi itu ada yang lebih besar manfaatnya maka dianjurkan untuk dipilih. Karena itu yang lebih utama dan lebih besar pahalanya. Misalnya dalam pembayaran Kaffarah sumpah. Seseorang diberi tiga pilihan sebagaimana keterangan di atas. Namun jika ia memilih membebaskan budak, maka itulah yang lebih utama karena manfaatnya yang lebih besar.
Demikian pula dalam pembayaran fidyatul adza. Seseorang diberi tiga alternatif. Asalnya ia boleh memilih salah satu dari ketiganya sesuai keinginannya. Namun jika ia memilih menyembelih seekor kambing, maka itulah yang lebih utama. Karena ditinjau dari sisi taqarrub dan pengorbanan harta yang ia keluarkan, alternatif inilah yang paling besar nilainya. [11]
Wallahu a’lam. [12]
_______
Footnote
[1]. Syarhul Qawa’idis Sa’diyyah, hlm. 205; al-Furruq 2/419: al-Mausu’atul Fiqhiyyah 11/67-81.
[2]. Yaitu memerhatikan perkara yang lebih bermanfaat bagi si yatim.
[3]. Al-Qawa’idul Kubra 2/158.
[4]. Jika tidak sanggup mengerjakan salah satu dari tiga pilihan tersebut barulah diperbolehkan untuk membayar Kaffarah dengan berpuasa tiga hari. (Minhajul Muslim, hlm. 400)
[5]. Al-Furuq 2/419.
[6]. Kafir harbi adalah orang kafir yang mengikuti kewarganegaraan negri kafir yang memerangi umat Islam. (Mu’jam Lughatil Fuqahaa’, pada kata الحربي)
[7]. Kelima alternatif tersebut berlaku jika tawanan itu laki-laki yang sudah baligh. Adapun tawanan wanita dan anak-anak maka tidak diperbolehkan untuk dibunuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadtis riwayat Bukhari 6/148 dan Muslim 3/1364 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
[8]. At Ta’liq ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah, hlm 202; al Mausu’atul Fiqhiyyah, 11/76.
[9]. Tentang fidyatul adza ini dijelaskan dalam HR. Bukhari no. 4517 dan Muslim no. 1201 dari Ka’ab bin Ujrah radhiyallahu anhu
[10]. At Ta’liq ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah, hlm. 200.
[11]. Syarhul Qawa’idis Sa’diyah, hlm. 205
[12]. Diangkat dari al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. Cetakan kedua. 1422 H/2001 M. Darul Wathan lin Nasyr. Riyadh. Hlm. 86-87. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-35: Barang siapa Terlepas Dari Hukuman Karena Suatu Sebab, Dilipatkan Pembayaran Gantinya
Kaidah Ketiga Puluh Lima
مَنْ سَقَطَتْ عِنْدَهُ الْعُقُوْبَةُ لِمُوْجِبٍ ضُوْعِفَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ
Barang siapa terlepas dari hukuman karena suatu sebab, maka dilipatkan pembayaran ganti rugi atasnya
Makna Kaidah
Para ulama menjelaskan, bahwa perkara-perkara haram dalam syariat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkara haram yang tidak ada hukuman duniawi di dalamnya. Yang kedua adalah perkara haram yang ada hukuman duniawi, baik berupa had, Qishas, Kaffarah, ataupun dhaman. Untuk jenis kedua ini, siapa saja yang mengerjakannya maka ia berhak mendapatkan hukuman sesuai yang telah ditentukan dalam syariat, yaitu apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya.
Kaidah di atas berkaitan dengan perkara haram jenis kedua. Apabila seseorang mengerjakan perkara haram yang mengakibatkan terjadinya hukuman duniawi atas dirinya, namun hukuman itu tidak bisa diterapkan karena tidak terpenuhi syaratnya atau karena adanya penghalang, maka hukuman itu tidak diterapkan kepadanya, akan tetapi ia dikenakan hukuman lain yaitu dilipatkan kewajiban membayar al-ghurm (denda) sebagai hukuman atas perbuatannya mengerjakan perkara haram tersebut. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Cukup banyak dalil yang mendasari kaidah ini, di antaranya adalah hadis Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.
Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash radhiyallahu anhuma dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang kurma yang masih berada di pohon, maka beliau ﷺbersabda: “Barang siapa membutuhkannya lalu memakan darinya, tanpa menyimpannya dalam baju, maka tidak mengapa baginya. Dan barang siapa membawa keluar darinya, maka ia wajib menggantinya dua kali lipat dan mendapatkan hukuman. Dan barang siapa mencuri darinya setelah diletakkan di tempat penjemuran, hingga mencapai harga perisai, maka ia diberi hukuman potong tangan.” [2]
Dalam hadis ini disebutkan, bahwa apabila seseorang mengambil kurma yang masih berada di pohonnya dengan dibawa keluar, maka hal itu setara dengan kasus pencurian. Dan hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Akan tetapi, dalam kasus ini hukuman itu tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhi syaratnya, karena ia mengambil bukan dari tempat penyimpanannya [3]. Ketika hukuman itu terlepas darinya, maka dilipatkanlah kewajiban pembayaran denda yang harus dibayarnya. [4]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, terutama berkaitan dengan permasalahan jinayat. Di antara contohnya adalah sebagai berikut:
- Orang yang mencuri sejumlah barang yang nilainya tidak sampai seperempat dinar, maka ia tidak dikenai hukum potong tangan. Karena di antara syarat diterapkannya hukum potong tangan ialah bahwa barang yang dicuri sudah sampai seperempat dinar atau lebih. [5] Namun, sebagai gantinya si pencuri wajib membayar denda sebesar dua kali lipat dari nilai barang yang dicuri.
- Seorang Muslim yang membunuh seorang kafir dzimmi [6] dengan sengaja dan terencana, tidak diterapkan kepadanya hukum Qishas. Karena di antara syarat diterapkannya hukum Qishas adalah kesetaraan agama antara si pembunuh dengan yang dibunuh. Dan sebagai gantinya, si pembunuh wajib membayar Diyat yang setara dengan Diyat pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang Muslim. Yaitu, dua kali lipat dari Diyat standar yang ditetapkan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap orang kafir dzimmi. [7]
- Tentang adh-dhalah (binatang tersesat). Apabila seseorang menemukan binatang tersesat lalu disembunyikan dan tidak diumumkan [8], maka ia wajib membayar denda sebesar dua kali lipat dari harga binatang tersebut, dan tidak diterapkan hukum potong tangan atasnya. Kasus ini serupa dengan pencurian, namun hukum potong tangan tidak diterapkan karena tidak terpenuhi syaratnya, lantaran barang tidak diambil dari tempat penyimpanannya (al-hirz). Maka, ketika hukuman potong tangan terlepas darinya, dilipatkanlah kewajiban membayar denda. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ضَالَّةُ اْلإِبِلِ الْمَكْتُوْمَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: “Unta tersesat yang disembunyikan wajib diganti dan ditambah yang semisal dengannya.” [9]
- Jika seseorang mencuri perhiasan emas yang tergantung di dinding, ia mencuri barang yang tidak disimpan di tempat penyimpanannya (al-hirz). Karena perhiasan tidak boleh diletakkan di tempat itu, harus diletakkan di tempat penyimpanan yang layak seperti kotak yang terkunci atau semisalnya. Maka kita katakan bahwa pencuri itu tidak dihukum potong tangan, mencuri barang bukan dari tempat penyimpananya. Akan tetapi dilipatkan denda yang harus ia bayarkan. Jika perhiasan itu bernilai 10.000 Riyal misalnya, maka ia wajib mengganti dengan 20.000 Riyal. Apabila perhiasan itu masih ada (belum dimanfaatkan oleh si pencuri), maka wajib baginya untuk mengembalikannya dan membayar 10.000 Riyal tambahan. [10]
- Apabila seorang anak kecil (belum baligh) melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan sengaja, maka ia tidak dihukum dengan hukum Qishas. Sebab, di antara syarat diterapkannya hukum Qishas, pelaku pembunuhan sudah berusia baligh. Namun, sebagai gantinya wajib dibayarkan Diyat sebanyak dua kali lipat. [11]
- Seseorang yang buta mata sebelah, mata kirinya buta, sedangkan mata kanannya normal. Jika ia memecahkan mata kanan seseorang yang kedua matanya normal, maka tidak dihukum dengan hukum Qishas, yaitu tidak dibalas dengan dipecahkan mata kanannya. Sebab, hal itu akan mengakibatkan ia tidak bisa melihat sama sekali. Namun, wajib baginya untuk membayar denda dua kali lipat dengan membayar Diyat sempurna sebagai ganti dari setengah Diyat. [12]
Keterangan Tambahan:
Apabila ada yang bertanya, “Apakah denda yang jumlahnya dilipatkan itu diberikan semua kepada pemilik barang yang dicuri ataukah setengahnya saja yang diberikan kepadanya?”
Berkaitan dengan pertanyaan ini Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bahwa yang diberikan kepada si pemilik harta hanyalah setengah dari denda tersebut. Adapun setengahnya lagi dimasukkan ke Baitul Mal. Sebab, bila diserahkan semua kepada pemilik harta, maka semua orang akan berkeinginaan supaya hartanya diambil oleh orang lain. Yaitu, dengan meletakkan hartanya di selain tempat penyimpananya supaya dicuri orang, kemudian ia bisa mendapatkan pembayaran denda dengan nilai yang dilipatkan dari si pencuri. Maka, setiap harta yang diambil sebagai hukuman atas pelanggaran, dimasukkan ke Baitul Mal. Seperti denda yang diambil dari kasus pelanggaran peraturan lalu-lintas dan semisalnya yang dimasukkan ke Baitul Mal. [13]
Wallahu a’lam. [14]
_______
Footnote
[1]. Lihat Talqihul Afhamil ‘Aliyyah bi Syarhil Qawa’idil Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, kaidah ke-60 dan Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, hlm. 321.
[2]. HR. Abu Dawud 4390, at-Tirmidzi 1289, Ibnu Majah 2597. Imam at-Tirmidzi rahimahullah berkata setelah menyebutkan hadis ini, “Ini adalah hadis hasan.” Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah juga menghasankan hadis ini. Sedangkan Imam Ibnu Qaththan rahimahullah mendhaifkannya.
[3]. Jumhur Fuqaha dari Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa di antara syarat diterapkannya hukum potong tangan bagi pencuri adalah bahwa si pencuri mengambil barang dari tempat penyimpanannya. Sedangkan buah-buahan selama masih berada di pohonnya, maka masih termasuk kategori barang yang tidak disimpan di tempat penyimpanannya. (Lihat al-Mausu’atul Fiqhiyyah 24/317)
[4]. Talqihul Afhamil ‘Aliyyah, kaidah ke-60
[5]. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Bukhari no. 6790 dan Muslim no. 1684.
[6]. Orang kafir dzimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri Islam dengan mendapatkan perlindungan dari negara dan wajib bagi mereka untuk membayar jizyah (upeti). (Lihat Mu’jam Lughatil Fuqaha pada kata الذمة dan الذمي ).
[7]. Pada pembunuhan karena khatha’ (tersalah), Diyat pembunuhan terhadap seorang kafir adalah setengah Diyat pembunuhan terhadap seorang Muslim. Namun karena dalam kasus ini, si pembunuh melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terencana, kemudian tidak bisa diterapkan Qishas karena syaratnya tidak terpenuhi, maka sebagai gantinya ia wajib membayar Diyat dua kali lipat. (Lihat Talqihul Afhamil ‘Aliyyah, kaidah ke-60)
[8]. Jika seseorang menemukan binatang yang tersesat, maka wajib baginya untuk mengumumkan penemuan tersebut dalam jangka waktu satu tahun, supaya si pemilik mengetahuinya. Kecuali binatang unta. Jika binatang yang hilang tersebut adalah unta maka tidak boleh diambil tetapi dibiarkan begitu saja karena Nabi ﷺ melarang untuk mengambilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Bukhari no. 2295 dan Muslim 1/1722
[9]. HR. Abu Dawud no. 1473 dan al- Baihaqi no. 11284
[10]. Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi hlm. 321
[11]. Talqihul Afhamil ‘Aliyyah, kaidah ke-60
[12]. Lihat al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah asy-Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid al-Musyaiqih, penjelasan bait ke-93
[13]. Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi hlm. 324
[14]. Diangkat dari al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Tahqiq Syaikh DR. Khalid al-Musyaiqih. Cet. II. Thn. 1422 H/2001 M. Darul Wathan lin Nasyr. Riyad, hlm. 87-88 dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-36: Barang siapa Merusakkan Barang Untuk Menghindari Bahaya, Maka Tidak Wajib Mengganti
Kaidah Ketiga Puluh Enam
مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ضَمِنَهُ وَمَنْ أَتْلَفَهُ دَفْعًا لِمَضَرَّتِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ
Barang siapa merusakkan suatu barang untuk ia manfaatkan maka ia wajib mengganti dan barang siapa merusakkannya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya maka tidak wajib mengganti
Makna Kaidah
Secara hukum asal, setiap orang yang merusak atau menghancurkan barang orang lain, ia wajib menggantinya. [1] Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syari. Meskipun hukum asal ini tidak berlaku secara mutlak, dan dikecualikan darinya beberapa kondisi. [2]
Jika seorang sengaja merusak barang orang lain, maka tidak lepas dari dua keadaan. Adakalanya itu dilakukan karena darurat, dan adakalanya tidak. Jika ia merusak bukan karena alasan darurat maka ia wajib mengganti. Namun jika ia merusaknya karena darurat maka tidak lepas dari dua keadaan pula. Pertama, ia merusaknya untuk memenuhi kebutuhan daruratnya, seperti orang yang sedang sangat lapar kemudian mendapatkan hewan ternak milik orang lain lalu ia sembelih dan ia makan. Kedua, ia merusaknya karena menghindar dari bahaya yang menyerangnya, misalnya orang yang diserang binatang milik orang lain dan ia berusaha mencegahnya sampai terpaksa membunuh binatang tersebut.
Untuk kasus pertama, dia wajib mengganti, sedangkan yang kasus yang kedua, tidak wajib mengganti.
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” [QS. an-Nisa’/4:29]
Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu:
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا ، فَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ.
Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata: “Salah seorang istri Nabi ﷺ menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi ﷺ bersabda: “Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah.“ [3]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya:
- Jika seseorang diserang, maka wajib bagi yang diserang untuk mencegahnya. Jika si penyerang sudah bisa dihentikan dengan dihardik, maka ia tidak boleh dipukul. Jika ia berhenti dengan dipukul, maka tidak boleh dilukai. Jika sudah berhenti dengan dilukai maka tidak boleh dibunuh. Jika tidak berhenti kecuali dengan dibunuh, maka ia boleh dibunuh dan orang yang diserang tidak wajib membayar Diyat ataupun Kaffarah. Karena ia membunuh tidak untuk mengambil manfaat darinya tetapi supaya terhindar dari bahaya penyerangannya. [4]
- Seseorang yang sedang kelaparan lalu mendapatkan seekor hewan ternak milik orang lain lalu ia sembelih dan dimakan untuk menghilangkan rasa laparnya maka ia wajib menggantinya, karena ia menyembelih hewan tersebut untuk memanfaatkannya. [5]
- Asalnya seseorang yang sedang berihram tidak boleh berburu hewan. [6] Namun, jika ia diserang oleh shaid (binatang buruan) maka ia harus mencegahnya dengan cara paling ringan yang bisa mencegah hewan tersebut. Jika tidak bisa ditolak kecuali dengan membunuhnya maka tidak mengapa ia membunuhnya. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti karena ia membunuhnya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya.
- Asalnya seseorang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk mencabut rambutnya. Namun suatu ketika jika ada rambut yang turun mengenai matanya sehingga menimbulkan rasa sakit di mata, dan tidak bisa menghilangkan sakit kecuali dengan mencabut rambut itu, maka hal itu diperbolehkan dan tidak ada kewajiban baginya membayar Fidyah.
- Apabila ada kaca yang jatuh dan akan menimpa seseorang, sedangkan tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan memecahkannya, maka boleh untuk memecahkannya, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti atau membayar ganti rugi.
- Jika seseorang diserang orang lain yang ingin merampas hartanya, sedangkan tidak mungkin dicegah kecuali dengan membunuh si penyerang, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ: ” فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ ” قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ: ” قَاتِلْهُ ” قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ: ” فَأَنْتَ شَهِيْدٌ ” ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ: ” هُوَ فِي النَّارِ.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata: “Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang datang kepadaku untuk merampas hartaku?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Jangan engkau berikan hartamu.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana jika ia memerangiku?” Beliau menjawab: “Perangilah ia!” Ia bertanya lagi, “Bagaimana jika ia membunuhku?” Beliau menjawab: “Engkau mati syahid.” Ia bertanya lagi, ”Bagaimana jika aku membunuhnya?” Beliau ﷺ menjawab: “Ia masuk Neraka.” [8]
Keterangan Tambahan:
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa seseorang yang merusakkan (menghancurkan) barang orang lain maka hukum asalnya ia wajib menggantinya. Namun ada beberapa keadaan yang dikecualikan. Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ada tiga keadaan dimana seseorang tidak wajib mengganti barang yang ia rusakkan, yaitu:
- Jika perusakan itu terjadi dalam rangka mencegah bahaya yang menyerangnya. Sebagaimana contoh-contoh di atas.
- Apabila hal itu telah diizinkan oleh si pemilik barang. Misalnya, apabila si pemilik telah mengizinkan orang lain untuk memakan makanannya, atau menyembelih hewan ternaknya.
- Apabila hal itu diizinkan oleh syariat. Misalnya seseorang yang merusak alat-alat musik yang melalaikan dari zikir kepada Allah ﷻ. Maka tidak ada kewajiban mengganti barang yang dirusakkan karena hal itu telah diizinkan oleh syariat. [9]
Wallahu a’lam. [10]
_______
Footnote
[1]. Hal ini berkaitan dengan hak Allah ﷻ maupun hak sesama manusia. Berkaitan dengan hak Allah ﷻ misalnya seseorang yang memburu hewan buruan di tanah haram atau seseorang yang berburu ketika dalam keadaan ihram. Dan berkaitan dengan hak sesama manusia misalnya seseoang yang mengambil harta orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. (Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, hlm. 231).
[2]. Penjelasan tentang beberapa keadaan yang dikecualikan tersebut akan disebutkan di akhir pembahasan.
[3]. HR. at-Tirmidzi dalam Kitab al-Ahkam, Bab Maa jaa-a fiiman yuksaru lahu as-Syai’u, no. 1359.
[4]. Syaikh Muhammad bin Saleh Al ‘Utsaimin menjelaskan bahwa jika orang yang diserang khawatir jika ia berusaha mencegah dengan cara yang lebih ringan (tanpa membunuh) dikhawatirkan si penyerang akan mendahului membunuhnya, maka si terserang boleh mendahului membunuh si penyerang. Dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi atasnya. (Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 232).
[5]. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila orang yang terpaksa mengambil hewan ternak itu adalah orang fakir, sedangkan si pemilik hewan adalah orang kaya, maka tidak ada kewajiban mengganti. Karena memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan hukumnya Fardhu Kifayah. (Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid As Sa’idan, kaidah ke-17).
[5]. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al Maidah/5:95.
[7]. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa larangan mencabut rambut di sini mencakup seluruh rambut yang tumbuh di badan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa yang dilarang dicabut khusus rambut kepala saja. (Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 231)
[8]. HR. Muslim dalam Kitab al-Imaan, Bab ad-Dalil ‘ala Anna Man Qashada Akhdza Maali Ghairihi bi Ghairi Haqqin, no. 308.
[9]. Hal ini tentu tetap dikaitkan dengan kaidah-kaidah dalam amar maruf nahi munkar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya tidak boleh mencegah suatu kemungkaran jika akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. (Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 231-234).
[10] Diangkat dari al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cetakan kedua. 1422 H/2001 M, Dar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 88. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-37: Jika Dua Orang Pelaku Muamalah Berselisih Keberpihakan Diberikan Yang Kuat Alasannya
Kaidah Ketiga Puluh Tujuh
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلاَنِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْمُعَامَلَةِ يُرَجَّحُ أَقْوَاهُمَا دَلِيْلاً
Jika dua orang pelaku muamalah berselisih tentang suatu hal berkaitan dengan muamalah itu maka keberpihakan diberikan kepada yang lebih kuat alasannya
Makna Kaidah
Kaidah ini menjadi rujukan dalam kasus perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak pelaku akad muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, gadai, atau selainnya. jika terjadi perselisihan di antara mereka berkaitan dengan persyaratan, harga, atau hal-hal lainnya, maka pihak yang lebih kuat alasannya yang lebih dikuatkan perkataannya. Dalam akad jual beli, misalnya, adakalanya yang lebih dikuatkan adalah perkataan si penjual dan adakalanya yang lebih dikuatkan adalah perkataan si pembeli.
Dalam kasus perselisihan semacam ini, sering kali penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum asal dari permasalahan yang bersangkutan. Di antaranya jika terjadi perselisihan tentang ada tidaknya persyaratan tambahan, maka hukum asalnya persyaratan itu tidak ada. Demikian pula, jika suatu akad jual beli telah selesai dan dinyatakan sah kemudian salah satu pihak menyatakan bahwa jual beli itu tidak sah karena sebab tertentu, maka keputusannya berpihak kepada orang yang menyatakannya sah, karena hukum asal suatu akad yang telah terjadi adalah sah. Demikian pula, berkaitan dengan cacat pada barang yang diperjual belikan, jika telah terjadi akad jual beli kemudian si pembeli menyatakan ada cacat pada barang maka hukum asalnya cacat tersebut tidak ada, kecuali jika ada bukti pendukung. Dan hukum-hukum asal lainnya sebagaimana dijelaskan para ulama. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadis Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhuma:
البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
“Bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang menuduh dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya.” [2]
Demikian pula disebutkan dalam hadis Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu:
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلاَنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ
“Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan muamalah dan tidak ada bukti pendukung antara keduanya maka perkataan berpihak kepada pemilik barang atau keduanya saling membatalkan jual beli itu.” [3]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, terutama berkaitan dengan permasalahan muamalah. Di antaranya:
- Jika seseorang menjual rumahnya kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian, ia mengatakan bahwa rumah tersebut masih dalam status gadai. [4] Dengan perkataannya itu, ia ingin membatalkan jual beli. Maka, perkataannya tidak diterima, karena hukum asal dalam akad jual beli adalah sah. Kecuali jika ia bisa mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwa rumah tersebut berstatus gadai, maka perkataannya diterima. [5]
- Apabila seseorang telah membeli sebuah mobil. Selang beberapa hari kemudian ia datang kepada si penjual dan mengatakan ada cacat pada mobil itu. Tujuannya mendapatkan hak khiyar. [6] Maka hukum asal dari dakwaan ini adalah tidak diterima kecuali jika si pembeli bisa mendatangkan bukti kebenaran dakwaannya tersebut. Karena hukum asal dari barang yang sudah dibeli adalah bebas dari aib (cacat). [7]
- Dua orang melakukan akad jual beli suatu barang. Selang beberapa waktu kemudian, si penjual mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah, karena ketika pelaksanaan akadnya dulu ia belum baligh. [8] Sedangkan si pembeli mengatakan bahwa jual beli itu sah. Maka dalam kasus ini perkataan si pembeli yang dimenangkan karena asal dalam akad jual beli adalah sah, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa akad itu tidak sah. [9]
- Seseorang menjual sebuah mobil kepada orang lain. Dua hari kemudian, ia datang kepada si pembeli seraya mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah karena dilaksanakan setelah azan Salat Jumat. [10] Sedangkan si pembeli mengatakan bahwa jual beli itu sah karena dilaksanakan di luar waktu itu. Maka perkataan berpihak kepada si pembeli. Karena hukum asal suatu akad jual beli adalah sah. Maka, dalam kasus ini si penjual harus mendatangkan bukti bahwa jual beli itu memang dilaksanakan setelah azan Salat Jumat. Jika ia tidak punya bukti, maka kita katakan kepada si pembeli supaya bersumpah bahwa jual beli itu terjadi di luar waktu tersebut dan dihukumi akan sahnya jual beli itu. [11]
- Jika seorang pembeli mengatakan adanya unsur jahalah (ketidakjelasan) atas barang yang ia beli, dan mengatakan bahwa ia tidak melihat barang ketika dilaksanakannya transaksi. Dengan tujuan untuk membatalkan jual beli tersebut. Maka, asalnya perkataan tersebut tidak diterima karena hukum asal dalam akad jual beli adalah sah. Demikian pula, keberadaan si pembeli yang membawa barang tersebut menunjukkan bahwa perkataannya tidak benar. Jika memang benar apa yang ia katakan, tentu ketika akan menerima barang ia menolak menerimanya karena adanya unsur jahalah. [12]
Keterangan Tambahan:
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa apabila terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan muamalah, maka dilihat siapa di antara keduanya yang lebih kuat alasan atau buktinya. Namun, suatu ketika timbul permasalahan baru, yaitu jika ternyata keduanya sama-sama mempunyai bukti yang kuat sehingga tidak bisa ditentukan perkataan pihak mana yang lebih dikuatkan. Dalam kasus seperti ini, Para ulama menjelaskan, bahwa jual beli tersebut dibatalkan. Yaitu dengan cara si pembeli mengembalikan barang yang telah ia bawa dan si penjual mengembalikan uang yang telah ia dapatkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu:
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلاَنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ
Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan muamalah dan tidak ada bukti pendukung antara keduanya maka perkataan berpihak kepada pemilik barang atau keduanya saling membatalkan jual beli itu. [13]
Namun demikian, jika salah satu pihak mau mengalah dan rida dengan perkataan pihak lainnya maka ini pun diperbolehkan. Misalnya dalam kasus jual beli yang pembayarannya ditunda, terjadi perselisihan antara si penjual dan pembeli berkaitan dengan harga barang yang semula telah disepakati, dikarenakan lupa, atau sebab-sebab lainnya. Si penjual menyebutkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang disebutkan si pembeli. Sedangkan tidak ada bukti yang lebih menguatkan salah satu dari keduanya. Kemudian si pembeli mengalah dan rela dengan harga yang disebutkan si penjual, maka ini termasuk dalam kategori perdamaian yang diperbolehkan. [14]
Wallahu a’lam. [15]
_______
Footnote
[1]. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil, Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa-at-Tauzi’, Hlm. 212.
[2]. HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra, Kitabud Da’awa wa al-Bayyinat, Bab al-Bayyinat ‘ala al-Mudda’i, 10/202. Asal hadis ini ada dalam Shahihul Bukhari no. 4277 dan Muslim 1/1711.
[3]. HR. Ahmad dalam Musnadnya 1/466, al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra 5/333 dan at-Tirmidzi 1/240. Derajat hadis ini Shahih li ghairihi dengan mengumpulkan semua jalannya. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil, Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, Hlm. 213-215.
[4]. Barang yang sedang dalam status gadai tidak boleh diperjual belikan. Sebagaimanan disebutkan dalam salah satu bait dalam Manzhumah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah karya Syaikh Abdurrahman as-Sa’di
[5]. Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 268.
[6]. Yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Lihat Minhajul Muslim, Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Tahun 2002 M, Dar Ibni al-Haitsam, Kairo, Hlm. 284.
[7]. Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil, Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa-at-Tauzi’, Hlm. 216.
[8]. Transaksi jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh tidak sah kecuali dengan izin walinya. Lihat as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1422 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, Hlm. 111.
[9]. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini, asalnya yang lebih dikuatkan adalah perkataan si penjual. Karena ada hukum asal lain yang lebih kuat, yaitu bahwa hukum asal seseorang adalah belum baligh. Maka dalam kasus tersebut yang wajib bagi si penjual adalah bersumpah bahwa ketika pelaksanaan akad ia belum sampai usia baligh dan jual beli itu dihukumi tidak sah. Ini tidak bertentangan dengan kaidah yang menjelaskan bahwa hukum asal suatu akad adalah sah, karena ada hukum asal lain yang lebih kuat darinya. Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 268.
[10]. Jual beli setelah dikumandangkannya azan Salat Jumat termasuk kategori jual beli yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Jumu’ah/62: 9
[11]. Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 267.
[12]. Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 268.
[13]. HR. Ahmad dalam Musnadnya 1/466, al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubra 5/333 dan at-Tirmidzi 1/240. Derajat hadis ini adalah Shahih li ghairihi dengan mengumpulkan semua jalannya. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil, Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, Hlm. 213-215.
[14]. Lihat at-Ta’liq ‘alal Qawa’id wa al-Ushulil Jami’ah, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cetakan pertama, 1430 H, Muassasah as-Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin al-Khairiyyah, Unaizah, hlm. 207.
[15]. Diangkat dari al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cetakan kedua. 1422 H/2001 M, Dar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 89. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-38: Jika Pengharaman Berkaitan Dengan Zat Suatu Ibadah Maka Ibadah Tersebut Batal
Kaidah Ketiga Puluh Delapan
إِذَا عَادَ التَّحْرِيْمُ إِلَى نَفْسِ اْلعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا فَسَدَتْ, وَإِذَا عَادَ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَمْ تَفْسُدْ, وَكَذَلِكَ الْمُعَامَلَةُ
Jika pengharaman berkaitan dengan zat suatu ibadah atau syaratnya maka ibadah tersebut batal. Dan jika berkaitan dengan perkara di luar zat dan syaratnya maka ibadah itu tidaklah batal. Demikian pula permasalahan muamalah.
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan tentang larangan yang ditujukan terhadap suatu perkara. Para ulama menjelaskan, bahwa larangan terhadap suatu perkara tidak lepas dari tiga keadaan:
- Pertama: Adakalanya larangan itu tertuju kepada zat perkara tersebut.
- Kedua: Adakalanya larangan itu tertuju kepada syarat sahnya.
- Ketiga: Adakalanya larangan tertuju kepada perkara di luar zat dan syaratnya.
Dalam hal ini, timbul pertanyaan, sejauh manakah pengaruh suatu larangan terhadap sesuatu yang dilarang dan segala yang berkait dengannya? Apakah secara otomatis batal atau bagaimana? Para ulama menjelaskan, bahwa, apabila larangan itu berkaitan dengan zat suatu perkara atau syarat sahnya, maka zat atau perkara yang dilarang itu akan batal jika dilakukan. Misal larangan terhadap zat yaitu puasa pada saat hari raya. Jika puasa ini dilakukan, maka puasa itu batal. Begitu juga jika larangan itu berkait dengan syarat sah suatu perkara, maka perkara itu juga akan batal jika tetap dilakukan, seperti salat tanpa menutup aurat. Adapun jika berkaitan dengan perkara di luar zat dan syarat sahnya maka tidak menunjukkan batalnya perkara tersebut. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha:
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ
“Setiap persyaratan yang tidak (dibenarkan) dalam kitab Allah, maka itu adalah persyaratan yang batal, walaupun sejumlah seratus persyaratan.“ [2]
Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih mengatakan: “Hadis ini menunjukkan bahwa larangan-larangan dalam syariat menyebabkan perkara yang dilarang itu menjadi batal.” [3]
Demikian pula sabda Nabi ﷺ dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu:
لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
“Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu.” [4]
Hadis ini menjelaskan, bahwa seseorang yang salat dalam keadaan berhadats maka salatnya tidak sah. Karena thaharah (bersuci) merupakan salah satu syarat sah salat. Dan larangan melaksanakan salat tanpa bersuci berkaitan dengan syarat sah salat yang berimplikasi pada batalnya salat yang dikerjakan. [5]
Dalam hadis yang lain, Nabi ﷺ bersabda:
لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
“Janganlah kalian menghadang para pembawa barang dagangan dari kampung. Barang siapa yang dihadang, kemudian dibeli darinya (suatu barang), kemudian ia tiba di pasar, maka ia (penjual) memiliki khiyar (pilihan).” [6]
Dalam hadis ini Nabi ﷺ melarang menghadang para pembawa barang dagangan dari kampung ke pasar untuk membeli barang dari mereka. Namun jika seseorang melakukannya, maka itu tidak membatalkan jual beli yang dilakukan karena larangan tersebut tidak berkaitan dengan zat jual beli ataupun syarat sahnya. Oleh karena itulah dalam kasus tersebut Nabi ﷺ menetapkan adanya hak khiyar [7] bagi si penjual jika telah sampai di pasar. [8]
Contoh Penerapan Kaidah
Banyak contoh permasalahan baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah yang merupakan implementasi kaidah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:
- Rasulullah ﷺ melarang kaum Muslimin berpuasa pada dua hari raya, yaitu hari raya idul fitri dan idul adha. [9] Barang siapa melaksanakan puasa pada dua hari tersebut, maka puasanya fasid (batal). Karena larangan tersebut berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri. [10]
- Apabila seseorang salat tanpa bersuci, maka salatnya batal. Karena di antara syarat sah salat adalah thaharah (bersuci). Maka, larangan salat tanpa bersuci berkaitan dengan salah satu syarat sah salat. [11]
- Berkaitan dengan ibadah puasa. Apabila seseorang mengatakan perkataan dusta, atau menggunjing (ghibah) sedangkan ia dalam keadaan berpuasa maka puasanya tetap sah, meskipun ia berdosa atas perbuatannya tersebut. Karena larangan dusta tidak berkaitan dengan zat ataupun syarat sah puasa. Oleh karena itu, tidak mengakibatkan puasanya batal. [12]
- Apabila seseorang melaksanakan salat [13] pada-waktu-waktu terlarang, maka salatnya tidak sah. [14] Karena larangan dalam masalah ini berkaitan dengan zat salat itu sendiri. Sedangkan suatu larangan jika berkaitan dengan zat suatu ibadah maka konsekuensinya ibadah itu batal jika dilakukan. [15]
- Rasulullah ﷺ telah melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya. Oleh karena itu, barang siapa menjual barang yang bukan miliknya maka jual beli itu batal. Karena di antara syarat sah jual beli adalah bahwa barang yang dijual adalah milik si penjual atau milik orang yang diwakilinya. Dalam kasus ini, larangan berkaitan dengan syarat sah jual beli. Dan larangan jika berkaitan dengan syarat sah suatu perkara maka menunjukkan batalnya perkara tersebut. [16]
- Seorang wanita yang melaksanakan haji tanpa mahram, maka hajinya tetap sah, meskipun berhaji tanpa mahram bagi seorang wanita itu terlarang. Kenapa? Karena larangan tersebut tidak berkaitan dengan zat ataupun syarat sah ibadah tersebut. Jadi hajinya tetap sah namun ia berdosa.
- Berkaitan dengan permasalahan muamalah. Barang siapa memperjualbelikan khamr, bangkai, babi, dan patung, maka jual beli tersebut tidak sah. Karena larangan jual-beli benda-benda tersebut berkaitan dengan zatnya, sehingga berkonsekuensi pada batalnnya perkara yang dilarang. [19]
- Disebutkan dalam salah satu hadis tentang larangan jual beli gharar [20], di antaranya jual beli anak hewan yang masih dalam perut. [21] Barang siapa melaksanakan transaksi tersebut, maka jual belinya tidak sah. Karena larangan tersebut berkaitan dengan salah satu syarat sah jual beli yaitu tahu harga dan barang yang menjadi obyek. [22]
- Seorang laki-laki dilarang memakai pakaian sutra [23]. Dalam hal ini, jika seseorang melaksanakan salat dengan memakai topi dari sutra maka salatnya tetap sah. Karena menutup kepala tidak termasuk syarat sah salat. Karena larangan tersebut tidak berkaitan dengan zat ataupun syarat sah salat, maka pelanggaran ini tidak berkonsekuensi batalnya salat. Namun demikian, seseorang yang melakukannya tetap berdosa. [24]
- Jika seseorang menikahi mahramnya maka nikahnya tidak sah. Karena larangan menikahi mahram berkaitan dengan zat perkara tersebut. [25]
- Barang siapa melaksanakan salat sedangkan ada najis di pakaiannya, maka salatnya batal. Karena sucinya badan, pakaian, dan tempat salat dari najis termasuk syarat sah salat. [26] Maka, larangan salat dalam keadaan ada najis di pakaian seseorang berkaitan dengan syarat sah salat. Sehingga berkonsekuensi batalnya salat yang dilakukan [27].
Keterangan Tambahan:
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa suatu larangan jika berkaitan dengan syarat sah suatu perkara (ibadah maupun muamalah), maka itu berkonsekuensi pada batalnya perkara yang dilarang. Dalam hal ini, Para ulama menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah larangan yang mengenai syarat sah secara khusus. [28] Adapun jika larangan itu berkaitan dengan syarat sah suatu perkara namun tidak secara khusus maka tidak berkonsekuensi batal. [29] Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh-contoh berikut:
- Seseorang yang berwudhu dengan air hasil curian, maka wudhunya tetap sah. Dalam hal ini, ada larangan dari melakukan pencurian secara umum. Namun tidak ada larangan secara khusus berwudhu dengan air hasil curian. Maka, meskipun larangan dalam kasus ini berkaitan dengan syarat sah salat, yaitu bersuci, namun tidak secara khusus berkaitan dengannya. Maka ketika seseorang melakukannya, ia berdosa karena perbuatan pencurian yang ia lakukan, namun wudhunya tetap sah. [30]
- Apabila seseorang mengerjakan salat dengan memakai pakaian hasil curian, maka salatnya tetap sah. Larangan dalam masalah ini berkaitan dengan syarat sah salat, yaitu menutup aurat. Namun, tidak berkaitan dengannya secara khusus. Karena larangan mencuri sifatnya umum, dan tidak ada larangan khusus dari melaksanakan salat memakai pakaian hasil curian. Maka, salat orang tersebut tetap sah, namun ia berdosa karena pencurian yang ia lakukan. [31]
Wallahu a’lam. [32]
_______
Footnote
[1]. Lihat Talqihul Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-9. Dan al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul, Syaikh Muhammad bin Saleh Al ‘Utsaimin, Cet. I, 1424 H, Dar Ibn al-Jauzi, Dammam, Hlm. 29-30.
[2]. Ini potongan hadis riwayat Imam al-Bukhari, no. 2047, dan Muslim, no. 1504 dari Aisyah radhiyallahu anha
[3]. al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan kaidah ke 20-22.
[4]. HR. al-Bukhari, no 135 dan Muslim, no. 225 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
[5]. Lihat Talqihul Afham al-‘Aliyyah, Kaidah ke-9.
[6]. HR. Muslim, no. 3802, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
[7]. Yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Lihat as-Syarhul Mumti’ ‘ala Zadil Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin, Cet I, Tahun 1422 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, 8/261.
[8]. Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 76.
[9]. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Bukhari no. 1197 dan Muslim no. 827 dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu anhu
[10]. Lihat al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul, Cet. I, 1424 H, Dar Ibn al-Jauzi, Dammam, Hlm. 29.
[11]. Thaharah (bersuci) termasuk salah satu syarat sah salat sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari, no. 135 dan Muslim, no. 225 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
[12]. al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, penjelasan kaidah ke 20-22.
[13]. Yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah muthlaq, yaitu salat sunnah yang dilakukan tanpa ada sebab tertentu. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah Az Zamil, Dar Athlas Al Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, hlm. 217.
[14]. Di antara hadis yang menyebutkan waktu-waktu terlarang melaksanakan salat yaitu riwayat al-Bukhari no. 586 dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu anhu
[15]. Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, hlm. 217.
[16]. Talqihul Afham al-‘Aliyyah, kaidah ke-9.
[17]. Keberadaan mahram bagi wanita untuk melaksanakan ibadah haji termasuk syarat wajib haji bukan syarat sahnya. Lihat Talqihul Afham al-‘Aliyyah, kaidah ke-9.
[18]. Tentang haramnya jual beli khamr, bangkai, babi, dan dan patung dijelaskan dalam riwayat al-Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581 dari Jabir radhiyallahu anhu
[19]. al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, penjelasan kaidah ke 20-22.
[20]. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim no. 1513 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
[21]. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Bukhari no. 2143 dan Muslim no. 1514 dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma
[22]. Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 75.
[23]. Sebagaimana disebutkan dalam HR. al-Bukhari no. 5426 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu
[24]. Lihat al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, penjelasan kaidah ke 20-22.
[25]. Di antara dalil yang menunjukkan haramnya menikahi mahram adalah firman Allah ﷻ dalam QS. An Nisa’/4:22
[26]. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa suci dari najis termasuk syarat sah salat adalah HR. al-Bukhari no. 220 dan Muslim no. 284 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
[27]. al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, penjelasan kaidah ke 20-22.
[28]. Larangan yang berkaitan dengan syarat sah secara khusus telah disebutkan contoh-contohnya di atas.
[29]. Lihat penjelasan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullahentang hal ini dalam at-Ta’liq ‘ala al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah, Cet. I, 1430 H, Muassasah Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin al-Khairiyyah, Unaizah, hlm. 209.
[30]. al-‘Aqduts Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, penjelasan kaidah ke 20-22.
[31]. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah Az Zamil, Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, Hlm. 219.
[32]. Diangkat dari al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II. 1422 H/2001 M, Dar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 90. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-39: Perkara Yang Diperintahkan Wajib Dikerjakan Seluruhnya
Kaidah Ketiga Puluh Sembilan
يَجِبُ فِعْلُ الْمَأْمُوْرِ بِهِ كُلِّهِ, فَإِنْ قَدِرَ عَلَى بَعْضٍ وَعَجَزَ عَنْ بَاقِيْهِ فَعَلَ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ
Perkara yang diperintahkan wajib dikerjakan seluruhnya, (namun) jika seseorang hanya mampu mengerjakan sebagiannya maka ia kerjakan apa yang ia mampu
Makna Kaidah
Apabila seseorang diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka akan ada tiga kemungkinan. Kemungkin pertama, ia mampu mengerjakannya dengan sempurna; Kedua, ia tidak mampu mengerjakannya sama sekali; Ketiga, ia mampu mengerjakan sebagian saja.
Jika ia mampu mengerjakannya dengan sempurna maka itulah yang harus ia lakukan. Jika ia tidak mampu mengerjakannya sama sekali, maka kewajibannya gugur. Jika ia mampu mengerjakan sebagian, maka ia harus mengerjakan apa yang dia mampu dari perintah tersebut, sedangkan bagian yang tidak ia mampu maka gugur kewajiban mengerjakannya.
Kaidah ini akan membahas keadaan ketiga dari tiga keadaan di atas [1].
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah dalam Manzhumah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah mengatakan:
وَيفْعَلُ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُوْرِ إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُوْرِ
Dan dikerjakan sebagian dari perkara yang diperintahkan
Jika kesulitan mengerjakan seluruh perkara yang diperintahkan [2]
Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam mengatakan: “Sesungguhnya orang yang diberikan beban mengerjakan suatu ketaatan dan ia mampu mengerjakan sebagiannya dan tidak mampu sebagian lainnya, maka ia kerjakan apa yang ia mampu dan gugur kewajiban dari apa yang tidak ia mampui.” [3]
Syaikh Dr. Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih mengatakan: “Hukum asal dalam perintah-perintah (Allah dan Rasul-Nya) adalah engkau mengerjakan semuanya. Jika tidak mampu maka engkau kerjakan apa yang engkau mampu darinya. Dan banyak contoh yang masuk dalam penerapan kaidah ini.” [4]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” [QS. at-Taghabun/64:16].
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah mengatakan: “Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kewajiban yang tidak mampu dikerjakan oleh seorang hamba, maka kewajiban mengerjakannya gugur. Dan jika ia mampu mengerjakan sebagian perkara dan tidak mampu mengerjakan sisanya, maka ia kerjakan apa yang ia mampu dan gugur darinya apa yang tidak ia mampui. [5]
Nabi ﷺ bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu:
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Apa-apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Dan apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian.” [6]
Al ‘Allamah Ibnu Hajar al-Haitsami ketika menjelaskan hadis ini mengatakan: “Ini adalah kaidah Islam yang penting. Dan termasuk Jawami’ul Kalim yang diberikan kepada Nabi ﷺ, karena masuk di dalamnya perkara-perkara yang tidak terhitung.” [7]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai implementasi dan contoh penerapan yang sangat banyak, baik berkaitan dengan permasalahan ibadah, muamalah, dan selainnya. Berikut ini merupakan sedikit contoh darinya:
- Pada dasarnya, ketika seseorang berwudhu maka ia wajib menyiramkan air ke seluruh anggota wudhunya. Namun, apabila suatu ketika hanya ada sedikit air dan tidak cukup untuk berwudhu, maka yang wajib baginya adalah menggunakan air itu seadanya, dan anggota wudhu yang belum terkena air ia Tayammumkan. [8]
- Pada dasarnya, seseorang wajib berdiri saat salat. Jika ia tidak mampu berdiri maka salat dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ‘Imran bin Hushain radhiyallahu anhu:
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ n عَنِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
Dari ‘Imran bin Hushain radhiyallahu anhu ia berkata: “Aku pernah terkena penyakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ bagaimana aku melaksanakan salat? Rasulullah ﷺ bersabda: “Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring.” [9]
- Pada dasarnya, kewajiban berdiri saat salat berlaku sejak rakaat pertama sampai akhir. Namun, jika mampu berdiri di sebagian rakaat dan tidak mampu di rakaat lainnya, maka wajib berdiri pada rakaat yang ia mampu dan boleh duduk di rakaat yang tidak ia mampu. [10]
- Dalam pembayaran Zakat Fitri, asalnya seseorang wajib membayarkan zakat untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya, seperti anak dan istrinya. Namun, jika makanan pokok yang ia miliki tidak cukup untuk membayar zakat seluruhnya, maka ia utamakan membayarkan zakat untuk dirinya dan orang yang paling dekat hubungan dengannya. [11]
- Seseorang yang melaksanakan salat, sedangkan ia baru hafal sebagian dari Surat al-Fatihah. Maka yang wajib baginya ialah membaca surat tersebut sebatas yang dihafalnya. [12]
- Berkaitan dengan ibadah haji. Asalnya seseorang wajib melaksanakan haji dengan hartanya dan ia laksanakan sendiri tanpa mewakilkan. Namun jika ia tidak mungkinmenunaikannya dengan badannya sendiri maka yang wajib adalah ia mewakilkan orang lain untuk menghajikannya. [13]
- Jika seseorang melihat suatu kemungkaran dan tidak mampu menghilangkannya. Yang ia mampu hanya meringankan atau menghilangkan sebagiannya, maka wajib baginya untuk meringankan atau menghilangkan sebagian kemungkaran tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ
“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah keimanan.” [14]
- Seseorang yang salat dan tidak mampu melaksanakan sebagian syarat atau rukun salat, maka ia melaksanakan sebagian syarat atau rukun yang ia mampu. Adapun sebagian syarat atau rukun salat yang tidak ia mampui maka gugur kewajiban mengerjakannya. [15]
Keterangan Tambahan:
Para ulama menjelaskan, bahwa apabila seseorang hanya mampu mengerjakan sebagian dari perkara yang diperintahkan, maka ada beberapa keadaan:
- Jika perkara yang dimampui itu sekadar wasilah (perantara) dari ibadah yang lain, maka tidak wajib dikerjakan. Misalnya, di antara rangkaian amalan dalam ibadah haji adalah al halq (mencukur rambut). Dalam hal ini, timbul permasalahan jika seseorang memang kepalanya tidak tumbuh rambut, apakah ia wajib menjalankan alat cukur di kepalanya. Maka jawabannya tidak, karena hal itu hanya wasilah dari ibadah lain yaitu mencukur rambut. [16] Demikian pula, berkaitan dengan khitan. Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, maka tidak wajib menjalankan pisau di bagian yang biasa dikhitan, karena hal itu hanyalah wasilah kepada ibadah lainnya. [17]
- Jika perkara tersebut hanya sekadar pelengkap dan penyempurna ibadah yang lain, maka tidak wajib dikerjakan. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana dimaklumi bahwa di antara amalan dalam ibadah haji adalah bermalam di Mina dan melempar jumrah di sana pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Amalan ini merupakan pelengkap dan penyempurna dari Wuquf di Arafah. Timbul permasalahan jika seseorang terlewat dari mengikuti Wuquf di Arafah apakah tetap wajib baginya untuk pergi ke Mina, bermalam tiga hari di sana dan melempar jumrah. Maka jawabannya tidak, karena amalan tersebut sekadar pelengkap dan penyempurna dari ibadah lain yaitu Wuquf. Sehingga tatkala seseorang terlewat dari pelaksanaan Wuquf maka tidak wajib mengerjakan amalan yang menjadi pelengkapnya, semisal bermalam di Mina dan melempar jumrah di sana. [18]
- Jika perkara yang dimampui itu merupakan bagian suatu ibadah namun jika berdiri sendiri tidak tergolong ibadah yang disyariatkan, maka tidak wajib dikerjakan. Misalnya dalam ibadah puasa, asalnya seseorang wajib berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Timbul permasalahan jika seseorang tidak mampu berpuasa sampai tenggelam matahari, ia hanya mampu berpuasa sampai waktu Zuhur. Apakah ia wajib berpuasa sampai waktu Zuhur saja. Jawabannya tidak, karena perkara yang ia mampui itu bagian dari ibadah yang mana jika dipisahkan dan berdiri sendiri maka tidak termasuk kategori ibadah. Di mana puasa harus dilaksanakan sejak terbit fajar samapi tenggelam matahari. [19]
- Jika perkara tersebut bagian dari suatu ibadah dan jika berdiri sendiri pun merupakan ibadah yang disyaraiatkan, maka wajib untuk dikerjakan. Keadaan keempat inilah letak pembahasan kaidah ini, dan telah disebutkan contoh-contoh penerapannya di atas. Adapaun tiga keadaan sebelumnya tidak masuk dalam pembahasan kaidah ini. [20]
Demikian pembahasan singkat kaidah ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kita akan kaidah-kaidah fikih dalam agama kita yang mulia ini. Wallahu a’lam. [21]
_______
Footnote
[1]. Kaidah ini sering disebut dengan ungkapan الميسور لا يسقط بالمعسور. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘anha, Syaikh Dr. Saleh bin Ghanim as-sadlan, Cet. I, Tahun 1417 H, Dar Balansiyah li an-Nasyri wa at-Tauzi’, Riyadh, hlm. 310.
[2]. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1423 H, Dar Ibn al-Jauzi, Dammam, hlm. 43.
[3]. Qawa’id al-Ahkam fii Masalehil Anam 2/6. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘anha, hlm. 313.
[4]. al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-15.
[5]. Taisirul Karimir Rahman, Syaikh Abdurrahman bin Nashir Assa’di, Tahun 1423 H/2003 M, Jam’iyyah
[6]. HR. Muslim dalam Kitab al-Fadhail, no. 1337.
[7]. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘anha, hlm. 315.
[8]. Lihat as-Syarhul Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil Jauzi, Damam, 1/381.
[9]. HR. al-Bukhari dalam Kitab as-Shalah, Bab Idza Lam Yuthiq Qaiman Fa ‘ala Janbin, I/280.
[10]. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, hlm. 44.
[11]. al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-15.
[12]. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘anha, hlm. 319.
[13]. al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Penjelasan bait ke-15.
[14]. HR. Muslim dalam Kitab al-Iman, no. 49.
[15]. Lihat makalah berjudul Qa’idah al-Maisur La Yasquthu bi al-Ma’sur, Syaikh Dr. Nashir bin Muhammad al-Ghamidi, dimuat di Majalah al-Ushul wa an-Nawazil No.2, Rajab 1430 H.
[16]. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az Zamil, Dar Athlas al-Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, hlm. 225-226.
[17]. Lihat Taqrirul Qawa’id wa Tahrirul Fawa’id, al-Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali, Ta’liq Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Cet. I, Tahun 1419 H/1998 M, Dar Ibni Affan li an-Nasyri wa at-Tauzi, Khubar, Jilid 1 Hlm. 43.
[18]. Lihat makalah berjudul Qa’idah al-Maisur La Yasquthu bi al-Ma’sur, Syaikh Dr. Nashir bin Muhammad al-Ghamidi, dimuat di Majalah al-Ushul wa an-Nawazil No.2, Rajab 1430 H.
[19]. Lihat Tuhfatu Ahli at-Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II, Tahun 1423 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 10.
[20]. Lihat Syarhul Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah Az Zamil, Dar Athlas Al Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, hlm. 226.
[21]. Diangkat dari al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II. 1422 H/2001 M, Dar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 91-93, dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-40: Tidak Boleh Mendahulukan Pelaksanaan Ibadah Atau Kaffarah Sebelum Adanya Sebab Wujub
Kaidah Keempat Puluh
لاَ يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الْعِبَادَاتِ أَوِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى سَبَبِ الْوُجُوْبِ وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا بَعْدَ وُجُوْدِ السَّبَبِ وَقَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوْبِ وَتَحَقُّقِهِ
Tidak boleh mendahulukan pelaksanaan ibadah atau Kaffarah sebelum adanya Sebab Wujub dan diperbolehkan melaksanakannya setelah adanya Sebab Wujubnya sebelum ada dan terpenuhi syarat wajibnya.
Makna Kaidah
Kaidah ini adalah salah satu di antara kaidah-kaidah penting dalam pembahasan fiqih. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan kaidah ini, kita perlu memahami apakah yang dimaksud dengan Sebab Wujub dan apakah yang dimaksud dengan Syarat Wujub. [1]
Yang dimaksud dengan Sebab Wujub dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang menjadi poros kewajiban satu ibadah sehingga bolehnya mengerjakan suatu ibadah tergantung kepadanya. Sebagai contoh, keberadaan seseorang telah bersumpah sebagai sebab diperbolehkannya membayar Kaffarah sumpah. Demikian pula telah masuknya waktu salat yang pertama untuk kebolehan mengerjakan salat yang kedua dalam salat jama’.
Para ulama menjelaskan, bahwa syarat terbagi menjadi dua, yaitu Syarat Wujub dan syarat sah. Syarat Wujub adalah sesuatu yang menjadikan kewajiban mengerjakan suatu ibadah tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya. Misalnya hints (melanggar sumpah) adalah Syarat Wujub pembayaran Kaffarah sumpah. Karena seseorang tidaklah wujub membayar Kaffarah sumpah sebelum ia melanggar sumpahnya. Demikian pula hilangnya nyawa si terbunuh merupakan Syarat Wujub dibayarkannya Kaffarah pembunuhan. Di mana pembayaran Kaffarah ini menjadi wujub dengan syarat hilangnya nyawa si terbunuh. Dan Syarat Wujub inilah yang menjadi pembahasan dalam kaidah ini.
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sah adalah perkara-perkara yang menjadikan suatu ibadah tidaklah sah kecuali dengan keberadaannya. Seperti keberadaan thaharah untuk keabsahan salat, dan keIslaman untuk keabsahan segala macam ibadah. Meskipun asal ibadah tersebut telah wujub meski tanpa keberadaan syarat ini. Di mana seseorang wujub melaksanakan salat meskipun tidak dalam keadaan thaharah, namun tidak sah kecuali dengannya. Demikian pula orang kafir wujub melaksanakan ibadah-ibadah, namun tidak sah kecuali jika telah beragama Islam.
Dari dua macam syarat tersebut yang menjadi pembahasan dalam kaidah ini adalah macam yang pertama, yaitu Syarat Wujub dan bukan syarat sah.
Perlu juga difahami bahwa pelaksanaan ibadah yang memiliki Sebab Wujub dan syarat wajib, ada tiga keadaan:
- Ibadah itu dilaksanakan sebelum adanya Sebab Wujubnya.
Jika ibadah itu dilaksanakan sebelum ada Sebab Wujubnya, maka tidaklah sah pelaksanaan ibadah itu, karena dilaksanakan sebelum waktunya. seperti Salat Zuhur sebelum masuk waktunya
- Ibadah dikerjakan setelah ada sebab wajibnya namun sebelum terpenuhi Syarat Wujubnya.
Jika dilaksanakan setelah ada sebab wajibnya namun belum terpenuhi Syarat Wujubnya maka hal itu diperbolehkan
- Ibadah dikerjakan setelah keberadaan sebab dan Syarat Wujubnya.
Jika dilaksanakan setelah ada sebab dan Syarat Wujubnya maka ketika itu pelaksanaan ibadah menjadi wajib. [2]
Imam Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan: “Seluruh ibadah, baik yang berkaitan dengan amalan anggota badan atau berkaitan dengan harta, atau gabungan keduanya, tidak boleh dilaksanakan mendahului Sebab Wujubnya. Dan boleh dilaksanakan setelah ada Sebab Wujubnya sebelum terpenuhi kewajiban atau Syarat Wujubnya.” [3]
Dasar Kaidah Ini
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah sabda Nabi ﷺ:
إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
“Demi Allah, sesungguhnya tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah kemudian aku melihat ada hal lain yang lebih baik darinya, kecuali aku akan membayar Kaffarah atas sumpahku dan aku kerjakan hal yang lebih baik itu.” [4] “
Syaikh Walid bin Rasyid As Sa’idan mengatakan: “Hadis ini merupakan dalil atas bolehnya membayar Kaffarah setelah sumpah dilaksanakan meskipun belum dilanggar. Menyelisihi pendapat yang melarangnya. [5]
Demikian pula hadis ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu:
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ
Dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu sesungguhnya Abbas radhiyallahu ‘anhu pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mengeluarkan zakat sebelum waktu pembayarannya. Maka Nabi ﷺ membolehkannya. [6]
Dalam hadis ini Rasulullah ﷺ membolehkan pembayaran zakat setelah sempurna nishabnya meskipun harta itu belum berputar selama satu tahun. Hal ini menunjukkan bolehnya melaksanakan ibadah setelah ada Sebab Wujubnya, meskipun Syarat Wujubnya belum terpenuhi. [7]
Contoh Penerapan Kaidah
Banyak contoh permasalahan baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah yang merupakan implementasi kaidah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:
- Apabila seseorang melanggar sumpahnya maka wajib baginya untuk membayar Kaffarah (denda) [8]. Pembayaran Kaffarah ini termasuk ibadah yang mempunyai Sebab Wujub dan Syarat Wujub. Keberadaan seseorang telah besumpah adalah Sebab Wujubnya. Sedangkan keberadaan seseorang telah melanggar sumpahnya merupakan Syarat Wujubnya. Maka, tidak boleh seseorang membayar Kaffarah sebelum bersumpah, karena belum terpenuhi Sebab Wujubnya. [9] Dan boleh membayarkannya setelah seseorang bersumpah sebelum melanggar sumpahnya, karena ketika itu telah terpenuhi Sebab Wujubnya. Adapun jika ia telah melanggar sumpahnya maka ketika itu pembayaran Kaffarah menjadi wujub. [10]
- Berkaitan dengan menjama’ salat, baik menjama’ Salat Zuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya’. Seolah-olah waktu kedua salat yang dijamak tersebut menjadi satu sebagaimana telah dimaklumi di kalangan Fuqaha. Dalam hal ini, masuknya waktu salat yang pertama merupakan Sebab Wujub untuk mengerjakan salat yang kedua. Sedangkan masuknya waktu salat yang kedua merupakan syarat wajibnya. Maka tidak boleh mengerjakan salat yang kedua sebelum masuknya waktu salat yang pertama. Boleh mengerjakannya setelah masuknya waktu salat yang pertama karena Sebab Wujubnya telah terpenuhi. Adapun jika telah masuk waktu salat yang kedua maka ketika itu hukumnya menjadi wajib. [11]
- Zakat adalah ibadah yang mempunyai Sebab Wujub dan Syarat Wujub. Sebab Wujubnya adalah keberadaan harta itu telah sampai nishab. Sedangkan Syarat Wujubnya adalah keberadaannya telah dimiliki selama satu tahun (haul). Maka, tidak sah mengeluarkan zakat sebelum sampai nishab karena belum terpenuhi Sebab Wujubnya. Diperbolehkan membayarkannya jika telah sampai nishab sebelum berlalu satu tahun, karena ketika itu Sebab Wujubnya telah terpenuhi. Adapun jika telah sampai satu tahun maka ketika itu pembayarannya menjadi wajib. [12]
- Pembayaran Kaffarah Zhihar [13] adalah suatu ibadah yang mempunyai Sebab Wujub dan Syarat Wujub. Sebab Wujubnya adalah keberadaan seseorang telah menzhihar istrinya. Sedang Syarat Wujubnya adalah keberadaan si suami telah berniat untuk kembali kepada istrinya. Maka tidak sah pembayaran Kaffarah sebelum Zhihar terjadi, karena ketika itu belum terpenuhi Sebab Wujubnya. Boleh dibayarkan setelah terjadinya Zhihar sebelum si suami berniat kembali kepada istrinya, karena ketika itu sebab wajibnya telah terpenuhi. Adapun jika si suami telah berniat kembali kepada istrinya maka ketika itu pembayaran Kaffarah menjadi wajib. [14]
- Pembayaran fidyatul adza [15] termasuk ibadah yang mempunyai Sebab Wujub dan Syarat Wujub. Sebab Wujubnya adalah keberadaan penyakit di kepala seseorang yang sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah dan Syarat Wujubnya ialah apabila seseorang telah mencukur rambutnya untuk mengobati penyakitnya itu. Jika seseorang membayar Fidyah sebelum adanya penyakit di kepala, maka tidak sah pembayaran Fidyah itu karena Sebab Wujubnya belum terpenuhi. Jika dibayarkan setelah munculnya penyakit sebelum ia mencukur rambutnya maka pembayaran Fidyah itu sah karena Sebab Wujubnya telah terpenuhi. Adapun jika ia telah mencukur rambutnya maka pembayaran Fidyah menjadi wajib. [16]
- Kaffarah (denda) pembunuhan mempunyai Sebab Wujub dan Syarat Wujub. Sebab Wujubnya adalah tikaman yang dilakukan si pembunuh. Sedangkan Syarat Wujubnya adalah hilangnya nyawa si terbunuh. Oleh karena itu, tidak sah membayar Kaffarah sebelum tikaman, karena belum terpenuhi Sebab Wujubnya. Dan boleh membayarkannya setelah tikaman sebelum hilangnya nyawa si terbunuh, karena ketika itu Sebab Wujubnya telah terpenuhi. Adapun jika nyawa si terbunuh telah hilang maka pembayaran Kaffarah ketika itu menjadi wajib. [17]
Wallahu a’lam. [18]
_______
Footnote
[1]. Kaidah ini membahas ibadah-ibadah yang mempunyai Sebab Wujub dan Syarat Wujub. Adapun ibadah-ibadah yang tidak memiliki Sebab Wujub, seperti puasa Ramadan, salat lima waktu yang tidak dijamak, dan semisalnya maka tidak masuk dalam pembahasan kaidah ini. (Lihat Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-2)
[2]. Lihat Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-2.
[3]. Taqrir al-Qawa’id wa Tahrir al-Fawa`id, al-Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali, Ta’liq Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Cet. I, Tahun 1419 H/1998 M, Dar Ibni Affan li an-Nasyri wa at-Tauzi, Khubar, Jilid 1 Hlm. 24.
[4]. HR. al-Bukhari dalam Kitab Kaffarah al-Aiman, Bab al-Istitsna’ fi al-Aiman, no. 6718. Muslim dalam Kitab al-Aiman, Bab Nadbi Man Halafa Yaminan fa Ra-a Ghairaha Khairan Minha An Ya’tiyalladzi Huwa Khair wa Yukaffiru ‘an Yaminihi, no. 1649.
[5]. Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-2.
[6]. HR. at-Tirmidzi, no. 678. Abu Dawud, no. 1624. Ibnu Majah, no. 1795. Hakim (III/332). ad-Darimi (1636). ad-Daruqutni, no. 212-213. al-Baihaqi (IV/111). Ahmad (I/104). Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi, no. 678.
[7]. Lihat Taudhih al-Ahkam, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Cet. V, Tahun 1423 H/2003 M, Maktabah al-Asadiy, Makkah al-Mukarramah, Hal. 331.
[8]. Kaffarah sumpah dibayarkan dengan memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak Mukmin, atau puasa tiga hari, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah: 89. (Lihat Minhaj al-Muslim, Syaikh Abu Bakr Jabir Al Jazairi, Tahun 2002, Dar Ibni al-Haitsam, Kairo, Hlm. 400).
[9]. Jika Kaffarah itu dibayarkan sebelum terpenuhi sebab wajibnya maka itu terhitung sedekah biasa saja dan tidak sah sebagai Kaffarah. (Lihat al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-33).
[10]. Lihat Taqrir al-Qawa’id wa Tahrir al-Fawaid, al-Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali, Ta’liq Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Cet. I, Tahun 1419 H/1998 M, Dar Ibni Affan li an-Nasyri wa at-Tauzi, Khubar, Jilid 1 Hlm. 28.
[11]. Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-2.
[12]. Lihat Tuhfatu Ahli at-Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II, Tahun 1423 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 6.
[13]. Zhihar adalah jika seorang suami menyatakan bahwa istrinya haram atasnya, dengan mengatakan: “Engkau bagiku seperti punggung ibuku”, atau ucapan semisalnya. Seorang suami yang telah menzhihar istrinya, lalu ingin kembali kepada istrinya maka harus membayar Kaffarah dengan membebeskan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Mujadilah: 3-4. (Lihat Minhaj al-Muslim. Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Tahun 2002 M. Dar Ibnu al-Haitsam. Kairo. Hal. 358).
[14]. Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 143-144.
[15]. Fidyatul adza adalah Fidyah yang dibayarkan karena seseorang mencukur rambutnya dalam rangka pengobatan sakit yang ada di kepalanya sedangkan ia dalam keadaan ihram haji atau umrah. (Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Cetakan Kedua, 1404 H/1983 M, Wizarah al-Auqaf wa as-Syu-un al-Islamiyah, Kuwait, Jilid 2 Hlm. 158.
[16]. Lihat Tuhfatu Ahli at-Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II, Tahun 1423 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 6.
[17]. Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-2.
[18]. Diangkat dari al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II. 1422 H/2001 M, Dar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 91. Dengan beberapa tambahan dari referensi lainnya.
Kaidah Ke-41: Apabila Dua Ibadah Sejenis Berkumpul Maka Pelaksanaannya Digabung
Kaidah Keempat Puluh Satu
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا وَاكْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مَقْصُوْدُهُمَا وَاحِدًا
Apabila dua ibadah sejenis berkumpul maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama
Makna Kaidah
Kaidah ini merupakan implementasi dari prinsip taisir (kemudahan) dalam agama yang mulia ini. Syaikh Abdurrahman bin Nashir Assa’di mengatakan: “Ini merupakan nikmat dan kemudahan dari Allah, di mana satu amalan bisa mewakili beberapa amalan sekaligus.” [1]
Kaidah ini menjelaskan tentang dua ibadah atau lebih yang berkumpul dalam satu waktu. Timbul pertanyaan, apakah seseorang diperbolehkan hanya melaksanakan salah satunya, dengan tetap terhitung mengerjakan semuanya? Bisakah ia meraih pahala semua ibadah itu hanya dengan melaksanakan salah satunya? Para ulama menjelaskan, bahwa hal itu bisa apabila terpenuhi empat syarat [2]:
- Kedua ibadah tersebut jenisnya sama. Yaitu salat dengan salat, Thawaf dengan Thawaf dan semisalnya. Jika jenisnya berbeda, seperti salat dengan puasa, maka tidak bisa digabungkan.
- Kedua ibadah itu berkumpul dalam satu waktu. Seperti Thawaf Ifadhah (yang ditunda pelaksanaannya sampai menjelang pulang ke kampung halaman) dan Thawaf Wada.
- Salah satu dari kedua ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkan. Jika salah satunya dilakukan dalam rangka qadha maka kedua ibadah tidak bisa digabungkan. Oleh karena itu, seseorang yang tertinggal Salat Zuhur karena tertidur sampai datang waktu ashar, maka tidak boleh baginya mengerjakan hanya empat rakaat salat dengan niat Salat Zuhur dan Ashar. Dia wajib melaksanakan Salat Zuhur kemudian Salat Ashar [3].
- Salah satu ibadah tersebut bukan pengikut atau pengiring ibadah lainnya [4]. Jika salah satunya pengikut bagi yang lain, maka tidak bisa digabungkan. Oleh karena itu, salat sunat qabliyah Subuh yang merupakan salah satu sunat Rawatib misalnya tidak bisa digabung dengan Salat Subuh, karena salat sunat Rawatib mengikuti salat wajibnya [5]. Demikian pula, orang yang punya utang puasa Ramadan dan mengqadhanya di bulan Syawal dengan niat qadha sekaligus puasa sunnah enam hari Syawal tidaklah mendapatkan kecuali puasa qadha saja. Karena puasa sunnah Syawal tidak bisa dikerjakan kecuali jika ia telah menyempurnakan kewajiban puasa Ramadan.
Sebagian ulama yang lain menyebutkan dua syarat tambahan [6]:
- Hendaknya salah satu ibadah yang digabung itu lebih besar dari yang lainnya. Seperti Thawaf Ifadhah dengan Thawaf Wada,yang mana Thawaf Ifadhah lebih wajib daripada Thawaf Wada; Mandi janabah dengan mandi Jumat, di mana mandi janabah lebih wajib dari mandi Jumat.
- Ketika mengerjakan ibadah itu, si pelaku meniatkan kedua ibadah itu atau meniatkan ibadah yang lebih besar. Jika ia meniatkan ibadah yang lebih kecil maka hanya itulah yang ia raih.
Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam dua ibadah atau lebih, maka ibadah-ibadah itu bisa digabungkan dan cukup mengerjakan satu ibadah saja dan mendapatkan pahala semua ibadah itu. Namun jika dipisah pelaksanaan masing-masing ibadah tersebut, artinya masing-masing dilaksanakan, maka tidak diragukan lagi bahwa itu lebih sempurna. Pembolehan ini sebagai bentuk kemudahan dan keringanan bagi Mukallaf.
Dalil yang Mendasarinya
Kaidah yang mulia ini masuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
Dari Umar bin al-Khathab radhiyallahu anhu, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya.” [7]
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh permasalahan yang masuk dalam implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Apabila di pagi hari Jumat seorang laki-laki dalam keadaan janabah, maka ketika itu terkumpul padanya dua tuntutan, yaitu kewajiban mandi janabah dan sunnah mandi Jumat. Dalam hal ini, jika ia hanya mandi sekali saja dengan niat mandi janabah dan mandi Jumat, atau dengan niat mandi janabah saja, maka itu sudah cukup, dan ia mendapatkan pahala dua ibadah tersebut [8].
- Jika seseorang berwudhu kemudian masuk masjid setelah azan Zuhur, maka ketika itu disyariatkan baginya melaksanakan tiga salat sunnah, yaitu salat sunnah wudhu, Salat Tahiyyatul Masjid, dan salat sunnah qabliyah. Dalam keadaan ini, cukup baginya melaksanakan salat dua rakaat dengan niat ketiga salat dan mendapatkan pahala ketiga salat tersebut [9].
- Barang siapa melaksanakan puasa sunnah enam hari bulan Syawal pada hari-hari yang disunnahkan berpuasa, seperti puasa hari-hari bidh [10], maka ia mendapatkan pahala dua puasa sunnah tersebut, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa hari-hari bidh. [11]
- Jika seseorang menyimak bacaan Alquran dari dua orang, dan keduanya sama-sama membaca ayat sajdah, maka cukup baginya melakukan sekali Sujud Tilawah saja. [12]
- Apabila seseorang bangun dari tidur malam dan ingin berwudhu, maka ketika itu terkumpul padanya dua tuntutan ibadah. Yaitu kewajiban mencuci kedua tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke bejana [13], dan sunnah mencuci tangan tiga kali ketika awal wudhu. Dalam hal ini cukup baginya mencuci kedua tangan tiga kali dengan niat mencuci yang wajib dan tercakup di dalamnya yang sunnah, karena ibadah yang kecil tercakup dalam ibadah yang besar.
- Jika seseorang masuk masjid dan mendapatkan jamaah sedang melaksanakan Salat Zuhur maka terkumpul pada haknya ketika itu dua ibadah, salat fardhu dan Salat Tahiyyatul Masjid. Jika ia masuk mengikuti Salat Zuhur maka telah tercakup Salat Tahiyyatul Masjid sebagai pengikut. [14]
- Dalam ibadah haji, jika seseorang mengakhirkan pelaksanaan Thawaf Ifadhah menjelang kembalinya ke kampung halaman, maka ketika itu wajib baginya melaksakan dua Thawaf, Thawaf Ifadhah dan Thawaf Wada. Dalam hal ini, cukup baginya melaksanakan satu kali Thawaf dengan niat keduanya atau dengan niat Thawaf Ifadhah saja dan telah tercakup di dalamnya Thawaf Wada sebagai pengikut. Adapun jika niatnya hanya Thawaf Wada saja maka ia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia niatkan itu, yaitu Thawaf Wada. [15]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. al-Qawa’id wal Ushulul Jami’ah wal Furuq wat Taqasimul Badi’atun Nafi’ah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II. 1422 H/2001 M, Dar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, hlm. 93
[2]. Lihat syarat-syarat ini dalam Talqihul Afhamil ‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’idil Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-18.
[3]. Lihat Tuhfatu Ahli at-Thalab fi Tahrir Ushul Qawa’id Ibni Rajab, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Cet. II, Tahun 1423 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 18.
[4]. Lihat pembahasan tentang syarat-syarat ini dalam at-Ta’liq ‘ala al-Qawa’id wal Ushulil Jami’ah, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cet. I, 1430 H, Muassasah Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin al-Khairiyyah, Unaizah, hlm. 216.
[5]. Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fikih Islami, Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Cet. II, Tahun 1432 H/2011 M, Pustaka Al Furqon, Gresik, Hlm. 208.
[6]. Talqihul Afhamil ‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’idil Fiqhiyyah, kaidah ke-18.
[7]. HR. al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907.
[8]. Lihat Talqihul Afhamil ‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’idil Fiqhiyyah, kaidah ke-18.
[9]. Dalam masalah ini Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa jika seseorang meniatkan ketiga salat tersebut maka ia mendapatkan ketiganya. Jika ia meniatkan salah satunya saja maka jika yang diniatkan adalah salat sunnah qabliyah, maka ia juga mendapat ketiganya. Jika yang diniatkan adalah salat sunnah wudhu saja maka ia hanya mendapatkan Salat Sunnah Wudhu dan Tahiyyatul Masjid. (at-Ta’liq ‘ala al-Qawa’id wal Ushulil Jami’ah, hlm. 217)
[10]. Hari-hari bidh adalah tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Disunnahkan berpuasa pada hari hari tersebut berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu riwayat at-Tirmidzi no. 761, an-Nasa-i no. 2422 dan selainnya. Dihasankan Syaikh al-Albani dalam Irwa-ul Ghalil no. 9947 dan as-Shahihah no. 1567.
[11]. Talqihul Afhamil ‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’idil Fiqhiyyah, kaidah ke-18.
[12]. Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami, Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, hlm. 211.
[13]. Sebagaimana disebutkan dalam HR. al-Bukhari no. 162 dan Muslim no. 278 dari Abu Hurairah Raadhiyallahu anhu.
[14]. Talqihul Afhamil ‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’idil Fiqhiyyah, kaidah ke-18.
[15]. Lihat Taqrirul Qawa’id wa Tahrirul Fawaid, al-Imam al-Hafizh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali, Ta’liq Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Cet. I, Tahun 1419 H/1998 M, Dar Ibni Affan li an-Nasyri wa at-Tauzi, Khubar, Jilid 1 Hlm. 149-150.
Kaidah Ke-42: Ibadah Yang Bisa Dikerjakan Dengan Beberapa Cara Pelaksanaan Dikerjakan Seluruhnya
Kaidah Keempat Puluh Dua
الْعِبَادَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى وُجُوْهٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُفْعَلُ عَلَى جَمِيْعِ وُجُوْهِهَا فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ
Ibadah yang bisa dikerjakan dengan beberapa cara pelaksanaan, maka dikerjakan dengan seluruh tata caranya pada waktu yang berbeda-beda
Makna Kaidah
Sebelum membahas kandungan kaidah ini, perlu kita ketahui bahwa ibadah-ibadah yang disyariatkan ditinjau dari tata cara pelaksanaaannya terbagi menjadi dua:
Pertama: Ibadah yang hanya mempunyai satu cara pelaksanaan. Dari sejak awal pensyariatannya dilaksanakan dengan satu cara saja. Seperti jumlah rakaat salat fardhu, juga ibadah puasa yang hanya mempunyai satu cara, yaitu menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ibadah jenis ini tidak masuk dan tidak ada kaitannya dengan kaidah ini.
Kedua: Ibadah yang disyariatkan dengan beberapa cara pelaksanaan yang dijelaskan dalam dalil-dalil yang Shahih. Ibadah semacam inilah yang dibahas dalam kaidah ini. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kita melaksanakan ibadah semacam ini? Apakah kita cari cara ibadah yang paling akhir dan menganggap yang awal mansukh? Ataukah kita menTarjih (menguatkan) salah satu cara dan kita tinggalkan cara yang lain? Jawabannya ada dalam kaidah ini, yaitu kita laksanakan ibadah itu dengan seluruh cara yang dituntunkan. Kita laksanakan terkadang dengan cara ini, dan terkadang dengan cara lainnya. Karena semua tata cara tersebut telah dijelaskan dengan dalil syari yang Shahih. Sesuatu yang telah tetapkan dengan dalil Shahih maka disyariatkan untuk dikerjakan. Ini adalah jawaban yang benar terhadap masalah ini.
Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah mengatakan: “Hendaknya difahami tentang satu kaidah yang diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah [1] dan ahli ilmu yang lainnya bahwa ibadah yang mempunyai beberapa cara pelaksanaan seyogyanya dikerjakan dengan seluruh tata caranya tersebut. Satu saat dengan cara ini, dan saat lain dengan cara lainnya, dengan syarat hal itu tidak menimbulkan permasalahan atau fitnah di tengah-tengah manusia.” [2]
Jika hal ini telah difahami, maka perlu kita ketahui bahwa beragamnya tata cara dalam pelaksanaan ibadah termasuk kesempurnaan syariat Islam, dan menunjukkan benarnya firman Allah ﷻ:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nimat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. [QS. al-Maidah/5:3]
Faidah Kaidah Ini
Dilaksanakannya ibadah dengan seluruh tata caranya mempunyai banyak faidah, di antaranya [3]:
- Menjaga Syariah supaya tidak hilang atau terlupakan. Karena jika kita melaksanakan satu cara saja dan meninggalkan cara lainnya maka hal itu akan mengakibatkan cara lainnya hilang atau terlupakan. Ini juga termasuk dalam kategori menghidupkan Sunnah Nabi ﷺ. Sebagaimana sabda beliau ﷺ:
مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا
“Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun.” [4]
- Meragamkan ibadah yang dikerjakan seorang hamba sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Secara naluri, manusia senang kepada sesuatu yang baru. Dengan adanya tata cara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan ibadah, maka akan tercukupi kecenderungan jiwa tersebut, sehingga jiwa akan selalu bersemangat.
- Senantiasa menghadirkan niat ketika melaksanakan amalan dan tidak menjadikannya sekadar kebiasaan. Karena sebagian orang menjadikan ibadah yang hanya memiliki satu cara sekadar kebiasaan. Dikarenakan dirinya sudah terbiasa mengerjakan gerakan-gerakan ibadah itu, maka ia mengerjakannya tanpa kekhusyukan dan tanpa menghadirkan hati atau konsentrasi. Misalnya salat, sebagian orang terbiasa mengerjakan gerakan-gerakannya sehingga ketika telah selesai salam, ia tidak tahu atau lupa apa yang ia baca ketika salat, dan apakah ia rukuk dan sujud atau tidak? Ini akan berbeda jika melaksanakan ibadah dengan tata cara yang beragam. Ia akan sangat perhatian dengan cara yang ia pilih. Sehingga ia pun melaksanakannya tahap demi tahap dengan penuh konsentrasi dan khusyuk, sehingga ibadahnya sempurna.
- Menyebarkan atau mensosialisasikan semua cara tersebut di tengah manusia sehingga tidak diingkari. Apabila kita hanya memakai satu cara saja, dan kita tinggalkan cara yang lainnya, maka orang awam hanya akan mengetahui satu cara itu saja. Sehingga, apabila suatu ketika kita amalkan cara yang lainnya, besar kemungkinan mereka mengingkarinya. Kondisi ini bisa menyebabkan mereka terjatuh pada suatu yang terlarang yaitu mengingkari syariat. Hal itu tentu tidak terjadi, jika kita laksanakan semua cara ibadah itu dan manusia mengetahuinya.
- Memeroleh hikmah dan maslahat dari semua cara ibadah tersebut. Kita meyakini bahwa semua yang disyariatkan dalam agama ini pasti mengandung hikmah yang dalam dan kebaikan yang banyak. Setiap cara dari ibadah tersebut masing-masing memiliki hikmah yang tinggi. Seandainya kita mencukupkan diri dengan sebagian kaifiyah (cara) tanpa sebagian yang lain maka kita tidak bisa mendapatkan maslahat dari cara yang ditinggalkan. Jika kita kerjakan seluruh caranya maka kita akan mendapatkan semua hikmah dan kebaikannya.
Apabila hal ini telah difahami, maka perlu kita ketahui bahwa ibadah-ibadah yang mempunyai beberapa tata cara pelaksanaan, terdiri atas dua macam. Pertama, ibadah yang semua caranya bisa dikumpulkan dalam satu waktu, Ibadah semacam ini tidak mengapa bagi kita untuk melaksanakan semua caranya di satu waktu. Misalnya beberapa zikir ketika rukuk dan sujud, yang mana beberapa lafalnya bisa digabungkan dalam satu waktu. Kedua, ibadah yang semua caranya tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Ibadah semacam ini kita laksanakan seluruh tata caranya dalam waktu yang berbeda-beda. Seperti lafal azan dan iqamah, dan semisalnya yang insya Allah akan datang penjelasannya.
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh permasalahan yang masuk dalam implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Azan adalah ibadah yang mempunyai dua cara pelaksanaan. Pertama, adalah azan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang di dalamya tidak ada tarji’. [5] Kedua, adalah azan Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya ada tarji’. Kedua cara benar berdasarkan dalil Shahih. Maka yang disunnahkan adalah kita mengumandangkan azan terkadang dengan azan Bilal dan terkadang dengan azan Abu Mahdzurah. Namun tidak boleh bagi seorang muadzin menggabungkan kedua cara tersebut dalam satu waktu. [6]
- Iqamah adalah ibadah yang memiliki dua cara pelaksanaan. [7] Pertama, iqamah Bilal radhiyallahu anhu. Yaitu dengan mengganjilkan seluruh lafalnya kecuali lafal takbir (اللهُ أَكْبَرُ) dan iqamah (قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ). Kedua, iqamah Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, yaitu sama seperti kaifiyah azan Bilal. Barang siapa yang mengumandangkan azan dengan azan Bilal disunnahkan baginya untuk iqamah dengan iqamah Bilal. Dan barang siapa mengumandangkan azan dengan azan Abu Mahdzurah disunnahkan baginya untuk iqamah dengan iqamah Abu Mahdzurah. Dan disunnahkan suatu ketika iqamah dengan iqamah Bilal dan suatu ketika dengan iqamah Abu Mahdzurah.
- Duduk Tawarruk ketika Tasyahud Akhir dalam salat yang mempunyai dua Tasyahud memiliki tiga cara pelaksanaannya. Pertama, menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. [8] Kedua, menghamparkan kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di antara betis dan paha kaki kanan. [9] Ketiga, menghamparkan kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. [10]
Semua cara tersebut dijelaskan dalam dalil yang Shahih. Maka yang disunnahkan adalah melaksanakan semua cara tersebut dalam beberapa salat yang berlainan.
- Salat Khauf mempunyai beberapa tata cara pelaksanaan. Maka yang disunnhakan adalah melaksanakan semua tata cara tersebut di waktu yang berbeda-beda. [11]
- Ada beberapa cara dalam mengerjakan Salat Witir. [12] Di antaranya, jika Salat Witir itu dilaksanakan tiga rakaat, maka bisa dikerjakan tiga rakaat sekaligus dengan sekali salam. Dan boleh juga dikerjakan dua rakaat terlebih dahulu kemudian salam, lalu ditambah satu rakaat lagi. Maka disunnahkan mengerjakan semua tata cara tersebut pada waktu yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan rinciannya dalam kitab-kitab fikih. [13]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Majmu’ al-Fatawa, 22/335-337.
[2]. as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil Jauzi, Damam, 2/65.
[3]. Tentang faidah penerapan kaidah ini di antaranya bisa dilihat dalam as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zaad al-Mustaqni’, 2/56-57.
[4]. HR. Ibnu Majah no. 209, pada sanadnya ada kelemahan, akan tetapi hadis ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang semakna, oleh karena itu syaikh al-Albani menShahihkannya dalam kitab Shahih Ibnu Majah, no. 173.
[5]. Tarji’ adalah mengucapkan syahadatain (dua kalimat syahadat) ketika azan dengan melirihkan suara supaya orang yang dekat masjid bisa mendengarnya, kemudian mengulanginya lagi dengan suara keras supaya orang yang jauh bisa mendengarnya. (Lihat Mu’jam Lughah al-Fuqaha. Prof. Dr. Muhammad Rawas Qal’ah Jiy dan Dr. Hamid Shadiq Qunaibi. Cetakan kedua. Tahun 1408 H/1988 M. Dar an-Nafais. Beirut. Pada kata (الترجيع)
[6]. Lihat as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, 2/55-56.
[7]. Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin menyebutkan tiga cara dalam iqamah. (Lihat as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, 2/64-65).
[8]. Sebagaimana dalam HR. al-Bukhari no. 828.
[9]. Sebagaimana dalam HR. Muslim no. 112 dan 579.
[10]. Sebagaimana dalam HR. Abu Dawud no. 965, al-Baihaqi 2/128, Ibnu Hibban no. 1867.
[11]. Syaikh al-Utsaimin menjelaskan bahwa ada enam atau tujuh cara pelaksanaan salat khauf. Lihat, as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, 4/408-411.
[12]. Tentang beberapa kaifiyah (tata cara) Salat Witir bisa dilihat dalam as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, 4/13-16.
[13]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Pertama. Dengan peringkasan dan penambahan.
Kaidah Ke-43: Ibadah Pada Waktu Tertentu
Kaidah Keempat Puluh Tiga
الْعِبَادَاتُ الْمُؤَقَّتَةُ بِوَقْتٍ تَفُوْتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ
Ibadah yang ditentukan pada waktu tertentu tidak bisa didapatkan jika telah keluar waktunya kecuali karena adanya uzur.
Makna Kaidah
Kaidah ini termasuk patokan penting dalam pembahasan fiqih. Karena kaidah menjelaskan tentang ibadah manakah yang tetap bisa dilakukan ketika waktunya telah lewat dan mana yang tidak? Maka perlu kita ketahui bahwa ibadah ditinjau dari waktunya terbagi menjadi dua:
- Ibadah yang tidak terkait dengan waktu tertentu, yaitu tidak ada waktu khusus dalam pelaksanaannya. Artinya bisa dikerjakan di setiap waktu. Jenis ibadah ini tidak masuk dalam pembahasan kaidah ini. Karena tidak ada batasan waktu, sehingga tidak ada istilah ‘waktunya sudah lewat’. Seperti sedekah sunnah, dan Birrul Walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua), Salat Sunnah Mutlaq selain di waktu terlarang, puasa sunnah di selain bari-hari yang terlarang, demikian pula umrah.
- Ibadah yang ditentukan waktunya, yaitu ada waktu khusus untuk pelaksanaannya. Ia mempunyai awal waktu dan akhir waktu pelaksanaan. Seperti puasa Ramadan, salat lima waktu, salat sunnah Rawatib qabliyah ataupun ba’diyah, Wuquf di Arafah, menyembelih Udhiyah (hewan kurban), Zakat Fitri, dan nadzar yang ditentukan dengan waktu tertentu.
Berkaitan dengan ibadah jenis kedua ini, para ulama bersepakat bahwa seseorang tidak boleh mengerjakannya sebelum waktunya. Lalu bagaimana hukumnya jika seseorang belum melaksanakan ibadah tersebut sampai waktunya terlewatkan? Bolehkah ia tetap mengerjakannya setelah itu? Inilah yang menjadi pembahasan kaidah ini.
Kita katakan bahwa seseorang yang belum mengerjakan suatu ibadah sampai lewat waktunya maka ia tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, ia belum mengerjakannya karena ada uzur syari. Kedua, ia belum mengerjakannya dengan sengaja tanpa uzur syari.
Jika hal itu terjadi karena ada uzur syari maka ia boleh mengerjakan ibadah tersebut meskipun telah lewat waktunya. Dan ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan pada waktunya, tidak berkurang pahalanya sedikit pun.
Adapun jika hal itu terjadi tanpa adanya uzur syari, misalnya ia sengaja meninggalkannya karena malas, atau sibuk dengan urusan dunia, atau semisalnya maka ibadah-ibadah itu jika telah lewat waktunya maka ia tidak diperbolehkan mengerjakannya lagi. Seandainya ia mengerjakan di selain waktunya seribu kali maka itu tidak cukup. Karena penentuan waktu untuk ibadah-ibadah itu mempunyai hikmah yang agung, dan syariat tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tersebut kecuali karena adanya maslahat dan hikmah yang dalam. Seandainya dilaksanakan diselain waktunya maka tidak akan terwujud maslahat yang diharapkan tersebut. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ tentang doa orang-orang yang beriman:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” [QS. al-Baqarah/2:286]
Disebutkan dalam salah satu Hadis Qudsi bekaitan dengan ayat ini, bahwasanya Allah ﷻ berfirman:
قَدْ فَعَلْتُ
“Sungguh Aku telah mengabulkannya.” [2]
Dan Allah ﷻ berfirman:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” [QS. al-Baqarah/2:184]
Dalam ayat ini disebutkan bahwa seseorang yang tidak berpuasa pada hari-hari di bulan Ramadan maka disyariatkan baginya untuk menggantinya di hari-hari lain, yaitu jika ia meninggalkannya karena uzur, seperti sakit atau safar. [3]
Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik di mana Nabi ﷺ bersabda:
مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ
“Barang siapa yang meninggalkan salat karena tertidur atau lupa, maka hendaklah ia mengerjakan salat setelah ingat dan tidak ada Kaffarah selain itu.” [4]
Dan sabda Nabi ﷺ:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
“Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, dan seorang anak sampai ia baligh, serta orang gila sampai ia sadar.” [5].
Contoh Penerapan Kaidah
Cukup banyak contoh kasus yang masuk dalam kaidah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:
- Seseorang yang meninggalkan salat karena lupa atau tertidur sampai keluar waktunya maka ia mengerjakannya saat ia ingat atau telah bangun. Dalam kasus ini ia diperbolehkan mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya karena ada uzur syari [6]
Adapun orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur syari maka ia tidak boleh mengqadhanya selama-lamanya. Seandainya ia mengerjakan salat itu seribu kali kewajiban salat itu tidak akan lepas darinya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan diperbolehkannya mengqadha salat adalah untuk orang yang ada uzur saja, adapun orang yang tidak beruzur maka tidak diberikan kelonggaran. Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah ﷻ dengan sebenar-benarnya dan hendaknya memperbanyak amalan salat sunnah untuk menutup kekurangan yang besar tersebut.
- Apabila seseorang belum mengeluarkan Zakat Fitri karena lupa atau tertidur dan tidak terbangun kecuali telah selesai Salat Ied, atau tidak menemui orang fakir kecuali setelah selesai Salat Ied, maka boleh baginya mengeluarkannya setelah Salat Ied. Dan insya Allah itu sah sebagai Zakat Fitri darinya dan diharapkan pahala yang sempurna baginya. [7]
Adapun orang yang belum mengeluarkan Zakat Fitri di waktu yang telah ditetapkan sampai leat waktunya tanpa uzur maka tidak sah jika ia mengeluarkan setelahnya.
- Jika seseorang ingin menyembelih Udhiyah (hewan kurban) tertentu, kemudian ia belum mengerjakannya sampai lewat waktunya, karena pingsan selama hari idul adha dan tiga hari tasyriq setelahnya, sedangkan tidak ada orang yang mewakilinya dan tidak bangun kecuali setelah tenggelamnya matahari pada hari ketiga hari tasyriq maka boleh baginya menyembelih dengan niat Udhiyah setelah itu.
Sedangkan orang yang sengaja menunda penyembelihan hewan kurban sampai lewat waktunya maka jika ia menyembelih setelah itu tidaklah sah sebagai Udhiyah, bahkan ia berdosa menurut pendapat yang mewajibkan Udhiyah.
- Barang siapa tidak berpuasa di hari-hari bulan Ramadan karena sakit, safar, atau uzur syari lainnya maka disyariatkan untuk mengqadha(menggantinya) di hari-hari lainnya. [8]
Adapun orang yang tidak berpuasa sehari saja dengan sengaja tanpa uzur syari maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mengqadhanya. Seandainya ia berpuasa sepanjang tahun tidaklah gugur tanggungannya untuk berpuasa di hari yang ditinggalkan tersebut. [9]
Maka sudah semestinya seorang Muslim bersemangat dalam mengejakan ibadah-ibadah yang disyaria’atkan dan melaksanakannya di waktu yang telah ditentukan, sehingga tanggungannya bisa gugur dan keluar dari lingkup tuntutan melaksanakan ibadah itu. Orang yang meninggalkannya tanpa uzur syari maka hendaknya bersegera bertaubat dan memperbanyak mengerjakan ibadah sejenisnya. Semoga dengan itu Allah ﷻ mengampuni kesalahan dan ketergelincirannya. [10]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Lihat penjelasan kaidah ini dalam as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin, Cet I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil Jauzi, Damam, VI/174.
[2]. HR. Muslim dalam Kitab al-Iman, no. 126.
[3]. Lihat Minhaj al-Muslim, Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, Hlm. 238-239.
[4]. HR. al-Bukhari dalam kitab Mawaqitush Salat, no. 597. Dan Muslim dalam kitab al-Masajid, no. 684 dari Anas bin Malik.
[5]. HR. Abu Dawud no. 4398, at-Tirmidzi no. 1423, an-Nasa’i no. 3432, dan Ibnu Majah no. 2041. Hadis diShahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih al-Jami’ no. 3512.
[6]. Lihat al-Mulakhash al-Fiqhiy, Syaikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, Cet. I, Tahun 1424 H/2003 M, Darul ‘Aqidah, Kairo, I/85.
[7]. Lihat as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zaad al-Mustaqni’, VI/174-175.
[8]. Tentang beberapa uzur syari yang menyebabkan seseorang diperbolehkan menqadha puasa Ramadan di antaranya bisa dilihat dalam al-Mulakhash al-Fiqhiy, Syaikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, I/307-308.
[9]. Terdapat ancaman yang keras bagi orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, di antaranya hadis Abu Umamah al Bahili riwayat Ibnu Hibban yang diShahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih at Targhib wat Tarhib, no. 1005.
[10]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-27.
Kaidah Ke-44: Ibadah Bertingkat-Tingkat Sesuai Dengan Maslahat Yang Mengiringinya
Kaidah Keempat Puluh Empat
الْعِبَادَاتُ تَتَفَاضَلُ بِاعْتِبَارِ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنَ الْمَصَالِحِ
Ibadah bertingkat-tingkat sesuai dengan maslahat yang mengiringinya
Makna Kaidah
Secara umum kaidah ini menjelaskan tentang perbedaan tingkatan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Perbedaan tingkat keutamaan ini tergantung pada maslahat dan kebaikan yang terkandung. Semakin besar maslahat yang terkandung dalam suatu ibadah maka akan semakin tinggi dibandingkan ibadah lainnya.
Dengan memahami kaidah ini seorang penuntut ilmu akan mampu menentukan ibadah mana yang lebih utama daripada yang lain. Karena adakalanya suatu ibadah yang asalnya lebih utama berubah menjadi lebih rendah keutamaannya, sebaliknya ibadah yang semula kurang utama menjadi lebih utama. Semua itu tergantung kepada ada atau tidaknya maslahat tertentu dalam ibadah tersebut. Maka seyogyanya bagi penuntut ilmu untuk memberikan perhatian kepada masalah maslahat, terlebih lagi perhatian terhadap maslahat dan mafsadat adalah inti syariat ini. Keberadaan syariat tiada lain hanya untuk menetapkan maslahat dan menyempurnakannya serta meniadakan mafsadat dan meminimalkannya [1]. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di dalam Manzhumah al Qawa’id al Fiqhiyyah:
الـدِّيْـنُ مَـبْـنِيٌّ عَـلَـى الْـمَصَـالِـحِ
فِـي جَـلْبِـهَـا وَالـدَّرْءِ لِــلْـقَبَـائِـحِ
Agama dibangun di atas maslahat,untuk mendatangkan maslahat itu dan menolak mafsadat
Dalil yang Mendasarinya
Banyak dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini, di antaranya firman Allah ﷻ:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
“Dan janganlah kamu memaki SeSembahan-SeSembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” [QS. al An’am/6:108].
Tidak diragukan bahwa mencela SeSembahan orang-orang musyrik adalah suatu amalan utama, dan meninggalkannya adalah amalan yang kurang utama. Namun, ketika celaan tersebut mengakibatkan mafsadat yang lebih besar, maka perkaranya menjadi terbalik. Maksudnya, perbuatan mencela SeSembahan orang-orang musyrik yang semula amalan utama menjadi kurang utama karena ada mafsadat yang mengiringinya, sedangkan meninggalkannya menjadi amalan yang lebih utama karena ada maslahat.
Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Mas’ud al-Anshari, bahwa Nabi ﷺ bersabda:
يؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
“Yang paling berhak menjadi imam pada suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Alqurannya. Jika mereka sama dalam hafalan maka yang paling berilmu tentang sunnah. Jika mereka sama dalam sunnah maka yang paling dahulu berijrah. Jika mereka sama dalam hijrah maka yang paling dahulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, dan janganlah ia duduk di tempat duduk khususnya di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya.” [3]
Dalam hadis tersebut Nabi ﷺ menjelaskan urutan orang yang paling berhak menjadi imam. Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang memiliki kedudukan khusus seperti pemimpin umum, atau pemimpin pasukan perang, atau imam tetap suatu masjid, atau pemilik rumah, lebih didahulukan menjadi imam daripada orang lain, meskipun selainnya lebih utama dari sisi kriteria secara umum. Maka orang yang lebih rendah kriterianya, jika ia adalah orang yang mempuyai kedudukan khusus seperti pemimpin umum, atau pemilik rumah, imam tetap masjid, dan semisalnya dalam kondisi ini lebih diutamakan untuk menjadi imam. Dan maslahat yang terkandung di dalamnya adalah terwujudnya persatuan dan terbendungnya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kaum Muslimin.
Dan sabda Nabi ﷺ dalam hadis ‘Aisyah radhiyallahu anha:
يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ وَ أَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَ جَعَلْتُ لَهُ بَابًا شَرْقِيًّا وَ بَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ
“Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru lepas dari kejahiliyahan, sungguh aku ingin memerintahkan mereka menghancurkan Kakbah lalu membangunnya, dan aku masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya, dan aku buat pintunya menempel dengan tanah, serta aku buatkan pintu timur dan barat, dan aku sesuaikan dengan pondasi Ibrahim.” [4]
Dalam hadis ini Nabi ﷺ menjelaskan tentang perkara yang lebih utama yaitu pembangunan Kakbah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis, sementara perkara yang tidak utama yaitu membiarkan bangunan Kakbah dengan tipe yang ada saat Nabi ﷺ bersabda ini. Akan tetapi perkara yang tidak utama ini berbalik menjadi lebih utama karena ada maslahat syariyah, yaitu supaya orang-orang yang baru masuk Islam tidak terfitnah dengan perubahan Kakbah.
Contoh Penerapan Kaidah
Berikut ini adalah beberapa contoh darinya:
- Pada asalnya membaca Alquran lebih utama daripada zikir. Namun dalam beberapa keadaan hukum asal ini bisa berubah. Misalnya ketika seseorang dalam keadaan rukuk atau sujud maka yang lebih utama adalah membaca zikir yang khusus ketika itu, bahkan membaca Alquran ketika itu terlarang secara syari.
- Telah maklum bahwa salat jenazah mempunyai pahala dan ganjaran yang besar, yaitu mendapatkan pahala satu qirath semisal gunung uhud sebagaimana disebutkan dalam hadis. [5] Dan meninggalkan salat jenazah adalah perkara yang tidak utama karena ia tidak mendapatkan pahala tersebut. Namun jika ada maslahat syariyah maka ketika itu lebih utama meninggalkannya. Misalnya jika si mayit adalah orang yang masih punya tanggungan utang, atau ahli bidah, pelaku bunuh diri, atau pelaku dosa besar. Dianjurkan kepada para pemimpin, tokoh masyarakat, ahli ilmu, dan ahli ibadah untuk tidak menyhalatinya karena ada maslahat yang besar. Yaitu menjadi peringatan bagi manusia agar tidak mengikuti perbuatan si mayit. Jadi, meninggalkan salat jenazah dalam keadaan tesebut menjadi lebih utama daripada melaksanakannya, karena ada maslahat yang mengiringinya. [6]
Pada asalnya menyembunyikan sedekah lebih utama daripada menampakkannya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:
وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
“Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.” [QS. al-Baqarah/2:271]
Disebutkan dalam hadis Abu Umamah al-Bahiliy riwayat at-Thabrani, bahwa Nabi ﷺ bersabda:
وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
Dan sedekah yang dirahasiakan akan meredam kemurkaan Rabb. [7]
Namun suatu ketika, menampakkan sedekah bisa menjadi amalan yang lebih utama daripada merahasiakannya. Yaitu, apabila hal itu diringi maslahat tertentu, misalnya mendorong dan memotivasi manusia untuk ikut mengeluarkan sedekah atau menolak persangkaan bakhil yang tertuju pada orang yang mengeluarkan sedekah itu, dan semisalnya. [8]
- Yang lebih utama dalam pelaksanakan salat adalah dilaksanakan pada awal waktunya. Dan menunda pelaksanaan sampai akhir waktunya adalah perkara yang tidak utama. Namun, jika mengakhirkannya mengandung maslahat tertentu yang lebih kuat, maka hal itu berubah menjadi yang lebih utama. Misalnya jika seseorang mengakhirkan salat karena di akhir waktu ia bisa mendapatkan air untuk berwudhu, sedangkan di awal waktu ia tidak menemui air. Atau karena di akhir waktu ia bisa melaksanakan salat dengan menutup aurat secara sempurna, sedangkan di awal waktunya tidak. Atau karena di awal waktu Salat Zuhur cuacanya sangat panas [9]. Atau mengakhirkannya supaya bisa menghafalkan Surat al-Fatihah dan lafal Tasyahud bagi orang yang baru masuk Islam. Maka ketika itu amalan yang semula asalnya kurang utama menjadi amalan yang lebih utama. [10]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Lihat Syarh al-Qawa’id as-Sa’diyah, Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah Az Zamil, Dar Athlas Al Kahadhra’ li an-Nasyri wa at-Tauzi’, hlm. 23.
[2]. Manzhumah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (dalam al-Majmu’ah al-Kamilah li Muallafati as-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di), Cet. II, 1992 M/1412 H, Markaz Saleh bin Saleh ats-Tsaqafi, Unaizah, 4/130.
[3]. HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah, no 673.
[4]. HR. Muslim, no. 1333.
[5]. Tentang pahala menghadiri jenazah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dalam Kitab as-Shalah, Bab Fadhlu Ittiba’i al-Janazah, no. 1325.
[6]. Lihat Fatwa berkaitan dengan permasalahan ini dalam Fatawa al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, Cet. II, Tahun 1421 H/2000 M, Dar al-Balansiyah, Riyadh, Fatwa no. 3782.
[7]. HR. at-Thabrani, dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih al-Jami’ no. 3797.
[8]. Lihat Tafsir Alquran al-Karim, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cet. I, 1423 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, 3/358.
[9]. Tentang disyariatkannya menunda Salat Zuhur karena cuaca yang sangat panas disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dalam Kitab Mawaqit as-Shalah, bab al-Ibrad bi azh-Zuhr fi as-Safar, no. 537. Dan Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah, Bab Istihab al-Ibrad bi azh-Zhuhr fi Syiddati al-Harri, no. 615.
[10]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-34 dengan penyesuaian dan penambahan.
Kaidah Ke-45: Dimaafkan Jika Sekadar Meneruskan Dan Dilarang Jika Memulai Dari Awal
Kaidah Keempat Puluh Lima
يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي اْلاِبْتِدَاءِ
Dimaafkan jika sekadar meneruskan dan dilarang jika memulai dari awal
Makna Kaidah
Memulai suatu perbuatan atau akad tertentu terkadang terlarang, namun jika sekadar meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya maka diperbolehkan dan diberi kelonggaran. Inilah inti pembahasan dalam kaidah ini.
Kaidah ini telah diisyaratkan dalam beberapa dalil dari Alquran dan Sunnah Nabi ﷺ. Kaidah ini juga mencakup unsur kemudahan dalam syariat yang sempurna ini. Karena dengan adanya perincian hukum sebagaimana disebutkan dalam kaidah ini maka akan memberikan kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan syariat. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah firman Allah ﷻ tentang larangan membunuh hewan buruan ketika seseorang dalam keadaan ihram:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.” [QS. al-Maidah/5:95]
Dalam ayat ini terdapat larangan bagi orang yang sedang berihram untuk membunuh binatang buruan. Namun jika ia membunuh binatang buruan itu sebelum memulai ihram dan di luar tanah haram, kemudian setelah itu ia berniat ihram dengan membawa hasil buruannya itu, maka dalam hal ini ia tidak wajib untuk meninggalkan hasil burunnya itu. Karena keberadaan binatang buruan bersamanya itu termasuk kategori al baqa’ (meneruskan apa yang telah diperbolehkan sebelumnya). Namun jika sedang ihram dan ia membunuh binatang buruan maka ia berdosa dan harus mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan itu. [2] Karena itu termasuk kategori al ibtida’ (memulai dari awal). Sedangkan kaidah menyatakan bahwa sekadar meneruskan itu lebih ringan daripada memulai. [3]
Demikian pula sabda Nabi ﷺ berkaitan dengan wabah yang berjangkit di suatu daerah:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِى أَرْضٍ فَلاَ تَقْدُمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ
“Kalian mendengar berita tentangnya (penyakit tha’un) di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Jika wabah penyakit itu sedang melanda daerah yang sedang kamu tempati, maka janganlah keluar (meninggalkan daerah itu) karena hendak lari dari penyakit tersebut.” [4]
Apabila ada wabah yang berjangkit di suatu daerah maka orang yang ada di dalamnya tidak boleh keluar darinya, meski ada kemungkinan dia terkena madharat. Karena itu termasuk dalam kategori meneruskan apa yang telah ada dan tidak dianggap menjerumuskan diri dalam bahaya. Adapun orang yang berada di luar daerah tersebut maka ia tidak boleh masuk ke daerah wabah. Karena seorang insan diperintahkan untuk menjaga jiwanya dan dilarang menjatuhkan dirinya dalam kebiasaan. [5]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah ini mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut:
- Di antara larangan ihram adalah mengadakan akad nikah, maka tidak boleh bagi orang yang sedang dalam keadaaan ihram untuk menikah atau dinikahkan. Berdasarkan hadis ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu anhu, di mana Nabi ﷺ bersabda:
لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ
“Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang.” [6]
Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan ihram melakukan akad nikah maka nikahnya tidak sah. Namun jika seseorang mentalak (menceraikan) istrinya, kemudian setelah itu ia berniat ihram, lalu muncul dalam hatinya keinginan untuk meruju’ istri yang telah diceraikan itu, maka boleh baginya untuk merujuknya. Karena ruju’ bukanlah memulai akad pernikahan baru namun hanya sekadar meneruskan akad nikah yang sudah ada. [7]
- Menikahi budak perempuan diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu seseorang tidak mampu memberikan mahar kepada wanita merdeka dan khawatir terjatuh pada perbuatan fahisyah (perzinaan). Berdasarkan firman Allah ﷻ:
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu.” [QS. an-Nisa’/4:25]
Apabila terpenuhi dua syarat ini maka boleh baginya untuk menikahi budak wanita. Apabila di kemudian hari ia telah mempunyai kemampuan untuk menikahi wanita merdeka atau telah hilang darinya kekhwatiran terjatuh dalam perzinaan, maka ketika itu haram baginya menikahi budak wanita untuk kedua kalinya. Adapun pernikahannya yang pertama tetap sah. Karena yang dilarang adalah memulai pernikahan dengan budak wanita mulai dari awal saat tidak terpenuhi syaratnya, adapun sekadar meneruskan maka diberi kelonggaran.
- Berkaitan dengan pelaksanaan Salat Sunnah Mutlaq, yaitu salat sunnah yang tidak ada sebab tertentu. Jika seseorang memulai salat mutlaq itu pada selain waktu larangan salat [8] kemudian di tengah-tengah salat waktu larangan masuk, maka hal itu tidak mengapa, karena ini masuk dalam kategori meneruskan apa yang diperbolehkan sebelumnya. Akan tetapi jika telah masuk waktu larangan kemudian ia baru memulai Salat Sunnah Mutlaq maka hal itu tidak diperbolehkan.
- Apabila seseorang memiliki harta haram disebabkan cara mendapatkan yang tidak dibenarkan syariat, namun ia tidak tahu bahwa cara seperti itu dilarang syariat. Seperti penghasilan dari muamalah ribawi dan semisalnya. Timbul pertanyaan, apabila dikemudian hari ia tahu hukumnya haram, apakah wajib baginya untuk membuang harta yang telah ia dapatkan tersebut ataukah tidak? Jawabannya, ia tidak wajib meninggalkan harta yang telah ia dapatkan itu, karena ia mendapatkan uzur dengan sebab ketidaktahuannya. Juga ini masuk dalam kategori al baqa’ (meneruskan apa yang sebelumnya). Namun ketika ia telah mengetahui ilmunya, maka ia tidak boleh untuk mencari penghasilan dengan cara tersebut sejak saat itu.
- Sebelum melaksanakan ihram untuk haji atau umrah disunnahkan bagi seseorang untuk memakai minyak wangi berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata:
كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَ لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِاْلبَيْتِ
“Dahulu aku memakaikan Nabi ﷺ wangi-wangian untuk ihramnya sebelum beliau ihram, dan ketika halalnya sebelum Thawaf di Kakbah.” [9]
Maka disunnahkan bagi orang yang akan berniat ihram untuk memakai minyak wangi di badannya. Tidak diragukan bahwa apabila ia telah masuk dalam ibadah ihram bekas minyak wangi tersebut tetap ada, dan ini diperbolehkan. Karena hal itu hanya sekadar meneruskan apa yang telah ada sebelumnya. Namun jika ia memulai memakai minyak wangi ketika sudah dalam keadaan ihram, maka hal itu tidak diperbolehkan dan wajib baginya untuk membayar Fidyah. [10] Karena memulai memakai minyak wangi ketika sudah dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan, sedangkan sekadar meneruskan apa yang ada sebelumnya maka diberi kelonggaran. [11]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Lihat pembahasan kaidah ini dalam al-Qawa’id al-Fiqhiyyah ma’a as-Syarh al-Mujaz, hlm. 82.
[2]. Sebagaimana firman Allah ﷻ l dalam QS. al-Maidah/5:95.
[3]. Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 305.
[4]. HR. al-Bukhari no. 5729 dan Muslim no. 2219 dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf radhiyallahu anhu
[5]. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. al-Baqarah/2:195
[6]. HR. Muslim no. 41.
[7]. Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, hlm. 305.
[8]. Di antara hadis yang menjelaskan rincian waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat ketika itu adalah HR. Muslim no. 731 dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu anhu. Dan hadis Abu Sa’id al Khudri riwayat al-Bukhari no. 586.
[9]. HR. al-Bukhari no.1539 dan Muslim no. 1189.
[10]. Fidyah yang harus dibayarkan adalah berpuasa tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka’ab bin ‘Ujrah riwayat al-Bukhari no. 1815 dan Muslim no. 1201.
[11]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-53, dengan penyesuaian dan penambahan.
Kaidah Ke-46: Didahulukan Bagian Kanan Dalam Perkara-Perkara Yang Mulia Maupun Berhias
Kaidah Keempat Puluh Enam
تُقَدَّمُ الْيَمِيْنُ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ وَالتَّزَيُّنِ وَالْيُسْرَى فِيْمَا عَدَاهُ
Didahulukan bagian kanan dalam perkara-perkara yang mulia maupun berhias dan didahulukan bagian kiri dalam perkara selainnya
Makna Kaidah
Sesungguhnya Allah ﷻ telah menciptakan para makhluk-Nya dan Dia telah memilih darinya sesuai kehendaki-Nya. Di antara yang dipilih-Nya adalah sisi sebelah kanan yang ditakdirkan memiliki keutamaan dan kemuliaan yang lebih dibandingkan sisi sebelah kiri. Jika kita mencermati dalil-dalil syari, maka kita dapati bahwa suatu perkara atau perbuatan jika termasuk dalam hal yang mulia, yang indah, dan ibadah, maka disyariatkan untuk dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Namun jika suatu perkara bukan termasuk dalam kategori tersebut, yaitu berupa hal-hal yang kurang utama, seperti menghilangkan atau mencuci najis, atau mengambil benda-benda yang kotor, maka yang lebih didahulukan adalah anggota badan yang kiri. Inilah makna dan kandungan kaidah ini secara umum. [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ
“Nabi ﷺ menyukai memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya.” [2]
Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ﷺ bersabda:
إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوْا بِمَيَامِنِكُمْ
“Apabila kalian berwudhu maka mulailah dari anggota badan sebelah kanan.” [3]
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam berkata: “Disunnahkan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan ketika berwudhu. Yaitu dengan membasuh tangan kanan terlebih dahulu kemudian tangan kiri, serta membasuh kaki kanan terlebih dahulu baru kemudian kaki kiri.” [4]
Disebutkan pula dalam hadis Anas radhiyallahu anhu tentang mendahulukan kaki ketika masuk masjid, ia berkata:
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى
“Termasuk dalam perkara sunnah adalah jika engkau masuk masjid maka engkau mendahulukan kaki kanan, dan jika engkau keluar masjid maka engkau dahulukan kaki kiri.” [5]
Hadis ini menjelaskan, bahwa apabila seseorang berpindah dari tempat yang kurang mulia ke tempat yang mulia hendaknya ia mendahulukan kaki kanannya terlebih dahulu barulah kemudian kaki kirinya.
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah yang mulia ini mempunyai implementasi dan contoh penerapan yang cukup banyak. Berikut ini sekadar beberapa contoh darinya:
- Yang lebih utama ketika menulis adalah menggunakan tangan kanan. Karena menulis termasuk hal mulia dan di antara karunia Allah [6]. Hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ:
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Alquran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu.” [QS. al-‘Ankabut/29:48]
- Ketika seseorang masuk rumahnya, yang lebih utama adalah mendahulukan kaki kanannya. Karena rumah adalah tempat yang mulia sedangkan jalanan adalah tempat yang kurang mulia. Sehingga tatkala berpindah ke tempat yang lebih mulia maka ia mendahulukan kaki kanannya. Sebagaimana Allah ﷻ jelaskan bahwa keberadaann rumah adalah kemuliaan bagi manusia. Allah ﷻ berfirman:
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا
“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal.” [QS. an-Nahl/16:80]
- Ketika memakai alas kaki disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan, tapi ketika melepasnya yang disunnahkan mendahulukan yang kiri. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى
“Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepas, mulailah dengan kaki kiri.” [7]
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memakai alas kaki dimulai dengan yang kanan, karena memakai alas kaki termasuk kemuliaan dan perhiasan. Adapun melepasnya maka dimulai dari yang kiri karena hal itu bermakna melepas perhiasan tersebut.
- Dalam salat berjamaah, shaf yang lebih utama adalah yang berada di sebelah kanan imam. Maka berdiri di sebelah kanan shaf lebih utama daripada berdiri di sebelah kirinya, berdasarkan hadis al-Barra’ bin ‘Azib radhiyallahu anhu:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ الله ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ
“Jika kami salat di belakang Rasulullah ﷺ kami senang berada di sebelah kanan beliau. Beliau ﷺ akan menghadapkan wajahnya kepada kami.” [8]
Namun jika berdiri di shaf sebelah kanan menyebabkan seseorang jauh dari imam, maka yang lebih utama adalah ia lebih dekat kepada imam meskipun berada di shaf sebelah kiri. Karena ada dalil-dalil Shahih tentang keutamaan berdiri dekat imam. [9]
- Ketika makan dan minum disyariatkan menggunakan tangan kanan, karena keduanya adalah suatu yang mulia, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ
“Jika salah seorang dari kalian makan maka hendaklah makan dengan tangan kanannya, dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya, sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya.” [10]
Adapun sebalikannya seperti buang air dan semisalnya maka yang disyariatkan adalah menggunakan tangan kiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha:
كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى
“Tangan kanan Rasulullah ﷺ digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kiri beliau dipergunakan untuk buang air dan dan segala hal yang kotor.” [11]
- Ketika memotong rambut dalam rangkaian ibadah haji atau umrah disunnahkan untuk memulai dari bagian kanan. Karena itu termasuk dalam kategori ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasa Rasulullah ﷺ sampai di Mina dan melempar jumrah, kemudian beliau menuju ke penginapannya di Mina dan menyembelih kurban, kemudian beliau bersabda kepada tukang cukur: “Cukurlah ini”, sambil menunjuk ke kepala sebelah kanan, lalu sebelah kiri, kemudian membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. [12]
Dan diqiyaskan dalam hal ini ketika seseorang mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan mencukur bulu kemaluan. Maka yang didahulukan adalah bagian kanan daripada bagian kiri. [13]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Imam an-Nawawi menyebutkan kaidah ini dalam kitab Riyadhus Salehin pada bab ke-99 dengan mengatakan: “Bab disunnahkan mendahulukan bagian kanan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan kemuliaan. (Lihat Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhus Salehin, Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘Id al-Hilali, Cet. ke-1, 1430 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, II/41)
[2]. HR. al-Bukhari no. 5926 dan Muslim 268 dari Aisyah radhiyallahu anha.
[3]. HR. Abu Dawud no. 4141, Ibnu Majah no. 302. DiShahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 4141.
[4]. Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Cet. ke-5, 1423 H/2003 M, Maktabah al-Asadiy, Makkah al-Mukarramah, I/232.
[5]. HR. al-Hakim dan diShahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Silsilah al-Ahadis as-Shahihah no. 2478.
[6]. Sebagaimana firman Allah ﷻ k dalam QS. Al-Qalam/68:1, dan firman-Nya dalam QS. Ali ‘Imran/3:48.
[7]. HR. al-Bukhari no. 5856 dan Muslim no. 2097 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
[8]. HR. Muslim no. 709 dari Al Barra’ bin ‘Azib radhiyallahu anhu
[9]. Di antaranya HR. Muslim no. 437 dari Abu Sa’id Al Khudri.
[10]. HR. Muslim no. 2020 dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma
[11]. HR. Abu Dawud no. 33 dan diShahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 26.
[12]. HR. al-Bukhari no. 171 dan Muslim no. 1305 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
[13]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-58 dengan beberapa penyesuaian.
Kaidah Ke-47: Apabila Terkumpul Faktor Hukumnya Boleh Dan Sebab Terlarang Maka Didahulukan Larangan
Kaidah Keempat Puluh Tujuh
إِذَا اجْتَمَعَ مُبِيْحٌ وَحَاظِرٌ غُلِّبَ جَانِبُ الْحَاظِرُ
Apabila terkumpul (pada sesuatu) faktor yang menyebabkan hukumnya boleh dan sebab yang menjadikannya terlarang maka didahulukan sisi larangan
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan, apabila terkumpul dalam suatu perkara dua sebab (faktor) yang berbeda. Faktor pertama menyebabkan bolehnya menggunakan atau memanfaatkan perkara tersebut, sedangkan faktor kedua mengakibatkan terlarangnya menggunakan memanfaatkan perkara tersebut. Dalam kondisi tersebut yang wajib bagi kita adalah Tawaqquf (tidak mengambil sikap tertentu) sampai urusan tersebut menjadi jelas.
Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi bait ke-31:
إِنْ يَـجْـتَـمِعْ مَـعَ مُـِبـيْحٍ مَـا مَـنَـعْ
فَـقَـدِّمَـنْ تَـغْــلِيْـبًا الَّــذِي مَـنَـعْ
Jika berkumpul hal yang membolehkan bersama larangan
Maka dahulukanlah sisi larangan daripada pembolehannya [1]
Kaidah ini juga merupakan realisasi sikap wara’ (hati-hati). Yaitu bersikap hati-hati dengan meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan agama ataupun kehormatannya. Termasuk juga, meninggalkan suatu yang masih belum jelas karena khawatir sesuatu itu termasuk perkara yang haram.
Dalil yang Mendasarinya
Kaidah ini telah ditunjukkan oleh beberapa dalil baik dari Alquran dan Sunnah Nabi ﷺ. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
“Dan janganlah kamu memaki SeSembahan-SeSembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” [QS. al An’am/6:108]
Dalam Sesembahan orang-orang musyrik terkumpul dua faktor. Faktor pertama berkonsekuensi bolehnya mencela, karena mereka dijadikan Sesembahan, sekutu bagi Allah ﷻ. Celaan itu merupakan bentuk penghinaan kepada mereka dan orang-orang yang menyembahnya. Namun di sana juga ada faktor yang berkonsekuensi terlarangnya mencela mereka, yaitu keberadaan orang-orang musyrik yang akan mencela Allah ﷻ jika Sesembahan mereka dicela. Dalam hal ini sisi larangan lebih didahulukan daripada sisi pembolehan. Yaitu jika kita mengetahui bahwa celaan kepada Sesembahan -Sesembahan tersebut akan menimbulkan celaan kepada Allah ﷻ, maka kita tidak boleh mencela Sesembahan mereka. [2]
Adapun dalil dari as-Sunnah di antaranya adalah hadis yang Muttafaq ‘alaih:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram pun telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya.” [3]
Jadi, perkara-perkara yang terkumpul padanya sebab yang menjadikannya haram dan sebab yang menjadikannya halal termasuk perkara syubhat (samar) yang tidak jelas keharaman atau kehalalannya. Dalam hadis tersebut Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk menjaga diri dan menjauhi perkara yang samar tersebut. Karena itu lebih selamat bagi agama dan kehormatan seseorang. Kita tidak mungkin menjaga diri kecuali dengan lebih mengedepankan sebab yang melarang daripada sebab yang membolehkan. [4]
Demikian pula disebutkan dalam hadis ‘Adi bin Hatim bahwa suatu ketika ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hewan buruan hasil tangkapan anjing, maka Nabi ﷺ bersabda:
إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ
“Apabila engkau melepas anjingmu yang telah terlatih, dan engkau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka makanlah hewan buruan yang ditangkapnya untukmu. Kecuali jika anjing itu memakan hewan buruan itu, karena aku khawatir anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. Jika ada anjing lain yang menyertai anjingmu maka janganlah engkau makan hasil buruannya.” [5]
Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa hewan hasil buruan anjing yang terlatih hukumnya halal kecuali dalam dua keadaan:
- Apabila anjing tersebut memakan hewan buruannya, karena terkumpul pada hewan tersebut dua sebab atau faktor; Satu sebab berkonsekuensi halal, sementara sebab yang lainnya berkonsekuensi haram. Sebab atau faktor yang berkonsekuensi halal adalah hewan itu diburu oleh anjing yang sudah terlatih dan si pemilik anjing telah melepasnya dengan menyebut nama Allah ﷻ. Adapun faktor yang menyebabkan haram adalah anjing itu memakannya. Ini merupakan indikasi kuat bahwa anjing itu memburu untuk dirinya sendiri bukan untuk pemiliknya. Maka dalam kasus ini dimenangkan sisi keharaman daripada sisi kehalalan.
- Apabila ada anjing lain yang ikut memburu hewan buruan tersebut, karena penyebab kematian hewan buruan itu ada dua kemungkinan. Salah satunya berkonsekuensi halal, yaitu diburu oleh anjing yang sudah terlatih dan si pemilik anjing telah melepasnya dengan menyebut nama Allah ﷻ. Dan sebab kedua berkonsekuensi haram, yaitu keberadaan anjing lain yang ikut memburunya, di mana si pemilik tidak menyebut nama Allah ketika terlepasnya anjing tersebut. Demikian pula tidak diketahui secara jelas kematian hewan buruan itu disebabkan oleh anjing yang mana. Maka dalam kasus ini juga hewan buruan tersebut dihukumi sebagai hewan yang haram dimakan. [6]
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah yang mulia ini mempunyai implementasi dan contoh penerapan yang cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut:
- Apabila seekor hewan disembelih oleh dua orang. Salah satunya, orang yang sembelihannya halal, sedangkan yang lain sembelihannya haram. [7] Salah satu dari keduanya memotong tenggorokan hewan, dan orang yang lain memotong pembuluh darahnya. Maka pada hewan itu terkumpul dua sebab, salah satunya berkonsekuensi halal, sebab lainnya berkonsekuensi haram. Dalam hal ini hewan itu dihukumi haram karena sisi keharaman lebih didahulukan daripada sisi kehalalan. [8]
- Hewan yang lahir dari hasil persilangan antara hewan yang haram dimakan dan hewan yang halal dimakan [9] dihukumi sebagai hewan yang haram dimakan. Hal ini karena sisi keharaman harus lebih dikedepankan daripada sisi kehalalan.
- Apabila seseorang memanah atau menembak hewan buruan lalu hewan itu jatuh ke air dan mati di sana. Maka dalam hal ini, penyebab kematiannya ada dua kemungkinan. Salah satunya berkonsekuensi halal, yaitu mati karena dipanah atau ditembak dengan terlebih dahulu disebutkan nama Allah ﷻ. Dan sebab yang lain berkonsekuensi haram, yaitu mati karena tenggelam. Dalam kasus ini, sisi keharaman harus lebih didahulukan daripada sisi kehalalan. Oleh karena itu, hewan itu dihukumi haram. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadis ‘Adi bin Hatim:
وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُل
“Dan apabila hewan buruan itu jatuh ke air maka janganlah engkau memakannya.” [10]
- Apabila seorang laki-laki melihat dua orang wanita, salah satunya adalah istrinya dan yang lainnya wanita bukan mahramnya, sementara dia tidak bisa membedakan mana si istri dan mana yang bukan. Dalam hal ini wajib baginya untuk tidak menyentuh salah satunya sampai jelas mana istrinya dan mana yang bukan. [11]
- Apabila ada dua potong daging, salah satunya daging halal, dan satunya lagi daging bangkai, sementara dia tidak tahu, mana yang halal dan mana yang bangkai. Dalam kondisi ini, maka wajib meninggalkan semuanya karena sisi keharaman lebih dikedepankan daripada sisi kehalalan [12].
Wallahu a’lam. [13]
_______
Footnote
[1]. Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 134.
[2]. Lihat penjelasan tentang ayat di atas dalam Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 130.
[3]. HR. al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599 dari Nu’man bin Basyir.
[4]. Lihat pula penjelasan hadis di atas dalam Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cet. III, Tahun 1425 H/2004 M, Dar ats-Tsurayya li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 124-134.
[5]. HR. al-Bukhari no. 5483 dan Muslim no. 1929 dari ‘Adi bin Hatim.
[6]. Lihat pula penjelasan hadis di atas dalam Taudhih al-Ahkam, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Cet. V, Tahun 1423 H/2003 M, Maktabah al-Asadiy, Makkah al-Mukarramah, VII/39-44.
[7]. Di antara syarat sahnya sembelihan adalah bahwa yang menyembelih adalah orang Muslim atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Adapun orang kafir selain ahli kitab maka sembelihannya haram. Berdasarkan mafhum firman Allah ﷻ dalam QS. Al Maaidah: 5. (Lihat Talkhis Ahkam al-Udhhiyyah wa adz-Dzakah, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Tahun 1430 H, Muassasah as-Syaikh Muhammmad bin Saleh al-Utsaimin al-Khairiyyah, al-Qasim, hlm. 38-39).
[8]. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (al-Manzhumah wa Syarhuha), Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Wizarah al-Auqaf wa as-Syu-un al-Islamiyah, al-Jahraa’, Hlm. 128.
[9]. Contohnya adalah bighal, yaitu hewan hasil persilangan antara kuda dan keledai. (Lihat Minhaj al-Muslim, Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, Hlm. 408.
[10]. HR. al-Bukhari no. 5484 dari ‘Adi bin Hatim.
[11]. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (al-Manzhumah wa Syarhuha), Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Wizarah al-Auqaf wa as-Syu-un al-Islamiyah, al-Jahraa’, Hlm. 128.
[12]. Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 135.
[13]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-53, dengan beberapa penyesuaian.
Kaidah Ke-48: Rasa Ragu Dari Orang Yang Sering Ragu Itu Tidak Dianggap
Kaidah Keempat Puluh Delapan
لاَ يُعْتَبَرُ الشَّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ وَمِنْ كَثِيْرِ الشَّكِّ
Rasa ragu setelah melakukan perbuatan dan rasa ragu dari orang yang sering ragu itu tidak dianggap
Makna Kaidah
Kaidah ini merupakan cabang atau bagian dari kaidah “keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sekadar keraguan”. Secara umum, kaidah ini menjelaskan tentang orang yang mengalami keragu-raguan dalam suatu amalan. Jika rasa ragu itu muncul setelah melakukan suatu amalan, maka rasa itu tidak perlu dihiraukan. Demikian pula, jika rasa ragu itu muncul dari orang yang sering ragu.
Sebelum membahas lebih jauh tentang kaidah ini perlu dipahami bahwa rasa ragu itu bisa muncul dari dua tipe orang. Pertama, dari orang yang sering ragu. Kedua, dari orang yang keraguannya biasa (normal).
Rasa ragu dari tipe orang pertama, tidak perlu dianggap, karena menurutkan rasa ragu dalam kondisi seperti itu akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan yang berat baginya, serta termasuk takalluf (memaksa diri memikulkan beban yang ia tidak mampu). Bahkan orang seperti ini rasa ragunya perlu diobati dengan cara tidak memperdulikan rasa ragu yang muncul dan memantapkan hati saat beramal. Keraguan orang semacam ini tidak dianggap, maksudnya, tidak ada konsekuensi hukumnya.
Rasa ragu dari tipe orang kedua adalah apabila keraguan itu muncul dari orang yang keraguannya normal. Keraguan jenis ini tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, rasa itu muncul saat sedang melaksanakan amalan. Kedua, rasa itu muncul setelah beramal.
Jika keraguan itu muncul setelah beramal maka ia tidak dianggap. Karena hukum asalnya, jika seseorang telah usai mengerjakan suatu amalan berarti amalan itu telah dilaksanakan secara sempurna. Keraguan yang muncul setelah beramal hanya sekadar bisikan setan. Obat dari rasa ragu jenis ini ialah tidak memperdulikannya.
Adapun jika keraguan itu muncul di tengah-tengah saat beramal, atau akan melaksanakan ibadah, maka ketika itu keraguannya dianggap. Karena jika seseorang ragu, apakah ia sudah mengerjakan ibadah atau belum, maka hukum asalnya ia belum mengerjakannya.
Jadi rasa ragu itu tidak dipedulikan dalam dua keadaan dan diperhitungkan dalam satu keadaan. Jika rasa ragu itu muncul dari orang yang sering ragu, maka itu tidak dianggap secara mutlak, baik munculnya saat pelaksanaan ibadah maupun setelahnya. Juga tidak dianggap, jika muncul dari orang yang normal namun munculnya setelah selesai beramal.
Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Manzhumah Ushulil-Fiqh wa Qawa’idihi pada bait ke-38:
وَالـشَّــكُّ بَــعْـدَ الْـفِـعْـلِ لَا يُــؤَثِّــرُ
وَهَــكَـذَا إِذَا الـشُّــكُــوْكُ تَــكْـثُــرُ
Dan keraguan setelah perbuatan tidaklah berpengaruh
Demikian pula jika keraguan itu sering terjadi [1]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” [QS. al-Baqarah/2:286]
Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: “Maksud ayat ini, Allah ﷻ tidak membebani seorang pun diluar kemampuannya. Ini merupakan wujud kelembutan, kasih sayang dan kebaikan Allah ﷻ kepada hamba-Nya.” [2]
Di antara perkara yang berat dan tidak mampu dipikul seorang hamba ialah apabila rasa ragu yang muncul dari orang yang mengalami penyakit ragu itu diperdulikan. Sehingga hal itu ditiadakan oleh Allah ﷻ. Dalam ayat yang lain Allah ﷻ berfirman:
إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah.” [QS. al Mujadilah/58:10].
Keragu-raguan yang muncul dari orang yang sering ragu pada hakikatnya berasal dari setan. [3] Oleh karena itu, keraguan itu tidak perlu dihiraukan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ bahwa setan senantiasa menggoda dalam diri manusia. Beliau ﷺ bersabda:
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ اْلإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
“Sesungguhnya setan berjalan di dalam diri manusia di tempat mengalirnya darah.” [4]
Demikian pula, kaidah ini telah ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ dalam salah satu hadis Shahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sesuatu di perutnya seolah-olah ia telah berhadats, sehingga ia ragu-ragu apakah telah berhadats ataukah belum, maka Nabi ﷺ bersabda:
لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيْحًا
“(Janganlah ia keluar dari salatnya sehingga mendengar suara atau mendapatkan baunya) [5], yaitu, janganlah ia keluar dari salatnya hanya karena yang ia rasakan itu sampai benar-benar yakin bahwa ia telah berhadats. Hadis ini sekaligus merupakan dalil umum bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan hanya karena sekadar keragu-raguan.”
Contoh Penerapan Kaidah
Banyak kasus yang masuk dalam penerapan kaidah mulia ini. Berikut beberapa contoh darinya:
- Seseorang selesai mengerjakan Salat Ashar, kemudian ragu-ragu apakah ia sudah Tasyahud Awal ataukah belum? Untuk orang ini, kita katakan bahwa keraguannya tidak perlu dihiraukan, baik rasa ragu itu muncul dari orang yang normal keraguannya maupun orang yang sering ragu. Kenapa tidak dihiraukan? Jawabnya, karena rasa itu ada setelah melakukan amalan. Kesimpulannya, Salat Asharnya sah dan tidak perlu menoleh kepada keraguan yang muncul, selama tidak ada indikasi yang menimbulkan rasa yakin bahwa ia memang belum duduk Tasyahud Awal.
- Seseorang yang tengah malempar jumrah ragu-ragu apakah sudah melempar enam kali atau tujuh kali. Jika keraguan itu muncul dari orang yang sering ragu, maka ia tidak perlu mempedulikan keraguaannya itu dan ia tinggal melakukan lemparan yang tersisa. Jika batu yang dipegangnya tidak tersisa, maka ia kuatkan hatinya bahwa lemparan jumrahnya itu telah sempurna. Adapun jika hal itu terjadi pada orang yang normal keraguannya, maka keraguannnya dianggap dan ia menambah lemparan yang ketujuh karena hukum asalnya lemparan ke tujuh itu adalah belum ada.
- Seseorang selesai wudhu kemudian ragu-ragu apakah sudah mengusap kepalanya ataukah belum? Keraguan yang demikian ini tidak perlu dihiraukan secara mutlak, karena keraguan tersebut muncul setelah selesai beramal.
- Seseorang sedang melaksanakan Thawaf dan ia ragu-ragu apakah putaran Thawaf yang sedang ia lakukan ini ke-5 atau ke-6? Pertama, apakah ia termasuk orang yang sering ragu-ragu atau tidak? Apabila ia orang yang sering ragu, maka hendaklah ia tidak memperdulikan rasa ragu itu dan ia memantapkan amalannya dengan menentukan bahwa ia sedang pada putara ke-6, tanpa menghiraukan keraguan yang muncul tersebut. Adapun jika keragu-raguan itu muncul dari orang yang keraguannya normal, maka keraguannya dianggap. Karena keraguan itu muncul di tengah-tengah pelaksanaan amalan, maka ia tentukan baru melaksananakan empat kali putaran, karena hukum asal putaran yang kelima belum ada sampai yakin bahwa itu telah dilaksanakan. [6]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Syarh Manzhumah Ushulil-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 153.
[2]. Tafsir Alquran al-‘Azhim, Imam ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, Cet. ke-5, Tahun 1421 H/2001 M, Jum’iyah Ihyaa’ at-Turats al-Islamiy, Kuwait, I/473.
[3]. Lihat al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-38.
[4]. HR al-Bukhari dalam Kitab al-I’tikaf, Bab: Hal Yakhrujul Mu’takifu li Hawaijihi ila Babil-Masjid, no. 2035; Muslim dalam Kitab as-Salam, no. 2175.
[5]. HR al-Bukhari dalam Kitab al-Wudhu’, Bab: La Yatawaddha’ Minasy-Syak, No. 137; Muslim dalam Kitab al-Haidh, Bab: al-Wudhu’ min Luhumil-Ibil, no. 361.
[6]. Diangkat dari Talqihul-Afham al-‘Aliyyah bi Syarhil-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-4, dengan penyesuaian dan penambahan.
Kaidah Ke-49: Hukum Asal Suatu Ibadah Tidaklah Ada Kecuali Jika Ada Dalilnya
Kaidah Keempat Puluh Sembilan
اْلأَصْلُ فِي شُـرُوْطِ الْعِبَـادَاتِ الْمَنْـعُ وَالْحَظْـرُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ
Hukum asal syarat sah suatu ibadah tidaklah ada kecuali jika ada dalilnya
Muqadimah
Sesungguhnya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ﷻ dengan mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Allah ﷻ telah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menunjukkan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Berkaitan dengan rincian ibadah, Allah ﷻ tidak memberikan kesempatan bagi akal manusia untuk menentukan dan menetapkannya. Karena akal tidak bisa berdiri sendiri untuk mengetahui mana ibadah yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Yang berhak menetapkan syarat-syarat sah suatu ibadah adalah Allah ﷻ semata, baik melalui Alquran maupun melalui lisan nabi-Nya. Maka seseorang tidak berhak mengaitkan keabsahan suatu ibadah dengan sesuatu hal kecuali jika ada dalil yang menjadi landasannya. Karena penentuan syarat suatu ibadah merupakan wewenang Allah ﷻ yang telah mensyariatkan ibadah itu. Barang siapa menentukan syarat sah suatu ibadah berdasarkan akal semata maka hakikatnya ia telah menjadikan dirinya sebagai pembuat syariat bersama Allah ﷻ.
Di samping itu, perlu dipahami juga bahwa tidak diperbolehkan mengaitkan suatu ibadah dengan suatu syarat yang didasarkan pada dalil lemah. Karena dalil yang lemah tidak dapat dijadikan pijakan dalam permasalahan ahkam (hukum-hukum syari).
Makna Kaidah
Sebagaimana telah diisyaratkan dalam uraian di atas, bahwa kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal penetapan syarat sah suatu ibadah. Di mana, keberadaan sesuatu bisa ditetapkan menjadi syarat sah suatu ibadah jika didasari dalil yang menjelaskannya.
Maka sebagaimana hukum asal suatu ibadah itu adalah terlarang, maka demikian pula syarat-syarat ibadah dan tata caranya, hukum asalnya juga terlarang, dan tidak boleh ditetapkan kecuali jika ada dalil Shahih dan sharih (tegas) yang menunjukkannya.
Dalil Kaidah Ini
Kaidah ini masuk dalam keumuman larangan Allah ﷻ dan Rasul-Nya dari mengada-adakan perkara baru dalam agama. Juga masuk dalam keumuman kaidah bahwa hukum asal suatu ibadah adalah dilarang kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya. Di antara dalil yang menjelaskannya adalah firman Allah ﷻ:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
“Apakah mereka mempunyai Sembahan-Sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” [QS. as-Syura/42:21]
Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: “Maka hukum asalnya adalah dilarang bagi setiap orang untuk menetapkan suatu amalan (ibadah) yang tidak ada tuntunannya dari Allah ﷻ dan tidak pula dari rasul-Nya.” [1]
Dan sabda Nabi ﷺ dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha:
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
“Barang siapa mengerjakan suatu amalan (ibadah) yang tidak berdasarkan perintah kami maka ia tertolak.” [2]
Imam Ibnu Rajab al-Hambali ketika menjelaskan ayat ini mengatakan: “Teks Hadis ini menjelaskan, bahwa setiap amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat, maka amalan itu tertolak. Dan secara tersirat menjelaskan bahwa setiap amalan yang dilandasi tuntunan dalam syariat, maka amalan itu tidaklah ditolak.” [3]
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut:
- Sebagian ulama mensyaratkan kehadiran minimal empat puluh orang untuk keabsahan Salat Jumat. Ini pendapat yang masyhur dalam Madzhab Hambali. [4] Namun, jika kita cermati, ternyata tidak ada dalil yang mendasarinya kecuali dalil yang lemah. Di antaranya adalah hadis Jabir bin ‘Abdlullah radhiyallahu anhu:
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمْعَةٌ
“Telah berlalu sunnah bahwa setiap empat puluh orang ke atas diwajibkan Salat Jumat.” [5]
Hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah.
Demikian pula sebagian ulama ada mensyaratkan kehadiran sejumlah dua belas orang untuk keabsahan Salat Jumat, sebagaimana dipegang oleh madzhab Maliki. Pendapat ini meskipun didasari oleh dalil yang Shahih namun tidak secara tegas menunjukkan tentang penetapannya sebagai syarat. [6]
Oleh karena tidak ada dalil yang mensyaratkan jumlah tertentu untuk keabsahan Salat Jumat, maka sebagian ulama memandang sahnya Salat Jumat yang dihadiri oleh dua orang saja, karena dua orang sudah terhitung jamaah. Sebagian ulama lainnya berpendapat sahnya Salat Jumat dengan dihadiri tiga orang, di mana satu orang berkhutbah dan dua orang lainnya mendengarkan khutbah. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang kuat karena menurut pendapat yang Shahih di kalangan ahli Ushul Fiqh bahwa jumlah jama’ paling sedikit adalah tiga. [7]
- Sebagian ulama mensyaratkan tujuh basuhan dalam membersihkan najis. Ini adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah [8]. Pendapat ini berdalil dengan hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma:
اِغْسِلُوْا اْلأَنْجَاسَ سَبْعًا
“Cucilah najis sebanyak tujuh kali”
Akan tetapi hadis tersebut tidak memiliki sanad yang Shahih, bahkan sekadar disebutkan dalam kitab-kitab fikih tanpa penyebutan sanadnya. Maka dalam membersihkan najis tidak disyaratkan jumlah tertentu dalam membasuhnya, kecuali najis jilatan anjing yang harus dibasuh sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah. Dikecualikan pula dalam istIjmar untuk membersihkan najis yang keluar dari dua jalan, yang harus diusap sebanyak tiga kali. Adapun selainnya maka tidak ada ketentuan jumlah tertentu dalam membasuhnya, karena hukum asal syarat sah suatu ibadah adalah Tawaqquf (membutuhkan adanya dalil), dan jika tidak ada dalil secara khusus maka asalnya dalam menbersihkan najis adalah dengan disiram dengan air sampai benda najisnya itu hilang. Dan tidak terikat dengan jumlah tertentu dalam membasuhnya. [9]
- Sebagian ulama mempersyaratkan ucapan tahmid, wasiat bertaqwa, shalawat kepada Nabi ﷺ, dan membaca ayat Alquran untuk keabsahan khutbah Jumat. Ini adalah penetapan syarat sah suatu ibadah, di mana hukum asal dalam hal ini adalah Tawaqquf. Dan jika kita perhatikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ini, ternyata dalil-dalil tersebut tidaklah menunjukkan makna wajib, hanya menunjukkan kepada perkara yang sunnah. Maka penetapan syarat sah tersebut merupakan suatu hal yang kurang tepat. [10]
- Sebagian Fuqaha mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sah salat bagi orang yang ingin mengerjakan Sujud Tilawah dan sujud syukur. Karena mereka berpendapat bahwa Sujud Tilawah dan sujud syukur sama dengan salat. Maka kita katakan bahwa hal itu merupakan penetapan syarat terhadap suatu ibadah, sehingga membutuhkan dalil yang menunjukkan hal itu. Apabila kita perhatikan dalil-dalil yang disebutkan dalam masalah ini, ternyata tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk menetapkan syarat tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana ia berkata:
كَانَ النَّبِيُّ nيَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ
“Dahulu Nabi ﷺ pernah membacakan kepada kami satu Surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, maka beliau sujud dan kami pun ikut sujud, sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya.” [11]
Dalam hadis tersebut Nabi ﷺ tidak memerintahkan para sahabat untuk berwudhu terlebih dahulu, sedangkan dalam kaidah dikatakan bahwa tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pensyaratan yang disebutkan sebagian Fuqaha tersebut tidaklah tepat.
Demikian pula Sujud Syukur. Tidak ada dalil yang menjelaskan wajibnya berwudhu, menutup aurat, atau pun menghadap Kiblat untuk melaksanakan Sujud Syukur. Maka penetapan syarat tersebut untuk Sujud Syukur adalah pensyaratan yang tidak didasari oleh dalil, sedangkan hukum asal syarat tersebut adalah tidak ada. Oleh karena itu lah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa tidak disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sah salat untuk keabsahan Sujud Tilawah dan Sujud Syukur. Karena sujud tersebut bukanlah salat. Namun tidak diragukan lagi, bahwa seorang yang melakukan Sujud Tilawah dan Sujud Syukur dengan memenuhi syarat-syarat salat adalah lebih utama dikarenakan dua alasan, yaitu dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, dan karena hal itu lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah. [12]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1423 H/202 M, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Hlm. 1064.
[2]. HR. al-Bukhari, dalam Kitab as-Shulh, no. 2697 dan Muslim dalam Kitab al-Aqdhiyah, no. 1718.
[3]. Jami’ul ‘Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadisan min Jawami’ al-Kalim, Imam Zainuddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Syihabuddin, Cet. I, Tahun 1429 H/2008 M, Dar Ibn Katsir, Beirut, Hlm. 156.
[4]. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan jumlah minimal jamaah yang disyaratkan hadir untuk keabsahan Salat Jumat. Di antara mereka ada yang berpendapat seorang saja bersama imam. Ini pendapat Imam at-Thabari rahimahullah. Ada pula yang berpendapat dua orang selain imam. Ada juga yang berpendapat tiga orang selain imam, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Di antara mereka ada yang mensyaratkan kehadiran minimal 40 orang. Ini pendapat Imam as-Syafi’i rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah. Ada pula yang mensyaratkan jumlah minimal 30 orang. Ada pula yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu, tetapi harus lebih dari empat orang. Ini adalah pendapat Imam Malik (Lihat Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Tanpa Tahun, Dar al-Fikr, I/115)
[5]. HR. al-Baihaqi dalam al- Kubra 3/ 177. Hadis ini dha’if sebagaimana didha’ifkan oleh Syaikh al Albani dalam Irwa’ul Ghalil no. 603.
[6]. Dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang berpegang dengan pendapat ini di antaranya adalah HR. Muslim no. 863dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
[7]. Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa jumlah minimal jamaah yang hadir agar Salat Jumat itu sah adalah tiga orang. Ini juga pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga madzhab Hanafi. (Lihat Mudzakkirah al-Fiqh, Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, I/230).
[8]. Lihat perselisihan ulama dalam masalah ini dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, I/62
[9]. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, yaitu tidak disyaratkan jumlah basuhan tertentu dalam membersihkan najis mutawasshithah, dan yang dijadikan ukuran adalah hilangnya benda najis tersebut. (Lihat Mudzakkiratul Fiqh, I/95).
[10]. Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin menjelaskan bahwa bacaan tahmid, wasiat bertakwa, membaca ayat Alquran, dan shalawat kepada Nabi bukanlah syarat sah Salat Jumat. Yang disyaratkan hanyalah khutbah itu berisi mau’izhah (nasehat). (Lihat Mudzakkiratul Fiqh, I/233).
[11]. HR. al-Bukhari, dalam Kitab Sujudil Qur’an, no. 1075. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’us Shalah, no. 575.
[12]. Diangkat dari Talqihul Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-30.
Kaidah Ke-50: Hukum Asal Muamalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya
Kaidah Kelima Puluh
اْلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ
Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)
Muqadimah
Pada edisi yang lalu telah dibahas bahwa hukum asal menetapkan syarat sah dalam ibadah adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Pada edisi kali ini akan diulas tentang hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah, yaitu perkara-perkara yang tidak termasuk ibadah. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.
Para Fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.
Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui pula bahwa dalam muamalah, terutama jual beli, ada istilah syurut shihhatil bai’ (syarat sah jual beli) dan syurut fil bai’ (syarat jual beli). Yang dimaksud syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli itu sah. Adapun syarat jual beli adalah syarat yang ditentukan oleh salah satu pelaku atau keduanya dan tidak berkaitan dengan keabsahan jual beli, seperti syarat pengantaran barang ke rumah si pembeli, atau persyaratan pembayaran secara cicilan, atau syarat lainnya.
Perbedaan antara syarat sah jual beli dengan persyaratan dalam jual beli dapat kita ketahui dari rincian berikut ini:
- Syarat sah jual beli disyaratkan pada semua jual beli, adapun syarat jual beli terkadang ada dan terkadang tidak.
- Jual beli tidak akan sah kecuali jika syarat sah terpenuhi, tapi jika yang tidak ada syarat jual beli maka akadnya tetap sah.
- Syarat sah itu tertentu, tidak berubah, dan berlaku dalam semua jual beli, adapun persyaratan dalam jual beli tidak tertentu dan bisa berbeda antara satu akad dengan akad yang lainnya.
- Syarat sah harus terpenuhi meskipun tidak disebutkan oleh kedua belah pihak. Adapun persyaratan dalam jual beli itu asalnya tidak ada kecuali jika dikehendaki dan disebutkan oleh salah satu pelaku akad dan disetujui oleh yang lainnya.
- Hukum asal syarat sah jual beli adalah tauqifi, artinya perlu dalil. Seseorang tidak boleh menetapkan sesuatu sebagai syarat sah kecuali jika ada dalil Shahih yang menunjukkannya. Adapun persyaratan dalam jual beli maka hukum asalnya halal dan diperbolehkan. Artinya, seseorang tidak boleh melarang suatu persyaratan yang dikehendakai pelaku akad muamalah tanpa ada dalil yang melarangnya. [1]
Persyaratan yang menjadi pembahasan kita dalam kaidah ini adalah syurut fil muamalah (persyaratan dalam muamalah), bukan syarat sah muamalah.
Makna Kaidah
Sebagaimana telah diisyaratkan dalam uraian di atas, bahwa kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam muamalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut.
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah sabda Nabi ﷺ:
وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
“Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” [2]
Dan hadis ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
“Sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (para wanita).” [3]
Demikian pula sabda Nabi ﷺ:
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ
“Mengapa ada beberapa kaum yang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah. Barang siapa menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah maka tidak ada hak baginya untuk melaksanakannya meskipun sejumlah seratus syarat.” [4]
Dalam hadis tersebut Nabi ﷺ tidak mengingkari persyaratan mereka, namun yang beliau ﷺ ingkari adalah syarat itu menyelisihi Kitabullah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal menentukan syarat tertentu dalam muamalah adalah diperbolehkan kecuali jika menyelisihi Kitabullah. [5]
Contoh Penerapan Kaidah
Berikut ini adalah contoh kasus yang masuk dalam implementasi kaidah ini:
- Jika seseorang membeli setumpuk kayu dengan syarat kayu tersebut diantar ke rumahnya atau digergaji di tempat tertentu maka jual beli dan persyaratan tersebut sah karena hukum asal persyaratan itu adalah boleh.
- Jika penjual mengatakan: “Aku jual barang ini jika si Fulan rela.” Atau ia mengatakan: “Aku jual barang ini jika si Fulan datang.”
Menurut Madzhab Hambali, jual beli dengan persyaratan seperti ini tidak sah disebabkan tidak adanya perpindahan kepemilikan. Karena ada kemungkinan si Fulan rela atau tidak rela, dan ada kemungkinan si Fulan datang dan mungkin juga tidak. Sedangkan hukum asal dalam jual beli adalah berpindahnya barang dagangan dari si penjual kepada si pembeli setelah sempurnanya akad. Maka persyaratan tersebut menyebabkan akad itu tidak sah.
Namun pendapat yang kuat adalah akad dan persyaratan tersebut sah. Karena hukum asal persyaratan dalam jual beli adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak ada dalil yang melarang persyaratan ini. Maka, jika si pembeli setuju dengan syarat tersebut maka ia boleh meneruskan akad jual beli. Namun jika ia tidak setuju maka tidak ada kewajiban baginya untuk meneruskan akad itu.
Jika ada yang mengatakan: “Bukankah akad tersebut masih menggantung dan kepemilikannya belum berpindah?” Kita jawab bahwa justru itulah tujuan penetapan syarat tersebut. Artinya, si penjual tidak mau kepemilikan barang itu berubah kecuali jika si Fulan rela dengan jual beli itu atau jika si Fulan datang.
- Persyaratan Inah [6] dalam jual beli. Apabila seseorang mengatakan: “Saya jual barang ini kepadamu dengan harga 1.000 Dirham dengan cara kredit, dengan syarat engkau menjualnya kembali kepadaku dengan harga 800 Dirham secara tunai.” Persyaratan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun persyaratan dalam jual beli hukum asalnya boleh, namun khusus untuk persyaratan seperti ini dilarang karena ada dalil yang melarang, seperti sabda Nabi ﷺ:
إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ, سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ
“Apabila kalian berjual beli dengan sistem Inah (salah satu bentuk riba), dan memegang ekor-ekor sapi, dan rida dengan pertanian (terlena dengan kehidupan dunia) dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kalian. Dia (Allah) tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sehingga kalian kembali ke agama kalian.” [7]
- Seseorang menjual rumahnya dengan syarat dia masih diijinkan menempatinya dalam waktu tertentu. Persyaratan seperti ini diperbolehkan. Demikian pula jika seseorang menjual hewan peliharaannya dengan syarat masih diijinkan memanfaatkannya selama waktu tertentu. [8]
- Apabila seseorang menjual budaknya dengan syarat si pembeli membebaskan budak itu setelah dibeli, maka hal itu diperbolehkan. Ini pendapat yang masyhur dalam Madzhab Hambali. Karena hukum asal menetapkan syarat dalam jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara khusus melarang penetapan syarat tersebut. Dalam hal ini, apabila dikemudian hari, si pembeli menolak untuk membebaskan budak itu, maka hakim berhak memaksanya untuk membebaskan budak itu.
- Apabila seseorang menjual suatu barang dengan syarat seandainya di kemudian hari si pembeli akan menjual kembali barang itu maka si penjual pertama yang paling berhak untuk membelinya. Dalam kasus seperti ini sebagian ulama mengharamkan persyarataan tersebut. Karena si pembeli tidak memiliki kebebasan untuk menjual barangnya kepada yang ia kehendaki, yang hal itu bertentangan dengan hakikat kepemilikan atas barang.
Namun menurut pendapat yang kuat, jual beli tersebut sah, demikian pula persyaratannya. Karena hukum asal persyaratan dalam jual beli adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan larangan terhadap syarat tersebut. Jadi, jika si pembeli rida dengan syarat tersebut maka ia bisa meneruskan akad itu, namun jika tidak, maka dia tidak wajib untuk melanjutkannya.
Dalam hal ini, jika di kemudian hari si pembeli menjual barang itu namun tidak mau menjualnya kepada si penjual pertama, maka hakim berhak memaksanya untuk menjualnya kepada pembeli pertama itu. Karena sejak semula ia telah bersedia dengan persyaratan tersebut dan telah menyetujuinya. Ini juga adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. [9]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1]. Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa di antara perbedaan antara syarat sah jual beli dengan persyaratan dalam jual beli adalah bahwa syarat sah ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditentukan oleh para pelaku akad. ( Lihat Mudzakkirah al-Fiqh, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, II/185).
[2]. HR. Abu Dawud no. 3594 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil no. 1303.
[3]. HR. al-Bukhari dalam Kitab as-Syuruth, no. 2721. Muslim dalam Kitab an-Nikah, no. 1418 dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu anhu.
[4]. HR. al-Bukhari dalam Kitab al-Buyu’, no.2155. Muslim dalam Kitab al-‘Ithqi, no.1504 dari Aisyah radhiyallahu anha.
[5]. Lihat penjelasan hadis di atas dalam al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, al-Imam Muhyiddin an-Nawawi, Cet. XIV, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ma’rifah, Beirut, IX/379-381.
[6]. Yang dimaksud Inah adalam jual beli adalah apabila seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. (Lihat Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, Nukhbah min al-‘Ulama, 1424 H, Majma’ al-Malik Fahd li Taba’at al-Mus-haf as-Syarif, al-Madinah al-Munawwarah, hlm. 217).
[7]. HR. Abu Dawud no. 3462 dari Abdullah bin ‘Umar c. Hadis ini diShahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani t dalam Silsilah al-Ahadis as-Shahihah no. 11.
[8]. Sebagimana disebutkan dalam HR. al-Bukhari dalam Kitab as-Syuruth, no. 2718. Muslim dalam Kitab al-Musaqat, no. 1599 dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu anhu.
[9]. Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-30.
Kaidah Ke-51: Barang siapa Bersungguh-Sungguh, Dianggap Mengerjakan Amalan Secara Sempurna
Kaidah Kelima Puluh Satu
مَنِ اجْتَهَدَ وَبَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَكُتِبَ لَهُ تَمَامَ سَعْيِهِ
Barang siapa bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya, maka tidak wajib mengganti dan dianggap mengerjakan amalan secara sempurna
Muqadimah
Agama Islam merupakan agama yang toleran dan mudah. Di dalamnya tidak ada kesulitan ataupun kesempitan. Semua yang diperinthakna Allah ﷻ sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada yang keluar dari kemampuan kita.
Namun terkadang dalam kondisi tertentu, seseorang tidak mampu melaksanakan perintah Allah ﷻ secara sempurna. Apabila ia tidak mampu melaksanakan perkara yang diperintahkan secara sempurna, maka yang wajib baginya ialah bersungguh-sungguh melaksanakannya dan mengerjakannya sesuai kemampuannya. Amalan yang ia kerjakan dalam keadaan seperti ini merupakan amalan yang sah.
Ketika seseorang telah mengerjakan perintah sesuai kadar kemampuannya, maka ia telah lepas dari beban perintah tersebut, meskipun ia tidak mengerjakannya secara sempurna. Tidak ada dosa baginya, dan tidak ada kewajiban mengulangi. Karena ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya secara syari. Bahkan termasuk kesempurnaan karunia Allah ﷻ, bahwa seorang Mukallaf, jika telah melaksanakan perintah sesuai kadar kemampuannya, kemudian ada kekurangan dalam pelaksanaannya disebabkan ketidakmampuan, maka kekurangan itu tidak dianggap, dan ditulis pahala baginya semisal pahala orang yang mengerjakannya secara sempurna.
Makna Kaidah
Sebagaimana telah diisyaratkan dalam uraian di atas, kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah bersungguh-sungguh mengerahkan upayanya untuk melaksanakan suatu amalan, dan ia melaksanakan amalan itu sesuai kadar kemampuannya, maka ia telah terlepas dari lingkup tuntutan pelaksanaan amalan tersebut. Sehingga tidak ada kewajiban mengganti atau mengulanginya lagi, dan tidak ada dosa atasnya ketika meninggalkan bagian amalan yang ia tidak mampu mengerjakannya, bahkan ia dianggap melaksanakan amalan tersebut secara sempurna.
Dalil yang Mendasarinya
Kaidah ini masuk dalam keumuman ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemudahan dalam agama ini, dan masuk pula dalam keumuman kaidah al masyaqqah tajlibu taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan).
Di antara dalil yang menjelaskannya ialah firman Allah ﷻ:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” [QS. al-Baqarah/2:286].
Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: “Maksud ayat ini adalah Allah ﷻ tidak membebani seorang pun diluar kemampuannya. Ini merupakan bentuk kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan Allah ﷻ kepada hamba-Nya.” [1]
Firman Allah ﷻ:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” [QS. al-Baqarah/2:185].
Demikian pula Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu:
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Apa-apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian.” [2]
Dalam hadis ‘Imran bin Hushain:
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
Dari ‘Imran bin Hushain radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku pernah terkena penyakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ bagaimana aku melaksanakan salat, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring.” [3]
Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Umat telah bersepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam salat fardhu, maka boleh baginya salat dengan duduk. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi salat itu, dan tidak pula berkurang pahalanya, berdasarkan khabar (dari Nabi)” [4]
Contoh Penerapan Kaidah
Banyak kasus yang masuk dalam penerapan kaidah yang mulia ini. Berikut ini beberapa contohnya:
Seseorang tidak tahu dengan jelas mana baju yang suci dan mana yang terkena najis. Ia tidak bisa membedakannya, dan tidak ada lagi pakaian yang lain, maka yang wajib baginya adalah berusaha keras untuk mengetahui mana yang suci dan mana yang terkena najis. Jika ia telah bersungguh-sungguh mencari tahu, sehingga ada dugaan kuat bahwa yang suci adalah yang ini (misalnya), maka ia boleh salat dengan baju yang dipilihnya itu. Jika, diketahui setelah itu bahwa ia salat dengan baju yang terkena najis maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi salat, karena ia telah berusaha keras dan berusaha bertakwa kepada Allah ﷻ sesuai kemampuannya. [5]
Seseorang yang tidak mampu rukuk dan sujud secara sempurna ketika salat, maka yang wajib baginya ialah mengerjakan rukuk dan sujud sesuai kemampuannya. Sehingga ketika rukuk hendaklah ia menundukkan punggungnya dalam keadaan berdiri sekadar kemampuannya. Demikian pula ketika sujud ia pun menundukkan punggungnya sesuai kemampuannya dalam keadaan duduk. Ia tidak dibebani melebihi kemampuannya, tidak pula ada kewajiban mengganti amalan tersebut, dan amalannya tersebut tidak berkurang nilainya [6]
Tentang orang yang menerima amanah untuk membawa barang orang lain, seperti orang yang mendapat titipan barang (al-wadi’), orang yang menemukan barang temuan (al-multaqith), orang yang meminjam (al-musta’ir), dan semisalnya. Apabila terjadi kerusakan pada barang yang diamanahkan itu, maka dalam hal ini tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, si pembawa barang telah bersungguh-sungguh menjaga barang tersebut, akan tetapi karena takdir Allah barang itu rusak, bukan karena keteledorannya. Dalam kasus ini ia tidak wajib mengganti barang tersebut. Karena ia telah mengerahkan segenap upaya dan kemampuannya. Kedua, barang itu rusak karena keteledorannya dan kurang bersungguh-sungguh dalam menjaganya. Dalam kasus ini ia wajib mengganti atau memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut, disebabkan kelalaiannya dalam mengerjakan kewajibannya. [7]
Seseorang mujtahid yang berIjtihad [8] dalam suatu permasalahan agama, dan mencurahkan kemampuannya untuk mengetahui status hukum permasalahan itu, kemudian ia beramal dengan hasil Ijtihadnya itu. Apabila hasil Ijtihadnya itu benar maka ia mendapat dua pahala, yaitu pahala Ijtihadnya dan pahala keselarasannya dengan kebenaran. Adapun jika hasil Ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala, yaitu pahala Ijtihad. [9] Dan amalan ibadah yang ia kerjakan berdasarkan hasil Ijtihadnya itu tidak batal, meskipun hasil Ijtihadnya itu tidak sesuai dengan kebenaran.
Apabila telah datang waktu salat, sedangkan seseorang berada di suatu tempat yang ia tidak mengetahui arah Kiblat. Maka yang wajib baginya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui arah Kiblat, baik dengan bertanya, atau melihat tanda-tanda yang menunjukkan arah Kiblat, atau dengan cara-cara lainnya. Setelah berupaya dan ada dugaan kuat akan arah Kiblat, maka diperbolehkan baginya melaksanakan salat menghadap ke arah tersebut. Apabila telah selesai mengerjakan salat kemudian nampak bahwa arah yang ia pilih itu ternyata bukan arah Kiblat yang benar, maka dalam kasus ini salatnya sah, dan tidak wajib baginya untuk mengulanginya. [10] Karena dalam keadaan tersebut ia telah mengerahkan kemampuan dan upayanya. Sedangkan seseorang yang telah bersungguh-sungguh mengerahkan upaya dan kemampuanya maka tidak ada kewajiban mengganti. Dan ia dianggap mengerjakan salat seperti orang yang mengerjakannya dengan menghadap Kiblat. [11]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Tafsir Alquran al-‘Azhim, Imam ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, Cet. ke-5, Tahun 1421 H/2001 M, Jum’iyah Ihyaa’ at-Turats al-Islamiy, Kuwait, I/473.
[2] HR Muslim dalam Kitab al-Fadha-il, no. 1337.
[3] HR al-Bukhari dalam Kitab ash-Shalah, no. 1117.
[4] Lihat Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Cet. ke-5, 1423 H/2003 M, Maktabah al-Asadiy, Makkah al-Mukarramah, II/555.
[5] Lihat pembahasan tentang masalah ini dalam asy-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil-Jauzi, Damam, I/ 65-66.
[6] Syaikh Abdul-‘Aziz bin Baz menjelaskan bahwa orang sakit yang tidak mampu rukuk dan sujud ketika salat maka ia berisyarat dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuknya. Dan jika ia mampu rukuk namun tidak mampu sujud maka ia mengerjakan rukuk dan berisyarat untuk sujud. Jika ia tidak mampu menunduk dengan punggungnya, maka ia menunduk dengan lehernya. Apabila punggungnya bengkok seolah-olah ia dalam keadaan rukuk maka ketika rukuk ia sedikit menundukkan punggungnya, dan ketika sujud ia lebih mendekatkan wajahnya ke lantai daripada ketika rukuk sesuai kemampuannya. Orang yang tidak mampu berisyarat dengan kepalanya maka cukup baginya niat dan ucapan. (Lihat Kaifiyah Shalah an-Nabi wa Ahkam Shalah al-Maridh wa Thaharatihi, Syaikh Abdul-‘Aziz bin Abdullah bin Baz, Cet. I, 1419 H, Madar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, hlm. 25.
[7] Lihat pembahasan berkaitan dengan masalah ini dalam at-Ta’liq ‘ala al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cet. I, 1430 H, Muassasah Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin al-Khairiyyah, Unaizah, hlm.121-123. Madar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, hlm. 25.
[8] Yang dimaksud dengan Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk mengetahui hukum syari. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang dikatakan mempunyai kapasitas berijtihad, di antaranya mengetahui dalil-dalil syari dalam permasalahan terkait, mengetahui keabsahan dan kelemahan hadis, mengetahui nasikh dan mansukh, memahami bahasa Arab dan Ushul Fiqh berkaitan dengan dalalatul-alfazh, dan selainnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh. Lihat al-Ushul min ‘Ilm al-Ushul, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, 1424 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, hlm. 85-86.
[9] Sebagaimana disebutkan dalam HR al-Bukhari dalam Kitab al-I’tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah, no. 7352 dari ‘Amr bin al-‘Ash.
[10] Lihat pula penjelasan Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz tentang masalah ini dalam Tuhfah al-Ikhwan bi Ajwibah al-Muhimmah Tata’allaqu bi Arkan al-Iman, 1421 H, Ri-asah Idarah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta`, Riyadh, hlm. 62.
[11] Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-61.
Kaidah Ke-52: Tidak Ada Taklif Kecuali Dengan Ilmu Dan Tidak Ada Hukuman Kecuali Setelah Datang Peringatan
Kaidah Kelima Puluh Dua
لاَ تَكْلِيْفَ إِلاَّ بِعِلْمٍ وَلاَ عِقَابَ إِلاَّ بَعْدَ إِنْذَارٍ
Tidak ada Taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan
Muqadimah
Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya supaya manusia mengenal-Nya. Demikian pula untuk menjelaskan mana ibadah yang disyariatkan dan mana yang tidak. Karena manusia tidak akan mungkin mengetahui perkara ibadah secara rinci kecuali dengan mengenal apa yang datang di dalam kitab suci dan yang dijelaskan oleh para rasul-Nya. Tanpa adanya risalah, maka manusia akan berada dalam kesesatan yang nyata.
Allah ﷻ dengan limpahan karunia dan rahmat-Nya telah menjelaskan hujjah kepada kita dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya. Termasuk rahmat-Nya dan bentuk konsekuensi keadilan-Nya adalah Dia tidak mengazab seorang pun kecuali setelah tegak hujjah atasnya.
Oleh karena itulah para ulama ahli Ushul Fiqih menetapkan syarat dalam Taklif (pembebanan) kepada seseorang yaitu orang tersebut sudah mengetahui al-Mukallaf bihi (perkara yang dibebankan) kepadanya. Barang siapa belum mengetahui perkara yang dibebankan kepadanya maka ia tidak termasuk orang yang kena beban tersebut. Dengan demikian, dia tidak terancam hukuman, karena suatu hukuman tidak diberlakukan kecuali setelah hujjah itu tegak.
Makna Kaidah
Sebagaimana telah diisyaratkan dalam penjelasan di atas bahwa kaidah ini membahas tentang persyaratan orang yang terkena beban. Yaitu dia harus tahu tentang perkara yang dibebankan kepadanya. Jika dia belum tahu maka ia belum terhitung sebagai Mukallaf (orang yang terkena beban, baik berupa perintah maupun larangan). Demikian halnya suatu sanksi (hukuman). Suatu sanksi tidak diberlakukan atas suatu pelanggaran kecuali setelah ada peringatan yang cukup terhadap perkara yang dilarang.
Kaidah ini telah disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin dalam Manzhumah Ushulil- Fiqh wa Qawa’idihi bait ke-16:
وَالـشَّـرْعُ لاَ يَـلْـزَمُ قَـبْـلَ الْـعِلْـمِ
دَلِـيْلُـهُ فِـعْـلُ الْمُـسِيْءِ فَـافْـتَهِـمِ
Dan syariat tidaklah wajib sebelum adanya ilmu
Dalilnya adalah hadis orang yang salah salatnya maka fahamilah ! [1]
Dalil yang Mendasarinya
Banyak dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. [QS. an-Nisa`/4:165].
Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah mengatakan: “Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa jikalau Allah ﷻ tidak mengutus para rasul-Nya, tentulah ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah ﷻ, dengan mengatakan: “Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami belum mengetahui, karena para rasul belum diutus kepada kami.” [2]
Dan juga firman-Nya:
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. “[QS. al-Isra`/17:15].
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini mengatakan: “Allah ﷻ adalah Zat yang Maha Adil. Dia ﷻ tidak mengazab seorang pun sampai tegak hujjah atasnya dengan risalah, namun ia menolaknya. Adapun orang yang berpegang dengan hujjah tersebut, atau orang yang memang belum sampai hujjah Allah ﷻ kepadanya, maka sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan mengazabnya”. [3]
Adapun dalil dari as-Sunnah di antaranya adalah hadis al-musi’ fi salatihi (orang yang salah dalam salatnya) riwayat Imam Bukhari dan Muslim:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا
Dari Abu Hurairah Radhiyalahu anhu, “Suatu ketika Nabi ﷺ masuk ke masjid, lalu ada seorang laki-laki juga masuk ke masjid dan melaksanakan salat. Kemudian orang itu datang seraya memberi salam kepada Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ menjawab salamnya dan bersabda: “Kembali dan ulangilah salatmu, karena engkau belum salat!” Orang itu kemudian mengulangi salat, lalu menghadap kembali kepada Nabi ﷺ dan memberi salam, namun beliau bersabda lagi, “Kembali dan ulangilah salatmu karena engkau belum salat!” Beliau memerintahkan orang itu sampai tiga kali, sehingga ia berkata: “Demi Zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarilah saya,” maka beliau pun bersabda: “Jika engkau melaksanakan salat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Alquran. Kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam rukuk. Lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga engkau tenang dalam keadaan berdiri. Setelah itu sujudlah sampai engkau tenang dalam sujud. Lalu angkatlah (kepalamu) untuk duduk hingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Setelah itu sujudlah sampai engkau tenang dalam sujud. Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh (rakaat) salatmu”. [4]
Syaikh Khalid bin’Ali al-Musyaiqih mengatakan: “Sisi pendalilan dari hadis ini adalah orang Arab pedalaman tersebut tidak tuma`ninah dalam salatnya. Bersama dengan itu, Nabi ﷺ tidak memerintahkannya mengulangi salat-salat yang telah lampau. Beliau hanya memerintahkannya mengulangi salat yang ia kerjakan ketika itu. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang jahil (belum mengetahui ilmu) diberi uzur atas kejahilannya, dan bahwa syariat tidaklah wajib sebelum seseorang mengetahui ilmunya.” [5]
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh kasus yang masuk dalam implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Apabila ada seorang wanita telah baligh ketika usianya masih relatif muda (misalnya kurang dari lima belas tahun), namun ia tetap tidak melaksanakan puasa karena menyangka bahwa puasa tidak wajib kecuali jika telah genap lima belas tahun, sementara ia tinggal di tempat yang jauh dari ahli ilmu. Dalam kasus seperti ini ia diberi uzur karena ketidaktahuannya itu, dan tidak wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan.
Apabila ada seseorang Muslim yang hidup di tengah masyarakat yang biasa berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dan tidak ada seorang pun yang menjelaskan bahwa perbuatan itu syirik. Dia berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu adalah wasilah (perantara) yang mendekatkannya kepada Alla Dalam kasus seperti ini ia tidak dihukumi kafir, dan diberi uzur karena ketidaktahuannya tersebut.
Apabila ada seseorang dalam keadaan janabah. Ketika hendak melaksanakan salat, ia langsung berwudhu dan melaksanakan salat tanpa mandi terlebih dahulu, karena ia tidak tahu kalau kondisi janabah menyebabkan ia wajib mandi. Ia tidak tahu sama sekali tentang hukumnya. Dalam kondisi tersebut, maka ia diberikan uzur, dan tidak ada kewajiban mengulangi salat.
Apabila seorang laki-laki telah berusia tiga belas tahun dan ia telah Ihtilam, [6] namun ia tetap tidak melaksanakan salat dan tidak pula puasa, karena dia menganggap bahwa seseorang laki-laki belum dihukumi baligh kecuali setelah genap berusia lima belas tahun. Jika ia memang benar-benar belum tahu hukum permasalahan ini, maka ia diberi uzur dan tidak wajib baginya untuik mengqadha` salat maupun puasa yang ia tinggalkan.
Keterangan Tambahan:
Berkaitan dengan pembahasan kaidah ini, perlu dipahami bahwa tidak setiap kejahilan atau ketidaktahuan menyebabkan sesorang mendapatkan uzur dalam meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Para ulama menjelaskan, bahwa kejahilan yang dimaksud adalah kejahilan seseorang yang tidak mendapatkan wasilah untuk menghilangkan kejahilannya itu. [7]
Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih menyebutkan beberapa keadaan, dimana seseorang diberi uzur karena ketidaktahuannya, di antaranya ialah:
Seseorang yang baru saja masuk agama Islam. Orang seperti ini mendapatkan uzur karena ketidaktahuannya. Jika ia baru masuk Islam kemudian ia minum khamr, atau judi, atau semisalnya maka ia diberi uzur dikarenakan belum mengetahui hukumnya.
Apabila seseorang tinggal di pedalaman, jauh dari perkotaan (komunitas) kaum Muslimin, ia tidak berkesempatan mendengar penjelasan ahli ilmu. Orang seperti ini diberi uzur. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis al–musi’ fi salatihi yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu orang a’rabi dalam hadis tersebut tinggal di pedalaman maka diberi uzur oleh Nabi ﷺ.
Seseorang yang tumbuh di negara kafir. Para ulama mengatakan bahwa orang seperti ini mendapatkan uzur dengan kejahilannya sebagaimana orang yang tinggal di daerah pedalaman.
Dalam permasalahan-permasalahan rumit dan sangat rinci yang tidak diketahui selain oleh ahli ilmu, maka orang awam diberi uzur dalam masalah tersebut.
Dalam perkara tertentu yang tidak terlintas dalam benak seseorang bahwa itu adalah perkara yang dilarang. Namun jika sebenarnya terlintas dalam benaknya kecurigaan bahwa hal itu dilarang, sementara ia mampu untuk belajar atau bertanya kepada orang yang berilmu, namun ia tidak melakukan hal-hal tersebut di atas, maka dalam kasus ini ia tidak mendapatkan uzur. [8]
Wallahu a’lam. [9]
_______
Footnote
[1] Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 53.
[2] Idem.
[3] Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, Syaikh Abdurrahmaan bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1423 H/202 M, Muassasah ar-Risalah, Beirut, hlm. 455.
[4] HR al-Bukhari dalam Kitab al-Azan, Bab: Wujub al-Qira’ah li al-Imam wa al-Ma’mum fi ash-Shalawat Kulliha fi al-Hadhari wa as-Safari wa Ma Yujharu fiha wa Ma Yukhafat, no. 757. Muslim dalam Kitab ash-Shalah, Bab: Wujub Qira’ah al-Fatihah fi Kulli Rak’atin wa Innahu Idza lam Yuhsin al-Fatihah wala Amkanahu Ta’allumuha Qara-a Ma Tayassara lahu min Ghairiha, no. 397.
[5] Al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-16.
[6] Yang dimaksud Ihtilam adalah apabila seseorang mengeluarkan air mani ketika tidur. Ini termasuk salah satu tanda baligh seseorang. (Lihat Mu’jam Lughah al-Fuqaha, Prof. Dr. Muhammad Rawas Qal’ah Jiy dan Dr. Hamid Shadiq Qunaibi, Cetakan II, Tahun 1408 H/1988 M, Dar an-Nafais, Beirut, pada kata (الاحتلام).
[7] Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’I dan dalam Syarah Manzhumah fi Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi li Ibni ‘Utsaimin, pelajaran pertama, dalam website beliau http://alsaeedan.net.
[8] Al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-17.
[9] Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-31.
Kaidah Ke-53: Hukum Suatu Perkara Dikaitkan Dengan Sebab Yang Sudah Diketahui
Kaidah Kelima Puluh Tiga
الْحُكْمُ الْحَادِثُ يُضَافُ إِلَى السَّبَبِ الْمَعْلُوْمِ لاَ إِلَى الْمُقَدَّرِ الْمَظْنُوْنِ
Hukum suatu perkara dikaitkan dengan sebab yang sudah diketahui bukan dengan sebab yang masih diperkirakan
Makna Kaidah
Dalam beberapa kondisi terkadang terjadi perbedaan hukum terhadap satu perkara. Perbedaan itu dipicu oleh perbedaan para ulama dalam menetapkan sebab hukum itu sendiri. Karena setiap hukum itu pasti memiliki sebab, dan terkadang satu perkara atau kejadian memiliki sebab lebih dari satu, sehingga ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat saat menetapkan hukum kejadian tersebut.
Kaidah di atas menjelaskan solusi apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan sebab dari suatu perkara, yang bisa dijadikan sandaran hukum. Faktor penyebab suatu kejadian bisa digolongkan menjadi dua. Pertama, sebab yang zahir (nyata terlihat) dan diketahui umum. Kedua, sebab yang masih dalam bentuk dugaan atau perkiraan. Jika seperti ini keadaannya, maka hukum perkara itu, kita sandarkan kepada sebab yang zahir, bukan kepada sebab yang masih dalam bentuk perkiraan. Karena, sebab yang zahir (nyata terlihat) dan diketahui umum adalah sebab yang matayaqqan ats-tsubut (pasti keberadaannya), sedangkan sebab yang masih diperkirakan itu adalah masykukun fi tsubutihi (diragukan keberadaannya). Sedangkan kaidah umum mengatakan bahwa al-yaqin la yazulu bi asy-syak (Sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa hilang hanya karena sesuatu yang masih diragukan)
Dalil Kaidah Ini
Kaidah ini masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-yaqin la yazulu bi asy-syak. Di antaranya, firman Allah ﷻ:
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.” [Yunus/10:36]
Syaikh Dr. Saleh bin Ghanim as-Sadlan berkata:“Yang dimaksud kebenaran (al-haq) dalam ayat ini ialah suatu hakikat yang benar-benar terjadinya, seperti keyakinan.” [1]
Adapun dalil dari as-Sunnah, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Riwayat Muslim rahimahullah:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا
Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya, sehingga muncul keraguan apakah sudah keluar sesuatu darinya ataukah belum, maka janganlah keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mencium baunya.” [2]
Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan: “Hadis ini adalah salah satu pokok agama Islam, dan (merupakan) salah satu kaidah penting dalam fiqih. Maksudnya, Yaitu, bahwasanya segala sesuatu itu tetap dihukumi sebagaimana asalnya sampai keberadaannya jelas menyelisihi keadaan awalnya. Dan keragu-raguan yang muncul tidak berpengaruh padanya”. [3]
Adapun dalil yang khusus berkaitan dengan kaidah ini di antaranya adalah hadis ‘Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dalam Riwayat al-Bukhari rahimahullah dan Muslim rahimahullah, Rasulullah ﷺ bersabda:
وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ
“Dan apabila engkau memanah hewan buruan kemudian setelah sehari atau dua hari engkau temukan hewan itu mati sedangkan tidak ada pada hewan itu selain bekas luka panahmu maka engkau boleh memakannya.” [4]
Dalam hadis ini dijelaskan tentang hewan buruan yang dipanah kemudian lari, setelah itu ditemukan dalam keadaan mati dan tidak didapati kecuali luka bekas panah itu, maka itu boleh dimakan. Padahal, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kematiannya. Kemungkinan pertama, disebabkan luka panah. Ini adalah sebab yang zahir (nyata terlihat) dan jika ini benar, maka hewan tersebut halal dimakan. Kemungkinan yang lain, banyak sekali, misalnya karena haus, jatuh, lapar, dan lain sebagainya, yang jika ini yang menyebab kematiannya, maka hewan itu haram dimakan. Meski demikian, Nabi ﷺ ternyata memperbolehkan untuk memakan hewan tersebut. Ini menunjukkan, beliau ﷺ mengaitkan kematian hewan tersebut dengan sebab yang zahir (nyata terlihat) dan diyakini keberadaannya. Adapun sebab-sebab yang wujud sekadar persangkaan atau perkiraan maka beliau ﷺ abaikan.
Contoh Penerapan Kaidah
Berikut beberapa di antaranya:
Apabila dalam suatu pernikahan disepakati maharnya berupa pengajaran hafalan Surat al-Baqarah dari si suami kepada istrinya. Setelah beberapa waktu, si istri menuduh suaminya belum menunaikannya. Hanya saja, faktanya si istri telah hafal Surat al-Baqarah. Penyebab hafalnya si istri ini memiliki beberapa kemungkinan. Mungkin karena diajari suami, mungkin juga karena yang lain. Dalam masalah ini, penyebab yang zahir adalah diajari suami, karena mereka tinggal serumah dan diajari suami. Sementara penyebab yang lainnya adalah sebab yang belum pasti, atau sekadar dugaan. Berdasarkan kaidah di atas, bahwa hukum suatu perkara ditetapkan berdasarkan sebab yang maklum. Maka dalam hal ini ditetapkan, si suami telah menunaikan mahar, dan tuduhan istri tertolak, kecuali jika ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa suami belum menunaikan mahar tersebut.
Apabila ada seseorang yang sedang dalam keadaan ihram melukai binatang buruan namun tidak mematikan. Beberapa waktu kemudian binatang itu ditemukan dalam keadaan mati dan tidak ada luka lain kecuali luka yang pertama. Dalam hal ini ada dua kemungkinan penyebab kematiannya. Pertama, sebab yang maklum (nampak) yaitu luka. Kedua, sebab yang masih diperkirakan, yaitu sebab-sebab lainnya, seperti jatuh, kelaparan dan semisalnya. Berdasarkan kaidah di atas, bahwa hukum suatu perkara ditetapkan berdasarkan sebab yang maklum. Maka berdasarkan ini ditetapkan kematiannya disebabkan oleh luka dari orang yang sedang ihram tersebut. Sehingga, dia berkewajiban menggantinya dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang mati itu. [5]
Jika seseorang melukai orang lain dengan luka yang tidak mematikan. Selang beberapa waktu kemudian ternyata orang itu meninggal. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan penyebab kematiannya. Mungkin disebabkan semakin parahnya luka tersebut, dan ini adalah sebab yang maklum (nampak). Dan mungkin juga disebabkan perkara lain yang diperkirakan. Sehingga berdasarkan kaidah ini, kematiannya disandarkan kepada sebab yang maklum, yaitu semakin parahnya luka tersebut. Maka dalam kasus ini, wajib diterapkam hukum Qishash jika hal itu terjadi karena ‘amdun ‘udwan (sengaja dan terencana), atau wajib Diyat jika hal itu terjadi karena khatha’ (tersalah), atau syibhu ‘amdin (menyerupai sengaja). [6] Namun, dalam kasus seperti ini perlu ada pemeriksaan dari dokter Muslim yang berkompeten yang menegaskan bahwa kematian tersebut memang disebabkan lukanya yang semakin parah.
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘anha, Dr. Saleh bin Ghanim as-Sadlan, Cet. I, Tahun 1417 H, Dar al-Balansiyah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, Riyadh, hlm. 102.
[2] HR Muslim dalam Kitab al-Haidh, Bab ad-Dalil ‘ala Anna Man Tayaqqana ath-Thaharah Tsumma Syakka fi al-Hadats Falahu an Yushalliya bi Thaharatihi Tilka, no. 803.
[3] Lihat al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj, al-Imam Muhyiddin an-Nawawiy, Cet. XV, Tahun 1429 H/ 2008 M, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 4/273.
[4] HR al-Bukhari dalam kitab adz-Dzaba-ih wa ash-Shaid, Bab as-Shaid Idza Ghaba ‘anhu Yaumain aw Tsalatsah, no. 5484. Muslim dalam kitab ash-Shaid wa adz-Dzaba-ih wa Maa Yu’kalu min al-Hayawan, Bab as-Shaid bi al-Kilab al-Mu’allamah, No. 1929.
[5] Tentang larangan membunuh binatang buruan bagi seorang muhrim (orang yang sedang dalam keadaan berihram) dan denda yang berkaitan dengannya disebutkan dalam QS al-Ma-idah/5 ayat ke-95.
[6] Tentang tiga macam pembunuhan tanpa haq dapat dilihat dalam Manhaj as-Salikin wa Taudhih al-Fiqh fi ad-Din, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1424 H/ 2003 M, Muassasah ar-Risalah, Beirut, hlm. 263.
Kaidah Ke-54: Hukum Asal Benda-Benda Adalah Suci Dan Boleh Dimanfaatkan
Kaidah Kelima Puluh Empat
اْلأَصْلُ فِي اْلأَعْيَانِ اْلإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ
Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga, hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan.
Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan semisalnya. Maka hukum asal dari semua itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikannya haram.
Oleh karena itulah Syaikul-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berkaitan dengan kaidah ini, “Ini adalah kalimat yang luas maknanya, perkataan yang umum, perkara utama yang banyak manfaatnya, serta luas barakahnya. Dijadikan rujukan oleh para pembawa syariah dalam perkara yang tidak terhitung, baik berupa amalan dan kejadian-kejadian di antara manusia.” [1]
Dalil yang Mendasarinya
Kaidah ini ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Alquran, as-Sunnah, maupun Ijma. Dalil dari Alquran, di antaranya firman Allah ﷻ:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” [QS. al-Baqarah/2:29].
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: “Dalam ayat yang agung ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah mubah dan suci. Karena ayat ini disebutkan dalam konteks pemberian karunia dari Allah ﷻ kepada para hamba-Nya.” [2]
Demikian pula firman Allah ﷻ:
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.” [QS. al-An’am/6:119].
Sisi pendalilan dari ayat ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, Allah ﷻ mencela orang-orang yang tidak mau memakan daging hewan yang disembelih atas nama Allah ﷻ sebelum hewan tersebut dinyatakan secara khusus sebagai hewan yang halal. Seandainya bukan karena hukum asal segala benda itu halal, tentu mereka tidak mendapatkan celaan itu. Kedua, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah ﷻ telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan. Ini menunjukkan, apa-apa yang tidak dijelaskan keharamannya maka itu bukan perkara yang haram. Dan apa-apa yang tidak haram, berarti itu halal. Karena tidak ada macam yang lain, kecuali benda itu halal atau haram.
Adapun dalil dari as-Sunnah di antaranya sabda Nabi ﷺ dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim:
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
Dari Sa’d bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya orang Muslim yang paling besar kesalahannya adalah orang yang mempertanyakan sesuatu yang semula tidak haram, kemudian diharamkan karena sebab pertanyaannya itu”. [3]
Hadis ini menunjukkan bahwa pengharaman itu adakalanya terjadi karena sebab pertanyaan. Artinya, sebelum munculnya pertanyaan, perkara tersebut tidaklah haram. Dan inilah hukum asalnya.
Dalil lain dari as-Sunnah adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi:
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ. فَقَالَ: الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ
Dari Salman al-Farisi, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang minyak samin, keju, dan (mengenakan) bulu binatang, maka beliau ﷺ bersabda: ‘Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah ﷻ di dalam Kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan termasuk sesuatu yang dimaafkan.” [4]
Hadis tersebut merupakan nash yang menunjukkan bahwa perkara-perkara yang didiamkan dan tidak disinggung tentang keharamannya maka itu bukanlah perkara yang menjatuhkan seseorang kepada dosa, sehingga bukan termasuk kategori perkara yang haram.
Demikian pula para ulama telah bersepakat tentang eksistensi kaidah ini, yaitu keberadaan hukum asal benda-benda adalah halal untuk dimanfaatkan, baik dimakan, diminum, atau semisalnya. Dan tidaklah haram darinya kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan: “Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu bahwa perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya maka perkara itu tidak haram secara mutlak. Banyak orang dari kalangan ahli Ushul Fiqih dan cabangnya yang menyebutkan kaidah ini. Dan saya memandang sebagian di antara mereka telah menyebutkan Ijma, baik secara yakin maupun persangkaan yang yakin”. [5]
Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah suci maka telah tercakup dalam dalil-dalil yang disebutkan di atas ditinjau dari dua sisi. Pertama, sesungguhnya dalil-dalil tersebut menunjukkan bolehnya semua bentuk pemanfaatan, baik dengan dimakan, diminum, dipakai, disentuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penetapan kesucian benda-benda itu telah tercakup di dalamnya. Kedua, telah dipahami dari dalil-dalil tersebut bahwa hukum asal benda-benda yang ada di sekitar kita itu boleh dimanfaatkan, seperti dimakan dan diminum. Maka diperbolehkannya barang-barang tersebut untuk disentuh sebagai benda yang tidak najis adalah lebih utama. Yang demikian, karena makanan itu bergabung dan bercampur dengan badan. Adapun sesuatu yang disentuh atau dipakai maka ia sekadar mengenai badan dari sisi luarnya saja. Apabila telah tetap kebolehan sesuatu dalam bentuk tergabung dan tercampur, maka kebolehan sesuatu sekadar dipakai atau disentuh adalah lebih utama. Hal itu diperkuat dengan dalil dari Ijma, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan: “Sesungguhnya para fuqaha seluruhnya bersepakat bahwa hukum asal benda-benda adalah suci, dan sesungguhnya najis itu jumlahnya tertentu dan terbatas. Sehingga semua benda di luar batasan tersebut hukumnya suci”. [6]
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara bentuk implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Hewan-hewan yang statusnya meragukan apakah halal ataukah haram seperti jerapah, gajah, dan semisalnya, maka sesungguhnya dihukumi sebagai binatang yang halal sesuai hukum asalnya.
Tanaman-tanaman yang tidak mengandung racun maka secara umum halal sesuai hukum asalnya. [7]
Beraneka-ragam makanan, minuman, buah-buahan, dan biji-bijian yang sampai kepada kita dari luar negeri, dan kita tidak mengetahui namanya, sedangkan tidak nampak kandungan zat yang berbahaya padanya maka hukumnya halal sesuai konsekuensi kaidah ini. [8]
Air, bebatuan, tanah, pakaian, dan wadah-wadah hukum asalnya suci berdasarkan kaidah ini.
Kotoran dan air kencing dari binatang yang halal dimakan hukumnya suci, karena benda-benda di sekitar kita hukum asalnya suci, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannnya, sehingga dikembalikan pada hukum asalnya. [9]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Majmu’ al-Fatawa, 21/535.
[2] Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, cet. I, Tahun 1423 H/202 M, Muassasah ar-Risalah, Beirut, hlm. 48.
[3] HR al-Bukhari dalam Kitab al-I’tisham, Bab: Ma Yukrahu min Katsrati as-Su-al wa Takallufi Ma la Ya’nihi, no. 7289. Muslim dalam Kitab al-Fadha-il, Bab: Tauqiruhu n wa Tarku Iktsari Su-alihi ‘Amma La Dharurata Ilaihi au la Yata’allaqu bihi Taklifun wa Ma la Yaqa’u wa Nahwi Dzalika, no. 2308.
[4] HR at-Tirmidzi dalam Kitab al-Libas, Bab: Ma Ja-a fi Lubsi al-Fira`, no. 1726. Ibnu Majah dalam Kitab al-Ath’imah, Bab: Aklu al-Jubni wa as-Samni, no. 3367. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi.
[5] Majmu’ al-Fatawa, 21/538.
[6] Majmu’ al-Fatawa, 21/542.
[7] Lihat al-Asybah wa an-Nazha-ir, as-Suyuthi, hlm. 60.
[8] Lihat al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, Muhammad Shidqi al-Burnu, hlm. 114.
[9] Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Miman, cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul- Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 193-198.
Kaidah Ke-55: Perintah Lebih Besar Daripada Larangan
Kaidah Kelima Puluh Lima
الْمَأْمُوْرُ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
Perintah lebih besar daripada larangan
Makna Kaidah
Kaidah ini termasuk kaidah yang besar di sisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan termasuk patokan pokok dalam metode fiqihnya. Hal ini nampak dari banyaknya Tarjih dan ikhtiyar beliau yang dikaitkan dengan kaidah ini dan kaidah-kaidah lain yang menjadi cabangnya.
Kaidah ini menjelaskan bahwa perhatian syariat terhadap perkara yang diperintahkan lebih besar dan lebih kuat daripada perhatiannya terhadap perkara yang dilarang. Sebagaimana dikatakan oleh Syaihul Islam Ibnu Taimiyah, “Sesungguhnya jenis mengerjakan perintah itu lebih besar daripada jenis meninggalkan larangan. Dan jenis meninggalkan perintah lebih besar daripada jenis mengerjakan larangan. Dan sesungguhnya pahala bani Adam karena mengerjakan kewajiban lebih besar daripada pahala yang diraihnya karena meninggalkan perkara yang haram. Dan dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan.” [1]
Karena perintah lebih besar daripada larangan, baik ditinjau dari jenisnya, pahalanya, maupun dosanya, maka ini menunjukkan bahwa perhatian syariat terhadap perkara yang diperintahkan lebih besar daripada perhatiannya terhadap perkara yang dilarang.
Ada beberapa kaidah lain yang menjadi cabang dan turunan dari kaidah ini. Semuanya semakin memperjelas dan menguatkan bahwa tingkat keutamaan dalam perintah lebih besar daripada yang ada dalam larangan. [2] Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:
Kaidah Pertama:
اْلأُمُوْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا يُعْفَى فِيْهَا عَنِ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ
Perkara-perkara yang terlarang, pelakunya dimaafkan jika dilakukan oleh orang yang lupa atau tersalah
Misalnya seseorang yang makan atau minum ketika berpuasa karena lupa maka ia dimaafkan dan puasanya tidak batal. Demikian pula seseorang yang memakai minyak wangi, atau memakai penutup kepala, atau memotong kukunya ketika dalam keadaan ihram karena lupa atau tersalah maka ia tidak berdosa dan tidak ada kewajiban membayar Fidyah, karena seseorang yang mengerjakan larangan karena lupa atau tersalah maka dimaafkan.
Ini berkaitan dengan larangan. Adapun perkara yang diperintahkan maka kewajiban pelaksanaannya tidak gugur dari orang yang lupa atau tersalah, bahkan tetap wajib untuk dikerjakan.
Kaidah Kedua:
مَا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِلذَّرِيْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ
Perkara yang dilarang dalam rangka preventif boleh dikerjakan saat ada maslahat yang lebih kuat.
Seperti haramnya seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Larangan tersebut ada karena hal itu bisa menjadi sarana yang mengantarkan kepada fitnah atau sarana perzinaan. Namun jika ada maslahat yang lebih kuat maka adakalanya hal tersebut diperbolehkan. Seperti seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita maka diperbolehkan baginya untuik melihat wajah si wanita. Atau seorang dokter yang perlu melihat anggota badan pasien wanita dalam rangka pengobatan.
Demikian pula haramnya salat di waktu-waktu larangan. Pengharaman tersebut ada karena bisa menjadi sarana yang mengantarkan pada tasyabbuh (menyerupai) ibadah orang-orang kafir yang sujud kepada matahari. Namun jika ada maslahat yang lebih kuat maka salat di waktu tersebut diperbolehkan, seperti mengqadha salat wajib yang terlewat, salat jenazah, dan salat-salat lainnya yang memiliki sebab menurut pendapat yang kuat. [3]
Dalil yang Mendasarinya
Berkaitan dengan kaidah ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk pendalilan yang sangat bagus. Beliau rahimahullah menyebutkan tidak kurang dari dua puluh dua pendalilan. Adapun yang paling kuat di antaranya adalah sebagai berikut:
Sesungguhnya perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ yang pertama kali adalah dilakukan oleh nenek moyang jin (iblis) dan nenek moyang manusia (Adam). Dalam hal ini, kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis lebih awal dan lebih besar. Kemaksiatan tersebut berupa penolakan iblis dari melaksanakan perintah Allah ﷻ berupa sujud kepada Adam. Ini termasuk kategori meninggalkan perintah. Adapun yang dilakukan oleh Adam, yaitu memakan dari pohon di Surga. Ini termasuk kategori mengerjakan larangan. Dari dua jenis tersebut, ternyata kadar dosa Adam q lebih ringan. Dari sini dapat diketahui bahwa jenis meninggalkan perintah itu lebih besar daripada jenis mengerjakan larangan.
Demikian pula, bentuk pelanggaran yang dilakukan iblis tersebut ternyata berupa dosa besar sekaligus kekufuran yang tidak diampuni. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam berupa kesalahan yang lebih ringan dan diberikan ampunan darinya. Sebagaimana firman-Nya:
فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [QS. al –Baqarah/2:37]
Lima rukun Islam merupakan amalan-amalan yang masuk kategori perkara yang diperintahkan. Apabila seseorang meninggalkannya maka banyak dari kalangan ulama yang mewajibkan hukuman bunuh bagi pelakunya. Bahkan adakalanya dihukumi sebagai seorang yang kafir, keluar dari agama Islam. [4]
Adapun mengerjakan larangan yang madharatnya tidak menyebar kepada orang lain maka para ulama tidak mewajibkan hukuman bunuh atas pelakunya, dan tidak pula dihukumi kufur asalkan perkara tersebut tidak membatalkan keimanan. Dari sini dapat diketahui, bahwa meninggalkan perintah perkaranya lebih besar daripada mengerjakan larangan.
Sesungguhnya maksud dari adanya larangan adalah supaya perkara yang dilarang itu tidak ada, yaitu tidak dikerjakan. Sedangkan al ‘adam (ketidakadaan) itu secara asal tidak ada unsur kebaikan di dalamnya. Adapun perkara yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang maujud (dituntut keberadaannya). Dan perkara yang maujud asalnya merupakan perkara yang baik, bermanfaat, dan dicari. Bahkan merupakan suatu kepastian bahwa setiap yang ada pasti ada manfaatnya. Karena setiap yang ada itu telah diciptakan oleh Allah ﷻ, dan Dia tidak menciptakan sesuatu pun kecuali dengan hikmah. Berbeda dengan sesuatu yang makdum (tidak ada) yang tidak ada sesuatu pun di dalamnya. Oleh karena itulah Allah ﷻ berfirman:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya.” [QS. as-Sajdah/32:7]
Dan Allah ﷻ berfirman:
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu.” [QS. an-Naml/27:88]
Dengan demikian dapat kita ketahui, bahwa apa yang terkandung di dalam perintah itu lebih sempurna dan lebih mulia daripada apa yang ada dalam larangan.
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Perkara-perkara yang diperintahkan tidaklah gugur karena nisyan (lupa) atau jahl (tidak tahu). Adapun perkara-perkara yang dilarang maka gugur (dimaafkan) jika seseorang lupa atau tidak tahu. [5]
Jika seseorang meninggalkan perkara yang diperintahkan maka ada kewajiban mengqadha (menggantinya), meskipun ia meninggalkannya karena uzur. Seperti seseorang yang meninggalkan puasa karena sakit atau safar, dan orang yang meninggalkan salat karena tertidur, maka wajib untuk mengqadhanya. Demikian pula orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam manasik haji maka tetap wajib mengerjakannya jika masih memungkinkan atau dengan membayar dam. Maka tidaklah gugur tuntutan dalam perintah tersebut sampai ia mengerjakannya.
Adapun orang yang mengerjakan perkara yang dilarang karena lupa, tersalah, tertidur, atau tidak tahu, maka ia dimaafkan. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar ganti rugi, kecuali jika hal itu mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain. [6]
Dipersyaratkan adanya niat untuk mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan, seperti salat, puasa, haji, dan semisalnya. [7] Adapun perkara-perkara yang dilarang maka tidak dipersyaratkan adanya niat untuk meninggalkannya, seperti menghilangkan najis, meninggalkan zina, meninggalkan pencurian, dan semisalnya. [8]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Majmu’ al-Fatawa, 20/85.
[2] Lihat pula pembahasan tentang kaidah ini dalam al-Qawa’id wa al-Fawa’id al-Ushuliyyah, Ibnu al-Lahham, hlm. 191; Fath al-Bari, Ibnu Hajar, 13/262. Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, Ibnu Rajab, hlm. 83-84. Fath al-Mubin li Syarh al-Arba’in, Ibnu Hajar al-Haitsami, hlm. 132-133. Al-Bahr al-Muhith, az-Zarkasyi, 1/274.
[3] Lihat pula pembahasan tentang kaidah cabang ini dalam Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawi’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 64-67.
[4] Di antaranya, apabila seseorang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat padahal ia mampu mengucapkannya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, “Adapun dua kalimat syahadat, apabila seseorang tidak mengucapkannya padahal ia mampu, maka ia adalah orang kafir berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.” (Majmu’ al-Fatawa, 7/609). (Lihat at-Takfir wa Dhawabithuhu, Syaikh Ibrahim bin ‘Amir ar-Ruhailiy, Dar al-Imam Ahmad, hlm. 229).
[5] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 21/477.
[6] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 20/95.
[7] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 21/477.
[8] Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Miman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 199-202.
Kaidah Ke-56: Pahala Tergantung Pada Besarnya Manfaat Bukan Kadar Kesulitan
Kaidah Kelima Puluh Enam
عَلَى قَدْرِ الْمَنْفَعَةِ لاَ الْمَشَقَّةِ
Pahala tergantung pada besarnya manfaat bukan kadar kesulitan
Makna Kaidah
Kaidah ini berkaitan dengan salah satu perinsip Taklif dalam syariat, yaitu meniadakan kesulitan dan kesempitan. Dalam kaidah dijelaskan bahwa seorang hamba ketika beramal tidak boleh sekadar bertujuan untuk menempuh kesulitan dalam amalan tersebut, akan tetapi yang menjadi tujuan hendaknya adalah mengerjakan amalan yang lebih bermanfaat baginya.
Imam As-Syathibi rahimahullah mengatakan: “Apabila maksud seorang Mukallaf sekadar mengerjakan kesulitan, maka sesungguhnya ia telah menyelisihi maksud syariat, karena syariat dalam memberikan Taklif tidaklah bertujuan memberikan kesulitan. Dan setiap tujuan yang menyelisihi tujuan syariat maka itu adalah perkara yang bathil.” [1]
Di antara hal yang perlu difahami bahwa keridaan Allah ﷻ dan kecintaa-Nya bukanlah karena siksaan dan kesulitan yang ditimpakan seseorang kepada dirinya sendiri, sehingga semakin sulit suatu amalan maka semakin utama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian kalangan. [2] Namun, keridaan Allah ﷻ dan kecintaan-Nya tergantung pada kadar ketaatan terhadap perintah dan keikhlasan seseorang dalam beramal. Oleh karena itu, besarnya pahala itu tergantung pada tingkat manfaat, maslahat, dan faidah. Apabila syariat memerintahkan kita mengerjakan perkara yang berat maka hal itu karena ada manfaat dan maslahat yang besar di dalamnya, seperti jihad. Bersamaan dengan itu, Allah ﷻ memberikan pahala atas kesulitan yang muncul darinya. Sebagaimana firman-Nya:
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
“Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan ditulislah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” [QS. at Taubah/9:120].
Maka apabila seorang insan ditimpa kesulitan ketika melaksanakan jihad, haji, amar maruf nahi munkar, atau menuntut ilmu, maka itu termasuk perkara yang dipuji dan diberi pahala.
Adapun sekadar memberikan kesusahan kepada diri sendiri, atau sekadar menempuh kesulitan sebagaimana anggapan sebagian manusia bahwa itu termasuk mujahadah, apabila tidak terdapat unsur manfaat dan ketaatan kepada Allah maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:
إِنَّ هَذَا الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ
“Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama, kecuali dirinya akan terkalahkan.” [3]
Berdasarkan kaidah ini dapat kita ketahui bahwa tidak setiap amalan yang berat itu memiliki keutamaan yang lebih besar daripada amalan yang ringan. Akan tetapi keutamaan suatu amalan tergantung pada tingkat ketaatan kepada Allah ﷻ dan kadar manfaat bagi pelakunya. Adakalanya amalan yang lebih utama itu berupa amalan yang ringan dan adakalnya berupa amalan yang berat. [4]
Dalil yang Mendasarinya
Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan eksistensi dan kandungan kaidah ini. Di antaranya adalah hadis Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhuma riwayat al-Bukhari:
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah tiba-tiba ada laki-laki yang berdiri. Lalu Nabi ﷺ menanyakan tentang orang itu, maka orang-orang menjawab: “Dia adalah Abu Isra’il, ia telah bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa. Maka Nabi ﷺ bersabda: “Perintahkan dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan hendaklah ia meneruskan puasanya.” [5]
Dalam hadis di atas Nabi ﷺ melarang orang tersebut melakukan perkara yang tidak bermanfaat, dan memerintahkannya meneruskan yang bermanfaat yaitu puasa, karena pahala itu tergantung pada kadar manfaat bukan kadar kesulitan.
Demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayat Imam al-Bukhari dan Muslim:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا ؟ فَقَالُوْا: نَذَرَ أَنْ يَمْسِيَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah melihat seorang tua yang dipapah oleh kedua anaknya. Lalu beliau ﷺ bertanya, “Ada apa gerangan dengan orang ini?” Orang-orang menjawab: “Ia telah bernadzar untuk berjalan.” Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah ﷻ tidak butuh atas penyiksaan orang ini kepada dirinya sendiri.” Kemudian beliau memerintahkan orang tersebut untuk naik kendaraan. [6]
Dalam hadis tersebut Nabi ﷺ mencela keinginan orang tua itu untuk memasukkan dirinya ke dalam kesulitan. Dan beliau mengisyaratkan bahwa pahala itu tidak tergantung pada kadar sulitnya amalan dengan menjelaskan bahwa Allah ﷻ tidak membutuhkan siksaan atau kesulitan yang ditimpakan seseorang kepada dirinya sendiri.
Dan hadis Ummul Mukminin Juwairiyyah radhiyallahu anha Riwayat Imam Muslim [7]:
عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ. فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.
Dari Ummul Mukminin Juwairiyyah, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah keluar di pagi hari dari rumahnya ketika Salat Subuh, sementara Juwairiyyah radhiyallahu anhum berada di tempat salatnya. Kemudian beliau ﷺ kembali setelah waktu dhuha, dan Juwairiyah masih duduk di tempat semula. Lalu Nabi ﷺ bertanya, “Engkau masih tetap di tempat semula seperti ketika aku meninggalkanmu tadi?” Ia menjawab: “ Ya.” Lalu Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali. Seandainya empat kalimat itu ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sepanjang hari tadi tentulah menandinginya (yaitu):
سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
Seandainya kadar pahala itu tergantung pada kadar sulitnya amalan, tentulah duduknya Ummul Mukminin di masjid dan zikir yang diucapkannya lebih utama daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.
Semisal dengan hadis-hadis di atas banyak, misalnya sabda Nabi ﷺ dalam hadis yang telah disepakati keShahihannya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ﷺ bersabda:
كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
“Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh ar-Rahman, yaitu: Subhanallahil ‘Azhim Subhanallahil wabihamdihi.” [8]
Dan sabda Nabi ﷺ dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu:
اْلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اْلأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اْلإِيْمَانِ.
“Iman itu terdiri atas tujuh puluh atau enam puluh sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan Laa ilaha illAllah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu termasuk bagian dari iman.” [9]
Seandainya besarnya pahala itu semata-mata tergantung pada besarnya kesulitan, tentulah menyingkirkan gangguan dari jalan itu lebih besar pahalanya daripada keimanan.
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh kasus yang masuk dalam implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Perbuatan seseorang membiarkan dirinya dalam cuaca panas atau cuaca dingin tanpa mengenakan baju, atau semisalnya, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai bentuk mujahadah, maka dalam hal ini pelakunya tercela dan tidak terpuji, jika di dalamnya tidak terkandung manfaat syariyah. [10]
Seseorang yang sedang dalam keadaan safar maka berbuka lebih utama daripada berpuasa, karena pahala tergantung pada kadar manfaat bukan kadar kesulitan, sedangkan pada keadaan tersebut berbuka lebih bermanfaat baginya daripada berpuasa. [11]
Mengqashar salat bagi musafir lebih utama daripada menyempurnakannya, dan itu adalah lebih ringan baginya. [12]
Haji Tamattu’ adalah cara manasik yang paling afdhal bagi orang yang tidak membawa binatang sembelihan, [13] karena itu adalah perkara terakhir dari Nabi ﷺ, dan itu lebih ringan. [14]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] al-Muwafaqat, 2/129.
[2] Sebagian ulama menyebutkan kaidah: “Semakin banyak yang dikerjakan maka semakin banyak keutamaannya.” Kaidah ini disebutkan di antaranya oleh al-Qarafi dan as-Suyuthi. Lihat al-Furuq karya al-Qarafi 2/131-133. al-Asybah wa an-Nazhair karya as-Suyuthi hal. 144. Kaidah yang sedang dibahas ini dan dalil-dalilnya merupakan bantahan atas kaidah tersebut. Sebagaimana sebagian ulama telah menyebutkan bantahan terhadap kaidah tersebut, di antaranya as-Syathibi dalam al-Muwafaqat 2/130-133, al-‘Izz bin Abdissalam dalam Qawa’id al-Ahkam 1/38, dan al-Muqriy dalam al-Qawa’id 2/411.
[3] HR. al-Bukhari, no. 39
[4] Lihat Majmu’ al-Fatawa 22/313
[5] HR. al-Bukhari, no. 6704.
[6] HR. al-Bukhari, no. 6701 dan Muslim, no. 1642.
[7] HR. Muslim, no. 2726.
[8] HR. al-Bukhari, no. 6406 dan Muslim, no. 2694.
[9] HR. Muslim, no. 35.
[10] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 23/315.
[11] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 26/37.
[12] Idem.
[13] Idem.
[14] Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Miman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 234-239.
Kaidah Ke-57: Segala Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terhindar Darinya Maka Dimaafkan
Kaidah Kelima Puluh Tujuh
كُلُّ مَا لاَ يُمْكِنُ اْلاِحْتِرَازُ عَنْ مُلاَبَسَتِهِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ
Segala sesuatu yang tidak mungkin terhindar darinya maka dimaafkan
Makna Kaidah
Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kebersihan dan kesucian. Islam datang dalam keadaan selaras dengan fitrah dan jiwa yang lurus yang tidak menyukai percampuran dengan hal-hal kotor dan najis. Islam juga sangat menganjurkan sisi kesucian dan senantiasa menjaganya. Dalam memerintahkan kepada aspek kesucian dan kebersihan, Islam menempuh jalan pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Dalam permasalahan ini, syariat tidak memberikan beban yang berat yang berimplikasi kepada kesulitan dan kesempitan. Demikian pula, syariat tidak bermudah-mudah dalam permasalahan ini, yang mengakibatkan hilangnya tujuan dan maksud dari pensyariatan thaharah (bersuci) dan membersihkan najis.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan: “Dalam permasalahan penghalalan dan pengharaman, termasuk menentukan suatu perkara suci atau najis, agama Islam bersikap pertengahan di antara kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana bersikap pertengahan dalam seluruh aspek syariat. Syariat tidak memberikan beban yang berat kepada kita dalam masalah pengharaman dan tentang hal-hal yang najis, seperti beban berat yang telah dipikul oleh kaum Yahudi. Di mana telah diharamkan atas mereka hal-hal yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka, disebabkan kezaliman dan maksiat yang mereka lakukan. Bahkan Allah ﷻ menghilangkan kesempitan dan beban berat yang mereka pikul dari diri kita. Seperti permasalahan meminjam pakaian, menjauhi wanita yang sedang haidh dari tempat makan dan tempat tidurnya, dan semisalnya. Dan tidak pula halal bagi kita perkara-perkara keji, sebagaimana hal itu terjadi di kalangan orang-orang nashara yang mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mau menempuh jalan agama yang haq. Sehingga mereka tidak menjauhi benda-benda najis, dan tidak pula mengharamkan perkara-perkara jelek. Bahkan puncak ucapan mereka hanyalah mengatakan: “Besihkanlah hatimu, lalu laksanakan salat.” Adapun kaum Yahudi mereka memberikan perhatian kepada kebersihan lahiriah namun mengabaikan kesucian hati. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka.” [QS. al Maidah/5:41]
Adapun orang-orang beriman, maka Allah ﷻ mensucikan hati dan badan mereka dari perkara-perkara najis. [1]
Di antara bentuk wasathiyyah (sikap pertengahan) tersebut, syariat datang dengan memberikan keringanan terhadap sebagian najis, dan dalam beberapa situasi serta kondisi tertentu. Seperti yang disebutkan dalam substansi kaidah ini, yaitu di suatu kondisi ketika menghindari suatu benda najis merupakan perkara yang sulit. Dikarenakan benda tersebut merupakan sesuatu yang sering kali bersinggungan dengan manusia. Sehingga merupakan hal yang berat apabila seorang Muslim diberikan beban (Taklif) untuk menjauhi benda tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, najis itu dimaafkan dan dihukumi sebagai sesuatu yang suci karena sulitnya terhindar darinya.
Perlu kita fahami juga bahwa ada beberapa keadaan atau kondisi yang ditentukan syariat sebagai sebab dimaafkannya najis selain yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah [2]:
Masyaqqah (kesulitan). Misalnya kasus orang yang selalu keluar najis darinya, seperti orang yang terkena salasul baul (senantiasa keluar air kencing darinya), dan wanita yang terkena istihadhah (selalu keluar darah dari farjinya), dan semisalnya. Sesungguhnya syariat telah memberikan keringanan kepada orang-orang tersebut, dan memberikan kelonggaran atas najis yang menimpa mereka.
‘Umumul balwa, maksudnya adalah banyaknya orang yang tertimpa hal tersebut di kalangan manusia secara umum. Misalnya keberadaan darah ataupun nanah yang keluar dari jerawat atau pun bisul, maka hal itu pun dimaafkan. Dikarenakan banyaknya manusia yang tertimpa hal itu.
Secara umum kaidah ini merupakan bagian dan cabang dari kaidah yang telah maruf di kalangan para ulama yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang termasuk salah satu dari al Qawa’id al-Khams al-Kubra (lima kaidah besar) dalam pembahasan fiqih.
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sulitnya terhindar dari sesuatu menjadi sebab akan adanya keringanan adalah sebagai berikut:
Hadis Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa kucing bukanlah hewan yang najis. Hal itu karena manusia sulit terhindar dari hewan ini. Seandainya kucing dihukumi hewan najis tentu hal itu merupakan kesulitan, karena hewan tersebut sering kali berada di sekitar manusia dan sering bersama manusia.
Nabi ﷺ bersabda:
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
“Kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian.” [3]
Setelah menyebutkan hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan: “Kami berpendapat bahwa jenis kesulitan untuk terhindar dari suatu hal memberikan pengaruh terhadap jenis keringanan. Apabila kesulitan tersebut berkaitan dengan seluruh jenisnya, maka dimaafkan keseluruhannya, sehingga dihukumi akan sucinya hal tersebut. Adapun jika kesulitan itu berkaitan dengan sebagiannya, maka dimaafkan sesuai kadar kesulitannya.” [4]
Keumuman dalil yang menunjukkan diangkatnya kesempitan dari umat ini. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” [QS. al Maidah/5:6]
Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, “Maksudnya adalah bahwa Allah ﷻ tidaklah memberikan beban kepada kalian dengan sesuatu yang tidak kalian mampui, dan tidak memberikan kewajiban yang menyulitkan kalian, kecuali Allah ﷻ akan memberikan kelapangan dan jalan keluar. Oleh karena itu, salat yang merupakan rukun Islam terbesar setelah dua kalimat syahadat wajib dilaksanakan empat rakaat ketika berada di tempat asal, adapun ketika safar maka diqashar menjadi dua rakaat. Dan ketika keadaan takut sebagian imam melaksanakannya satu rakaat, dan dikerjakan dengan berjalan ataupun berkendaraan, dengan menghadap Kiblat atau tidak. Demikian pula pelaksanaan salat sunnah ketika safar boleh menghadap Kiblat ataupun tidak. Dan kewajiban berdiri digugurkan ketika seseorang mempunyai uzur sakit, sehingga diperbolehkan baginya untuk salat dengan duduk, jika tidak mampu maka diperbolehkan dengan berbaring. Dan selainnya dari rukhshah dan keringanan dalam seluruh kewajiban. [5]
Oleh karena itu, kesempitan dan kesulitan telah diangkat dari syariat ini termasuk dalam permasalahan thaharah (bersuci).
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Tanah yang tercampur najis di jalanan, apabila tertempel sedikit pada kaki atau pakaian maka dimaafkan karena sulitnya terhindar darinya.
Air mani dihukumi sebagai sesuatu yang suci, meskipun hal yang mengonsekuensikan kenajisannya ada. Hal ini dikarenakan seringnya mani tersebut mengenai badan, pakaian, atau kasur tanpa kesengajaan manusia, dan sulitnya terhindar darinya. [6]
Dimaafkannya bekas najis yang tersisa setelah istIjmar, dengan syarat telah dilaksanakan istIjmar tersebut sesuai tuntunan syari. [7]
Wallahu a’lam. [8]
_______
Footnote
[1] Majmu’ al-Fatawa, 21/332-333.
[2] Lihat Ahkamun Najasat fil Fiqhil Islami, karya ‘Abdul Majid Shalahin, hlm. 2/548-550.
[3] HR. Abu Dawud, no. 75; at-Tirmidzi, no. 92; an-Nasa’i, no. 68. Ibnu Majah, no. 367. Semuanya dari riwayat Abu Qatadah z
[4] Majmu’ al-Fatawa, 21/599.
[5] Tafsir Alquranil ‘Azhim, karya Ibnu Katsir 1/342.
[6] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 21/592.
[7] Lihat al Inshaf karya Al Mardawi 1/329 dan Syarh Muntahal Iradah karya al-Buhuti 1/103. Lihat pula contoh-contoh lain dari najis yang dimaafkan pada empat madzhab dalam kitab-kitab berikut: al Binayah ‘alal Hidayah, karya al ‘Aini, 1/735. al Mabshuth, karya as-Sarkhasi, 1/60-61. Syarh Fathil Qadir, karya Ibnul Hammam, 1/177-179. Bada-i’us Shana-i’, karya al-Kasani, 1/79. Mawahibul Jalil Syarh Mukhtashar Khalil, karya al Hatthab, 1/154. Hasyiyah al Baijuri ‘ala Ibni Qasim, 1/35. Mughnil Muhtaj, karya as-Syarbini al-Khathib, 1/81. Nihayatul Muhtaj, karya ar-Ramli, 1/71. Raudhatut Thalibin, karya an-Nawawi, 1/279-280. Syarh Muntahal Iradat, karya Al Buhuti, 1/103. Kassyaful Qina’, karya Al Buhuti, 1/218.
[8] Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Maiman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, Hlm. 335-338.
Kaidah Ke-58: Kebiasaan Berubah Menjadi Ibadah Dengan Niat Yang Saleh
Kaidah Kelima Puluh Delapan
الْعَادَاتُ تَنْقَلِبُ عِبَادَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّالِحَاتِ
Kebiasaan berubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh. [1]
Muqadimah
Sebagaimana telah kita pahami bahwa ibadah adalah pekara yang bersifat tauqifiyyah, sehingga tidak boleh seseorang melaksanakan suatu amalan ibadah, kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Adapun perkara adat dan kebiasan, maka hukum asalnya halal dan mubah, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Maka, perkara adat yang menjadi kebiasaan penduduk suatu negeri hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali jika menyelisihi nash syari, maka ketika itu wajib untuk ditinggalkan.
Seorang hamba dalam kehidupannya senantiasa berkisar antara dua hal tersebut. Adakalanya ia dalam keadaan mengerjakan amal ibadah, dan adakalanya mengerjakan aktivitas adat. Dan telah maklum bahwa waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan aktifitas yang bersifat kebiasan dan adat itu lebih banyak daripada waktu yang kita pergunakan dalam rangka mengerjakan amal ibadah. Demikianlah keadaan kebanyakan orang.
Namun jika seseorang menerapkan kaidah ini, maka seluruh waktunya akan bernilai ibadah, dan tidak berlalu sedikit pun waktu kecuali menjadi bagian timbangan amal kebaikannya. Hal itu tidak memerlukan usaha yang besar, hanya membutuhkan pembiasaan dan kerjasama antar anggota keluarga, atau sesama rekan untuk saling mengingatkan, disertai memohon pertolongan kepada Allah ﷻ untuk bisa merealisasikannya.
Makna Kaidah
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kaidah ini menjelaskan tentang keberadaan amalan dan aktivitas yang termasuk kategori adat yang hukum asalnya mubah, namun akan bernilai ibadah apabila diiringi dengan niat yang saleh. Untuk merealisasikan hal itu, seseorang dituntut untuk memunculkan perasaan ta’abbud (peribadahan) di dalam hatinya setiap kali hendak mengerjakan perkara yang mubah tersebut, dan juga ketika mengerjakannya. Jika hal itu dilakukan, maka perkara adat dan kebiasaan tersebut akan berubah dari statusnya sebagai perkara yang mubah menjadi ibadah dan menjadi bagian amal kebaikan baginya.
Dengan demikian, setiap aktivitas adat kebiasaan yang kita dasari dengan niat saleh, akan berubah menjadi ibadah, sebagaimana perkara adat juga bisa berubah menjadi kemaksiatan jika disertai dengan niat yang jelek.
Dalil yang Mendasarinya
Kaidah ini adalah salah satu cabang dari kaidah yang termasuk lima kaidah besar dalam pembahasn fiqih yaitu kaidah al-umuru bimaqashidiha (setiap amalan tergantung dengan niatnya). Adapun dalil dari kaidah ini di antaranya adalah hadis ‘Umar bin Khaththab dari Rasulullah ﷺ yang bersabda:
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
“Sesungguhnya semua amalan itu dikerjakan dengan niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan.” [2]
Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah ﷺ bersabda:
وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ
“Dan seseorang mencampuri istrinya pun termasuk sedekah.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkannya di jalan yang haram, bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika dia menyalurkannya pada jalan yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” [3]
Imam Ibnu Daqiqil ‘Id rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini mengatakan: “Telah berlalu pembahasan bahwa perkara-perkara mubah akan menjadi ketaatan dikarenakan niat. Maka, mencampuri istri akan menjadi ibadah jika seseorang meniatkannya untuk memenuhi hak istri dan memergauliya dengan maruf, atau berniat supaya mendapatkan keturunan yang saleh, atau menjaga kehormatan dirinya dan istrinya, atau selainnya dari maksud-maksud yang baik.” [4]
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh penerapan kaidah yang mulia ini adalah sebagai berikut:
Makan dan minum pada asalnya merupakan rutinitas dan kebiasaan keseharian yang mubah. Seseorang tidak mendapatkan pahala ataupun dosa ketika mengerjakannya. Namun, aktifitas tersebut bisa berubah dari statusnya sebagai sesuatu yang mubah menjadi suatu amalan yang bernilai ibadah dengan mengimplementasikan kaidah ini. Yaitu, sebelum seseorang meletakkan tangannya untuk mengambil makanan dan sebelum mengangkat minuman ke mulutnya, maka ia munculkan niat untuk menguatkan badannya dalam rangka beribadah dengan sarana makan dan minum itu. Hal ini dikarenakan badan tidaklah mampu melaksanakan ibadah kecuali jika mempunyai kekuatan, dan itu akan diperoleh melalui makan dan minum. Maka, hendaklah seseorang memunculkan niat yang mulia ini ketika makan dan minum, disertai dengan menerapkan adab-adab syari di dalamnya, seperti mengawali dengan menyebut nama Allah ﷻ, makan dengan tangan kanan, mulai mengambil makanan dari yang terdekat, dan lain-lain. Jika hal itu dilakukan maka waktu yang dihabiskan untuk makan dan minum itu akan bernilai ibadah dan termasuk bentuk taqarrub yang mendatangkan pahala baginya.
Membeli barang-barang seperti mobil, pakaian, rumah, beraneka-ragam makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga dan semisalnya, asalnya adalah perkara yang mubah. Hal itu akan berubah menjadi ibadah jika diiringi dengan niat yang saleh. Misalnya, dengan niat untuk memperlancar kegiatannya dalam beribadah kepada Allah ﷻ, menguatkan badannya dalam mengerjakan ketaatan, menunaikan perintah Allah ﷻ dalam menutup aurat dan menjaga kehormatannya, serta niat-niat saleh semisalnya. Maka, dengan niat tersebut ia akan memeroleh pahala atas belanja yang dilakukannya dan menjadi bagian timbangan amalan kebaikannya nanti di Hari Kiamat.
Memakai jam tangan hukum asalnya adalah mubah, akan tetapi jika seseorang memakainya dengan niat untuk menjaga waktu-waktu salat, atau menjadikan sarana untuk menunaikan janji-janji yang telah dibuatnya, demikian pula sebagai wasilah untuk mengatur waktunya supaya senantiasa di dalam ketaatan, dan niat-niat lainnya, maka hal itu akan merubahnya dari kategori adat kebiasaan menjadi ibadah. Karena adat akan berubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh. Dan perlu kita perhatikan bahwa niat tersebut hanyalah sekadar tekad yang ada di dalam hati, dan tidak perlu diucapkan, tidak pula diawali dengan berwudhu, atau semisalnya. Sesungguhnya niat adalah amalan hati yang sederhana dan mudah tanpa adanya kesulitan di sana.
Berangkat menuju ke tempat kerja, hukum asalnya termasuk kebiasaan yang mubah. Seseorang tidak diberi pahala ataupun mendapatkan dosa atasnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa seseorang menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaannya. Maka, bagi seorang yang berakal semestinya berusaha untuk menjadikan aktifitas tersebut menjadi bagian amal salehnya. Dan hal itu bisa didapatkan dengan memunculkan niat yang saleh. Di antaranya dengan niat untuk mencari harta yang halal, sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain, dan menjadi sarana baginya untuk menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada orang-orang yang ditanggungnya, baik istri ataupun anaknya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadis Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu:
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ
“Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah kecuali pasti diberi pahala atasnya, sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” [5]
Tidur termasuk kategori kebiasaan yang mubah, seseorang asalnya tidak mendapatkan pahala ataupun dosa karena melakukannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa seseorang akan menghabiskan banyak waktu untuk tidurnya. Maka bagaimanakah kiat supaya kebiasaan tersebut bernilai ibadah? Jawabannya: Tidur akan bernilai ibadah jika seseorang meniatkannya dengan kebaikan. Seperti berniat untuk mengembalikan kekuatan badannya dalam rangka mengerjakan amal ketaatan kepada Allah ﷻ. Yang demikian itu dikarenakan banyaknya aktifitas sehari-hari akan menyebabkan hilangnya kekuatan badan, jika tidak diimbangi dengan istirahat. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan tidur, bahkan itu termasuk kebutuhan badan yang utama. Bertolak dari realita bahwa seorang tidak mungkin terlepas dari tidur, dan banyak waktu yang terpakai untuk keperluan tersebut, maka tidak sepantasnya kita menyia-nyiakan waktu tidur tanpa ada manfaat yang kita dapatkan. Kita hendaknya berupaya supaya aktifitas tersebut menjadi bagian timbangan amal kebaikan kita. Hal itu akan didapatkan dengan meniatkannya untuk beribadah kepada Allah ﷻ dan mengharapkan pahala dari-Nya, disertai dengan memerhatikan adab-adab ketika tidur secara syari, seperti berwudhu terlebih dahulu sebelumnya, mengucapkan zikir-zikir yang disunnahkan, dan tidur dengan sisi badan sebelah kanan. Jika seseorang melakukannya disertai dengan niat yang saleh, maka tidurnya akan berubah dari adat menjadi ibadah.
Bartamasya menikmati pemandangan, keindahan alam, dan semisalnya hukum asalnya adalah mubah, selama tidak mengantarkan kepada perkara yang haram. Kegiatan tersebut bisa mendatangkan pahala bagi seseorang dan menjadi bagian timbangan amal kebaikannya, jika ia mengiringinya dengan niat yang baik. Misalnya, dengan niat untuk memberikan ketenangan, waktu rehat dan mengendurkan pikiran dan jiwa sehingga ketika beribadah bisa lebih fokus dan memusatkan perhatian. Karena jiwa akan merasakan kejenuhan dengan banyaknya rutinitas maupun pekerjaan sehari-hari. Hal ini juga akan berpengaruh pada peribadahan seseorang. Maka, harus ada waktu khusus supaya jiwa merasakan santai dari tekanan sehingga siap untuk mengerjakan aktifitas selanjutnya, termasuk aktifitas peribadahan kepada Allah ﷻ.
Ini adalah sebagian contoh penerapan kaidah ini, dan secara ringkas kita katakan bahwa adat kebiasaan jika dilakukan dengan niat yang baik maka menjadi amal ketaatan, dan jika dilakukan dengan niat yang jelek maka akan menjadi perkara dosa dan kemaksiatan. [6]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Yang dimaksud dengan adat ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan manfaat dunia saja. Seperti: makan, minum, tidur, bekerja, nikah dan lainnya.
Adapun maksud ibadah di sini adalah perbuatan manusia yang dilakukan untuk mendapatkan kebaikan Akhirat saja atau kebaikan dunia dan Akhirat. Seperti: salat, zikir, puasa, haji dan lain-lainnya.
[2] HR. al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907.
[3] HR. Muslim no. 1006.
[4] Lihat Syarh al-Arba’in an-Nawawiyyah fi al-Ahadis as-Shahihah an-Nabawiyyah, Majmu’ah min al-‘Ulama (I’tana bihi: Mahmud bin al-Jamil Abu ‘Abdillah), Cet. I, Tahun 1426 H, Dar al-Mustaqbal, Kairo, Hlm. 287.
[5] HR. al-Bukhari no. 56.
[6] Diangkat dari Risalah fi Tahqiq Qawa’id an-Niyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah II.
Kaidah Ke-59: Keutamaan Niat
Kaidah Kelima Puluh Sembilan
نِيَّةُ الْمَرْءِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ
Niat lebih utama daripada amalan
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan keberkahan dan nilai pahala yang besar dalam niat. Karena niat semata sudah termasuk kategori ibadah yang diberi pahala oleh Allah ﷻ.
Di antara yang menyebabkan timbangan amal kebaikan seseorang bertambah dan derajatnya naik di Akhirat adalah niat yang saleh. Barang siapa berniat baik maka ia akan mendapatkan pahala meskipun dia belum mampu merealisasikannya dengan amalan. Apabila niat baik itu disertai dengan amalan maka ia meraih dua pahala, yaitu pahala niat dan pahala amalan.
Oleh karena itu, niat lebih mendalam dan lebih utama daripada amalan. Apabila kedua terpadu, maka itu cahaya di atas cahaya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Adapun niat maka ia adalah pokok dan tiang seluruh perkara. Niat juga adalah asas dan pondasi yang terbangun di atasnya segala perkara. Sesungguhnya niat adalah ruh amalan, pemimpin dan pengendalinya, sedangkan amalan sekadar mengikuti. Amalan menjadi sah sesuai keabsahan niat dan menjadi rusak dengan rusaknya niat. Dengan niat tersebut akan didapatkan taufiq, adapun ketiadaan niat akan mendatangkan kehinaaan. Dengan niat pula bertingkat-tingklatlah derajat manusia di dunia dan Akhirat.” [1]
Dalil yang Mendasarinya
Banyak dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini. Di antaranya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata: “Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan, kemudian beliau ﷺ bersabda:
إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً ، إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلاَّ شَرَكُوْكُمْ فِي اْلأَجْرِ.
“Sesungguhnya di Madinah ada beberapa laki-laki yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidak pula melewati lembah melainkan mereka bersama kalian, sakit telah menghalangi mereka.”
Dalam riwayat yang lain “Melainkan mereka berserikat dengan kalian dalam pahala” [2]
Juga hadis Abu Kabsyah al Anmari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:
إنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَزَقهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمَ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمٍ، لاَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهَذَا بأَخْبَثِ المَنَازِلِ. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلاَ عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ
“Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang: (pertama) Seorang hamba yang Allah l berikan rezeki berupa harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya pada rezeki itu. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, dan ia mengetahui hak Allah padanya. Hamba ini berada pada kedudukan terbaik. (Kedua) Seorang hamba yang Allah beri ilmu namun tidak diberi harta. Orang ini memiliki niat yang baik, dan mengatakan: “Seandainya aku memiliki harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si Fulan”. Dengan niatnya yang baik itu maka pahala keduanya sama. (ketiga) Seorang hamba yang Allah ﷻ beri harta namun tidak diberi ilmu, kemudian dia berbuat sembarangan dengan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam masalah harta itu, tidak berbuat baik kepada kerabatnya dengan hartanya, dan tidak mengetahui hak Allah pada harta itu. Hamba ini berada pada kedudukan yang terburuk. (Keempat) Dan seorang hamba yang Allah tidak memberinya harta maupun ilmu, kemudian dia mengatakan: “Seandainya aku memiliki harta aku akan berbuat seperti perbuatan si Fulan (orang ketiga)”. Maka dengan niatnya itu maka keduanya mendapatkan dosa yang sama.” [3]
Sisi pendalilan dari hadis ini, yaitu berkaitan dengan orang kedua yang diberi ilmu namun tidak diberi harta. Ia mendapatkan pahala sebagaimana orang pertama, karena ia memiliki niat jujur dan tekad kuat untuk melakukan amalan orang pertama, apabila ia diberi harta. Ini menunjukkan bahwa niat itu lebih penting daripada sekadar amalan.
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh penerapan kaidah yang mulia ini adalah sebagai berikut:
Seseorang yang ingin memberikan zakat kepada orang fakir, dan ia telah berusaha untuk mencarinya. Kemudian ia mendapatkan seseorang yang menurut perkiraan kuatnya dia adalah orang fakir, lalu ia memberikan zakat kepadanya. Ternyata orang tersebut adalah orang kaya maka menurut pendapat yang Shahih adalah bahwa kewajiban zakatnya telah gugur, karena perkiran kuat itu telah cukup dalam mengerjakan amalan. Bahkan ia mendapatkan pahala semisal orang yang menyerahkan zakat kepada yang berhak menerimanya meskipun realitanya ia memberikan kepada orang kaya. Hal tersebut dikarenakan niatnya yang saleh. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ dalam hadist Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1022 tentang kisah seorang pembayar zakat.
Seorang wanita yang di malam hari berniat untuk melaksanakan puasa Arafah atau puasa Asyura’ esok harinya, ternyata kemudian terhalangi karena haid, maka insya Allah dicatat baginya pahala melaksanakan puasa tersebut.
Seseorang yang berniat untuk melaksanakan salat malam dan telah mempersiapkan segala yang bisa membantunya bangun malam, namun ternyata ia tidak terbangun, maka dengan niat yang saleh tersebut insya Allah ia dicatat melaksanakan salat malam.
Seseorang yang berniat untuk mengeluarkan zakat dan telah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan untuk bisa melaksanakannya akan tetapi kemudian harta yang akan dizakati itu terbakar, bukan karena keteledorannya, maka sesungguhnya telah gugur kewajiban zakat darinya. Bahkan diharapkan ia mendapat pahala mengeluarkan zakat karena ia telah berniat dan bertekat untuk menunaikannnnya, hanya saja muncul perkara yang mengahalangi, sehingga tidak bisa mewujudkan niatnya itu. Sedangkan niat lebih utama dari sekadar amalan.
Demikian sebagian contoh penerapan kaidah yang mulia ini, sekaligus menggambarkan betapa pentingnya niat dan betapa besar pahala yang bisa didapatkan dengan niat yang baik. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa memerhatikan perkara niat dan hendaklah kita berusaha meniatkan kebaikan di setiap ucapan dan perbiuatan yang kita lakukan. [4]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] I’lam al-Muwaqqi’in, 6/105.
[2] HR al-Bukhari no. 4423 dan Muslim no. 1911.
[3] HR. at-Tirmidzi no. 2325 dan Ibnu Majah no. 4228. DiShahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah no. 3406.
[4] Diangkat dari Risalah fi Tahqiq Qawa’id an-Niyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Keenam.
Kaidah Ke-60: Berpahala Dengan Niat
Kaidah Keenam Puluh
لاَ ثَوَابَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ
Tidak ada pahala kecuali dengan niat
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan tentang urgensi niat bagi seorang hamba. Karena pahala di Akhirat dan balasan yang baik dari amalan yang dilakukan seorang hamba tidak akan diperoleh kecuali diiringi niat baik dalam rangka bertaqarrub kepada Allah ﷻ. Sehingga hanya orang yang melaksanakan ibadah dengan niat ikhlas yang akan meraih pahala. Adapun yang beramal karena ingin memeroleh keuntungan dunia, maka ia tidak akan meraih pahala dari-Nya.
Kaidah ini menjelaskan perbedaan antara amalan yang dilakukan dengan niat yang baik dan amalan yang dilakukan dengan niat yang buruk. Meskipun secara lahiriah kedua amalan tersebut sama namun hakikatnya memiliki perbedaan yang jauh ditinjau dari sisi hasilnya.
Dalil yang Mendasarinya
Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan eksistensi dan kandungan kaidah ini. Di antaranya adalah hadis Mu’adz bin Jabal riwayat Abu Dawud, Rasulullah ﷺ bersabda:
اْلغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَ أَطَاعَ اْلإِمَامَ وَ أَنْفَقَ اْلكَرِيْمَةَ وَ يَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَ اجْتَنَبَ اْلفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَ نَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَ رِيَاءًا وَ سُمْعَةً وَ عَصىَ اْلإِمَامَ وَ أَفْسَدَ فىِ اْلأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِاْلكَفَافِ
“Berperang itu ada dua macam. Adapun orang yang berperang karena mencari rida Allah ﷻ, menaati imam, menginfakkan harta berharganya, memberi kemudahan kepada kawannya, dan menjauhi kerusakan, maka seluruh tidur dan terjaganya terhitung pahala. Adapun orang yang berperang karena kebanggaan, riya’ dan sum’ah, menentang pemimpin, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka ia tidak akan kembali dengan membawa balasan.” [1]
Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada pahala kecuali disertai niat yang baik.
Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat al-Bukhari, Nabi ﷺ bersabda:
مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Barang siapa memelihara seekor kuda untuk fii sabilillah karena keimanan kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka sesungguhnya makan dan minumnya kuda itu, kotoran dan kencingnya, akan menjadi timbangan kebaikan baginya pada Hari Kiamat.” [2]
Hadis di atas termasuk dalil paling jelas yang menunjukkan eksistensi kaidah ini.
Contoh Penerapan Kaidah
Kaidah yang mulia ini mempunyai banyak contoh implementatif, baik berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah. Berikut ini beberapa di antara contohnya:
Telah dimaklumi bahwa menaati penguasa dalam perkara maruf termasuk kewajiban syari, namun seseorang yang menaati penguasa sekadar untuk mendapatkan keuntungan dunia, meraih jabatan atau mempertahankannya, tanpa terbesit dalam hatinya niat beribadah dan taqarrub kepada Allah ﷻ maka tidak ada pahala baginya dalam ketaatannya itu. Bahkan bisa jadi perbuatannya itu akan menjadi musibah baginya di dunia dan Akhirat. Adapun seseorang yang taat kepada penguasa karena Allah yang telah memerintahkan, sehingga ia melakukannya karena melaksanakan perintah Allah ﷻ, juga perintah Rasulullah ﷺ maka orang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala dari-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat al-Bukhari, Rasulullah ﷺ bersabda:
ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطََّرِيْقِ ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ وَاللهِ الََّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً )).
“Tiga golongan manusia yang kelak pada Hari Kiamat, Allah tidak akan sudi memandang, tidak menyucikan mereka, dan disediakan bagi mereka siksaan yang pedih, yaitu Orang yang memiliki kelebihan air di perjalanan, akan tetapi ia enggan untuk memberikannya kepada ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan); Orang yang berbai’at kepada seorang pemimpin akan tetapi ia tidaklah berbai’at kecuali karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, yaitu bila sang pemimpin memberinya harta, maka ia rida dan bila sang pemimpin tidak memberinya harta, maka ia benci; Orang yang menawarkan dagangannya seusai Salat Ashar, dan pada penawarannya ia berkata: “Sungguh, demi Allah yang tiada SeSembahan yang benar selain-Nya, aku telah mendapatkan penawaran demikian dan demikian. Sehingga ada konsumen yang mempercayainya. Selanjutnya Nabi ﷺ membaca ayat, yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.” [3]
Menulis kitab yang bermanfaat sesungguhnya termasuk kategori amal saleh. Namun seorang penulis tidak akan memeroleh pahala kecuali jika niatnya niat yang baik. Apabila niatnya saat menulis sekadar untuk berbangga-bangga, sum’ah, atau untuk mencari perhatian manusia, atau mencari keuntungan dunia semata, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun.
Tidak diragukan bahwa mengajak kepada perkara maruf dan mencegah dari perkara munkar termasuk ibadah. Akan tetapi pahala amalan tersebut tergantung dengan ada tidaknya niat yang baik. Seseorang yang mengerjakannya dengan maksud untuk memeroleh pujian manusia dan sanjungan semata, atau sekadar karena tuntutan pekerjaan yang harus ia kerjakan, maka tidak ada pahala baginya karena tidak ada pahala kecuali dengan niat yang saleh.
Sesungguhnya niat dalam rangka beribadah kepada Allah ﷻ semata merupakan salah satu di antara syarat sah salat. Oleh karena itu, jika seorang hamba melaksanakan salat dengan niatan riya, sumah, atau sekadar untuk mendapatkan keuntungan dunia maka salatnya tidaklah diterima, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Qudsi, Allah ﷻ berfirman:
أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ
“Aku adalah Zat Yang Paling tidak butuh kepada persekutuan para sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia memersekutukan-Ku dengan sesuatu selain-Ku, maka Aku akan meninggalkannya berserta kesyirikan yang diperbuatnya.” [4]
Melunasi utang dan penunaian hak-hak sesama hamba yang lainnya, apabila diiringi niat yang baik maka akan mendatangkan pahala bagi pelakunya. Namun jika dilakukan tanpa niatan tersebut, atau melakukannya karena terpaksa, maka ia tidak berhak mendapatkan pahala. Ini tidak berarti bahwa pembayaran utang tersebut tidak sah, karena penunaian hak-hak semacam itu tidak dipersyaratkan niat untuk keabsahannya, namun pembahasan di sini berkaitan dengan berpahala atau tidak. Jika ia meniatkan kebaikan dalam rangka melaksanakan perintah Allah ﷻ maka ia akan mendapatkan pahala dan jika tidak maka tidak ada pahala baginya.
Setiap amalan yang disertai riya’ sedangkan pelakunya tidak berusaha menolaknya, bahkan ia membiarkan dan rida dengannya maka itu adalah amalan yang bathil dan tidak ada pahala di dalamnya. Sebagaimana seseorang yang melakukan salat sekadar supaya terhindar dari hukuman penguasa, atau seseorang yang membayar zakat supaya tidak terkena hukuman dari pemerintah maka tidaklah ada pahala bagi pelakunya, karena amalan tersebut kosong dari niat peribadahan dan taqarrub kepada Allah ﷻ. [5]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] HR. Abu Dawud no. 2515. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Silsilah al-Ahadis as-Shahihah, no. 1990.
[2] HR. al-Bukhari no. 2853, an-Nasa’i no. 3582, Ahmad 2/374.
[3] HR. al-Bukhari no. 2358.
[4] HR. Muslim no. 2985.
[5] Diangkat dari Risalah fi Tahqiq Qawa’id an-Niyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ketiga.
Kaidah Ke-61: Darurat Tidak Menggugurkan Hak Orang Lain
Kaidah Keenam Puluh Satu
الاِضْطِرَارُ لاَ يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ
Keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain
Makna Kaidah
Kaidah ini merupakan salah satu cabang kaidah “Kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan” yang termasuk salah satu dari lima kaidah besar dalam pembahasan fiqih. Juga merupakan penjelasan lanjutan dari kaidah “Keadaan darurat menjadi sebab diperbolehkannya perkara yang dilarang.” [1]
Sebagaimana telah kita fahami bahwa seseorang yang berada dalam keadaan darurat, yang menyebabkannya harus mengonsumi sesuatu yang haram, maka ia diberikan uzur untuk melakukannya. Misalnya, orang yang sangat lapar dan tidak ada makanan yang didapatkan kecuali daging bangkai maka dalam keadaan itu diperbolehkan baginya untuk memakan daging tersebut sekadarnya. Allah ﷻ berfirman:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.” [QS. al-Baqarah/2:173]
Namun demikian, timbul pertanyaan apabila perbuatan seseorang mengambil atau mengonsumsi perkara yang haram itu menyebabkan hilang atau rusaknya harta orang lain? Apakah ia wajib menggantinya ataukah tidak? Inilah yang dibahas dalam kaidah ini. Kaidah ini menjelaskan bahwa keadaan darurat meskipun menjadikan seseorang mendapatkan uzur untuk mengambil perkara yang haram dan tidak berdosa ketika ia melakukannya namun tidak berarti bahwa itu juga menjadi sebab diperbolehkannya menggugurkan (atau menghilangkan) hak orang lain. Sehingga apabila keadaan darurat menyebabkan seseorang terpaksa mengambil atau memanfaatkan harta orang lain maka ia tetap harus mengganti harta yang telah ia manfaatkan dari harta orang lain tersebut. [2]
Dalil yang Mendasarinya
Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah beberapa nash firman Allah ﷻ dan sabda Nabi ﷺ yang menjelaskan tentang haramnya mengambil harta seorang Muslim dengan cara yang batil. Di antaranya firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [QS. an-Nisa’/4:29]
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “Allah ﷻ melarang para hamba-Nya yang beriman dari memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Larangan ini mencakup memakannya dengan cara merampas, mencuri, atau mengambilnya dengan perjudian, dan cara-cara hina lainnya.” [3]
Adapun dalil dari as-Sunnah di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Beliau ﷺ bersabda:
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ
“Setiap orang Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.” [4]
Demikian pula sabda Nabi ﷺ:
لاَ يَحِلُّ ماَلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ
“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan darinya.” [5]
Demikian pula di antara yang mendukung eksistensi kaidah ini adalah beberapa kaidah fikih berkaitan dengan keadaan darurat yang dialami oleh seorang insan. Di antaranya:
الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ
Madharat tidak boleh dihilangkan dengan madharat lainnya
الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ
Madharat tidak boleh dihilangkan dengan madharat semisalnya
Kaidah ini mengharuskan adanya dhoman (ganti rugi) atas harta yang diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang sedang mengalami keadaan darurat. Jika tidak demikian, berarti itu adalah betuk menghilangkan madharat dengan madharat lainnya, atau dengan madharat semisal, atau bahkan dengan madharat yang lebih besar dari madharat pertama, dan ini bertentangan dengan kaidah tersebut.
Al-Bazdawi mengatakan: “Sesungguhnya pengaruh keadaan darurat nampak dari gugurnya dosa, bukan hukumnya yang gugur. Maka wajib bagi seseorang yang mengalami keadaan darurat membayar ta’widh (ganti rugi). Barang siapa mengalami kelaparan boleh baginya memakan harta orang lain namun (kewajibannya) ganti rugi tidak gugur darinya. [6]
Contoh Penerapan Kaidah
Banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam kandungan kaidah ini. [7] Berikut ini beberapa contoh darinya:
Jika seseorang dalam keadaan lapar sehingga terpaksa memakan makanan orang lain, maka ia wajib mengganti makanan itu atau membayar ganti rugi kepada pemiliknya. Karena keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. [8]
Apabila sebuah perahu dikhawatirkan akan tenggelam karena banyaknya muatan, kemudian si pemilik perahu itu melemparkan sebagian barang milik penumpang ke laut, maka ia wajib mengganti barang yang dilemparkan tersebut kepada pemiliknya. [9]
Apabila seseorang menyewa perahu selama jangka waktu tertentu, kemudian ia tidak bisa mengembalikan perahu itu tepat waktu dikarenakan adanya penghalang berupa ombak yang besar atau semisalnya yang menyebabkan keterlambatan sampai di daratan, maka dalam keadaan ini ia wajib membayar ganti rugi kepada pemilik perahu sesuai standar harga sewa secara umum dan sesuai kadar lamanya waktu tambahan dari pengembalian itu. [10] Hal ini dikarenakan keadaan darurat yang dialami si penyewa tidak menggugurkan hak si pemilik perahu tersebut. [11]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang dialami seseorang, apabila tidak di atasi maka akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan orang tersebut yang bersifat dharuri. (Lihat –Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah karya Syaikh Nashir bin ‘Abdillah al-Maiman, hlm. 288)
[2] Lihat pembahasan kaidah ini dalam Qawa’id Ibni Rajab, hlm. 136, dan Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, karya Az-Zarqa, hlm. 161.
[3] Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, 2/54.
[4] HR. Muslim no. 2564.
[5] HR. Ahmad. Lihat Kunuz al-Haqaiq fi Hadis Khair al-Khala’iq karya al-Munawi 2/175.
[6] Kasyfu al-Asrar karya al-Bazdawi 1/1511. Lihat al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘anha karya Syaikh Dr. Saleh bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 300.
[7] Lihat al-Qawa’id karya Ibnu Rajab, hlm. 36. al-Qawa’id wa al-Fawaid al-Ushuliyyah karya Ibnu al-Laham, hlm. 34. al-Furuq karya al-Qarafi, 1/95.
[8] Apabila barang yang dimanfaatkan tersebut berupa barang yang ada semisalnya maka wajib diganti dengan barang semisal. Jika tidak maka diganti dengan membayar harganya. (Lihat al-Qawa’id al-Kulliyyah wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah karya Dr. Muhammad ‘Utsman Syabir, hlm. 227).
[9] Lihat al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, hlm. 186; al-Qawa’id karya Ibnu Rajab, hlm. 36. al-Qawa’id al-Kulliyyah wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah karya Dr. Muhammad ‘Utsman Syabir, hlm. 228.
[10] Lihat al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, hlm. 186
[11] Diangkat dari kitab al-Mufasshal fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Dr. Ya’qub bin Abdul Wahhab al-Bahisin, Cet. II, Tahun 1432 H/2011 M, Dar at-Tadmuriyyah, Riyadh,Hlm. 270-272.
Kaidah Ke-62: Beramal Dengan Dugaan Kuat Dalam Ibadah Telah Mencukupi
Kaidah Keenam Puluh Dua
الْعَمَلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي الْعِبَادَاتِ كَافٍ فِي التَّعَبُّدِ
Beramal dengan dugaan kuat dalam ibadah telah mencukupi
Muqaddimah
Substansi kaidah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah ﷻ kepada para hamba-Nya, sekaligus termasuk kemudahan yang diberikan kepada umat ini. Karena Allah ﷻ menghendaki kemudahan dan keringan, bukan kesulitan dan kesempitan bagi kita. Allah ﷻ telah mengugurkan kesulitan dan beban berat yang dahulu dipikul oleh umat-umat sebelum kita. Maka sesungguhnya syariat ini adalah syariat yang lurus, lapang dan mudah. Bentuk-bentuk keringanan dan kemudahan dalam syariat ini sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang terkandung dalam kaidah ini.
Sebelum masuk pada pembahasan lebih jauh, perlu kita fahami bahwa jenis-jenis pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi dan paing mulia adalah tingkatan keyakinan, yaitu mengetahui sesuatu secara pasti. Tingkat ini merupakan syarat dalam permasalahan aqidah, seperti pengetahuan tentang adanya Allah ﷻ, beriman kepada rububiyah dan uluhiyah-Nya, Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, taqdir, serta seluruh permasalahan aqidah yang yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkara-perkara tersebut dituntut keyakinan yang sempurna tanpa tercampuri ragu. Sehingga tidak diperbolehkan ragu, bimbang dalam permasalahan aqidah, sebagaimana firman Allah ﷻ:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.” [QS. Al Hujurat/49:15]
Adapun dalam permasalahan fikih maka di antaranya ada yang diketahui secara yakin, dan ada pula yang cukup dengan ghalabtu az-zhan (dugaan kuat). Sehingga dalam permasalahan ibadah, apabila seseorang telah memiliki dugaan kuat terhadap sesuatu maka cukuplah ia beramal dengannya. Karena dalam permasalahan ibadah tidak disyaratkan ilmu yakin dalam setiap kondisi. Banyak permasalahan fikih yang dibangun di atas dugaan, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Akan tetapi itu, bukan dugaan atau persangkaan yang dibangun di atas hawa nafsu yang tercela. Dugaan dan persangkaan yang maksud adalah yang dibangun dengan melihat kepada dalil dan mencermati perkataan para ahli ilmu dan meneliti hujah-hujjah mereka.
Makna Kaidah
Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan di atas bahwa kaidah ini membahas tentang permasalahan ibadah, di mana seseorang cukup dalam mengerjakannya bersandarkan pada dugaan kuat. Karena pemasalahan ibadah berkaitan dengan hak Allah ﷻ sehingga ada sisi keringanan di dalamnya. Berbeda dengan permasalahan muamalat yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka yang menjadi ukuran adalah realitas yang ada, tidak sekadar perkiraan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin rahimahullah dalam Manzhumah Ushulil Fiqhi wa Qawa’idihi:
وَالظَّـــنُّ فِــيْ الْعِـبَــادَةِ الْـمُـعْـتَــبَرُ
وَنَـفْـسَ اْلأَمْــرِ فِــيْ الْعُـقُـوْدِ اعْـتَـبَــرُوْا
Dugaan di dalam ibadah itu sesuatu yang dianggap
Dan realitas perkara itulah yang dianggap dalam akad-akad [1]
Dalil yang Mendasarinya
Banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim tentang tata cara mandi Nabi ﷺ. Aisyah radhiyallahu anha berkata:
حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
“Sehingga ketika beliau ﷺ telah menduga bahwa air sudah membasahi kulit kepalanya maka beliau ﷺ menyiram kepalanya tiga kali.” [2]
Syaikh Khalid bin ’Ali al-Musyaiqih mengatakan: “Hadis ini menjelaskan, bahwa pelaksanan ibadah itu cukup dengan dugaan, sehingga apabila pakaian seseorang terkena najis maka kita katakana, ‘Pakaian itu cukup dicuci sampai muncul dugaan bahwa najisnya hilang’. Demikian pula jika seseorang dalam kondisi yang mewajibkan mandi, seperti janabah, haid, nifas, dan semisalnya, maka yang wajib baginya adalah menyiramkan air ke seluruh badannya sampai muncul dugaan bahwa seluruh badannya telah basah terkena air, jika ia telah menduga bahwa air telah sampai ke seluruh badannya maka itu sudah cukup.” [3]
Demikian pula di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah hadis Asma’ binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, ia berkata:
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
Kami pernah berbuka puasa di zaman Nabi ﷺ saat mendung, kemudian tiba-tiba matahari muncul. [4]
Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sebagian Sahabat berbuka puasa dengan dugaan kuat bahwa matahari telah terbenam. Setelah itu nampak bahwa ternyata matahari belum terbenam. Hal ini menunjukkan bolehnya beramal dengan dugaan kuat. Jika tidak diperbolehkan, tentu Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa.
Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin rahimahullah mengatakan: “Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka mengqadha puasa. Seandainya mengqada’ dalam kondisi itu wajib tentulah Nabi ﷺ memerintahkannya. Dan seandainya Beliau memerintahkan tentulah sudah dinukil untuk kita, karena jika Beliau n memerintahkan pastilah itu termasuk bagian syariat, sedangkan syariat Allah ﷻ senantiasa terjaga.” [5]
Contoh Penerapan Kaidah
Berikut ini beberapa contoh kasus sebagai penjelasan aplikatif dari kaidah yang mulia ini:
Apabila seseorang mencuci baju yang terkena najis sampai muncul dugaan kuat bahwa najis itu telah hilang, maka baju tersebut dihukumi suci, meskipun tanpa sepengetahuannya masih tersisa najis di baju tersebut.
Seseorang yang melaksanakan Salat Zuhur, ketika sudah sampai di Tasyahhud Akhir ia merasa ragu apakah ia telah salat tiga rakaat ataukah empat rakaat, dan ia punya dugaan kuat bahwa salatnya telah sempurna empat rakaat. Maka dalam hal ini yang ia lakukan adalah mengikuti dugaan kuatnya dan menganggap salatnya sempurna empat rakaat, kemudian mengerjakan dua kali Sujud Sahwi setelah salam. Seandainya secara realitas salatnya baru tiga rakaat, maka salatnya tetap sah.
Seseorang yang menyerahkan zakatnya kepada orang yang menurut dugaan kuatnya termasuk berhak menerima zakat, kemudian diketahui bahwa orang itu bukanlah orang yang berhak menerima zakat maka zakatnya sah dan telah gugur kewajibannya, karena ia telah melakukan pembayaran zakat itu sesuai dugaan kuatnya.
Hal ini sebagaimna sabda Nabi ﷺ tentang kisah seorang pembayar zakat:
قاَلَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيُّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ
Seseorang telah berkata: “Sungguh aku akan bersedekah malam ini.” Kemudian ia keluar untuk bersedekah maka ia menyedekahkannya ke tangan seorang pezina. Pada keesokan harinya, orang-orang membicarakan bahwa sedekah telah diberikan kepada pezina. Ia berkata: “Ya Allah ﷻ, segala puji bagi-Mu, sedekahku ternyata jatuh pada pezina, sungguh aku akan bersedekah kembali”. Kemudian ia keluar untuk bersedekah maka ia menyedekahkannya kepada orang kaya. Pada keesokan harinya, orang-orang membicarakan bahwa sedekah telah diberikan kepada orang kaya. Ia berkata: “Ya Allah ﷻ, segala puji bagi-Mu, sedekahku ternyata jatuh pada seorang kaya, sungguh aku akan bersedekah kembali”. Kemudian ia keluar untuk bersedekah maka ia menyedekahkannya kepada pencuri. Pada keesokan harinya, orang-orang membicarakan bahwa sedekah telah diberikan kepada pencuri. Ia berkata: “Ya Allah ﷻ, segala puji bagi-Mu, sedekahku ternyata jatuh pada seorang pezina, orang kaya, dan seorang pencuri”. Maka ia didatangi (dalam mimpi) dan dikatakan padanya, “Adapun sedekahmu maka telah diterima. Adapun pezina mudah-mudahan dengan sebab sedekahmu ia mejaga diri dari perzinaan. Dan mudah-mudahan orang kaya tersebut mengambil pelajaran kemudian menginfakkan harta yang Allah ﷻ berikan kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu pencuri tersebut menjaga diri dari kebiasannya mencuri.” [6]
Seseorang yang berbuka puasa karena menduga matahari telah tenggelam kemudian nampak bahwa ternyata matahari belum tenggelam maka puasanya sah. Akan tetapi wajib baginya untuk kembali berpuasa sejak ia mengetahui belum tenggelamnya matahari sampai matahari benar-benar terbenam.
Apabila seseorang melaksanakan Thawaf di Kakbah dan ia ragu-ragu apakah Thawafnya sudah enam putaran atau tujuh putaran, dan muncul dugaan kuat darinya bahwa ia telah Thawaf sebanyak tujuh putaran, maka yang ia lakukan adalah mencukupkan dengan dugaan kuat tersebut dan menganggap Thawafnya sempurnya tujuh putaran. Hal ini karena dalam permasalahan ibadah cukuplah seseorang bersandar dengan dugaan kuatnya.
Demikian pembahasan singkat dari kaidah ini semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin dan semakin membuka wawasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam agama kita yang mulia ini. [7]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 147.
[2] HR. Al-Bukhari no. 272 dan Muslim 316.
[3] al-‘Aqdu ats-Tsamin fi Syarh Manzhumah Syaikh Ibni ‘Utsaimin, Syaikh Khalid bin ‘Ali al-Musyaiqih, Penjelasan bait ke-35.
[4] HR. Al-Bukhari no. 1959.
[5] Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 149.
[6] HR Muslim no. 1022.
[7] Diangkat dari Tahrir al-Qawa’id wa Majma’ al-Faraid, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-32.
Kaidah Ke-63: Pertengahan Dalam Ibadah Termasuk Sebesar-Besar Tujuan Syariat
Kaidah Keenam Puluh Tiga
الْعَدْلُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ
Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat
Makna Kaidah
Keadilan dan pertengahan adalah ciri menonjol dari agama Islam dan umatnya. Allah ﷻ telah mengkhususkan umat ini dengan syariat yang paling sempurna dan manhaj yang paling lurus. Maka umat Islam senantiasa berada di posisi pertengahan dalam setiap perkara dan setiap sisi kehidupannya.
Syariat agama Islam ini seluruhnya dibangun di atas keadilan dan pertengahan. Itu adalah sebaik-baik dan paling tingginya perkara. Sebagaimana Surga Firdaus adalah Surga tertinggi dan pertengahannya [1], maka barang siapa yang amalannya seperti itu insya Allah tempat kembalinya adalah Surga Firdaus tersebut.
Ibadah termasuk perkara yang wajib dikerjakan secara adil dan pertengahan. Karena berlebih-lebihan dalam ibadah termasuk pelanggaran yang dilarang oleh syariat. Bahkan itu bisa menimbulkan rasa jenuh, terputus dari amalan, dan tidak istiqamah dalam mengerjakannya. Demikian pula, hal itu bisa mengakibatkan gangguan terhadap badan dan kesehatan pelakunya.
Maka yang wajib dalam beribadah adalah mengerjakannya sesuai kemampuannya secara pertengahan dan tidak berlebih-lebihan. Karena itu termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Dan hendaklah seseorang tidak memberikan tekanan kepada dirinya sendiri dengan sesuatu yang melampaui batas sehingga mengakibatkan madharat terhadap agama dan dunianya.
Dalil yang Mendasarinya
Banyak dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik riwayat al-Bukhari dan Muslim, di mana ia berkata:
جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
“Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi ﷺ untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Maka tatkala mereka telah diberitahu, seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah Rasulullah ﷺ itu sedikit. Lalu mereka mengatakan: “Siapa kita dibandingkan dengan Nabi ﷺ? Sesungguhnya Beliau ﷺ telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.” Salah seorang dari mereka berkata: “Adapun saya, maka saya akan salat malam terus menerus (tidak akan tidur).” Dan yang lainnya mengatakan: “Saya akan berpuasa terus selamanya dan tidak akan berbuka.” Yang lainnya lagi mengatakan: “Saya tidak akan menikah selamanya.” Lalu datanglah Rasulullah ﷺ seraya bersabda: “Apakah kalian yang telah mengatakan seperti ini dan itu? Demi Allah ﷻ sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kapada Allah ﷻ dan yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya salat dan saya tidur, dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” [2]
Demikian pula hadis Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash Radhikyallahu anhuma riwayat al-Bukhari dan Muslim:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنها ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» ، فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ» ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: «نِصْفَ الدَّهْرِ» ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Dari Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku, “Wahai Abdullah, apakah benar berita bahwa engkau berpuasa di waktu siang lalu salat malam sepanjang malam?” Saya menjawab: “Benar, wahai Rasulullah ﷺ ”. Beliau ﷺ bersabda: “Janganlah engkau lakukan itu, tetapi berpuasa dan berbukalah! Salat malam dan tidurlah! karena badanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, matamu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, dan tamumu pun punya hak yang harus engkau tunaikan. Cukuplah bila engkau berpuasa selama tiga hari setiap bulan, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu berarti engkau telah melaksanakan puasa sepanjang tahun”. Kemudian saya meminta tambahan, lalu beliau menambahkannya. Saya mengatakan: “Wahai Rasulullah ﷺ, saya merasa diriku memiliki kemampuan”. Maka beliau ﷺ bersabda: “Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah Dawud Alaihissallam dan jangan engkau tambah lebih dari itu”. Saya bertanya, “Bagaimanakah cara puasanya Nabi Dawud Alaihissallam?” Beliau ﷺ menjawab: “Beliau berpuasa setengah dari puasa dahr (puasa sepanjang tahun). Maka setelah Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash sampai di usia tua ia berkata: “Seandainya dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi ﷺ ” [3]
Dan hadis Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:
عَنْ بُرَيْدَةَ اْلأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ n: عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ
Dari Buraidah al-Aslami Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Hendaklah kalian mengikuti petunjuk dan beramal sewajarnya (tidak berlebih-lebihan). Sesungguhnya barang siapa yang memperberat diri dalam agama ini pasti dia akan kalah.” [4]
Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa yang disyariatkan, diperintahkan dan dicintai oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya adalah sikap pertengahan dan adil dalam ibadah. Amalan ibadah yang keluar dari batasan ini maka itu adalah perkara yang tercela dan menyelisihi syariat. [5]
Contoh Penerapan Kaidah
Banyak contoh kasus yang masuk dalam aplikasi kaidah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:
Seseorang yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah, seperti berpuasa terus-menerus, atau salat malam terus-menerus,sehingga menyebabkan badannya lemah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka ia telah berbuat kesalahan, berdosa, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. [6]
Apabila mengerjakan ibadah sunnah sampai tidak bisa mencari rezeki yang wajib, atau mencari ilmu yang wajib, atau menyebabkannya meninggalkan jihad yang wajib, maka ketika itu tidak diperbolehkan baginya mengerjakan ibadah sunnah tersebut. [7]
Apabila seseorang mengerjakan suatu amalan ibadah, namun menyebabkan ia terjatuh dalam kondisi yang haram, di mana maslahat yang ada dalam peribadahan itu tidak bisa menandingi keburukan yang timbul, maka haram baginya mengerjakan peribadahan itu. Misalnya seperti orang yang mengeluarkan semua hartanya untuk disedekahkan, namun kemudian ia meminta-minta kepada manusia. [8]
Apabila memperbanyak amalan ibadah mengakibatkan seseorang jatuh dalam perkara yang makruh, maka itu adalah perkara yang makruh juga. Hal ini seperti orang yang mengerjakan suatu amalan ibadah namun mengakibatkannya lemah dari mengerjakan amalan yang lebih maslahat. [9]
Demikian pembahasan singkat kaidah ini, semoga bermanfaat. [10]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam Kitab al-Jihad wa as-Sair, no. 2790 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu
[2] HR. Al-Bukhari dalam Kitab an-Nikah, no. 5063. Muslim dalam Kitab an-Nikah, no. 1401
[3] HR. al-Bukhari dalam Kitab as-Shaum, no. 1975. Muslim dalam Kitab as-Shiyam,, no. 183.
[4] HR. Ahmad dalam al-Musnad 5/361.
[5] Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa memperbanyak amal peribadahan adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak makruh. Kemudian mereka menyebutkan beberapa syarat dalam memperbanyak amal ibadah tersebut, sehingga sampai ke tingkatan pertengahan di dalamnya. Maka mereka mempersyaratkan kepada orang yang memperbanyak amalan ibadah: Hendaknya hal itu tidak menyebabkan kejenuhan, tidak memberatkan diri di luar kemampuannya, tidak menyebabkan meninggalkan perkara yang lebih penting, dan syarat-syarat lainnya. Keberadaan syarat-syarat tersebut memastikan pelaksanaan ibadah dilakukan secara pertengahan. Lihat kitab Iqamatul Hujjah ‘ala Anna al-Iktsar min at-Ta’abbud Laisa Bidah, karya ‘Abdul Hayyi al-Laknawi.
[6] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 22/136.
[7] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 25/272.
[8] Lihat Majmu’ al-Fatawa, 25/273.
[9] Idem.
[10] Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Maiman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, Hlm. 188-192.
Kaidah Ke-64: Kemakruhan Hilang Karena Hajat
Kaidah Keenam Puluh Empat
الْكَرَاهَةُ تَزُوْلُ بِالْحَاجَةِ
Kemakruhan hilang karena hajat
Makna Makruh dan Hajat
Makruh dan haram termasuk hukum-hukum syari yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf. Keduanya mengandung makna larangan yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam. Allah ﷻ Yang Maha Mengetahui tahu bahwa seorang Mukallaf tidak mampu terus-menerus meninggalkan perkara yang dilarang dalam setiap kondisi dan situasi. Maka Allah ﷻ menjadikan keadaan dharurat (terpaksa) dan hajat, dua sebab gugurnya hukum perkara yang dilarang.
Makruh menurut istilah para Fuqaha maknanya adalah larangan terhadap suatu perbuatan tanpa adanya ilzam (keharusan) untuk ditinggalkan. Hukumnya adalah orang yang meninggalkan perkara makruh dalam rangka imtitsal (mentaati perintah Allah ﷻ ) maka ia mendapatkan pahala, dan orang yang mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. [1]
Adapun yang dimaksud dengan hajat adalah suatu keadaan yang dimana seseorang harus melakukan sesuatu,jika dia tidak melakukannya, maka dia akan terjatuh dalam kesempitan dan kesulitan meskipun tidak sampai membahayakan kemaslahatannya yang bersifat dharuri (pokok). [2] Jadi, hajat itu tingkatannya di bawah dharurat, akan tetapi terkadang mendapatkan hukum dharurat dalam beberapa keadaan dan menggugurkan hukum haram.
Makna Kaidah
Sebagaimana telah diisyaratkan dalam penjelasan di atas bahwa kaidah yang sedang kita bahas ini membahas tentang hajat yang bisa menggugurkan hukum makruh. Di mana apabila dalam suatu kondisi seseorang mempuyai hajat untuk mengerjakan suatu perkara yang dilarang dalam syariat dengan larangan yang tidak sampai pada ilzam (keharusan), maka ketika itu kemakruhan dalam perkara tersebut gugur dalam rangka memerhatikan hajat hamba tersebut.
Syaikh Muhammad bin Saleh Al ‘Utsaimin mengatakan dalam Manzhumah Ushulil Fiqhi wa Qawa’idihi:
وَكُــلُّ مَـمْـنُوْعٍ فَـلِلـضَّرُوْرَةِ يُـبَاحُ وَالْمَـكْـرُوْهُ عِـنْـدَ الْحَـاجَـةِ
Dan setiap larangan diperbolehkan karena dharurah
Dan perkara makruh diperbolehkan karena hajat [3]
Beliau menjelaskan bait tersebut dengan mengatakan: “Perkara yang makruh boleh dilakukan jika ada hajat, karena perkara yang makruh tingkatannya berada di bawah perkara haram. Perkara haram dilarang secara ilzam (wajib ditinggalkan) dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan perkara makruh dilarang secara aulawiyyah (keutamaan), dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman, oleh karena itu diperbolehkan ketika adanya hajat.” [4]
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh aplikasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Memejamkan mata ketika salat termasuk perkara yang makruh. [5] Namun jika ia melakukannya karena ada hajat seperti bisa membantunya untuk khusyuk maka itu diperbolehkan. [6]
Menoleh ketika salat termasuk perkara yang makruh, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:
هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ
“Itulah pencurian yang dilakukan setan dari salat seorang hamba.” [7]
Namun apabila seseorang menoleh karena adanya hajat maka hal itu diperbolehkan, seperti seseorang yang menoleh untuk meludah ke sebelah kirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا
Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah melihat dahak di arah Kiblat (dinding masjid). Beliau merasa terganggu dengannya hingga terlihat di wajah beliau. Lalu beliau berdiri dan menggosoknya dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri dalam salatnya maka ia sedang bermunajat kepada Rabbnya -atau Rabbnya berada di antara dia dan Kiblat-, maka janganlah ia meludah ke arah Kiblat. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya.” Lalu beliau memegang ujung selendangnya dan meludah padanya, kemudian menggosok-gosokkan kainnya tersebut. Setelah itu beliau bersabda: “Atau melakukan yang seperti ini.” [8]
Demikian pula jika ia menoleh untuk memastikan keberadaan barang bawaannya ketika khawatir hilang, atau menoleh untuk melihat anaknya jika dikhawatirkan akan jatuh ke lubang atau semisalnya. [9]
Mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa termasuk perkara yang makruh. Namun apabila ada hajat untuk melakukannya maka hal itu diperbolehkan. [10]
Gerakan yang ringan di dalam salat selain dari kemaslahatan salat diperbolehkan apabila ada hajat untuk melakukannya [11], sebagaimana Nabi ﷺ ketika salat pernah menggendong cucu beliau Umamah binti Zainab dan meletakkannya ketika sujud. Disebutkan dalam hadis Abu Qatadah al Anshari:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah salat dengan menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah ﷺ, dari suaminya Abul ‘Ash bin Rabi’ah bin Abdus Syams. Apabila Nabi ﷺ sujud, beliau letakkan Umamah dan jika berdiri, beliau menggendong Umamah lagi.” [12]
Apabila seseorang sedang melaksanakan salat sunnah, kemudian ia mendengar seseorang memanggilnya, tapi ia belum tahu pasti orang yang memanggil itu; Apakah ayahnya, ibunya, atau orang lain? Lalu ia menoleh untuk meyakinkan diri maka itu diperbolehkan. Karena dalam kondisi tersebut apabila yang memanggil adalah ayahnya atau ibunya, maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan. [13]
Demikian pembahasan singkat dari kaidah ini semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin dan semakin membuka wawasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam agama kita yang mulia ini. [14]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Lihat al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, hlm. 58
[2] Lihat al-Muwafaqat karya as-Syathibi 2/10, al-Mahshul karya ar-Razi 2/222, Irsyad al-Fuhul karya as-Syaukani hlm. 216, Raf’u al-Haraj fi as-Syariah al-Islamiyyah karya Dr. Ya’qub Aba Husain, hlm. 600.
[3] Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, Hlm. 59.
[4] Idem, Hlm. 62.
[5] Sebab makruhnya adalah menyerupai perbuatan orang-orang majusi ketika beribadah kepada matahari dan bulan. Ada pula yang mengatakan bahwa sebab makruhnya karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, padahal Nabi ﷺ melarang kita dari menyerupai orang-orang kafir. (Lihat Lihat al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, hlm. 59).
[6] Lihat ar-Raudh al-Murbi’ bi Syarh Zad al-Mustaqni’ karya Manshur al-Buhuthi, hlm. 55
[7] HR. Al-Bukhari no. 751
[8] HR. Al-Bukhari no 405 dan Muslim no. 551
[9] Namun yang dimaksud menoleh di sini adalah menoleh yang sifatnya ringan. Adapun jika seseorang menoleh dengan seluruh badannya atau sampai membelakangi Kiblat, maka itu membatalkan salat, kecuali jika dilakukan karena uzur berupa ketakutan yang sangat dan semisalnya. (Lihat al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, hlm. 58)
[10] Lihat ar-Raudh al-Murbi’ bi Syarh Zad al-Mustaqni’ karya Manshur al-Buhuthi, hlm. 127.
[11] Lihat at-Ta’liq ‘ala al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa at-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah, karya Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Hlm. 337-338.
[12] HR. Al-Bukhari no. 494, dan Muslim no. 543.
[13] Yaitu jika ia tidak mengetahui apakah orang tuanya rida atau tidak jika ia tidak memenuhi panggilannya. (Lihat Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawa’idihi, Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin, hlm. 63
[14] Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Maiman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 302-303
Kaidah Ke-65: Mengamalkan Dua Dalil Sekaligus Lebih Utama
Kaidah Keenam Puluh Lima
إِعْمَالُ الدَّلِيْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا مَا أَمْكَنَ
Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan
Makna Kaidah
Kaidah ini menjelaskan patokan yang harus dipegang ketika kita menemui dua dalil yang nampaknya berseberangan atau bertentangan. Maka sikap kita adalah menjamak dan menggabungkan dua dalil tersebut selama masih memungkinkan. Karena keberadaan dalil-dalil itu untuk diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali berdasarkan dalil yang lain. Jadi hukum asalnya adalah tetap mengamalkan dalil tersebut.
Cara Menyikapi Pertentangan Dalil
Apabila ada dua dalil yang nampaknya berseberangan maka ada tiga alternatif dalam menyikapinya.
Pertama: Kita menjamakkan dan mengkompromikan keduanya dengan mengkhusukan yang umum atau memberikan taqyid kepada yang mutlaq. Ini dilakukan apabila memang hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkin, maka berpindah ke alternatif
Kedua: Yaitu dengan an-naskh. Alternatif ini dilakukan dengan mencari dalil yang datangnya lebih akhir lalu kita jadikan sebagai nasikh (penghapus) kandungan dalil yang datang lebih awal. Jika tidak memungkinkan juga, maka kita menempuh alternatif
Ketiga: Yaitu kita menTarjih dengan memilih salah satu dari dua dalil tersebut mana yang lebih kuat. [1]
Alternatif pertama lebih didahulukan daripada alternatif kedua karena dengan menjamak berarti dua dalil tersebut telah diamalkan dalam satu waktu. Ini lebih utama daripada mengamalkan dua dalil tersebut dalam waktu yang berbeda. Kita mendahulukan alternatif kedua daripada alternatif ketiga karena an-naskh sebenarnya juga mengamalkan dua dalil tersebut hanya saja bukan pada waktu yang bersamaan, tetapi pada waktu yang berbeda. Dalil yang dimansukh (dihapus hukumnya) diamalkan sebelum naskh, dan dalil yang menghapus diamalkan setelah naskh. Jadi, dalil yang mansukh tidak ditinggalkan secara mutlak, ia diamalkan pada waktunya sebelum dinaskh karena ia juga dalil Shahih. Adapun Tarjih maka hakikatnya adalah membatalkan salah satu dalil secara utuh dan diyakini tidak boleh diamalkan mutlak, tidak pada masa silam ataupun sekarang. Oleh karena itulah para ulama menjadikannya alternatif setelah an-naskh. [2]
Contoh Penerapan Kaidah
Berikut ini beberapa contoh kasus sebagai penjelasan aplikatif dari kaidah ini:
Dalam sebagian ayat dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bisa memberikan hidayah, sebagaimana firman Allah ﷻ:
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” [QS. asy-Syura/42:52]
Namun di ayat lain disebutkan bahwa beliau ﷺ tidak bisa memberikan hidayah, yaitu dalam firman-Nya:
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki.” [QS. Al-Qashash/28: 56]
Untuk menggabungkan kedua ayat tersebut maka kita katakana, bahwa hidayah yang dimaksudkan pada ayat pertama adalah hidayah (petunjuk) untuk mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran. Ini yang bisa dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sedangkan hidayah yang dimaksudkan pada ayat kedua adalah petunjuk dalam arti Taufik supaya seseorang mau menerima kebenaran. Hidayah ini semata-mata menjadi hak Allah ﷻ, tidak dimiliki oleh Nabi ﷺ maupun orang lain. [3]
Disebutkan dalam hadis Busrah binti Shafwan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
“Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu.” [4]
Namun dalam hadis lain disebutkan, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Dalam hadis Thalq bin ‘Ali Radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika salat, apakah ia wajib berwudhu, maka Rasulullah ﷺ menjawab:
لاَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ
Tidak, sesungguhnya kemaluan itu bagian anggota tubuhmu. [5]
Maka dua dalil tersebut digabungkan dengan penjelasan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu menyentuh tanpa penghalang [6] dan dilakukan dengan syahwat. Adapun jika tidak terpenuhi dua syarat tersebut maka menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu.
Menyentuh secara langsung tanpa penghalang membatalkan wudhu berdasarkan hadis Abu Hurairah Radhiyallah anhu. Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُوْنَهَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ
“Barang siapa menyentuh kemaluannya dengan tangannya, sedangkan antara sentuhan dan kemaluannya tidak dihalangi sesuatu pun, maka ia wajib berwudhu.” [7]
Adapun dipersyaratkan adanya syahwat dikarenakan menyentuh kemaluan tanpa syahwat adalah seperti menyentuh tangan, hidung, dan semisalnya yang tentu saja tidak membatalkan wudhu, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Thalq bin ‘Ali di atas. [8]
Inilah pendapat yang yang rajih, karena mengamalkan semua dalil yang ada, tanpa meninggalkan satu dalil pun, tanpa naskh ataupun Tarjih. Inilah yang lebih utama karena mengkompromikan dalil-dalil yang ada itu lebih utama selama masih memungkinkan.
Pendapat yang rajah (kuat), orang-orang kafir itu najis ditinjau dari i’tiqadnya (keyakinannya) bukan dari sisi lahiriyahnya. Pendapat ini diambil karena menggabungkan firman Allah ﷻ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.” [QS. At Taubah/9:28]
Dengan firman Allah ﷻ:
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka.” [QS. al-Maidah/5:5]
Ayat pertama di atas menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu najis, sedangkan ayat kedua menunjukkan mereka tidak najis karena makanan (sembelihan) mereka halal bagi kita, dan wanita-wanita mereka pun boleh dinikahi. Oleh karena itu, dalil yang menunjukkan kenajisan orang kafir dimaknai dengan kenajisan dari sisi keyakinan. Adapun dalil yang menunjukkan ketidak najisan mereka dimaknai dari sisi lahiriyah mereka. Dengan demikian kedua dalil tersebut bisa kompromikan, tanpa meninggalkan sebagiannya. [9]
Demikian pembahasan kaidah ini, semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin sekalian. [10]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan Tarjih, di mana tidak ditemukan sarana untuk merajihkan (menguatkan) salah satu dari dua dalil tersebut, maka sikap kita adalah Tawaqquf. Namun tidak ada contoh yang Shahih dalam kasus seperti ini. (Lihat al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul, Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1424 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, hlm. 77).
[2] Lihat penjelasan berkaitan dengan hal ini dalam as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh Al ‘Utsaimin, Cetakan I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil Jauzi, Damam, I/281-282.
[3] Lihat al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul, Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, hlm. 75.
[4] HR. Abu Dawud no. 181, an-Nasa-i no. 163, at-Tirmidzi no. 82 ia berkata: “Ini hadis hasan Shahih.” Ibnu Majah no. 4479. Hadis ini diShahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil 1/150.
[5] HR. Abu Dawud no. 182, at-Tirmidzi no. 85, an-Nasa-i no. 165, Ibnu Majah no. 483. Hadis ini diShahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/334.
[6] Lihat as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh Al ‘Utsaimin, I/278.
[7] HR. Ahmad 2/333, Ibnu Hibban 1118, ad_daruquthni 1/147, al-Baihaqi 2/131. Hadis ini diShahihkan oleh al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu ‘Abdil Bar, dan An Nawawi. (Lihat as-Syarh al-Mumti’ 1/279).
[8] Lihat penjelasan tentang hal ini dalam as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, I/282.
[9] Lihat penjelasan tentang hal ini dalam as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zaad al-Mustaqni’, I/448.
[10] Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, kaidah ke-20.
Kaidah Ke-66: Niat Dalam Sumpah Membuat Lafal Yang Umum Menjadi Khusus
Kaidah Keenam Puluh Enam
النِّيَّةُ فِي الْيَمِيْنِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَتُعَمِّمُ اللَّفْظَ الْخَاصَّ
Niat dalam sumpah membuat lafal yang umum menjadi khusus dan lafal khusus menjadi umum
Makna Lafdziyah
Kaidah ini terdiri atas beberapa kata yang perlu kita fahami maknanya. Kata yamin maknanya sumpah. Dinamakan demikian karena kebiasaan yang ada, ketika seseorang besumpah maka akan disertai dengan saling berjabat tangan dengan tangan kanan. Sedangkan makna secara syari adalah suatu akad yang berfungsi menguatkan kesungguhan dalam mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Oleh karena itu, sumpah dalam pembahasan ini tidaklah terbatas dalam sumpah dengan nama Allah ﷻ semata, akan tetapi juga mencakup permasalahan thalaq (perceraian), ‘ithq (pembebasan budak), ila’ [1] dan semisalnya.
Kata al-‘am maksudnya adalah lafal yang mencakup seluruh satuannya tanpa ada pembatasan. [2] Sebaliknya, kata al-khash maksudnya adalah lafal yang menunjukkan kepada satu perkara baik bersifat satuan atau jenis. Sedangkan kata at-takhshish maksudnya membatasi lafal umum pada sebagian anggotanya. [3]
Makna Kaidah Secara Umum
Kaidah ini menjelaskan bahwa niat memiliki pengaruh dan peran dalam sumpah. Apabila seseorang bersumpah dengan lafal yang umum dan ia meniatkannya dengan sesuatu yang khusus, maka niatnya itu menjadkan lafalh yang umum tersebut bermakna khusus, dan sumpah yang diucapkan dihukumi sesuai apa yang ia niatkan. Demikian pula sebaliknya, apabila ia mengucapkan lafal khusus dan ia meniatkan sesuatu yang bersifat umum maka niat itu menjadikan lafal khusus tersebut bermakna umum, dan yang danggap dan diterapkan adalah apa yang ia niatkan itu. [4]
Secara umum kaidah ini terdiri atas dua bagian. [5]
Pertama: Peran niat dalam mengkususkan sesuatu yang bersifat umum. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama
Kedua: Peran niat dalam menjadikan sesuatu yang khusus menjadi umum. Ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan sebagain Hanafiyah menetapkannya. Mereka berpendapat bahwa niat berperan dalam menjadikan lafal khusus menjadi umum, sebagaimana niat juga menjadikan lafal umum menjadi khusus. Adapun ulama Syafi’iyah dan sebagian Hanafiyah menolak hal tersebut sehingga lafal kaidah ini menurut mereka adalah (النِّيَّةُ فِي الْيَمِيْنِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلاَ تُعَمِّمُ الْخَاصَّ).
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh aplikatif penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut:
Apabila seseorang mengucapkan sumpah untuk tidak mengajak bicara seorang pun. Ketika bersumpah, niatnya adalah tidak mau berbicara dengan Zaid saja. Jika kemudian ia mengajak bicara kepada seseorang selain Zaid maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Dalam hal ini, meskipun sumpahnya bersifat umum namun telah dikhususkan dengan niatnya. [6]
Apabila seseorang bersumpah untuk tidak makan daging. Dan ketika bersumpah niatnya adalah tidak makan daging unta saja. Jika kemudian ia makan selain daging unta, seperti daging ayam atau kambing maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Dalam kasus ini, meskipun sumpahnya bersifat umum namun telah dikhususkan dengan niatnya.
Apabila seorang laki-laki mempunyai beberapa istri, dan ia berkata: “Seluruh istriku aku ceraikan.” Ketika mengucapkan lafal tersebut, dalam hatinya ia mengecualikan salah satu istrinya. Berdasarkan kaidah ini maka istri yang dikecualikan tersebut tidak dihukumi diceraikan. Meskipun lafal yang ia ucapkan itu bersifat umum, namun telah dikuhususkan dengan niat yang ada dalam hatinya. [7]
Apabila seseorang bersumpah untuk tidak meminum air milik si Fulan. Ketika bersumpah niatnya adalah tidak memanfaatkan air tersebut untuk keperluan apapun. Jika kemudian ia memanfaatkan air tersebut selain meminumnya, seperti menggunakannya untuk mandi, mencuci pakaian dan semisalnya, maka berdasarkan kaidah ini ia dihukumi telah melanggar sumpahnya. Meskipun lafal sumpahnya bersifat khusus, yaitu hanya berkaitan dengan minum saja, namun telah menjadi umum dengan niatnya. Di mana niat berpengaruh untuk menjadikan lafal khusus menjadi bermakna umum. Hal ini sesuai dengan yang dianut dalam madzhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah.
Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan sebagian Hanafiyah, orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpah kecuali apabila minum dari air itu. Dan tidak dihukumi melanggar sumpahnya jika ia memanfaatkan untuk keperluan lain seperti mandi, mencuci pakaian, memasak makanan, dan semisalnya. Karena menurut pendapat kedua ini, niat tidak berperan dalam menjadikan lafal khusus manjadi umum di dalam sumpah. [8]
Apabila seseorang bersumpah untuk tidak menemui beberapa orang di rumah mereka. Ketika bersumpah ia berniat untuk menjauhi orang-orang tersebut dan tidak menemui mereka di mana saja. Jika kemudian ia menemui orang-orang tersebut di suatu tempat selain rumah mereka, maka berdasarkan kaidah ini ia telah melanggar sumpahnya. Meskipun lafal sumpah tersebut bersifat khusus namun telah menjadi umum dengan niatnya. Inilah yang ditetapkan dalam madzhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah.
Adapun menurut madzhab Syafi’iyah dan sebagian Hanafiyah, orang tersebut tidaklah melanggar sumpahnya kecuali jika menemui orang-orang tersebut di rumah mereka secara khusus, dan tidak dihukumi melanggar sumpahnya kalau ia menemui mereka di tempat lain karena niat tidak berperan dalam menjadikan lafal khusus menjadi umum di dalam sumpah. [9]
Wallahu a’lam. [10]
_______
Footnote
[1] Yang dimaksud dengan ila’ adalah apabila seorang suami bersumpah dengan nama Allah ﷻ atau dengan salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya diqubulnya selama-lamanya, atau selama lebih dari empat bulan, sedangkan si suami mampu untuk menggaulinya. (Lihat Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, Nukhbah min al-‘Ulama, 1424 H, Majma’ al-Malik Fahd li Taba’at al-Mus-haf as-Syarif, al-Madinah al-Munawwarah, hlm. 318).
[2] Al-Ushul min ‘Ilmi al-Ushul, Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, Cetakan Pertama, Tahun 1424 H, Dar Ibn al-Jauzi, Damam, hlm. 34.
[3] Lihat al-Mufasshal fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Dr. Ya’qub bin Abdul Wahhab al-Bahisin, Cet. II, Tahun 1432 H/2011 M, Dar at-Tadmuriyyah, Riyadh,Hlm. 184.
[4] Lihat pembahasan kaidah ini dalam Qawanin al-Ahkam as-Syariyyah, hlm. 156. Al-Asybah wa an-Nazha-ir, karya Ibnu as-Subki, 1/69-72. Taqrir al-Qawa’id wa Tahrir al-Fawa-id, hlm. 279-283. Al-Asybah wa an-Nazha-ir, karya as-Suyuthi, hlm. 105. Al-Asybah wa an-Nazha-ir, karya Ibnu an-Nujaim, hlm. 56. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, hlm. 152-155.
[5] Lihat juga pembahasan tentang hal ini dalam Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al Burnu, Cetakan Keempat, Tahun 1416 H/1996 M, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlm. 152-153.
[6] Lihat Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, hlm. 153.
[7] Lihat al-Mufasshal fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Dr. Ya’qub bin Abdul Wahhab al-Bahisin, Cet. II, Tahun 1432 H/2011 M, Dar at-Tadmuriyyah, Riyadh,Hlm. 187.
[8] Lihat Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah, hlm. 153.
[9] Lihat al-Mufasshal fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, hlm. 187.
[10] Diangkat dari kitab al-Mumti’ fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Dr. Musallam bin Muhammad bin Majid ad-Dausriy, Cetakan Pertama, Tahun 1428 H/2007 M, Dar Zidni, Riyadh, Hlm. 91-94.
Kaidah Ke-67: Mengejar Ibadah Yang Jika Terlewat Tidak Ada Badalnya
Kaidah Ke Enam Puluh Tujuh
إِدْرَاكُ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَفُوْتُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْلَى مِنْ إِدْرَاكِ مَايَفُوْتُ إِلَى بَدَلٍ
Mengejar ibadah yang jika terlewat tidak ada badalnya lebih utama daripada mengejar ibadah yang ada badalnya
Makna Kaidah
Sebelum membahas lebih jauh tentang kaidah ini, perlu kita ketahui bahwa suatu ibadah apabila terlewat dan tidak dikerjakan, maka tidak lepas dari dua keadaan. Adakalanya ibadah itu yang terlewat itu ada pengganti (badal), dan adakalanya tidak ada penggantinya. Dan hukum asal suatu ibadah itu adalah tidak ada penggantinya kecuali jika ada dalil Shahih yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut memiliki pengganti. Sehingga apabila ada dua ibadah berbarengan seperti ini dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka kita harus memilih salah satunya untuk diamalkan. Di antara yang menjadi pertimbangan dalam memilih satu dari dua amalan yang berbarengan tersebut adalah dengan melihat manakah di antara keduanya yang memiiliki pengganti? Lalu kita pilih amalan yang tidak ada penggantinya untuk kita amalkan.
Kaidah ini menjelaskan pedoman dalam memilih antara dua amalan ibadah yang berbarengan dalam satu waktu dan tidak memungkin kita untuk mengamalkan keduanya. Jika dua amalan tersebut salah satunya memiliki pengganti dan yang lainnya tidak, maka kita pilih dan kita dahulukan amalan yang tidak ada penggantinya. [1] Karena amalan yang ada pengantinya apabila terluput maka sesungguhnya maslahat amalan tersebut tidak hilang begitu saja, namun maslahatnya bisa tergantikan oleh badal (pengganti)nya. Adapun ibadah yang tidak ada penggantinya jika luput dan tidak dikerjakan maka maslahatnya hilang total karena tidak ada penggantinya.
Dalil Yang Mendasarinya
Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah keumuman ayat-ayat dalam Alquran yang menjelaskan anjuran menTarjihkan di antara maslahat-maslahat yang ada. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
“Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik.” [QS. Az-Zumar/39:18]
Dan firman Allah ﷻ:
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.” [QS. Az Zumar/39:55]
Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang anjuran mengejar dan mendapatkan kemaslahatan yang tertinggi dan kebaikan yang terbesar kemudian baru mencari kemaslahatan yang tinggi. [2]
Contoh Penerapan Kaidah
Aplikasi dan penerapan kaidah ini bisa kita lihat dalam contoh-contoh kasus berikut:
Apabila seseorang sedang membaca Alquran, kemudian terdengar azan. Dalam kondisi terkumpul dua ibadah dalam waktu bersamaan, yaitu membaca Alquran dan menjawab azan. Timbul permasalahan, apakah ia meneruskan bacaannya ataukah menjawab azan tersebut? Jika diperhatikan, ibadah membaca Alquran jika terlewat maka masih ada penggantinya, yaitu bisa ia lakukan setelah azan. Adapun menjawab azan jika terluput maka tidak ada penggantinya. Dengan demikian dalam kasus ini, yang lebih utama baginya adalah menghentikan bacaan Alquran untuk menjawab azan, karena ibadah yang terlewat tanpa adanya pengganti lebih utama untuk dipilih dan didahulukan.
Telah maklum bahwa salat sunnah lebih utama jika dikerjakan di rumah. Namun, apabila dikerjakan di rumah menyebabkannya terluput dari shaf pertama di masjid maka dalam hal ini hendaknya ia melaksanakan salat sunnah tersebut di masjid. Karena salat sunnah tersebut jika tidak ia kerjakan di rumah maka ada penggantinya yaitu bisa ia kerjakan di masjid, adapun shaf pertama jika ia terluput darinya maka tidak ada penggantinya.
Seseorang yang tinggalnya jauh dari Mekah, ketika ia datang ke Masjidil Haram, timbul pertanyaan apakah yang terbaik baginya memperbanyak salat sunnah ataukah memperbanyak Thawaf. Jika kita perhatikan, apabila seseorang terluput dari melaksanakan salat sunnah maka ada penggantinya, yaitu bisa dilakukan ketika ia kembali ke negerinya, dan tidak dipersyaratkan harus dilaksanakan di Masjidil Haram. Adapun Thawaf maka tidak bisa dilakukan kecuali di Masjidil Haram, dan tidak ada Thawaf kecuali di Kakbah. Apabila seseorang terlewat darinya maka tidak ada penggantinya. Oleh karena itu, bagi orang yang berasal dari tempat yang jauh dari Mekah, memperbanyak Thawaf di Kakbah lebih utama baginya daripada memperbanyak salat sunnah di sana, karena salat jika terlewat maka ada penggantinya, adapun Thawaf maka tidak ada penggantinya.
Bagi orang yang tinggal di Mekah mengikuti salat Tarawih lebih utama baginya daripada melaksanakan ibadah Thawaf. Hal ini dikarenakan salat Tarawih apabila terluput maka tidak ada penggantinya. Adapun ibadah Thawaf apabila terluput maka bisa ia lakukan kapan saja di waktu lain karena ia tinggal di Mekah. Dan contoh kasus ini merupakan kesebalikan dari contoh sebelumnya.
Apabila seseorang sedang berpuasa lalu ia menemui orang lain yang jiwanya terancam bahaya, baik tenggelam, terbakar atau semisalnya, dan ia tidak bisa menyelamatkan orang itu kecuali dengan membatalkan puasanya, maka timbul permasalahan apakah yang ia pilih meneruskan puasanya ataukah menyelamatkan orang tersebut. Jika kita perhatikan, maka ibadah puasa apabila terluput maka ada penggantinya yaitu bisa diqadha di waktu lainnya. Adapun nyawa seseorang jika hilang maka tidak ada penggantinya. Maka dalam kasus ini yang ia pilih adalah maslahat menjaga jiwa seorang Muslim karena tidak ada penggantinya, daripada maslahat berpuasa, karena maslahatnya bisa digantikan.
Seseorang yang berada pada cuaca yang sangat dingin diperbolehkan baginya untuk berTayammum, apabila bersuci menggunakan air membahayakannya. Hal ini karena bersuci dengan air ada penggantinya yaitu bersuci dengan debu (Tayammum), adapun jiwa seseorang tidaklah ada penggantinya. Sehingga lebih diutamakan perkara yang tidak ada penggantinya daripada perkara yang ada penggantinya.
Demikian pembahasan singkat kaidah ini. Semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin sekalian.
Wallahu a’lam. [3]
_______
Footnote
[1] Lihat pembahasan kaidah ini dalam Majmu’ al-Fatawa, 23/312-313.
[2] Lihat al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Maiman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 279.
[3] Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-40.
Kaidah Ke-68: Disyariatkan Meninggalkan Perbuatan Yang Tidak Dilakukan Nabi
Kaidah Keenam Puluh Delapan
كُلُّ فِعْلٍ تَوَفَّرَ سَبَبُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَالْمَشْرُوْعُ تَرْكُهُ
Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi ﷺ namun beliau ﷺ tidak mengerjakan perbuatan tersebut maka yang disyariatkan adalah meninggalkan perbuatan (yang tidak dilakukanoleh Nabi) itu.
Perbuatan Nabi ﷺ termasuk rujukan dalam penetapan hukum syari, apabila beliau ﷺ mengerjakan perbuatan tersebut dalam rangka pensyariatan. Demikian juga, apa yang beliau ﷺ tinggalkan pun menjadi rujukan dalam pensyariatan. Dan kaidah yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan apa-apa yang beliau ﷺ tinggalkan tersebut.
Kaidah ini menjelaskan bahwa perbuatan yang seharusnya bisa dan mudah dikerjakan oleh Nabi ﷺ, namun beliau ﷺ tidak melakukannya tanpa unsur paksaan, maka kita juga harus meninggalkan perbuatan itu dalam rangka beribadah kepada Allah ﷻ. Karena apabila perbuatan tersebut disyariatkan tentu Nabi ﷺ tidak meninggalkannya.
Sesungguhnya Nabi ﷺ telah menyampaikan syariat kepada umatnya dengan tuntas dan jelas. Allah ﷻ juga telah menyempurnakan agama ini dengan perantaraan Nabi-Nya. Sehingga tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau ﷺ telah menunjukkannya, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau ﷺ telah memeringatkan umat darinya. Oleh karena itu, tindakan beliau ﷺ yang meninggalkan suatu perbuatan itu juga merupakan salah satu bentuk pensyariatan sebagaimana tindakan beliau ﷺ yang mengerjakan sesuatu. Sebagaimana kita mengikuti beliau ﷺ dalam perbuatan Beliau ﷺ maka kita juga mencontoh beliau ﷺ dengan meninggalkan apa yang Beliau ﷺ tinggalkan, terutama perbuatan yang beliau ﷺ mampu mengerjakannya namun ternyata beliau tinggalkan padahal tidak ada yang menghalangi beliau dari melakukannya. Karena beliau adalah contoh, suri teladan dan pemimpin kita. Allah ﷻ berfirman:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [QS. Al-Ahzab/33:21]
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini, “Maka keteladanan yang baik itu ada pada diri Rasul ﷺ, sesungguhnya orang yang mengikuti beliau ﷺ telah menempuh jalan yang mengantarkan kepada kemuliaan di sisi Allah ﷻ, dan itulah jalan yang lurus.” [1]
Kaidah ini bisa diaplikasikan dalam banyak permasalahan. Berikut ini sekadar beberapa contoh darinya
Sebagian pengikut tarekat shufiyah dan pengagung kuburan mendakwakan bahwa Thawaf di sekitar kuburan termasuk ibadah yang disyariatkan. Kita katakan bahwa di zaman Nabi ﷺ telah ada kuburan, bahkan beliau ﷺ melakukan ziarah kubur, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Akan tetapi beliau ﷺ tidak pernah Thawaf (mengelilingi) kuburan, padahal sebab dan pendorongnya telah ada ketika itu. Ketika beliau ﷺ tidak mengerjakannya, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah tidak Thawaf di kuburan. Jika perbuatan itu termasuk ibadah tentu beliau ﷺ tidak akan meninggalkannya. Tatkala beliau tidak mengerjakannya, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan ibadah yang disyariatkan, bahkan masuk dalam keumuman firman Allah ﷻ:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
“Apakah mereka mempunyai SeSembahan-SeSembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” [QS. asy-Syura/42:21]
Sebagian orang menyatakan tentang disyariatkannya zikir jama’i, yaitu zikir yang dilakukan bersama-sama dengan satu suara. Jika kita perhatikan, amalan tersebut termasuk amalan yang ada sebabnya di zaman Nabi ﷺ yaitu Beliau dan para sahabat melaksanakan salat berjamaah kemudian berzikir setelahnya. Namun tidak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ memerintahkan para sahabat untuk berzikir secara bersama-sama dengan satu suara. Sekiranya perbuatan tersebut termasuk amal ibadah yang disyariatkan tentu beliau ﷺ mengerjakan dan memerintahkannya. Tatkala beliau tidak mengerjakannya, ini menunjukkan bahwa amalan tersebut tidak termasuk ibadah yang disyariatkan.
Sebagian orang beranggapan bahwa bersiwak ketika memasuki masjid secara khusus disunnahkan. [2] Apabila kita cermati, amalan tersebut telah ada sebabnya di masa Nabi ﷺ karena ketika itu siwak telah ada dan beliau sangat sering memasuki masjid, namun bersamaan dengan itu tidak ada nukilan yang menjelaskan bahwa beliau bersiwak ketika masuk Oleh karena itu tidak sepantasnya meyakini keutamaan bersiwak ketika itu secara khusus. Bahkan bersiwak disunnahkan di setiap waktu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ﷺ bersabda:
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
“Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridaan Allah.” [3]
Sebagian makmum dalam salat mengucapkan ( اِسْتَعَنَّا بِاللهِ ) atau ( بِاللهِ أَسْتَعِيْنُ ) ketika imam membaca (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ). Jika kita perhatikan, ucapan tersebut telah ada pendorongnya di zaman Nabi ﷺ, karena Beliau biasa melaksanakan salat berjamaah bersama para Sahabat, namun beliau tidak pernah memerintahkan Sahabat untuk mengucapkannya. Seandainya perkataan tersebut termasuk sunnah tentulah Beliau memerintahkan dan mengerjakannya. Ketika beliau ﷺ tidak memerintahkan dan tidak pula mengerjakannya, itu menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah tidak melakukannya.
Sebagian orang melaksanakan puasa pada bulan Rajab seluruhnya atau sebagiannya dengan meyakini keutamaan khusus padanya. Ini adalah suatu amalan yang telah ada sebabnya di zaman Nabi ﷺ, namun tidak pernah dinukil bahwa beliau mengerjakannya, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkannya. [4]
Dengan beberapa contoh di atas kiranya substansi kaidah ini telah menjadi jelas. Intinya ketika seseorang mendapati suatu amalan yang didakwakan sebagai amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah ﷻ maka hendaklah ia melihat apakah amalan itu pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ? Jika beliau ﷺ pernah melakukannya atau memerintahkannya maka tidak ada masalah jika dia mengamalkannya. Namun jika ternyata tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ dan tidak pernah beliau perintahkan padahal sebab pendorongnya telah ada maka hal itu menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkan amalan tersebut. [5]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Cet. I, Tahun 1423 H/202 M, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Hlm. 661.
[2] Sebagian ulama Madzhab Hanabilah berpendapat akan disunnahkannya bersiwak ketika masuk masjid dengan dalil Qiyas terhadap kesunnahan bersiwak ketika masuk rumah. (Lihat Syarh Zad al-Mustaqni’ karya Syaikh Hamd bin Abdillah al-Hamd, di http://al-zad.net/imgsit/mp_1403078399.pdf)
[3] HR. Al-Bukhari secara mu’allaq, an-Nasa’i no. 5, Ibnu Majah no. 289, Ahmad no. 23072. Hadis ini diShahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam al-Jami’ ash-Shaghir no. 6008.
[4] Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa hukumnya makruh karena hal itu termasuk syi’ar orang-orang jahiliyah. Mereka dahulu sangat mengagungkan bulan Rajab. Apabila seseorang berpuasa pada bulan Rajab disertai puasa pada bulan lainnya, maka tidak dimakruhkan, karena ketika itu ia tidak dianggap mengkhususkan bulan tersebut untuk berpuasa. (Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau’ al-Kitab wa as-Sunnah, Nukhbah min al-‘Ulama, 1424 H, Majma’ al-Malik Fahd li Taba’at al-Mus-haf as-Syarif, al-Madinah al-Munawwarah, hlm. 164-165).
[5] Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah Ke-6.
Kaidah Ke-69: Ibadah Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dalil Syari Tidak Boleh Dibatalkan
Kaidah Keenam Puluh Sembilan
كُلُّ عِبَادَةٍ اِنْعَقَدَتْ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ فَلاَ يَجُوْزُ إِبْطَالُهَا إِلاَّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ آخَرَ
Setiap ibadah yang dilaksanakan berdasarkan dalil syari tidak boleh dibatakan kecuali dengan dalil syari lainnya
Sesungguhnya setiap amalan ibadah dalam syariat Islam bersumber dan berdasarkan dalil-dalil syari. Oleh karena itu, hukum asal dalam amal-amal peribadahan adalah terlarang sampai ada dalil syari Shahih yang menunjukkannya. Dan perlu kita fahami bahwa setiap amal ibadah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan dalil syari maka tidak boleh seorangpun menyatakan ibadah itu batal kecuali berdasarkan dalil syari juga. Jika tidak ada dalil, maka ia tidak boleh menyatakan ibadah tersebut batal.
Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.” [QS. an-Nahl/16:116]
Allah ﷻ berfirman:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Katakanlah, “Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) memersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” [QS. al-A’raf /7:33]
Oleh karena itu, menjadikan suatu perkara sebagai pembatal ibadah termasuk permasalahan tauqifiyyah (hanya berdasarkan dalil), dan tidak ada peran syahwat, pendapat madzhab, maupun Qiyas-Qiyas yang batil. Apa yang ditentukan dalil sebagai pembatal suatu ibadah maka kita tetapkan sebagai pembatal, dan apa yang tidak ditentukan dalil sebagai pembatal ibadah kita pun tidak menetapkannya.
Syaikh Muhammad bin Saleh al-‘Utsaimin mengatakan: “Kita tidak boleh memberanikan diri menyatakan batalnya suatu ibadah yang dikerjakan dalam rangka menghamba kepada Allah kecuali dengan dalil yang jelas.” [1]
Untuk lebih memperjelas substansi kaidah ini, kita bisa mencermati beberapa contoh penerapan kaidah berikut ini:
Wudhu adalah suatu ibadah berdasarkan dalil syari sebagai pengangkat hadats. Dalil syari juga telah menunjukkan bahwa wudhu menjadi batal karena keluarnya sesuatu dari dua jalan, tidur lelap dan yang lebih berat darinya seperti gila dan pingsan, demikian pula karena hal-hal yang mewajibkan mandi, menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa penghalang, dan dengan makan daging onta. Perkara-perkara tersebut telah ditetapkan berdasarkan dalil syari sebagai pembatal wudhu. Sebagian berpendapat bahwa menyentuh wanita meskipun dengan syahwat [2], memikul jenazah [3] atau memandikannya, tertawa terbahak-bahak [4] dan semisalnya termasuk pembatal wudhu. Pendapat ini tidak tepat karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut.
Adakalanya dalil yang dipakai Shahih namun tidak secara tegas menunjukkannya, atau dalil tersebut jelas menunjukkannya akan tetapi tidak Shahih. Kita tidak boleh bersandar kepada dalil-dalil semisal itu, karena wudhu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil syari maka kita tidak boleh membatalkannya kecuali berdasarkan dalil syari juga.
Telah diketahui bersama berdasarkan dalil syari bahwa seseorang dikatakan masuk dalam rangkaian ibadah salat jika ia telah mengucapkan takbiratul ihram. Berdasarkan kaidah di atas, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyatakan salat yang dilakukannya itu batal kecuali berdasarkan dalil.
Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang mengatakan bahwa salat itu bisa batal dengan berdehem jika muncul dua huruf, karenakan mereka tidak bisa menunjukkan dalil. Demikian pula kita mengetahui salahnya pendapat yang menyatakan salat seseorang itu batal jika ia memberi isyarat dengan isyarat yang bisa difahami orang lain. Padahal disebutkan dalam hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu anhuma mengatakan:
فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ
Aku bertanya kepada Bilal, ‘Bagaimanakah engkau melihat Rasulullah ﷺ menjawab salam ketika mereka mengucapkan salam padahal beliau ﷺ sedang salat?’ Bilal radhiyallahu anhu menjawab: ‘Begini.’ Kemudian ia membuka telapak tangannya. Ja’far bin ‘Aun (perawi hadis ini) membuka telapak tangannya dan menjadikan perut telapak tangan di bawah, sedangkan punggung telapak tangan di atas.’ [5]
Demikian pula ketika Mu’awiyah bin al-Hakam as-Sulami berbicara ketika salat, para sahabat mengarahkan pandangan kepadanya dan mereka menepukkan tangan ke kaki-kaki mereka. [6] Apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut merupakan isyarat yang difahami.
Dari sini dapat kita ketahui bahwa isyarat yang difahami baik dengan tangan, kepala, atau semisalnya tidaklah membatalkan salat karena tidak adanya dalil yang menunjukkannya, bahkan ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.
Kita ketahui juga akan salahnya pendapat yang menyatakan batalnya salat dengan berbicara karena lupa atau adanya najis karena lupa atau ketidaktahuan. Hadis Mu’awiyah bin al-Hakam dalam Shahih Muslim [7] dan hadis tentang salatnya Nabi ﷺ dengan memakai sandal yang terkena najis [8] menjadi hujjah yang membantahnya.
Demikianlah, setiap orang yang mendakwakan suatu perkataan atau perbuatan menjadi pembatal salat, maka ia dituntut mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya salat yang dilakukan tidaklah batal, dan dalil dituntut dari orang yang mengeluarkan dari hukum asal bukan dari orang yang berpegang dengan hukum asal.
Tentang ibadah puasa yang terlaksana dengan niat menahan diri dari segala pembatal puasa sejak fajar sampai matahari tenggelam. Apabila seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah puasa dengan tata cara yang telah ditentukan tersebut, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyatakan batalnya puasa yang dilakukan kecuali disertai dalil yang Shahih dan sharih (jelas). Dari sini dapat kita ketahui kesalahan orang yang berpendapat bahwa memakai pacar kuku, atau menggunakan obat tetes mata, suntikan yang bukan nutrisi makan itu membatalkan puasa. Hal ini karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Demikan pula kita ketahui kesalahan pendapat yang menyatakan bahwa ghibah [9], mencium istri [10], keluarnya madzi, pingsan, mencium aroma harum, mencicipi makanan, menelan ludah [11] atau dahak, dan semisalnya termasuk pembatal puasa. Pendapat yang benar adalah bahwa hal-hal tersebut tidak termasuk pembatal puasa.
Demikian pembahasan kaidah ini semoga semakin menambah wawasan dan pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah fikih dalam agama kita yang mulia ini sebagai jembatan untuk semakin bertaqarrub dan meningkatkan penghambaan hanya kepada-Nya. [12]
Wallahu a’lam.
_______
Footnote
[1] As-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Saleh al ‘Utsaimin, Cetakan I, Tahun 1422 H, Dar Ibnil Jauzi, Damam, VI/370.
[2] Menurut madzhab Syafi’iyah dan Dawud az-Zahiri, menyentuh wanita membatalkan wudhu meskipun tidak diiringi syahwat. Madzhab Maliki dan salah satu pendapat dalam madzhab Hanabilah menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu jika disertai syahwat. Sedangkan madzhab Hanafi, salah satu riwayat dalam madzhab Hanabilah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlaq kecuali jika keluar sesuatu dari kemaluan. (Lihat al-Fiqh al-Muyassar Qism al-Ibadat, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Cetakan ke-2, Tahun 1433 H/2012 M, Madar al-Wathan li an-Nasyr, Riyadh, I/74-75)
[3] Imam Ibnu Rusyd berkata: “Sebagian kaum mempunyai pendapat yang syadz dengan mewajibkan wudhu karena memikul jenazah. Memang ada atsar tapi dha’if, ‘Barang siapa memandikan jenazah maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa memikulnya maka hendaklah ia berwudhu.” (Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Tanpa Tahun, Dar al-Fikr, I/29)
[4] Imam Ibnu Rusyd berkata: “Imam Abu Hanifah memiliki pendapat syadz dengan mewajibkan wudhu karena tertawa ketika salat berdasarkan hadis mursal dari Abul ‘Aliyah bahwa ada suatu kaum yang tertawa ketika salat lalu Nabi ﷺmemerintahkan mereka untuk mengulangi wudhu dan salat. (Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, Tanpa Tahun, Dar al-Fikr, I/29)
[5] HR. Abu Dawud, no. 927 dan at-Tirmidzi, no. 368. Imam at-Tirmidzi berkata: ‘Hadis hasan Shahih.”
[6] HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Salat,, no. 536.
[7] Idem.
[8] HR. Abu Dawud,, no. 650 dari Abu Sa’id al Khudri. Hadis ini diShahihkan Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud, 1/192
[9] Syaikh al-Utsaimin berkata: “Sebagian salaf berpendapat bahwa perkatan haram dan perbuatan haram ketika berpuasa membatalkannya, seperti ghibah, akan tetapi Imam Ahmad tatkala ditanya tentang hal tersebut dan ditanyakan kepadanya, “Sesungguhnya Fulan berkata bahwa ghibah membatalkan puasa.” Maka beliau menjawab: “Seandainya ghibah membatalkan puasa maka tidak ada puasa yang tersisa bagi kita.” (as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’)
[10] Imam Ibnu Rusyd berkata: “Sebagian kaum mempunyai pendapat yang syadz dengan mengatakan bahwa mencium istri membatalkan wudhu. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Maimunah bintu Sa’d di mana ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang orang berpuasa yang mencium istrinya, maka Beliau ﷺ bersabda: “Keduanya batal puasanya.” (Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, I/212)
[11] Syaikh Muhammad bin Shalil Al Utsaimin berkata: “Dalam permasalahan ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa megumpulkan ludah membatalkan puasa, yaitu apabila seseorang mengumpulkan ludahnya lalu menelannya. (as-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zad al-Mustaqni’, VI/423)
[12] Diangkat dari Talqih al-Afham al-‘Aliyyah bi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Syaikh Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Kaidah ke-24.



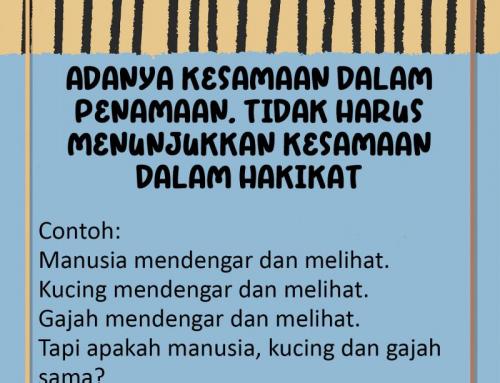



[…] https://t.me/nasihatsahabat Pinterest: https://id.pinterest.com/nasihatsahabat Baca juga: https://nasihatsahabat.com/kaidah-fikih-qawaid-fiqhiyah/ KENAPA ORANG KAFIR LEBIH KAYA? By Admin Nasihat Sahabat|2020-02-02T07:07:45+00:00February 2nd, […]