Telah kita pahami bersama, bahwa ibadah itu mencakup semua amalan hati, amalan jawarih (anggota badan) maupun ucapan-ucapan lisan yang dicintai dan diridhoi Alloh subhanahu wata’ala, sebab ibadah itu merupakan puncak kecintaan bagi Alloh subhanahu wata’ala.
Kita bisa mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Alloh subhanahu wata’ala adalah dari disyari’atkannya amalan tersebut oleh Alloh azza wajalla maupun oleh Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam. Bila suatu amalan disyari’atkan oleh Alloh subhanahu wata’ala atau oleh Rosul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam, menunjukkan amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh-Nya. Sebaliknya, bila tidak disyari’atkan, maka berarti amalan tersebut pun tidak dicintai dan tidak pula diridhoi.
Jadi ibadah itu hanya kita ketahui ketetapannya dari adanya dalil-dalil yang mensyari’atkannya. Demikian pula tentang tatacara praktik ibadah pun tidak diketahui dengan baik, selain dengan memahami dalil-dalil yang menerangkannya. Oleh sebab itulah para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah menetapkan bahwa ibadah itu bersifat tauqifiyah.
Syaikh DR. Sholih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan:
“Ibadah itu tauqifiyah, maknanya ia tidak disyari’atkan sedikit pun kecuali dengan dalil dari al-Qur’an dan Sunnah. Dan apa pun yang tidak disyari’atkan dianggap bid’ah yang tertolak, sebagaimana sabda Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam:
“Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak.” Maknanya, amalan tersebut ditolak dan tidak diterima. Bahkan ia berdosa karenanya, sebab amalan (yang tidak diperintahkan) tersebut termasuk kemaksiatan, bukan ketaatan” [Lihat Aqidatut Tauhid oleh Syaikh DR. Sholih bin Fauzan al-Fauzan hlm. 54a].
Dari sini kita pahami bahwa untuk menetapkan suatu amalan tertentu sebagai sebuah ibadah atau bukan, harus berdasarkan dalil dan bukan dengan perasaan hati, akal atau ilham; bukan pula dengan kira-kira maupun prasangka belaka.



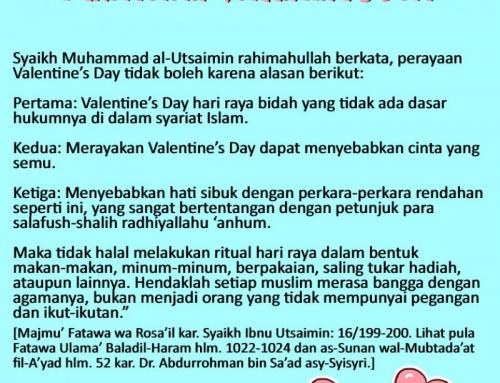
Leave A Comment