#KaidahFikih
KAIDAH: PERINTAH LEBIH BESAR DARIPADA LARANGAN
الْمَأْمُوْرُ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
Kaidah: Perintah lebih besar daripada larangan
Makna Kaidah
Kaidah ini termasuk kaidah yang besar di sisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan termasuk patokan pokok dalam metode fikihnya. Hal ini nampak dari banyaknya tarjih dan ikhtiyar beliau yang dikaitkan dengan kaidah ini dan kaidah-kaidah lain yang menjadi cabangnya.
Kaidah ini menjelaskan, bahwa perhatian syariat terhadap perkara yang diperintahkan, lebih besar dan lebih kuat, daripada perhatiannya terhadap perkara yang dilarang. Sebagaimana dikatakan oleh Syaihul Islam Ibnu Taimiyah:
“Sesungguhnya jenis mengerjakan perintah itu lebih besar daripada jenis meninggalkan larangan. Dan jenis meninggalkan perintah lebih besar daripada jenis mengerjakan larangan. Dan sesungguhnya pahala bani Adam karena mengerjakan kewajiban lebih besar daripada pahala yang diraihnya karena meninggalkan perkara yang haram. Dan dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan.” [Majmu’ al-Fatawa, 20/85].
Karena perintah lebih besar daripada larangan, baik ditinjau dari jenisnya, pahalanya, maupun dosanya. Maka ini menunjukkan, bahwa perhatian syariat terhadap perkara yang diperintahkan lebih besar daripada perhatiannya terhadap perkara yang dilarang.
Ada beberapa kaidah lain yang menjadi cabang dan turunan dari kaidah ini. Semuanya semakin memerjelas dan menguatkan, bahwa tingkat keutamaan dalam perintah lebih besar daripada yang ada dalam larangan [Lihat pula pembahasan tentang kaidah ini dalam al-Qawa’id wa al-Fawa’id al-Ushuliyyah, Ibnu al-Lahham, hlm. 191; Fath al-Bari, Ibnu Hajar, 13/262. Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, Ibnu Rajab, hlm. 83-84. Fath al-Mubin li Syarh al-Arba’in, Ibnu Hajar al-Haitsami, hlm. 132-133. Al-Bahr al-Muhith, az-Zarkasyi, 1/274].
Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:
Kaidah Pertama:
اْلأُمُوْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا يُعْفَى فِيْهَا عَنِ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ
Perkara-perkara yang terlarang, pelakunya dimaafkan jika dilakukan oleh orang yang lupa atau tersalah
Misalnya seseorang yang makan atau minum ketika berpuasa karena lupa, maka ia dimaafkan dan puasanya tidak batal. Demikian pula seseorang yang memakai minyak wangi, atau memakai penutup kepala, atau memotong kukunya ketika dalam keadaan ihram karena lupa atau tersalah, maka ia tidak berdosa, dan tidak ada kewajiban membayar fidyah, karena seseorang yang mengerjakan larangan karena lupa atau tersalah maka dimaafkan.
Ini berkaitan dengan larangan. Adapun perkara yang diperintahkan, maka kewajiban pelaksanaannya tidak gugur dari orang yang lupa atau tersalah, bahkan tetap wajib untuk dikerjakan.
Kaidah Kedua:
مَا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِلذَّرِيْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ
Perkara yang dilarang dalam rangka preventif boleh dikerjakan saat ada maslahat yang lebih kuat
Seperti haramnya seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Larangan tersebut ada, karena hal itu bisa menjadi sarana yang mengantarkan kepada fitnah atau sarana perzinaan. Namun jika ada maslahat yang lebih kuat, maka adakalanya hal tersebut diperbolehkan. Seperti seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita, maka diperbolehkan baginya untuik melihat wajah si wanita. Atau seorang dokter yang perlu melihat anggota badan pasien wanita dalam rangka pengobatan.
Demikian pula haramnya shalat di waktu-waktu larangan. Pengharaman tersebut ada, karena bisa menjadi sarana yang mengantarkan pada tasyabbuh (menyerupai) ibadah orang-orang kafir yang sujud kepada matahari. Namun jika ada maslahat yang lebih kuat, maka shalat di waktu tersebut diperbolehkan, seperti mengqadha’ shalat wajib yang terlewat, shalat jenazah, dan shalat-shalat lainnya yang memiliki sebab menurut pendapat yang kuat [Lihat pula pembahasan tentang kaidah cabang ini dalam Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawi’idihi, Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam, hlm. 64-67].
Dalil Yang Mendasarinya
Berkaitan dengan kaidah ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk pendalilan yang sangat bagus. Beliau rahimahullah menyebutkan, tidak kurang dari dua puluh dua pendalilan. Adapun yang paling kuat di antaranya adalah sebagai berikut:
- Sesungguhnya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang pertama kali adalah dilakukan oleh nenek moyang jin (iblis) dan nenek moyang manusia (Adam). Dalam hal ini, kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis lebih awal dan lebih besar. Kemaksiatan tersebut berupa PENOLAKAN iblis dari melaksanakan PERINTAH Allah Azza wa Jalla berupa sujud kepada Adam. Ini termasuk kategori meninggalkan perintah. Adapun yang dilakukan oleh Adam, yaitu memakan dari pohon di Surga. Ini termasuk kategori MENGERJAKAN LARANGAN. Dari dua jenis tersebut, ternyata kadar dosa Adam lebih ringan. Dari sini dapat diketahui, bahwa jenis meninggalkan perintah itu lebih besar daripada jenis mengerjakan larangan.
Demikian pula, bentuk pelanggaran yang dilakukan iblis tersebut ternyata berupa dosa besar, sekaligus kekufuran yang tidak diampuni. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam berupa kesalahan yang lebih ringan, dan diberikan ampunan darinya. Sebagaimana firman-Nya:
فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [al –Baqarah/2:37]
Lima rukun Islam merupakan amalan-amalan yang masuk kategori perkara yang diperintahkan. Apabila seseorang meninggalkannya, maka banyak dari kalangan Ulama yang mewajibkan hukuman bunuh bagi pelakunya. Bahkan adakalanya dihukumi sebagai seorang yang kafir, keluar dari agama Islam. Di antaranya, apabila seseorang tidak mau mengucapkan Dua Kalimat Syahadat padahal ia mampu mengucapkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah:, “Adapun Dua Kalimat Syahadat, apabila seseorang tidak mengucapkannya padahal ia mampu, maka ia adalah orang kafir berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.” (Majmu’ al-Fatawa, 7/609). (Lihat at-Takfir wa Dhawabithuhu, Syaikh Ibrahim bin ‘Amir ar-Ruhailiy, Dar al-Imam Ahmad, hlm. 229)
Adapun mengerjakan larangan yang madharatnya tidak menyebar kepada orang lain, maka para ulama tidak mewajibkan hukuman bunuh atas pelakunya, dan tidak pula dihukumi kufur, asalkan perkara tersebut tidak membatalkan keimanan. Dari sini dapat diketahui, bahwa meninggalkan perintah perkaranya lebih besar daripada mengerjakan larangan.
Sesungguhnya maksud dari adanya larangan, adalah supaya perkara yang dilarang itu tidak ada, yaitu tidak dikerjakan. Sedangkan Al ‘Adam (Ketidakadaan) itu secara asal tidak ada unsur kebaikan di dalamnya. Adapun perkara yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang maujud (dituntut keberadaannya). Dan perkara yang maujud asalnya merupakan perkara yang baik, bermanfaat, dan dicari. Bahkan merupakan suatu kepastian, bahwa setiap yang ada pasti ada manfaatnya. Karena setiap yang ada itu telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla , dan Dia tidak menciptakan sesuatu pun kecuali dengan hikmah. Berbeda dengan sesuatu yang ma’dum (tidak ada) yang tidak ada sesuatu pun di dalamnya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. [as-Sajdah/32:7]
Dan Allah Azza wa Jalla berfirman:
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. [an-Naml/27:88]
Dengan demikian dapat kita ketahui, bahwa apa yang terkandung di dalam perintah itu lebih sempurna dan lebih mulia, daripada apa yang ada dalam larangan.
Contoh Penerapan Kaidah
Di antara contoh implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:
Perkara-perkara yang diperintahkan tidaklah gugur karena nisyan (lupa) atau jahl (tidak tahu). Adapun perkara-perkara yang dilarang, maka gugur (dimaafkan) jika seseorang lupa atau tidak tahu [Lihat Majmu’ al-Fatawa, 21/477].
Jika seseorang meninggalkan perkara yang diperintahkan maka ada kewajiban mengqadha’ (menggantinya), meskipun ia meninggalkannya karena uzur. Seperti seseorang yang meninggalkan puasa karena sakit atau safar, dan orang yang meninggalkan shalat karena tertidur, maka wajib untuk mengqadha’nya. Demikian pula orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam manasik haji maka tetap wajib mengerjakannya jika masih memungkinkan atau dengan membayar dam. Maka tidaklah gugur tuntutan dalam perintah tersebut sampai ia mengerjakannya.
Adapun orang yang mengerjakan perkara yang dilarang karena lupa, tersalah, tertidur, atau tidak tahu, maka ia dimaafkan. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar ganti rugi, kecuali jika hal itu mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain [Lihat Majmu’ al-Fatawa, 20/95].
Dipersyaratkan adanya niat untuk mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, haji, dan semisalnya [Lihat Majmu’ al-Fatawa, 21/477]. Adapun perkara-perkara yang dilarang maka tidak dipersyaratkan adanya niat untuk meninggalkannya, seperti menghilangkan najis, meninggalkan zina, meninggalkan pencurian, dan semisalnya [Diangkat dari kitab al-Qawa’id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah ‘inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah, Nashir bin ‘Abdillah al-Miman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami’ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 199-202].
Wallahu a’lam.
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XVII/1435H/2014. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196. Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
Sumber: https://almanhaj.or.id/4385-kaidah-ke-55-perintah-lebih-besar-daripada-larangan.html

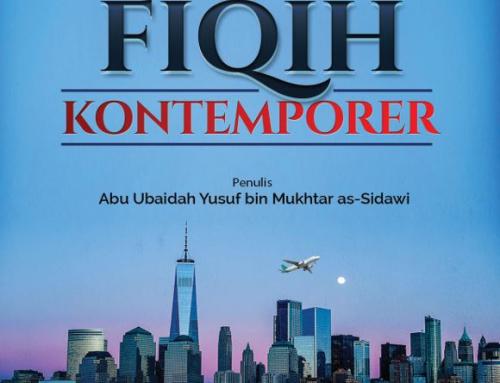
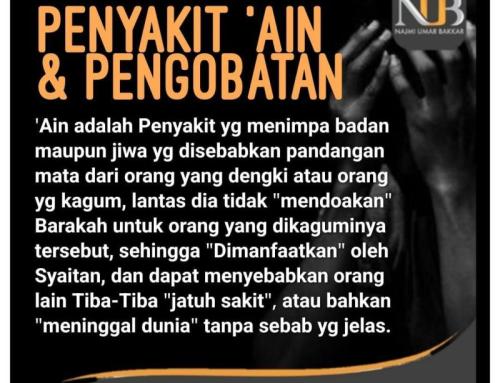



Leave A Comment