بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HUKUM SHALAT QASHAR DAN SHALAT JAMAK
Shalat Qashar
Dari Muhammad bin Ja’far: ”Telah bercerita kepadaku Syu’bah, dari Yahya bin Yazid Al-Hanna’i yang menuturkan: “Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqashar shalat. Sedangkan aku pergi ke Kufah, maka aku shalat dua rakaat hingga aku kembali. Kemudian Anas berkata: “Artinya: Adalah Rasulullah ﷺ, manakala keluar sejauh tiga mil atau tiga farskah (Syu’bah ragu), dia mengqashar shalat. (Dalam suatu riwayat): Dia shalat dua rakaat”. (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad (3/129) dan Al-Baihaqi (2/146).
Syaikh Al Albani menilai hadis ini sanadnya Jayyid (Bagus). Semua perawinya tsiqah,yakni para perawi Asy-Syaikhain, kecuali Al-Hanna’i di mana dia adalah perawi Muslim. Namun segolongan orang-orang tsiqah juga telah meriwayatkan darinya.
Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim (2/145), Abu Dawud (1201), Ibnu Abi Syaibah (2/108/1/2). Juga diriwayatkan darinya oleh Abu Ya’la dalam Musnad-nya (Q. 99/2) dari beberapa jalur yang berasal dari Muhammad bin Ja’far, tanpa dengan ucapan Al-Hanna’i: “Sedangkan aku pergi ke Kufah….sampai aku kembali”. Meskipun ini tambahan yang benar. Bahkan oleh karenanya, hadis ini berlaku. Demikian pula hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Awannah (2/346) dari jalur Abu Dawud (dia adalah Ath-Thayalisi), dia berkata: “Telah bercerita kepadaku Syu’bah. Namun Ath-Thayalisi tidak meriwayatkannya dalam Musnad-nya”.
(Al-Farsakh) berarti tiga mil. Dan satu mil adalah sejauh mata memandang ke bumi, di mana mata akan kabur ke atas permukaan tanah, sehingga tidak mampu lagi menangkap pemandangan. Demikianlah penjelasan Al-Jauhari.
Namun dikatakan pula, batas satu mil adalah jika sekira memandang kepada seseorang di kejauhan, kemudian tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, dan dia hendak pergi atau hendak datang, seperti keterangan dalam Al-Fath (2/467). Dan menurut ukuran sebagian ulama sekarang adalah sekitar 1680 meter.
Kandungan Hukumnya
Hadis ini menjelaskan, bahwa jika seseorang pergi sejauh tiga farsakh (satu farsakh sekitar 8 km), maka dia boleh mengqashar shalat. Al-Khuththabi telah menjelaskan dalam Ma’alimus Sunan (2/49): “Meskipun hadis ini telah menetapkan, bahwa jarak tiga farsakh merupakan batas, di mana boleh melakukan qashar shalat, namun sungguh saya tidak mengetahui seorang pun dari ulama fikih yang berpendapat demikian”.
Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan:
Bahwa hadis ini memang tetap seperti semula, namun Imam Muslim mengeluarkannya dan tidak dinilai lemah oleh lainnya.
Hadis ini tidak berbahaya dan boleh saja diamalkan. Soal tidak mengetahui adanya seorang pun ulama fikih yang mengatakan demikian, itu tidak menghalangi untuk mengamalkan hadis ini. Tidak menemukan, bukan berarti tidak ada.
Sesungguhnya perawinya telah mengatakan demikian, yaitu Anas bin Malik. Sedang Yahya bin Yazid Al-Hanna’i, sebagai perawinya juga telah berfatwa demikian, seperti keterangan yang telah lewat. Bahkan telah berlaku pula dari sebagian sahabat yang melakukan shalat qashar dalam perjalanan yang lebih pendek daripada jarak itu. Maka Ibnu Abi Syaibah (2/108/1) telah meriwayatkan pula dari Muhammad bin Zaid bin Khalidah, dari Ibnu Umar yang menuturkan. “Shalat itu boleh diqashar dalam jarak sejauh tiga mil”. Hadis ini sanadnya Shahih. Seperti yang telah Syaikh Al Albani jelaskan dalam Irwa’ul Ghalil (no. 561).
Kemudian diriwayatkan dari jalur lain yang juga berasal dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: “Sesunguhnya aku pergi sesaat pada waktu siang, dan aku mengqashar (shalat)”.
Hadis ini sanadnya juga Shahih, dan dishahihkan pula oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath (2/467). Kemudian dia meriwayatkan dari Ibnu Umar (2/111/1).
“Sesungguhnya dia mukim di Makkah, dan manakala dia keluar ke Mina, dia mengqashar (shalat),” Hadis ini sanadnya juga Shahih, dan dikuatkan. Apabila penduduk Makkah hendak keluar bersama Nabi ﷺ ke Mina, dalam haji Wada’, maka mereka mengqashar shalat juga, sebagaimana sudah tidak ada lagi dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan jarak antara Makkah dan Mina hanya satu farsakh. Ini seperti keterangan dalam Mu’jamul Buldan.
Sementara itu Jibilah bin Sahim memberitahukan: “Aku mendengar Ibnu Umar berkata: “Kalau aku keluar satu mil, maka aku mengqashar shalat”
Hadis ini disebutkan pula oleh Al-Hafidz dan dinilainya Shahih.
Hal ini tidak menafikan terhadap apa yang terdapat dalam Al-Muwatha maupun lainnya dengan sanad-sanadnya yang Shahih, dari Ibnu Umar, bahwa dia mengqashar dalam jarak yang jauh daripada itu. Juga tidak menafikan jarak perjalanan yang lebih pendek daripada itu. Nash-nash yang telah Syaikh Al Albani sebutkan adalah jelas memerbolehkan mengqashar shalat dalam jarak yang lebih pendek daripada itu. Ini tidak bisa disanggah, terlebih lagi karena adanya hadis yang menunjukkan lebih pendek lagi daripada itu.
Al-Hafidzh telah menandaskan di dalam Al-Fath (2/467-468): “Sesunguhnya hadis itu merupakan hadis yang lebih Shahih dan lebih jelas dalam menerangkan soal ini. Adapun ada yang berbeda dengannya, mungkin soal jarak diperbolehkannya mengqashar, di mana bukan batas akhir perjalanannya.
Apalagi Al-Baihaqi juga menyebutkan, bahwa Yahya bin Yazid bercerita: “Saya bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat. Saya keluar Kufah, yakni Bashrah, saya shalat dua rakaat dua rakaat, sampai saya kembali. Maka Anas berkata: (Kemudian menyebutkan hadis ini)”.
Jadi jelas, bahwa Yahya bin Yazid bertanya kepada Anas tentang diperbolehkannya mengqashar shalat dalam bepergian, bukan tentang tempat di mana dimulai shalat qashar. Kemudian yang benar dalam hal ini adalah, bahwa soal qashar itu tidak dikaitkan dengan jarak perjalanan, tetapi dengan melewati batas daerah, di mana seorang telah keluar darinya. Al-Qurthubi menyanggahnya sebagai suatu yang diragukan, sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. Jika yang dimaksudkannya adalah bahwa jarak tiga mil itu tidak bisa dijadikan pegangan adalah bagus, akan tetapi tidak ada larangan untuk berpegang pada batas tiga farsakh. Karena tiga mil memang terlalu sedikit, maka diambil yang lebih banyak sebagai sikap berhati-hati.
Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Hatim bin Ismail, dari Abdurrahman bin Harmilah yang menuturkan: “Aku bertanya kepada Sa’id bin Musayyab: “Apakah boleh mengqashar shalat dan berbuka di Burid dari Madinah?” Dia menjawab: “Ya”. Wallahu a’lam. [Syaikh Al Albani mengatakan sanad atsar ini, menurut Ibnu Abi Syaibah (2/15/1) adalah Shahih.]
Diriwayatkan dari Allajlaj, dia menceritakan: “Kami pergi bersama Umar Radhiyallahu ‘anhu sejauh tiga mil, maka kami diberi keringanan dalam shalat dan kami berbuka”.
Hadis ini sanadnya cukup memadai untuk perbaikan. Semua adalah tsiqah, kecuali Abil Warad bin Tsamamah, di mana hanya ada tiga orang meriwayatkan darinya. Ibnu Sa’ad mengatakan: “Dia itu dikenal sedikit hadisnya”.
Atsar-atsar itu menunjukkan diperbolehkan melakukan shalat qashar dalam jarak yang lebih pendek daripada apa yang terdapat dalam hadis tersebut.
Ini sesuai dengan pemahaman para sahabat Radhiyallahu anhum. Karena dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah, kata safar (bepergian) adalah mutlak, tidak dibatasi oleh jarak tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta’al,.“ yang artinya:
“Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat….” [An-Nisaa: 101]
Dengan demikian, maka tidak ada pertentangan antara hadis tersebut dengan atsar-atsar ini. Karena ia memang tidak menafikan diperbolehkannya qashar dalam jarak bepergian yang lebih pendek daripada yang disebutkan di dalam hadis tersebut.
Oleh karena itu, Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil ‘Ibad (juz I, hal. 189) mengatakan: “Nabi ﷺ tidak membatasi bagi umatnya pada jarak tertentu untuk mengqashar shalat dan berbuka. Bahkan hal itu mutlak saja bagi mereka mengenai jarak perjalanan itu. Sebagaimana Nabi ﷺ memersilakan kepada mereka untuk bertayamum dalam setiap bepergian. Adapun mengenai riwayat tentang batas sehari, dua hari atau tiga hari, sama sekali tidak benar. Wallahu ‘alam”.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan: “Setiap nama di mana tidak ada batas tertentu baginya dalam bahasa maupun agama, maka dalam hal itu dikembalikan kepada pengertian umum saja, sebagaimana ‘bepergian” dalam pengertian kebanyakan orang yaitu bepergian, di mana Allah mengaitkannya dengan suatu hukum”.
Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jarak perjalanan diperbolehkannya qashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari dua puluh pendapat. Namun apa yang kami sebutkan dari pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah adalah yang paling mendekati kebenaran, dan lebih sesuai dengan kemudahan Islam.
Pembatasan dengan sehari, dua hari, tiga hari atau lainnya, seolah juga mengharuskan mengetahui jarak perjalanan yang telah ditempuh, yang tentu tidak mampu bagi kebanyakan orang. Apalagi untuk jarak yang belum pernah ditempuh sebelumnya.
Dalam hadis tersebut juga ada makna lain, yakni bahwa qashar itu dimulai dari sejak keluar dari daerah. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama.
Sebagaimana dalam kitab Nailul Authar (3/83) di mana penulisnya mengatakan: “Sebagian ulama-ulama Kufah, manakala hendak berpergian memilih shalat dua rakaat, meskipun masih di daerahnya. Sebagian mereka ada yang berkata:”Jika seseorang itu naik kendaraan, maka qashar saja kalau mau”.
Sementara itu Ibnul Mundzir lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Di mana mereka sepakat, bahwa boleh qashar setelah meninggalkan rumah. Namun mereka berbeda mengenai sesuatu sebelumnya. Tapi hendaknya seseorang menyempurnakan sesuatu yang perlu disempurnakan, sehingga dia diperbolehkan mengqashar shalat. Ibnul Mundzir berkata lagi: “Sungguh saya tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ mengqashar shalat dalam suatu perjalanannya, kecuali setelah keluar dari Madinah”.
Syaikh Al Albani menemukan: Sesungguhnya hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini adalah banyak. Syaikh Al Albani telah mengeluarkan sebagian darinya dalam Al-Irwa’ yaitu dari hadis Anas, Abi Hurairah, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Silakan periksa no. 562!
Adapun mengenai shalat qashar, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat: “Qashar shalat itu dianjurkan, bukan wajib, walau dari zhahir nas terlihat wajib, sebab di sana sini masih banyak nas lainnya yang menunjukkan tidak wajib. Safar yang bisa membolehkan qashar shalat, berbuka puasa, menyapu dua sepatu atau dua kaos kaki, adalah tiga hari lamanya. Hal ini masih diperselisihkan ulama. Sebagian mereka mensyaratkan, bahwa jarak qashar itu harus mencapai sekitar 81 Km. Sebagian lainnya tidak menentukan jarak tertentu, yang penting sesuai dengan adat yang berlaku, sebab syara’ tidak menentukannya. Dalam suatu nazham disebutkan: “Setiap perkara yang timbul dan tak ada ketentuan syara’, maka lindungilah dengan ketentuan adat suatu tempat (‘uruf)“.
Dengan demikian, jika telah berlaku hukum safar, baik menurut jarak atau ‘uruf, maka setiap orang patut mengikutinya, baik dalam hal qashar shalat, berbuka puasa atau menyapu sepatu, dalam waktu tiga hari lamanya. Jika tidak ada kesulitan, maka puasa lebih baik tetap dipenuhi, bagi yang tengah dalam perjalanan.
Qashar Dalam Perjalanan
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam berpendapat sebagai berikut:
Qashar di sini berlaku untuk shalat-shalat empat rakaat, yaitu Zuhur, Ashar dan Isya. Dinukil dari Ibnul Mundzir adanya ijma’, bahwa tidak ada qashar dalam shalat Maghrib dan Subuh. Tidak ada sebab untuk qashar ini kecuali perjalanan, karena ini merupakan rukhshah yang ditetapkan sebagai rahmat bagi musafir, dan adanya kesulitan yang dialaminya.
Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhum, dia berkata: ‘Aku menyertai Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak melebihkan shalat dalam perjalanan dari dua rakaat, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan Utsaman”.
Makna Hadis
Abdullah bin Umar menuturkan, bahwa dia pernah menyertai Nabi ﷺ dalam perjalan beliau. Dia juga pernah menyertai Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam perjalanan mereka. Ternyata masing-masing di antara mereka senantiasa mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, dan tidak lebih dari dua rakaat itu.
Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama
Para ulama saling berbeda pendapat tentang qashar, apakah itu wajib ataukah rukhshah yang disunnatkan pelaksanaannya?
Tiga Imam, Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad membolehkan penyempurnaan shalat, namun yang lebih baik adalah mengqasharnya. Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan qashar, yang juga didukung Ibnu Hazm. Dia berkata: “Fardhunya musafir ialah shalat dua rakaat”.
Dalil orang yang mewajibkan qashar ialah tindakan Rasulullah ﷺ yang senantiasa mengqashar dalam perjalanan. Hal ini dapat ditanggapi, bahwa perbuatan tidak menunjukkan kewajiban. Begitulah pendapat jumhur. Mereka juga berhujjah dengan hadis Aisyah Radhiyallahu ‘anha di dalam Ash-Shahihaian: “Shalat diwajibakan dua rakaat, lalu ditetapkan shalat dalam perjalanan, dan shalat orang yang menetap disempurnakan.
Hujjah ini dapat ditanggapi dengan beberapa jawaban. Yang paling baik ialah, ini merupakan perkataan Aisyah yang tidak dimarfu’kan kepada Nabi ﷺ. Sementara Aisyah juga tidak mengikuti masa difardhulkannya shalat.
Adapun dalil-dalil jumhur tentang tidak wajibnya qashar ialah firman Allah “Maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat kalian” [An-Nisa: 101]
Penafian kesalahan di dalam ayat ini menunjukkan, bahwa qashar itu merupakan rukhshah dan bukan sesuatu yang dipastikan. Di samping itu, dasarnya adalah penyempurnaannya. Adanya qashar, karena dirasa shalat itu terlalu panjang. Dalil lainnya adalah hadis Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengqqashar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah puasa dan tidak puasa [Diriwayatkan Ad-Daruquthni, yang menurutnya, ini hadis Hasan]
Dalil-dalil jumhur dapat ditanggapi sebagai berikut: Ayat ini disebutkan tentang qashar sifat dalam shalat khauf dan hadis tentang hal ini dipermasalahkan. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah berkata: “Ini merupakan hadis yang didustakan terhadap Rasulullah ﷺ”.
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam mengatakan, sebaiknya musafir tidak meninggalkan qashar, karena mengikuti Rasulullah ﷺ dan sebagai cara untuk keluar dari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya, dan memang qashar inilah yang lebih baik menurut mayoritas ulama.
Dikutip dari Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ikhtiyarat, tentang kemakruhan menyempurnakannya. Dia menyebutkan nukilan dari Al-Imam Ahmad, yang tidak mengomentari sahnya shalat orang yang menyempurnakan shalat dalam perjalanan, Ibnu Taimiyah juga berkata: “Telah diketahui secara mutawatir, bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa shalat dua rakaat dalam perjalanan. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakar dan Umar setelah beliau. Hal ini menunjukkan, bahwa dua rakaat adalah lebih baik. Begitulah pendapat mayoritas ulama.
Kesimpulan Hadis
- Pensyaratan qashar shalat empat rakaat dalam perjalanan menjadi dua rakaat saja.
- Qashar merupakan sunnah Rasulullah ﷺ dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidun dalam perjalanan mereka.
- Qashar bersifat umum dalam perjalanan haji, jihad dan segala perjalanan untuk ketaatan. Para ulama juga memasukkan perjalanan yang mubah. Menurut An-Nawawy, jumhur berpendapat bahwa dalam semua perjalanan yang mubah boleh dilakukan qashar. Sebagian ulama tidak membolehkan qashar dalam perjalanan kedurhakaan. Yang benar, rukhshah ini bersifat umum dan sama untuk semua orang.
- Kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya dan keluwesan syariat ini, yang memberi kemudahan dalam beribadah kepada makhluk. Karena perjalanan lebih sering mendatangkan kesulitan, maka dibuat keringanan untuk sebagian shalat, dengan mengurangi bilangan rakaat shalat. Jika tingkat kesulitan semakin tinggi seperti karena memerangi musuh, maka sebagian shalat juga diringankan.
- Perjalanan di dalam hadis ini tidak terbatas, tidak dibatasi dengan jarak jauh. Yang lebih baik ialah dibiarkan menurut kemutlakannya. Lalu rukhshah diberikan kepada apapun yang disebut perjalanan. Pembatasanya dengan tempo tertentu atau jarak farsakh tertetntu, tidak pernah disebutkan di dalam nash. Syaihul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Perjalanan tidak pernah dibatasi oleh syariat, tidak ada pembatasan menurut bahasa. Hal ini dikembalikan kepada tradisi manusia. Apa yang mereka sebut dengan perjalanan, maka itulah perjalanan”
Shalat Jamak
“Adalah Rasulullah ﷺ dalam peperangan Tabuk, apabila hendak berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau ﷺ mengakhirkan Zuhur, hingga beliau ﷺ mengumpulkannya dengan Ashar. Lalu beliau ﷺ melakukan dua shalat itu sekalian. Dan apabila beliau ﷺ hendak berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau ﷺ menyegerakan Ashar bersama Zuhur, dan melakukan shalat Zuhur dan Ashar sekalian. Kemudian beliau ﷺ berjalan. Dan apabila beliau ﷺ hendak berangkat sebelum Maghrib maka beliau ﷺ mengakhirkan Maghrib sehingga mengerjakan bersama Isya’, dan apabila beliau ﷺ berangkat setelah Maghrib, maka beliau ﷺ menyegerakan Isya’ dan melakukan shalat Isya’ bersama Maghrib“. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud (1220), At-Tirmidzi (2/438) Ad-Daruquthni (151), Al-Baihaqi (3/165) dan Ahmad (5/241-242), mereka semua memerolehnya dari jalur Qutaibah bin Sa’id: ” Telah bercerita kepadaku Al-Laits bin Sa’ad dari Yazid bin Abi Habib dari Abi Thufail Amir bin Watsilah dari Mu’adz bin Jabal, secara marfu. Dalam hal ini Abu Dawud berkomentar:”Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Qutaibah saja”.
Syaikh Al Albani menilai: “Dia adalah tsiqah dan tepat. Maka tidak mengapa meskipun dia sendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Al-Laits selain darinya. Inilah yang benar, semua perawinya tsiqah. Yakni para perawi Asy-Syaikhain. Juga telah dinilai Shahih oleh Ibnul Qayyim dan lainnya. Namun Al-Hakim dan lainnya menganggapnya ada ‘illat yang tidak baik, seperti yang telah saya jelaskan dalam Irwa ‘Al-Ghalil (571). Di sana saya menyebutkan mutabi’ (hadis yang mengikuti) kepada Qutaibah dan beberapa syahid (hadis pendukung) yang memastikan keShahihannya.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik (I/143/2) dari jalur lain yang berasal dari Abi Thufail dengan redaksi: “Sesungguhnya mereka keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Tabuk. Maka adalah Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara Zuhur dan Ashar serta Magrib dan Isya. Abu Thufail berkata: ‘Kemudian beliau mengakhirkan (Jamak Takhir) shalat pada suatu hari. Lalu beliau ﷺ keluar dan shalat Zuhur dan Ashar sekalian. Kemudian beliau ﷺ masuk (datang). Kemudian keluar dan shalat Maghrib serta Isya sekalian“.
Dan dari jalur Malik telah dikeluarkan oleh Imam Muslim (7/60) dan Abu Dawud (1206), An-Nasa’i (juz I, hal 98), Ad-Darimi (juz I, hal 356), Ath-Thahawi (I/95), Al-Baihaqi (3/162), Ahmad (5/237) dan dalam riwayat Muslim (2/162) dan lainnya dari jalur lain:
“Kemudian saya berkata: ‘Apa maksudnya demikian?” Dia berkata: Maksudnya agar tidak memberatkan umatnya”.
Kandungan Hukumnya
Dalam hadis ini terdapat beberapa masalah.
- Boleh mengumpulkan dua shalat pada waktu bepergian, walaupun pada tempat selain Arafah dan Muzdalifah. Demikian pendapat jumhurul ulama. Berbeda dengan mazdhab Hanafiyah. Mereka menakwilkannya dengan ‘Jamak Shuwari,’ yakni mengakhirkan DZuhur sampai mendekati waktu Ashar, demikian pula Maghrib dan Isya’. Pendapat ini telah dibantah oleh Jumhurul Ulama dari berbagai segi. Pertama: Pendapat ini jelas menyalahi pengertian jamak secara zahir. Kedua: Tujuan disyariatkan jamak adalah untuk memermudah dan menghindarkan kesulitan, seperti yang telah dijelaskan oleh riwayat Muslim. Sedangkan jamak dalam pengertian ‘Shuwari’ masih mengandung kesulitan. Ketiga: Sebagian hadis tentang jamak jelas menyalahkan pendapat mereka itu. Seperti hadis Anas bin Malik yang berbunyi. “Mengakhirkan Zuhur sehingga masuk awal Ashar, kemudian dia menjamak (mengumpulkan) keduanya”. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim (2/151) dan lainnya. Keempat: Bahkan pendapat itu juga bertentangan dengan pengertian Jama Taqdim sebagaimana dijelaskan oleh hadis Mu’adz berikut ini:
“Dan apabila dia berangkat setelah tergelincir matahari, maka dia akan menyegerakan Ashar kepada Zuhur”. Dan sesungguhnya hadis-hadis yang serupa ini adalah banyak, sebagaimana telah disinggung.
- Sesungguhnya soal jamak (mengumpulkan dua shalat), disamping boleh Jama Takhir, boleh juga Jama Taqdim. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam Al-Um (I/67), disamping oleh Imam Ahmad dan Ishaq, sebagaimana dikatakan oleh At-Tarmidzi (2/441).
- Sesungguhnya diperbolehkan jamak pada waktu turunnya (dari kendaraan), sebagaimana diperbolehkan manakala berlangsung perjalanan. Imam Syafi’i dalam Al-Um, setelah meriwayatkan hadis ini dari jalur Malik, mengatakan: “Ini menunjukkan, bahwa dia sedang turun bukan sedang jalan. Karena kata ‘dakhala’ dan ‘kharaja’ (masuk dan keluar) adalah tidak lain bahwa dia sedang turun. Maka bagi seorang musafir, boleh menjamak pada saat turun dan pada saat berjalan’.
Syaikh Al Albani berpendapat: Dengan nash ini maka tidaklah perlu menghiraukan kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma’ad (1/189) menuturkan: “Bukanlah petunjuk Nabi ﷺ, melakukan jamak sambil naik kendaraan dalam perjalanannya, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan tidak juga jamak itu harus pada waktu dia turun“.
Nampaknya banyak kaum Muslimin yang terkecoh oleh kata-kata Ibnul Qayyim ini. Oleh karenanya mestilah ingat kembali.
Adalah janggal, bila Ibnul Qayyim tidak memahi nash yang ada dalam Al-Muwatha’, Shahih Muslim dan lain-lain ini. Akan tetapi keheranan tersebut akan hilang, manakala kita ingat, bahwa dia menulis kitab Az-Zad itu adalah pada waktu di mana dia jauh dari kitab-kitab lain, yakni dia dalam perjalanan, sebagai seorang musafir. Inilah sebabnya mengapa dalam kitab tersebut, di samping kesalahan itu, banyak juga kesalahan yang lain. Dan mengenai hal ini telah saya jelaskan dalam At-Ta’liqat Al-Jiyad ‘Ala Zadil Ma’ad.
Yang membuat pendapat ini tetap janggal adalah, bahwa gurunya, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, telah menjelaskan dalam sebuah bukunya, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Mengapa hal itu tidak diketahui oleh Ibnul Qayyim padahal dia orang yang paling mengenal Ibnu Taimiyah dengan segala pendapatnya? Setelah menuturkan hadis itu, Syaikhul Islam dalam Majmu’atur Rasail wal-Masa’il (2/26-27) mengatakan: “Pengertian jamak itu ada tiga tingkatan: Manakala sambil berjalan, maka pada waktu yang pertama. Sedangkan bila turun, maka pada waktu yang kedua. Inilah jamak sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shahihain dari hadis Anas dan Ibnu Umar. Itu menyerupai jamak di Muzdalifah. Adapun manakala di waktu yang kedua, baik dengan berjalan maupun dengan kendaraan, maka dijamak pada waktu yang pertama. Ini menyerupai jamak di Arafah. Sungguh hal ini telah diriwayatkan dalam As-Sunnan (yakni hadis Mu’adz ini). Adapun manakala turun pada waktu keduanya, maka dalam hal ini tidak aku ketahui hadis ini menunjukkan, bahwa beliau Nabi turun di kemahnya dalam bepergian itu. Dan bahwa beliau mengakhirkan Zuhur, kemudian keluar, lalu shalat Zuhur dan Ashar sekalian.
Kemudian beliau masuk ke tempatnya, lalu keluar lagi dan melakukan shalat Maghrib dan Isya’ sekalian. Sesungguhnya kala ‘ad-dukhul’ (masuk) dan ‘khuruj’ (keluar), hanyalah ada di rumah (kemah saja). Sedangkan orang yang berjalan tidak akan dikatakan masuk atau keluar. Tetapi turun atau naik.
“Dan Tabuk adalah akhir peperangan Nabi ﷺ. Sesudah itu beliau ﷺ tidak pernah bepergian, kecuali ketika haji Wada’. Tidak ada kasus jamak darinya, kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Adapun di Mina, maka tidak ada seorang pun yang menukil, bahwa beliau pernah menjamak di sana.
Mereka hanya menukilkan, bahwa beliau ﷺ memang mengqashar di sana. Ini menunjukkan, bahwa beliau ﷺ dalam suatu bepergian terkadang menjamak dan terkadang tidak. Bahkan yang lebih sering adalah bahwa beliau ﷺ tidak menjamak . Hal ini menunjukkan, bahwa beliau ﷺ tidak menjamak. Dan juga menunjukkan, bahwa jamak bukan menjadi sunah Safar sebagaimana qashar, tetapi dilakukan hanya bila diperlukan saja, baik dalam bepergian, maupun sewaktu tidak dalam bepergian, supaya tidak memberatkan umatnya. Maka seorang musafir, bilamana memerlukan jamak, maka lakukan saja, baik pada waktu kedua atau pertama, baik ia turun untuknya atau untuk keperluan lain seperti tidur dan istirahat pada waktu Zuhur dan waktu Isya’. Kemudian dia turun pada waktu Zuhur dan waktu Isya. Dia turun pada waktu Zuhur karena lelah dan mengantuk serta lapar, sehingga memerlukan istirahat, tidur dan makan. Dia boleh mengakhirkan Zuhur kepada waktu Ashar, kemudian menjamak Taqdim Isya dengan Maghrib, lalu sesudah itu bisa tidur, agar bisa bangun di tengah malam dalam bepergiannya.
Maka menurut hadis ini dan lainnya, adalah diperbolehkan menjamak. Adapun bagi orang yang singgah beberapa hari di suatu kampung atau kota, maka meskipun ia boleh mengqashar, karena dia musafir, namun tidak diperkenankan menjamak. Ia seperti halnya tidak boleh shalat di atas kendaraan, tidak boleh shalat dengan tayamum dan tidak boleh makan bangkai.
Hal-hal seperti ini hanya diperbolehkan sewaktu diperlukan saja. Lain halnya dengan soal qashar. sesungguhnya ia memang menjadi sunnah dalam shalat perjalanan”.
Menjamak Dua Shalat Dalam Perjalanan
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam berpendapat sebagai berikut:
Diperbolehkan baginya manjamak shalat Zuhur dengan Ashar dalam salah satu waktu di antara keduanya, menjamak shalat Maghrib dengan Isya’ dalam salah satu waktu di antara keduanya. Semua ini merupakan keluwesan syariat yang dibawa Rasulullah ﷺ dan kemudahannya, yang berarti merupakan karunia dari Allah, agar tidak ada keberatan dalam agama.
“Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: ‘Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara Zuhur dan Ashar jika berada dalam perjalanan, juga menjamak antara Maghrib dan Isya” [Ini lafazh Al-Bukhary dan bukan Muslim, seperti yang dikatakan Abdul haq yang menghimpun Ash-Shahihain. Ibnu Daqiq Al-Id juga mengingatkan hal ini. Mushannif mengaitkan takhrij hadis ini kepada keduanya, karena melihat asal hadis sebagaimana kebiasaan para ahli hadis, karena Muslim mentakhrij dari riwayat Ibnu Abbas tentang jamak antara dua shalat, tanpa memertimbangkan lafalnya. Inilah yang telah disepakati bersama. Menurut Ash-Shan’any. Al-Bukhary tidak metakhrijnya kecuali berupa catatan. Hanya saja dia menggunakan bentuk kalimat yang pasti]
Makna Hadis
Di antara kebiasaan Rasulullah ﷺ jika mengadakan perjalanan, apalagi di tengah perjalanan, maka beliau ﷺ menjamak antara shalat Zuhur dan Ashar, entah taqdim entah Ta’khir. Beliau ﷺ juga menjamak antara Maghrib dan Isya, entah taqdim entah Ta’khir, tergantung mana yang lebih memungkinkan untuk dikerjakan, dan dengan siapa beliau ﷺ mengadakan perjalanan. Yang pasti, perjalanan ini menjadi sebab jamak dan shalat pada salah satu waktu di antara dua waktunya, karena waktu itu merupakan waktu bagi kedua shalat.
Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama
Para ulama saling berbeda pendapat tentang jamak ini. Mayoritas sahabat dan tabi’in memerbolehkan jamak, baik taqdim maupun Ta’khir. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad dan Ats-Tsaury. Mereka berhujjah dengan hadis-hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, begitu pula hadis Mu’adz, bahwa jika Rasulullah ﷺ berangkat sebelum matahari condong, maka beliau ﷺ menjamak shalat Zuhur dan Ashar pada waktu shalat Ashar. Beliau ﷺ mengerjakan keduanya secara bersamaan. Tapi jika beliau ﷺ berangkat sesudah matahari condong, maka beliau ﷺ shalat Zuhur dengan Ashar, lalu berangkat. Jika beliau ﷺ berangkat sebelum Maghrib, maka belaiu ﷺ menunda shalat Maghrib dan mengerjakannya bersama shalat Isya. Jika beliau ﷺ berangkat sesudah masuk waktu Maghrib, maka beliau ﷺ mengerjakan shalat Isya bersama shalat Maghrib. [Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidizy]
Sebagian Imam menshahihkan hadis ini, sementara yang lain memermasalahakannya. Asal hadis ini ada dalam riwayat Muslim tanpa menyebutkan Jama Taqdim.
Sementara Abu Hanifah dan dua rekannya. Al-Hasan dan An-Nakha’y tidak memerbolehkan jamak. Mereka menakwil hadis-hadis tentang jamak, bahwa itu merupakan jamak imajiner. Gambarannya, menurut pendapat mereka, beliau ﷺ mengakhirkan shalat Zuhur hingga akhir waktunya, lalu mengerjakannya, dan setelah itu mengerjakan shalat Ashar pada awal waktunya. Begitu pula untuk shalat Maghrib dan Isya.
Tentu saja ini tidak mengenai dan bertentangan dengan pengertian lafal jamak, yang artinya menjadikan dua shalat di salah satu waktu di antara dua waktunya, yang juga ditentang ketetapan Jamak Taqdim, sehingga menafikan cara penakwilan seperti itu. Al-Khaththaby dan Ibnu Abdil Barr menyatakan, jamak sebagai rukhshah. Mengerjakan dua shalat, yang pertama pada akhir waktunya, dan yang kedua pada awal waktunya, justru berat dan sulit. Sebab orang-orang yang khusus pun sulit mencari ketetapan waktunya. Lalu bagaimana dengan orang-orang awam?
Ibnu Hazm dan salah satu riwayat dari Malik menyatakan, yang boleh dilakukan ialah Jamak Ta’khir dan tidak Jamak Taqdim. Mereka menanggapi hadis-hadis yang dikatakan sebagian ulama, yang dipermasalahkan.
Mereka juga saling berbeda pendapat tentang hukum jamak. Asy-Syafi’i, Ahmad dan jumhur berpendapat, perjalanan merupakan sebab Jamak Taqdim dan Ta’khir. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Malik. Pendapat Malik dalam riwayat yang masyhur darinya, pengkhususan darinya, pengkhususan jamak pada waktu dibutuhkan saja, yaitu jika sedang mengadakan perjalanan. Ini juga merupakan pilihan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim. Menurut Al-Bajy, ketidaksukaan Malik terhadap jamak, karena khawatir jamak ini dilakukan orang yang sebenarnya tidak mendapat kesulitan. Adapun pembolehannya jika mengadakan perjalanan, didasarkan kepada hadis Ibnu Umar.
Abu Hanifah tidak memerbolehkan jamak, kecuali di Arafah dan Muzdalifah, karena untuk keperluan manasik haji dan bukan karena perjalanan.
Jumhur berhujjah dengan hadis-hadis yang menyebutkan jamak secara mutlak tanpa ada batasan perjalanan, ketika singgah atau ketika mengadakan perjalanan. Begitu pula yang disebutkan di dalam Al-Muwaththa’ dari Muadz bin Jabal, bahwa pada Perang Tabuk Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat, kemudian keluar shalat Zuhur dan Ashar bersama-sama, kemudian masuk dan keluar lagi untuk shalat Maghrib dan Isya’. Menurut Ibnu Abdil Barr, isnad hadis ini kuat. Asy-Syafi’y menyebutkannya di dalam Al-Umm. Menurut Ibnu Abdul Barr dan Al-Bajy, keluar dan masuknya Rasulullah ﷺ menunjukkan, bahwa beliau ﷺ sedang singgah dan tidak sedang dalam perjalanan. Ini merupakan penolakan secara tegas terhadap orang yang menyatakan, bahwa beliau ﷺ tidak menjamak, kecuali ketika mengadakan perjalanan.
Dalil Al-Imam Malik, Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim ialah hadis Ibnu Umar, bahwa jika beliau mengadakan perjalan, maka beliau menjamak Maghrib dan Isya’, seraya berkata: “Jika Rasulullah ﷺ mengadakan perjalanan, maka beliau ﷺ menjamak keduanya”.
Tapi menurut jumhur, tambahan bukti dalam beberapa hadis yang lain layak untuk diterima. Bagaimanapun juga, bepergian mendatangkan banyak kesulitan, baik ketika singgah maupun ketika dalam perjalanan. Rukhshah jamak tidak dibuat, melainkan untuk memberikan kemudahan didalamnya.
Ibnul Qayyim di dalam Al-Hadyu, menjadikan hadis Mu’adz dan sejenisnya termasuk dalil-dalilnya,bahwa rukhshah jamak tidak ditetapkan, melainkan ketika mengadakan perjalanan (bukan ketika singgah). Adapun pendapat Abu Hanifah tertolak oleh berbagai hadis yang Shahih dan jelas maknanya.
Faidah Hadis
Pertama:
Seperti yang disebutkan pengarang tentang jamak karena perjalanan, maka di sana ada beberapa alasan selain perjalanan yang memerbolehkan jamak, di antaranya hujan. Al-Bukhary meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ menjamak Maghrib dan Isya’ pada suatu malam ketika turun hujan. Jamak ini dikhususkan untuk Maghrib dan Isya’, bukan untuk Zuhur dan Ashar. Namun ulama lain membolehkannya juga, di antaranya Al-Imam Ahmad dan rekan-rekannya.
Begitu pula alasan sakit. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjamak Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya’ bukan karena takut dan hujan. Dalam riwayat lain disebutkan, bukan karena takut dan perjalanan. Tidak ada sebab lain kecuali sakit. Banyak ulama yang memerbolehkannya, di antaranya Malik, Ahmad, Ishaq dan Al-Hasan. Ini juga merupakan pendapat segolongan ulama dari madzhab Syafi’y, seperti Al-Khaththaby dan ini juga merupakan pilihan An-Nawawy di dalam Shahih Muslim. Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahwa Al-Imam Ahmad menetapkan pembolehan jamak bagi orang yang terluka dan karena kesibukan, yang didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan tentang masalah ini. Ada pula yang menetapkan pembolehan jamak bagi wanita istihadhah, karena istihadhah termasuk penyakit.
Kedua:
Batasan perjalanan yang menyebabkan pembolehan jamak diperselisihkan para ulama. Asy-Syafi’i dan Ahmad menetapkan lama perjalanan selama dua hari hingga ke tujuan, atau sejauh enam belas farskah [Satu farskah sama dengan empat mil. Satu mil sama dengan satu setengah kilometer. Enam belas farsakh sama dengan enam puluh emapt mil, atau sama dengan sembilan puluh enam kilometer]
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan pilihan, bahwa apa pun yang disebut dengan perjalanan, pendek atau jauh, diperbolehkan jamak di dalamnya. Jadi tidak diukur dengan jarak tertentu. Menurut pendapatnya, di dalam nash Al-Kitab dan As-Sunnah tidak disebutkan perbedaan antara jarak dekat dengan jarak jauh. Siapa yang membuat perbedaan antara jarak dekat dan jarak jauh, berarti dia memisahkan apa yang sudah dihimpun Allah, dengan sebagian pemisahan dan pembagian yang tidak ada dasarnya. Pendapat Syaikhul Islam ini sama dengan pendapat golongan Zhahiriyah, yang juga didukung pengarang Al-Mughny.
Ibnul Qayyim menyatakan di dalam Al-Hadyu, tentang riwayat yang membatasi perjalanan sehari, dua hari atau tiga hari, maka itu bukan riwayat yang Shahih.
Ketiga:
Menurut jumhur ulama, meninggalkan jamak lebih utama daripada jamak, kecuali dalam dua jamak, di Arafah dan Muzdalifah, karena di sana ada kemaslahatan.
Kesimpulan Hadis
- Boleh menjamak shalat Zuhur dengan Ashar, shalat Maghrib denan Isya’
- Keumuman hadis menimbulkan pengertian tentang diperbolehkannya Jamak Taqdim dan Ta’khir antara dua shalat. Beberapa dalil menunjukkan hal ini seperti yang sudah disebutkan di atas.
- Menurut zhahirnya dikhususkan saat mengadakan perjalanan. Di atas telah disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan dalil dari masing-masing pihak. Menurut Ibnu Daqiq Al-Id, hadis ini menunjukkan jamak jika dalam perjalan. Sekiranya tidak ada hadis-hadis lain yang menyebutkan jamak tidak seperti gambaran ini, tentu dalil ini mengharuskan jamak dalam kondisi yang lain. Diperbolehkannya jamak di dalam hadis ini berkaitan dengan suatu sifat yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Jika jamak dibenarkan ketika singgah, maka pengamalannya lebih baik, karena adanya dalil lain tentang pembolehannya diluar gambaran ini, yaitu dalam perjalanan. Tegaknya dalil ini menunjukkan pengabaian pengungkapan sifat ini semata. Dalil ini tentu tidak dapat dianggap bertentangan dengan pengertian di dalam hadis ini, karena pembuktian pembolehan apa yang disampaikan di dalam gambaran ini secara khusus, jauh lebih kuat.
- Hadis ini dan juga hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa jamak dikhususkan untuk shalat Zuhur dengan Ashar, Mgahrib dengan Isya, sedangkan Subuh tidak dapat dijamak dengan shalat lainnya.
Hukum Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jumat
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sebagai berikut:
Tidak boleh menjamak (menggabungkan) shalat Ashar dengan shalat Jumat, ketika diperbolehkan menjamak antara shalat Ashar dan Zuhur (karena ada alasan syari, seperti perjalanan,-red). Seandainya seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh melintasi suatu daerah, lalu dia melakukan shalat Jumat bersama kaum Muslimin di sana, maka (dia) tidak boleh menjamak Ashar dengan shalat Jumat.
Seandainya ada seorang yang menderita penyakit sehingga diperbolehkan untuk menjamak shalat, (lalu ia) menghadiri shalat dan mengerjakan shalat Jumat, maka dia tidak boleh menjamak shalat Ashar dengan shalat Jumat. Dalilnya ialah firman Allah subhanahu wa ta’ala:
“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” [An-Nisaa: 103]
Maksudnya, (ialah) sudah ditentukan waktunya. Sebagian dari waktu-waktu ini sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta’ala secara global dalam firman-Nya:
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh Malaikat)” [Al-Israa: 78]
Jika ada yang mengatakan, apakah tidak boleh mengqiyaskan jama shalat Ashar ke Jumat dengan menjamak shalat Ashar ke Zuhur?
Jawabnya adalah tidak boleh, karena beberapa sebab:
- Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah.
- Shalat Jumat merupakan shalat tersendiri, memiliki lebih dari 20 hukum (ketentuan-ketentuan) tersendiri yang berbeda dengan shalat Zuhur. Perbedaan seperti ini menyebabkannya tidak bisa disamakan (diqiyaskan) ke shalat yang lainnya.
- Qiyas seperti (dalam pertanyaan di atas, -pent) ini bertentangan dengan zahir sunnah. Dalam Shahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi ﷺ menjamak Maghrib dengan Isya di Madinah dalam kondisi aman dan tidak hujan.
Pada masa Rasulullah ﷺ pernah juga turun hujan yang menimbulkan kesulitan. Akan tetapi beliau ﷺ tidak menjamak shalat Ashar dengan Jumat, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan lainnya dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ pernah meminta hujan pada hari Jumat saat beliau ﷺ di atas mimbar. Sebelum beliau ﷺ turun dari mimbar, hujan turun dan mengalir dari jenggotnya. Ini tidak akan terjadi, kecuali disebabkan oleh hujan yang bisa dijadikan alasan untuk menjamak shalat, seandainya boleh menjamak Ashar dengan shalat Jumat. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, pada hari Jumat berikutnya, seseorang datang dan berkata: “Wahai, Rasulullah. Harta benda sudah tenggelam dan bangunan hancur, maka berdoalah kepada Allah agar memberhentikan hujan dari kami”.
Kondisi seperti ini, (tentunya) memerbolehkan untuk menjamak, jika seandainya boleh menjamak shalat Ashar dengan shalat Jumat.
Jika ada yang mengatakan: “Mana dalil yang melarang menjamak shalat Ashar dengan shalat Zuhur?”
Pertanyaan seperti ini tidak tepat, karena hukum asal beribadah adalah terlarang, kecuali ada dalil (yang merubah hukum asal ini menjadi wajib atau sunat, -pent). Maka orang yang melarang pelaksanaan ibadah kepada Allah dengan suatu amalan fisik atau hati, tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Akan tetapi, yang dituntut untuk mendatangkan dalil ialah orang yang melakukan ibadah tersebut, berdasarkan firman Allah yang mengingkari orang-orang yang beribadah kepadanya, tanpa dasar syari “Apakah mereka memunyai Sembahan-Sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah” [Asy-Syuura: 21]
Dan firman-Nya:
“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agamamu” [Al-Maidah: 3]
Berdasarkan ini, jika ada yang menanyakan: “Mana dalil larangan menjamak shalat Ashar dengan shalat Jumat?” (Maka) kita mengembalikan pertanyaan: “Mana dalil yang memerbolehkannya? Karena hukum asal shalat Ashar dikerjakan pada waktunya. Ketika ada faktor yang memerbolehkan untuk menjamak shalat Ashar, hukum asal ini bisa diselisihi. (Maka yang) selain itu tetap pada hukum asalnya, yaitu tidak boleh diajukan dari waktunya.
Jika ada yang mengatakan: “Bagaimana pendapatmu jika dia berniat shalat Zuhur ketika shalat Jumat agar bisa menjamak?”
Jawab, jika seorang imam shalat Jumat di suatu daerah, berniat shalat Zuhur dengan shalat Jumatnya, maka tidak syak lagi (demikian) ini merupakan perbuatan haram, dan shalatnya batal. Karena bagi mereka, shalat Jumat itu wajib. Jika ia mengalihkan shalat Jumat ke shalat Zuhur, berarti mereka berpaling dari perintah-perintah Allah kepada sesuatu yang tidak diperintahkan, sehingga berdasarkan hadis di atas, (maka) amalnya batal dan tertolak.
Sedangkan jika yang berniat melaksanakan shalat Jumat dengan niat Zuhur adalah -seorang musafir (misalnya), yang bermakmum kepada orang yang wajib melaksanakannya, maka perbuatan musafir ini juga tidak sah. Karena, ketika dia menghadiri shalat Jumat, berarti dia wajib melakukannya. Orang yang terkena kewajiban shalat Jumat, namun dia melaksanakan shalat Zuhur sebelum imam salam dari shalat Jumat, maka shalat Zuhurnya tidak sah.
Sumber:
- Silsilah Al-Hadis Ash-Shahihah Wa Syaiun Min Fiqhiha Wa Fawaaidiha, edisi Indonesia Silsilah Hadis Shahih dan Sekelumit Kandungan Hukumnya, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terbitan CV. Pustaka Mantiq, hal. 362-372.
- 257 Tanya Jawab Fatwa-fatwa Al-Utsaimin, oleh Syaikh Muhammad Al-Shalih Al-‘Utsaimin, terbitan Gema Risalah Press, hal 133-134.
- Kitab Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam, Edisi Indonesia Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, Pengarang Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Penerbit Darul Fallah
- Majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun IX/1426H/2005. Diambil dari Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
- http://www.almanhaj.or.id
https://jacksite.wordpress.com/2007/12/06/hukum-shalat-qashar-dan-shalat-jama/

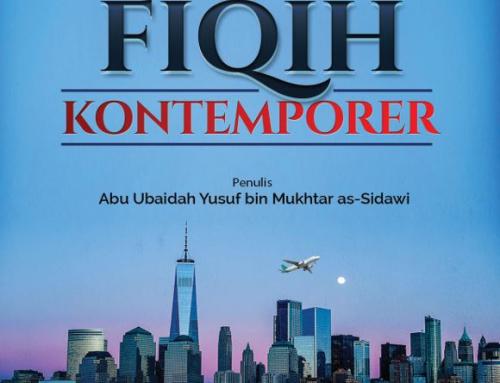
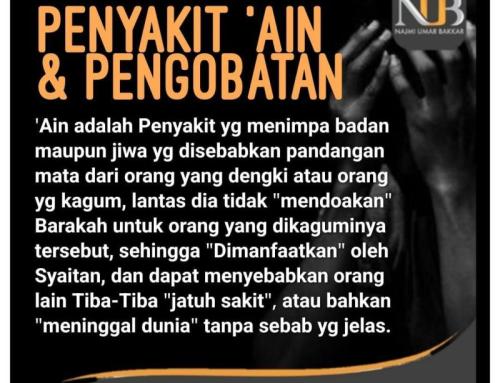



Leave A Comment