Jangan Gegabah Memvonis Kafir Orang Lain. Kaidah, Syarat dan Penghalang Takfir
Pengafiran bukanlah masalah yang mudah, melainkan masalah yang sangat berat risikonya, dan amat berbahaya. Pengafiran juga berdampak pada hukum-hukum yang sangat banyak, baik masalah Akhirat maupun dunia, seperti ancaman pedih baginya berupa laknat, murka, terhapusnya amal, tidak diampuni, kekal di Neraka. Demikian juga hukum-hukum dunia seperti cerai dengan istri, dihukum bunuh, tidak ada hak waris, haram disholati, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum Muslimin, dan hukum-hukum lainnya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih.
Mengingat begitu berbahayanya pengafiran ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memeringatkan kita dengan ancaman yang sangat berat, agar jangan tergesa-gesa dalam memvonis kafir. Berikut ini beberapa hadis beliau:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».
Dari Abdullah ibn Umar Radhiallahu’anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang yang mengatakan kepada saudaranya ‘Wahai kafir’ dan ternyata tidak, maka akan kembali kepada salah satu di antara keduanya.” Dalam riwayat Muslim dengan lafadz, “Barang siapa mengafirkan saudaranya maka akan kembali kepada salah satunya.” (HR al-Bukhari: 6104 dan Muslim: 111)
عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ».
Dari Abu Dzar Radhiallahu’anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan kekufuran, kecuali akan kembali kepada dirinya kalau ternyata yang dituduh tidak demikian.” (HR al-Bukhari: 6045)
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا».
Dari Abu Hurairah Radhiallahu’anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya ‘Wahai kafir’ maka akan kembali kepada salah satunya.” (HR al-Bukhari: 6103)
Berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama pun telah memeringatkan kepada kita semua, agar jangan tergesa-gesa dan jangan gegabah dalam mengafirkan kaum Muslimin.
Al-Imam asy-Syaukani berkata: “Ketahuilah, bahwa menghukumi seorang Muslim bahwa dia keluar dari agama Islam menuju kekafiran, tidaklah pantas dilakukan seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kecuali dengan BUKTI YANG LEBIH TERANG DARI MATAHARI. Sebab, telah shahih dari sejumlah sahabat, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Barang siapa mengatakan kepada saudaranya »Wahai kafir«, maka akan kembali kepada salah satu di antaranya.’ Dalam hadis-hadis ini terdapat peringatan keras dari tergesa-gesa dalam mengafirkan.” (Sailul Jarrar 4/578)
Abdullah Abu Buthain berkata: “Kesimpulannya, wajib atas setiap orang yang menasihati dirinya supaya TIDAK berbicara dalam masalah ini, kecuali dengan ilmu dan bukti dari Allah. Dan hendaknya dia berwaspada dari mengeluarkan seorang dari Islam dengan sekadar pemahamannya dan akalnya. Karena mengeluarkan seorang atau memasukkannya, termasuk perkara agama yang sangat agung. Setan telah menggelincirkan banyak manusia dalam masalah ini.” (ad-Durar as-Saniyyah 10/374–375)
Marilah kita merenungi sebuah hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang semoga bisa menjadi pelajaran dan renungan bagi kita semua akan bahayanya masalah ini:
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.
Abu Hurairah Radhiallahu’anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Dahulu ada dua orang di Bani Isra’il yang bersaudara. Salah satunya suka berbuat dosa dan yang lainnya rajin beribadah. Saudaranya yang ahli ibadah setiap melihat saudaranya yang suka berdosa maka dia menasihatinya, ‘Berhentilah kamu.’ Pada suatu saat, dia mendapatinya melakukan dosa lalu menasihatinya. Tetapi saudaranya yang berdosa mengatakan, ‘Biarkanlah diriku dengan Rabbku, apakah kamu diutus untuk mengawasiku?’ Maka saudaranya berkata: ‘Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu atau tidak akan memasukkanmu ke Surga.’ Akhirnya, dibangkitkan ruh keduanya. Maka keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam. Lalu Allah mengatakan kepada yang rajin ibadah, ‘Apakah kamu lebih tahu daripada Aku? Apakah kamu memiliki kekuasaan apa yang berada pada Tangan-Ku.’ Dan Allah berfirman kepada yang berdosa, ‘Pergilah kamu dan masuklah ke surga dengan sebab rahmat-Ku’ dan mengatakan untuk saudaranya yang lain, ‘Seretlah dia ke Neraka.’” Abu Hurairah Radhiallahu’anhu berkata: “Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh dia telah mengucapkan suatu ucapan yang menyengsarakan dunia dan Akhiratnya.” (HR Abu Dawud: 4901 dan dihasankan oleh al-Albani dalam takhrij Syarh ath-Thahawiyyah hlm. 319 karya Ibnu Abil Izzi al-Hanafi, terbitan Maktab Islami)
Mengafirkan Ulama dan Umara
Para ulama dan umara adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى اْلأَمْرِ مِنكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. (QS an-Nisa’ [4]: 59)
Para ulama mengatakan bahwa Ulil Amri mencakup dua golongan, yaitu ulama dan penguasa [Lihat Tafsir ath-Thabari 5/93, Tafsir Ibnu Katsir 1/530, Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 18/158, Risalah Tabukiyyah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah hlm. 46].
Begitu banyak dalil yang menganjurkan kita untuk memuliakan para ulama dan umara dalam hal bukan maksiat, karena hal itu mengandung kemaslahatan yang banyak bagi manusia. Namun, bagaimanakah kiranya jika mereka dilecehkan, dihina, bahkan dikafirkan?!! Tentu ini lebih berbahaya dan dampaknya sangat mencekam. Sebab mengafirkan ulama dan umara memiliki dua dampak negatif yang besar: dampak negatif dari segi syari dan kemasyarakatan. Berikut pembahasannya:
Pertama: Dampak Negatif dari Segi Syari, karena ulama yang dicap kafir tidak akan dipercaya lagi oleh manusia, atau minimal adalah diragukan kredibilitas mereka. Dengan demikian, pada hakikatnya orang yang mengafirkan ulama tersebut berarti menghancurkan syariat Islam. Sebab syariat Islam itu diambil dari para ulama para ahli waris nabi, sedangkan yang diwariskan oleh para nabi bukanlah Dinar dan Dirham, melainkan ilmu. (HR Abu Dawud: 3641, at-Tirmidzi: 2682, Ibnu Majah: 223; dishahihkan oleh al-Albani) [Al-Imam Ibnu Rajab memiliki buku khusus tentang penjelasan hadis ini berjudul Waratsatul Anbiya’ fi Syarhi Hadis Abi Darda’]
Kedua: Dampak Kemasyarakatan, karena apabila pemerintah telah dianggap kafir, maka akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan pemberontakan yang tidak diketahui kesudahannya kecuali oleh Allah.
Oleh karenanya, kita harus waspada terhadap pemikiran seperti ini dan hendaknya mengingatkan orang yang berpemikiran rusak tersebut. Katakan kepadanya, “Jika Anda menilai bahwa seorang alim melakukan kekufuran, maka hubungilah dia dan berdialoglah dengannya tentang masalah tersebut agar masalahnya jelas.” [Tulisan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam surat kabar al-Muslimun, Edisi 593. Tanggal 28/1/1417 H (14/6/1996 M), sebagaimana dalam Fitnah Takfir hlm. 69–70 oleh Ali ibn Husain Abu Lauz].
Syarat dan Penghalang Takfir
Termasuk kaidah fiqih yang sangat berharga ialah bahwa sesuatu hukum tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, baik dalam wudhu, sholat, pernikahan, jual beli, dan sebagainya [Lihat al-Qawa’id wal Ushul Jami’ah karya as-Sa’di hlm. 33–35, Syarh Qawa’id as-Sa’diyyah karya asy-Syaikh Abdul Muhsin az-Zamil hlm. 85–89, Syarh Manzhumah Qawa’id Fiqhiyyah karya Dr. Abdul Aziz al-’Uwaid hlm. 235–237]. Di antaranya juga adalah masalah takfir yang menjadi topik pembahasan kita kali ini.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Pengafiran memiliki syarat-syarat dan penghalang. Maka pengafiran secara mutlak tidak mengharuskan pengafiran secara individu orang, kecuali apabila terpenuhi syarat dan hilang segala penghalangnya. Hal yang menunjukkan hal ini bahwa al-Imam Ahmad dan mayoritas para imam yang sering mengatakan secara umum, bahwa barang siapa mengatakan atau melakukan ini kafir, namun mereka tidak mengafirkan kebanyakan orang yang mengatakan ucapan tersebut.” (Majmu’ Fatawa 12/487)
Oleh karenanya, sangat penting kita mengetahui masalah ini agar kita mengetahui betapa ketatnya masalah ini:
- Baligh dan berakal
Hal ini berdasarkan dalil bahwa anak kecil dan orang yang tidak berakal, diangkat pena dari mereka, sebagaimana dalam hadis:
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل».
“Pena diangkat dari tiga golongan: Dari orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sadar.” (HR Ahmad: 24694, Ibnu Majah: 2041, al-Hakim 2/67 dan dishahihkan al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil 2/5)
Hadis ini menunjukkan gugurnya beban dari tiga golongan tersebut. Dan dari hadis ini pula para ulama mengambil kaidah ushul yang populer, bahwa baligh dan berakal adalah syarat taklif (beban hukum) [Lihat al-Qawa’id wal Fawa’id al-Ushuliyyah hlm. 33 oleh Ibnu Lahham dan al-Qawa’id wal Ushul Jami’ah hlm. 33 oleh as-Sa’di].
Para ulama juga menilai bahwa baligh dan berakal adalah syarat untuk menghukumi seorang tertentu dengan kekafiran. Sebab itu, mereka tidak menganggap murtadnya anak kecil dan orang gila [Lihat al-Ijma’ hlm. 122 oleh Ibnul Mundzir, al-Mughni 12/266 oleh Ibnu Qudamah].
- Sengaja
Ini juga merupakan syarat yang penting. Adapun jika seseorang salah bicara atau berbuat tanpa kesengajaan dan kemauan dari dirinya, baik karena terpaksa, sangat takut, sangat gembira, dan sebagainya, maka tidak bisa dikafirkan. Dalil tentang “terpaksa” ialah firman Allah:
مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاْلإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُُ
Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar. (QS an-Nahl [16]: 106)
Dalil tentang “Karena sangat gembira” adalah kisah yang dibawakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa Allah lebih bergembira dengan taubat hamba-Nya daripada gembiranya seorang yang berada di tengah padang pasir lalu kehilangan hewan tunggangan yang membawa perbekalan safarnya, lalu dia beristirahat dalam keadaan putus asa, ternyata tiba-tiba hewannya datang kembali. Melihat hal itu, karena sangat gembiranya dia mengatakan, “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu”, dia salah berucap karena sangat gembiranya. (HR al-Bukhari: 2747 dan Muslim 4/2104)
Lihatlah orang ini, dia mengatakan bahwa Allah adalah hambanya dan dia adalah Rabb-nya Allah. Bukankah ini adalah suatu kekufuran? Namun, tatkala dia mengatakan hal itu di luar kesadarannya, maka hal itu dimaafkan. Al-Qadhi Iyadh berkata: “Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa apa yang dikatakan oleh seseorang di luar kesadarannya baik karena gembira atau lalai maka tidaklah berdosa.” (Ikmalul Mu’lim 8/245)
Dalil tentang “Sangat takut” adalah kisah yang diceritakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang seorang yang mengatakan, “Jika aku telah meninggal maka bakarlah aku, kemudian tumbuklah halus-halus, lalu buanglah ke lautan. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta’ala membangkitkanku, maka Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah ada di alam ini.” Akhirnya, mereka pun melaksanakan wasiat tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ala membangkitkannya, Allah Subhanahu wa Ta’ala bertanya kepadanya, “Apa yang membuatmu melakukan ini?” Jawabnya, “Aku takut kepada-Mu.” Lantas Allah mengampuninya. (HR al-Bukhari: 6481 dan Muslim: 2756)
Lihatlah orang ini, dia mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkan hamba setelah kematian. Bukankah ini adalah suatu kekufuran?! Namun, dia melakukannya karena sangat takutnya kepada Allah, maka Allah mengampuninya.
- Sampai Hujjah Padanya
Ini adalah syarat yang penting. Adapun jika orang tersebut jahil (bodoh), maka tidak dikafirkan. Dalil tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya ialah permintaan para sahabat agar dibuatkan untuk mereka Dzatu Anwath guna mengharap berkah dan i’tikaf di sana sebagaimana kaum Musyrikin, namun Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengafirkan mereka yang meminta tersebut. Hal ini sangat jelas menunjukkan, bahwa orang jahil diberi udzur sampai tegak hujjah padanya. Mereka adalah generasi terbaik yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lantas, bagaimana kiranya dengan selain mereka yang lebih jahil dan jauh dari zaman Nabi?! (ad-Durr an-Nadhid hlm. 9)
Al-Imam adz-Dzahabi berkata: “Seorang tidak berdosa kecuali setelah dia mengetahui hukumnya dan ditegakkan hujjah padanya. Allah Maha Lembut dan Kasih Sayang. Allah berfirman:
وَمَاكُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS al-Isra’ [17]: 15)
Para sahabat ketika di Habasyah, telah turun wahyu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berupa kewajiban dan larangan. Namun, beliau tidak menyampaikannya kepada mereka, melainkan setelah beberapa bulan. Mereka pada saat itu diberi udzur sampai datang dalil kepada mereka. Demikian pula, orang yang tidak mengetahui diberi udzur, sehingga dia mendengarkan dalilnya. Wallahu A’lam.” (al-Kaba’ir hlm. 12)
- Bukan Karena Takwil
Maksud dari syarat ini ialah, bahwa ada sebagian orang yang sudah mengerti dalil, tetapi dia mengartikan makna lain yang tidak benar, sehingga dia terjatuh dalam kesalahan tanpa sadar.
Dalil tentang hal ini adalah kisah Mu’adz ibn Jabal Radhiallahu’anhu yang sujud kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya, “Apa ini, wahai Mu’adz?” Dia menjawab, “Saya datang ke Syam dan saya dapati mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka saya ingin melakukan hal itu kepada dirimu, wahai Nabi.” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jangan lakukan hal itu, karena seandainya saya boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.” (HR Ibnu Majah: 1853, Ahmad 32/145 dan dishahihkan al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah: 1203)
Dalam hadis ini, Mu’adz telah sujud kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan sujud kepada selain Allah adalah suatu kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam [Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 1/74]. Namun, tatkala perbuatan Mu’adz Radhiallahu’anhu tersebut disebabkan oleh takwil, yakni dia menganggap hal itu adalah sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan mengafirkannya, melainkan hanya melarangnya saja dan menjelaskan bahwa sujud itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah [Lihat pembahasan ini dalam at-Takfir wa Dhawabituhu karya Dr. Ibrahim ar-Ruhaili hlm. 263–297].
Siapakah yang Berhak Mengafirkan?
Setelah membaca penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa mengafirkan itu TIDAK MUDAH DAN TIDAK BOLEH SEMBARANGAN. Kita harus memahami kaidah-kaidah, syarat-syarat, dan penghalang-penghalangnya.
Oleh karena itu, masalah (pengafiran) ini harus diserahkan kepada ahli ilmu yang kuat dan paham akan Alquran dan sunnah serta kaidah-kaidah masalah ini. Mereka (ahli ilmu)lah yang dapat menghukumi secara adil dan berdasarkan ilmu, bukan asal-asalan dan berdasarkan hawa nafsu.
Asy-Syaikh Dr. Shalih ibn Fauzan al-Fauzan berkata: “Tidak boleh berbicara tentang masalah ini selain orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan, sehingga dia tidak mengafirkan, kecuali orang yang dikafirkan Allah dan rasul-Nya disebabkan melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman yang disepakati oleh ulama. Oleh karenanya, seorang Muslim harus berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan tidak berbicara kecuali di atas ilmu. Sebab, jika tidak demikian lalu dia mengafirkan seorang Muslim, maka dia telah melakukan dua tindak kriminal yang sangat berbahaya:
Pertama: Mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu, padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَاتِهِ إِنَّهُ لاَيُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
Dan siapakah yang lebih dzalim (aniaya) daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang dzalim tidak mendapat keberuntungan. (QS al-An’am [6]: 21)
وَلاَتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلاَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. (QS al-Isra’ [17]: 36)
Kedua: Melakukan kejahatan kepada seorang Muslim yang dia kafirkan. Sebab apabila dia mengafirkan seorang Muslim, berarti dia harus dipisah dari istrinya, tidak ada saling mewarisi, tidak dikubur di kuburan kaum Muslimin, dan sebagainya.
Oleh karenanya, seorang yang berbicara pada masalah ini harus memiliki ilmu yang diambil dari para ulama Rabbaniyyun yang kuat, bukan hanya sekadar hafalan kitab atau menelaah kitab saja.” (at-Takfir wa Dhawabituhu hlm. 101–102)
Sebagai penutup, alangkah indahnya nasihat asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin tatkala berkata: “Hendaknya seorang manusia bersikap hati-hati dari mengafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau melontarkan permusuhan Allah kepada seorang yang bukan musuh Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya dia menahan lidahnya karena lidah adalah sumber bencana.” (Fatawa fil Aqidah 2/754)
Penulis: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi
http://abiubaidah.com/pikirkan-sebelum-mengafirkan.html/
Catatan Tambahan:
Takfir: Mengafirkan orang lain tanpa bukti yang dibenarkan oleh syariat / penetapan hukum kafir terhadap seseorang.




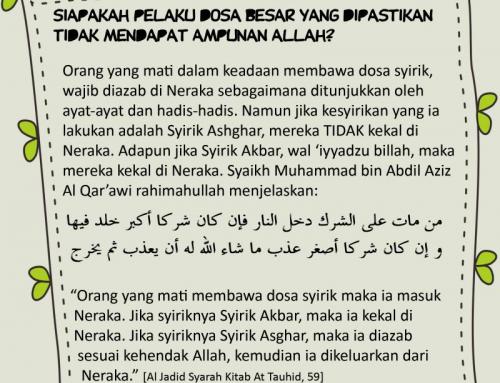

Leave A Comment